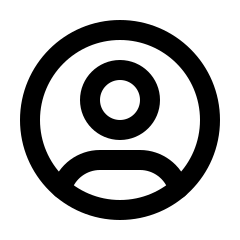Menentang Demokrasi Cangkang Kosong
Oleh: Immawan Wahyudi, pengajar di Fakultas Hukum UAD, mantan Ketua Umum DPP (S) IMM 1985-1986
Beberapa hari ini viedo Saudara Tiyo, Ketua BEM UGM sedang ”ngetrend.” Tiyo jadi tokoh populer karena kritikannya sangat keras terhadap Presiden dan secara khusus kepada pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebenarnya kritik terhadap program MBG secara kuantitatif bisa dikatakan sudah kelewat banyak. Hal itu merupakan ungkapan kesal, geram atau bahkan marah karena terlalu banyak kasus keracunan akibat menerima makanan dari MBG. Apapun diksi yang digunakan sebagai ungkapan protes masih dalam koridor kontrol sosial yang dibolehkan secara hukum dan secara moral.
Tulisan sederhana ini tidak akan membahas MBG dalam konteks beribu masalah yang mengitarinya. Tulisan ini lebih fokus pada makna kritik ataupun kontrol sosial yang seharusnya diperankan oleh semua elemen bangsa sebagai bagian penting dan bermakna dari demokrasi. Tanpa kontrol sosial yang kuat dari elemen-elemen di atas, demokrasi akan terjebak dalam "Empty Shell Democracy" (Demokrasi Cangkang Kosong), di mana institusinya ada (ada pemilu, ada parlemen, ada pula prinsip negara hukum), namun semua itu isinya tidak mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945,
Demokrasi Vs Oligarki
Sebenarnya oligarki ada dalam sistem pemerintahan manapun. Namun ketika ditarik untuk dihadap-hadapkan antara demokrasi dengan oligarki menjadi nampak begitu jelas ketimpangannya. Demokrasi dan oligarki sering kali berhadap-hadapan dalam sistem pemerintahan, karena keduanya mencerminkan bentuk distribusi kekuasaan yang bertolak belakang. Demokrasi, khususnya dalam konteks modern, berlandaskan pada prinsip partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pemilihan umum dan kontrol terhadap kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, tujuan utama adalah tercapainya keadilan sosial, transparansi, dan keterwakilan yang lebih luas dari beragam kelompok masyarakat (Held, 2006).
Sebaliknya, oligarki merujuk pada bentuk kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite atau kelompok kecil yang memiliki kendali atas sektor-sektor penting negara, seperti ekonomi, politik, media, dan sumber daya alam. Biasanya, oligark menguasai sumber daya negara yang besar dan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan posisi dan memperluas pengaruh, baik di bidang ekonomi maupun dalam kebijakan publik (Winters, 2011). Dalam oligarki, kepentingan kelompok kecil lebih diutamakan daripada kepentingan umum, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik. Hal yang menjadikan rakyat merasa ditinggalkan sesudah memberikan mandat kepada para pejabat publik adalah sikap dan political will pejabat yang merasa kekuasaannya adalah murni dari diri dan kelompoknya dan oleh sebab itu merasa bebas bersikap mesra dengan oligarki dan marah kepada rakyat.
Apa yang seringkali dikemukakan oleh para Aktivis Kampus, NGO, BEM, Organisasi Sosial, dan lain-lain organisasi yang menaruh kepedulian tinggi terhadap realitas ketimpangan kehidupan bernegara yang kemudian direspon secara negatif oleh pemerintah (bahkan seringkali dengan respon yang berlebihan) hal ini sudah cukup memberikan gambaran ketimpangan demokrasi versus oligarki. Ketimpangan itu wujudnya adalah sikap pemerintah yang lebih sering seiring sejalan dengan oligarki daripada mendengarkan kritik dan/atau saran dari elemen bangsa yang mengambil peran sebagai agen social control.
Menyelami Makna Demokrasi
Esensi konsep demokrasi adalah pada konsep mengagungkan kedaulatan rakyat : pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun sering kali dipertanyakan, dikritik, atau dikonseptualisasi ulang oleh para pakar politik, filsuf, dan akademisi dunia. Kritikan ini umumnya berakar pada ketidakefektifan prosedur demokrasi, misalnya potensi "tirani mayoritas", hingga ketidakmampuan rakyat awam untuk terus mengikuti pembuatan kebijakan yang rumit secara prosedur dan secara substantif merugikan rakyat.
Penulis nukilkan dua dari beberapa pandangan pakar dunia yang pandangan mempertanyakan konsep demokrasi dalam konteks kedaulatan rakyat. Diantaranya adalah Jason Brennan (Epistokrasi). Dalam bukunya Against Democracy (2016), Brennan berpendapat bahwa pemilih awam sering kali tidak berpengetahuan, tidak rasional, atau bias secara ideologis. Oleh sebab itu ia mempertanyakan apakah kedaulatan benar-benar harus berada di tangan "rakyat" jika keputusan yang dihasilkan merugikan. Sejalan dengan pendapatnya ini Jason memberikan alternatif, dengan mengusulkan Epistokrasi (pemerintahan oleh mereka yang berpengetahuan/ahli), di mana suara orang yang berpengetahuan lebih tinggi atau hanya ahli yang mengambil kebijakan teknis.
Pakar lainnya adalah Hans Kelsen yang berpandangan bahwa dalam negara modern, kedaulatan rakyat tidak bisa dilakukan secara langsung. "Rakyat" tidak memerintah langsung, melainkan melalui perantara partai politik. Ia menyoroti bahwa struktur dan organisasi internal partai lebih menentukan hasil demokrasi daripada kehendak rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu dalam konteks kedaulatan rakyat Kelsen memberikan analisis terhadap demokrasi terkait dengan beberapa hal berikut. Terjadinya tirani mayoritas yang berpotensi menindas minoritas. Terjadinya ketegangan antara populisme versus konstitusionalisme artinya pertentangan antara kehendak rakyat yang dimobilisasi secara populis dengan batasan konstitusi yang menjaga hak asasi. Selanjutnya kekhawatiran akan terjadinya kesenjangan sosial.
Demokrasi Prosedural versus Substantif-Deliberatif
Untuk memberikan pemahaman mengapa demokrasi kian bertambah hari bertambah limbung ibarat orang yang berjalan dalam keadaan mabuk perlu kiranya dihadap-hadapkan demokrasi prosedural yang hanya bertumpu pada terpenuhinya hak rakyat dalam menentukan wakilnya melalui pemilihan umum (Pemilu). Artinya demokrasi prosedural hanya mementingkan ritual berupa pemilu. Dalam demokrasi seperti inilah yang sedang terjadi saat ini.
Jika kita berharap dengan sungguh-sungguh dengan demokrasi maka demokrasi yang semestinya kita rancang untuk masa depan kehidupan rakyat berkualitas dan tiap keputusan publik menguntungkan rakyat maka diperlukan demokrasi yang bersifat substantif dan deliberatif (menyertakan rakyat berpendapat) karena sebagai pemilik asli kedaulatan. Sebab itu dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dan menentukan nasib negara dan nasib rakyat demokrasi harus dibuka jalan yang luas untuk rakyat berpartisipasi. Penghadapan antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif-deliberatif sebagai berikut.
Tabel Perbandingan: Prosedural vs. Substantif-Deliberatif
| Aspek | Demokrasi Prosedural | Demokrasi Substantif-Deliberatif |
| Fokus Utama | Pemilu, angka, suara terbanyak. | Diskusi, kualitas argumen, konsensus. |
| Kedaulatan | Selesai setelah mencoblos di TPS. | Terus berlanjut melalui kontrol harian. |
| Peran Rakyat | Objek suara (konstituen). | Subjek aktif (warga negara/citizen). |
| Output | Kemenangan politik. | Keadilan sosial dan kemaslahatan publik. |
Menutup Celah Kesenjangan Perwakilan
Sila keempat dalam Pancasila menyatakan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila keempat ini adalah jantung demokrasi Republik Indonesia. Jika bangsa Indonesia kurang energi untuk menjaga kesehatan jantung demokrasi maka demokrasi hanya akan meninggalkan kata-kata kosong atau dalam bahasa yang lebih keren Empty Shell Democracy (Demokrasi Cangkang Kosong). Dalam bahasa jalanan demokrasi yang menipu.
Dengan melihat realitas sosial setelah dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir produk-produk legislasi banyak yang berpotensi merugikan rakyat seperti Undang Undang Cipta Kerja dan hampir semua produk kebijakan lebih menyenangkan kelompok elite, baik oligarki maupun para pendukungnya (para pejabat publik), rakyat berhadapan dengan jalan rumit dan berbatu tajam. Kita bisa mencari celah agar rakyat bisa menjaga ”jantung kesehatan demokrasi” dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dengan serius dan intens. Dalam wacana yang demikian maka Peran masyarakat melalui LSM atau organisasi sosial dan keagamaan, peran Mahasiswa, peran Intelektual, peran Budayawan dan peran tokoh-tokoh berkharisma menjadi sangat penting dan menentukan.
Masyarakat secara luas, LSM, organisasi sosial keagamaan dan tentu Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus maupun Intra Kampus memiliki bargaining power yang kuat dan dapat berfungsi untuk menarik kembali kedaulatan yang telah "dititipkan" kepada wakil rakyat. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari konsensus yang rasional, bukan sekadar lobi-lobi politik di ruang tertutup dan menghidupkan demokrasi dengan spirit baru demokrasi substantif-deliberatif.
Celah yang masih memungkinkan dalam kehidupan real negara RI yang telah hampir semua dibagi habis oleh persekongkolan oligarki dengan pejabat pengabdinya, harus lebih sering dan lebih keras dalam mengontrol. Mengapa sedemikian penting kontrol sosial untuk menghidupan demokrasi yang berbasis pada kedaulatan rakyat karena tanpa kontrol sosial yang kuat dari elemen-elemen di atas, demokrasi akan terjebak dalam Empty Shell Democracy (Demokrasi Cangkang Kosong). Institusinya ada (parlemen pusat dan daerah, pemilu, hukum), namun isinya tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sebenar-benarnya dan lebih merupakan isi tanpa manfaat apalagi maslahat.
Patutlah dihormati munculnya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang dimotori oleh Said Didu dan tokoh-tokoh penting lainnya. Memang masih ada pertanyaan yang mengganjal dari kehadiran GMKR apakah ini sebagai gerakan moral murni ataukah langkah-strategis politis. Penulis berpandangan bahwa kemunculan GKMR di tengah ”kebisuan” dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara yang kian hari kian rumit, layaklah diapresiasi GMKR secara positif.
Para pakar dunia pada umumnya tidak selalu anti-demokrasi, melainkan mempertanyakan bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan agar tidak menghasilkan "tirani" atau kebijakan yang tidak bermanfaat. Kontrol sosial oleh seluruh elemen bangsa, oleh mahasiswa, oleh organisasi sosial bukan sekadar bentuk protes, melainkan sebagai syarat mutlak agar demokrasi tidak berubah menjadi oligarki. Kelompok penekan ini diharapkan bertindak sebagai sistem keseimbangan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat sehingga kekuasaan tetap berpijak pada nalar publik. Dalam bahasa Tiyo; ”Rakyat butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami.” Apa yang dihimbau Tiyo adalah sesuatu yang sangat bernilai dan patut direspon justru karena keruwetan penyelenggaraan negara yang nampaknya makin bertambah hari makin bertambah runyam.*