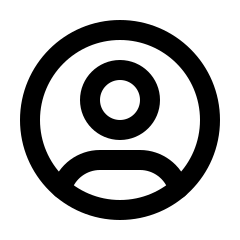Hamka dalam Catatan Harian: Aku Ingin Seperti Buya
Oleh: Ahmad Hasan Fatih, Wakil Sekretaris PWPM Kalimantan Tengah
Apakah kalian pernah memiliki rasa kagum terhadap seseorang sampai ingin sekali menuliskan namanya di setiap catatan harian? Saya mengalami itu ketika membaca karya-karya dan kisah hidup Buya Hamka. Rasanya seperti ada sebuah getaran dalam hati yang menggerakan alam bawah sadar untuk menuliskan: "Aku ingin seperti Buya." Hal ini bukan hanya sekadar beliau seorang ulama tersohor di tanah air, tapi karena kepribadiannya yang memadukan ilmu, keteguhan hati, dan keberanian moral.
Hamka—Haji Abdul Malik Karim Amrullah—lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Sejak kecil, beliau tumbuh di lingkungan yang cukup keras namun kaya akan ilmu. Ayahnya, Haji Rasul, seorang ulama reformis, mendidik Hamka dengan disiplin. Namun, justru dari kegelisahan dan rasa “terkungkung” itulah Hamka muda tumbuh menjadi pribadi yang haus pengetahuan. Ia belajar bukan hanya dari kitab kuning di surau, tetapi juga dari buku-buku modern, majalah, bahkan pergaulannya dengan beragam kalangan.
Ada satu kalimat Buya Hamka yang sering saya renungkan:
“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”
Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa kemalasan bukan sekadar soal tidak bergerak, melainkan termasuk sebuah kejahatan terhadap potensi diri.
Catatan Harian: Belajar dari Perjalanan Buya
Dalam catatan harian pribadi semasa sekolah, saya pernah menuliskan kegelisahan sebagai anak muda zaman sekarang: terlalu sibuk dengan media sosial, malas membaca, mudah menyerah ketika tantangan datang. Lalu saya membandingkannya dengan Buya Hamka.
Hamka kecil justru melahap buku-buku sejarah, sastra, dan filsafat dengan penuh semangat. Ia bahkan sempat meninggalkan pendidikan formal karena dianggap “nakal”, tetapi justru di luar kelas itulah ia menemukan jalan ilmunya. Di usia belasan tahun, Hamka sudah merantau ke Yogyakarta, bertemu tokoh pergerakan, belajar dari Muhammadiyah, dan mengasah kemampuan menulisnya.
Bayangkan, ketika usia segitu, anak muda sekarang masih sering kebingungan arah hidup, tapi Buya Hamka muda sudah berani menulis di surat kabar dan berdakwah dengan kata-kata. Ia membuktikan bahwa ilmu tidak hanya milik mereka yang “bersekolah tinggi”, tapi milik siapa saja yang punya tekad untuk belajar.
Satu hal yang membuat saya semakin kagum adalah bagaimana Hamka memandang kekuatan tulisan. Dalam bukunya Lembaga Budi, ia menulis:
“Tinta seorang ulama lebih berharga daripada darah seorang syuhada.”
Bagi Hamka, menulis bukan sekadar menuangkan kata-kata, tapi bagian dari jihad intelektual. Tak heran, karya monumentalnya seperti Tafsir Al-Azhar dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijck bukan hanya bertahan dan dipajang dalam rak-rak perpustakaan, tapi juga dalam hati jutaan orang.
Data dari Perpustakaan Nasional mencatat, karya-karya Hamka termasuk yang paling sering dipinjam dan dibaca, terutama generasi muda. Bahkan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck beberapa kali diadaptasi ke layar lebar dan masih memikat pembaca lintas generasi.
Suatu ketika saya membaca novel itu, saya menyadari bahwa Hamka bukan hanya seorang ulama, tetapi ia juga sastrawan yang mengerti betul isi hati manusia. Ini juga yang menjadi alasan mengapa saya ingin seperti Buya: mampu menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang indah, menyentuh, dan mudah dipahami siapa saja.
Ujian Hidup: Belajar dari Keteguhan Buya
Tak ada hidup yang selalu berjalan dengan mulus. Hamka pun pernah mengalami ujian hidup dengan cobaan berat. Pada masa Orde Lama, ia dipenjara karena dianggap menentang kebijakan politik pemerintah dan dituduh sebagai antek asing. Tetapi justru di balik jeruji besi itu pula lahir karya besarnya, Tafsir Al-Azhar.
Di titik inilah saya kembali menulis di catatan harian saya: “Jika aku diuji, mampukah aku sekuat Buya?”
Hamka pernah berkata:
“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.”
Kata-kata ini menusuk tajam. Bahwa hidup harus punya nilai, kerja harus punya makna. Cobaan, fitnah, bahkan penjara, tidak membuat Hamka menyerah begitu saja. Justru ia menunjukkan kemuliaan hati seorang ulama yang tidak membalas dendam. Setelah bebas, Hamka tetap menulis, berdakwah, dan memaafkan mereka yang telah menyakitinya.
Relevansi Buya Hamka untuk Generasi Hari Ini
Mengutip data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah, dengan indeks literasi hanya sekitar 0,001. Artinya, dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang benar-benar gemar untuk membaca. Fakta ini membuat saya merenung: seandainya Hamka masih hidup, mungkin beliau akan kembali mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai ilmu dan pengetahuan.
IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dalam beberapa forum pernah menegaskan bahwa semangat literasi ala Hamka harus diwarisi oleh mahasiswa sekarang. Bukan sekadar membaca, tapi juga menulis, mengkritisi, dan membangun peradaban lewat pena.
Di akhir catatan harian, saya selalu menulis sederhana: “Aku ingin seperti Buya.” Bukan berarti saya ingin jadi ulama besar atau penulis terkenal. Hanya saja, saya ingin meneladani semangatnya: semangat belajar tanpa henti, keberanian berkata benar, kekuatan menulis, dan keteguhan hati untuk menghadapi setiap cobaan yang datang dalam kehidupan.
Buya Hamka telah menunjukkan bahwa hidup ini bukan persoalan panjang atau pendek, tapi soal makna. Ia wafat pada 24 Juli 1981, tapi hingga kini namanya terus hidup dalam ingatan.
Mungkin benar kata beliau:
“Hidup adalah tentang memberikan makna dan manfaat bagi orang lain, karena itulah tujuan sejati dari keberadaan kita di dunia.”
Dan bagi saya, kenangan dari Buya Hamka bukan hanya buku-bukunya yang sering saya baca atau film perjalanan hidupnya yang saya tonton berkali-kali, tapi juga inspirasi yang terus menyalakan api semangat dalam hati.