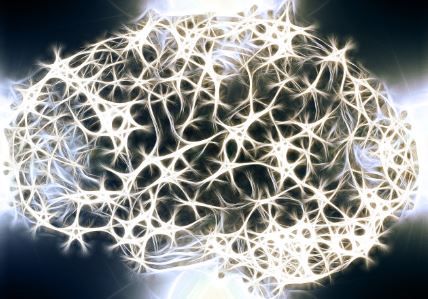Inspirasi dari Peluru di Dada KH Nawawi
Oleh: Babay Parid Wazdi, Kader Muhammadiyah, Aktifis IPM 1988-1991
Senja turun perlahan di kampung Karokrok. Langit berwarna tembaga, kerbau-kerbau telah kembali ke kandang, dan asap dapur mengepul di antara cahaya redup lampu minyak tanah. Di tengah kedamaian itu, lima bayangan bergerak cepat dari arah Talagasari. Mereka membawa karung, langkahnya tergesa, wajahnya tegang.
Di ujung kampung mereka bertanya “Di mana rumah tokoh Masyumi?” tanya salah seorang kepada warga yang polos menjawab, “Di dekat pesantren”.
Tak lama langkah mereka berhenti di depan rumah panggung milik KH Nawawi, sang kiai yang disegani di Karokrok. Di surau kecil di samping rumah, beliau tengah menjadi imam shalat Maghrib. Suaranya tenang, doanya khusyuk, seperti tak ada tanda bahaya yang mendekat. Selesai wirid dan doa, KH Nawawi melangkah naik ke tangga rumah panggung.
Lalu dentuman itu terdengar. Peluru panas menembus punggung, menyalib dada, menghantam pintu jati yang kini menjadi saksi bisu kesyahidan sang kiai. Lima bayangan itu lenyap dalam gelap malam, meninggalkan duka yang menoreh sejarah keluarga kami dan kampung kami.
Begitulah kisah yang kerap diceritakan oleh Hj Sofiah, simbah putri kami, dengan mata berkaca-kaca. Malam itu walapun kami merasakan getirnya kehilangan tetapi kami mendapatkan sebuah cahaya penuntun untuk generasi setelah simbah. “Kakekmu wafat setelah menjadi imam shalat Maghrib”, katanya suatu malam, “Itulah mati terbaik, dalam ibadah, dalam perjuangan”.
Namun rupanya duka belum berhenti di situ. Beberapa tahun sebelumnya, adik bungsu Hj. Sofiah, Kapten ACA, gugur dalam pertempuran Karawang-Bekasi. Dalam Agresi Militer Belanda II tahun 1947-1948, jasadnya sempat diseret di jalan oleh pasukan musuh. Baru bertahun-tahun kemudian kami tahu bahwa beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Karawang.
Kisah-kisah kepahlawanan yang diceritakan kepadaku itu tumbuh bersemai dalam jiwaku di tubuk kecilku. Aku mendengar kisah perjuangan bukan dari buku sejarah tebal, tapi dari air mata dan doa seorang nenek yang kehilangan suami dan adik sekaligus. Dari situ aku mulai mengkonfirmasi bahwa kemerdekaan Indonesia didapatkan melalui warisan darah dan kesetiaan pada kebenaran. Dari rahim keluarga itulah aku tumbuh.
Selanjutnya ketika menjadi mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muhammadiyah, nilai-nilai kejujuran dan pengabdian itu pun semakin menancap di dadaku. Aku diajarkan bahwa korupsi adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dani dosa moral terhadap amanah publik.
Maka ketika aku bekerja, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau keluarga, apalagi orang lain. Setiap keputusan kuambil dengan hati-hati, agar tak ada benturan kepentingan, tak ada suap, tak ada dusta di antara tanggung jawab dan nurani.
Namun hidup memang tak selalu lurus seperti jalan yang kita rancang. Setelah 27 tahun mengabdi dengan menjaga prinsip itu, aku justru dituduh melakukan hal yang paling kujauhi, korupsi. Dunia seperti berbalik. Ruang kerja berganti dengan jeruji besi, kebebasan berganti dengan tatapan curiga.
Di awal masa itu, aku sempat bertanya-tanya, “Mengapa kejujuran justru berbuah fitnah?”, “Mengapa mengambil jalan lurus terasa begitu terjal?”. Tapi perlahan aku mengerti, mungkin inilah cara Allah meneguhkan janji-Nya bahwa ujian adalah harga yang harus dibayar oleh orang yang berusaha hidup jujur.
Dari balik jeruji inilah aku mulai menulis. Menyusun ulang kisah keluarga dan jejak pengabdian, seolah ingin mengembalikan napas ke dalam luka. Dalam tulisan inilah aku bertawasul melalui amal kecil yang pernah kulakukan yaitu menolak suap, menolak kolusi, dan menolak menjual nurani. Aku memohon agar Allah menjadikan semua itu wasilah untuk membebaskan diriku dari segala fitnah dan dakwaan.
Ketika malam menjadi sunyi di Salemba, aku sering membayangkan kembali peristiwa peluru yang menembus dada KH. Nawawi. Betapa panasnya logam itu, tetapi betapa sejuknya iman yang menyambut ajal. Barangkali ujian yang kualami ini hanyalah serpihan kecil dari pengorbanan beliau. Jika peluru mampu menghentikan jantung seorang kiai, fitnah pun mungkin hanya melukai permukaan jiwa seorang cucunya, tak akan mampu memadamkan keyakinan bahwa kebenaran tetap milik Allah Swt.
Aku tahu bahwa pengabdian sejati tidak selalu dilihat dari jabatan atau penghargaan, tetapi dari kemampuan menjaga nurani ketika dunia meragukanmu. Mungkin beginilah caranya Allah menegur agar aku kembali meneguhkan makna amanah. Darah para syuhada Karawang-Bekasi telah mengalir di tanah ini, yang telah menebus kemerdekaan dengan nyawanya. Maka tanggung jawab kita hari ini adalah menebus moral bangsa dengan kejujuran. Bila peluru menembus dada KH. Nawawi, maka jangan biarkan peluru korupsi dan ketamakan menembus dada bangsa kita.
Aku menulis ini untuk bersaksi bahwa masih ada orang yang berusaha menjaga amanah, walau dunia menuduh sebaliknya. Dan sebagaimana KH. Nawawi wafat setelah menjadi imam Maghrib, aku pun ingin menutup hidup ini dalam keadaan menjaga iman dan kejujuran.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapa pun yang sedang meniti jalan pengabdian, jangan takut pada fitnah ketika kita berpihak pada kebenaran, karena peluru hanya menembus tubuh, tetapi kejujuran menembus langit.
Penulis adalah Direksi Bank DKI (2018 sd 2022) & Dirut Bank Sumut (2023 sd 2025). Esay ini di ketik ulang dari tulisan tangan ayahku yang berada di rutan Salemba & Esay ini bagian dari Manifesto Tawasul Sang Burung Pipit (The Bright Way to Freedom and Faith), salam Ahmad Raihan Hakim (Alumni SMA Muh 3 Jkt 2018).
(Rutan Salemba, 27 Oktober 2025)