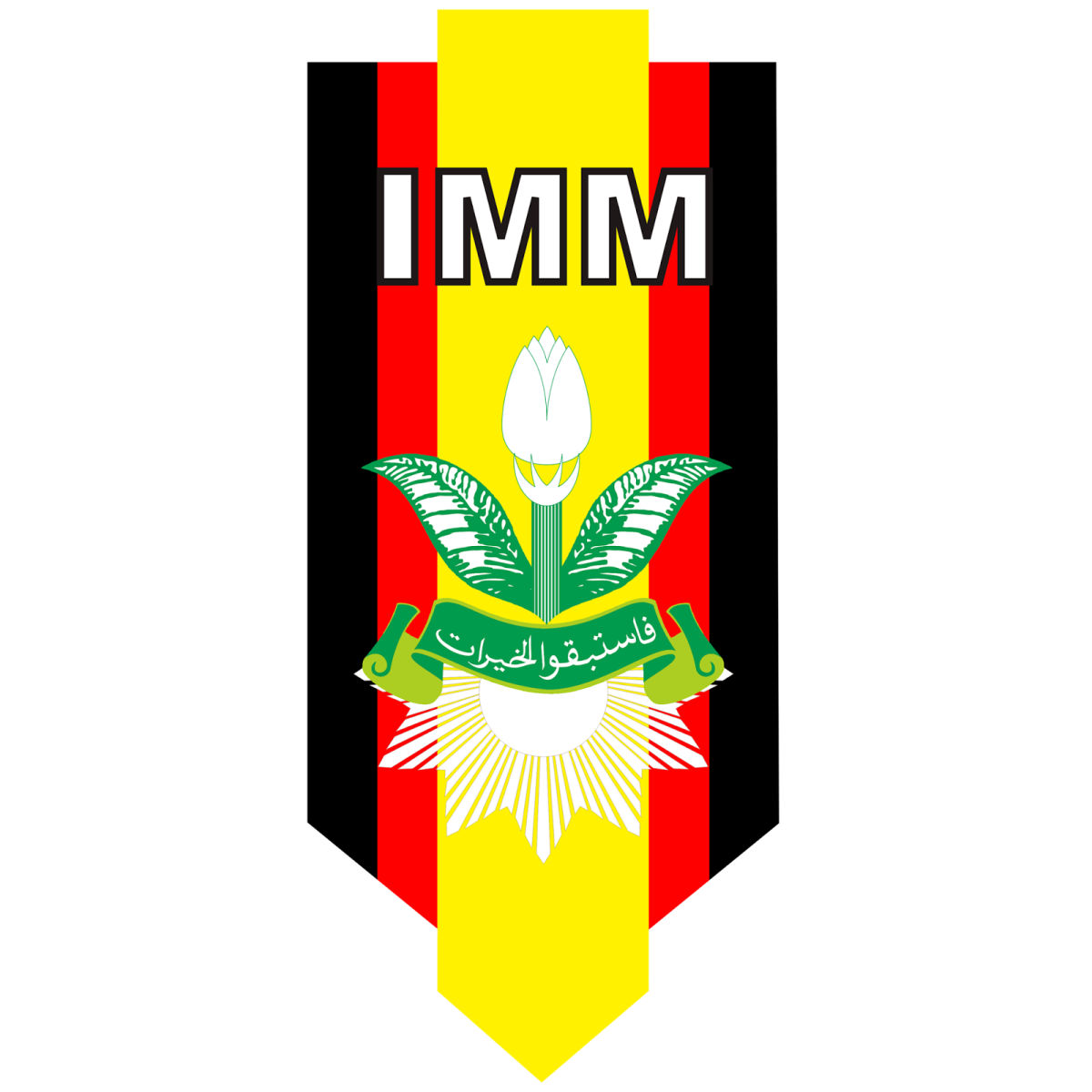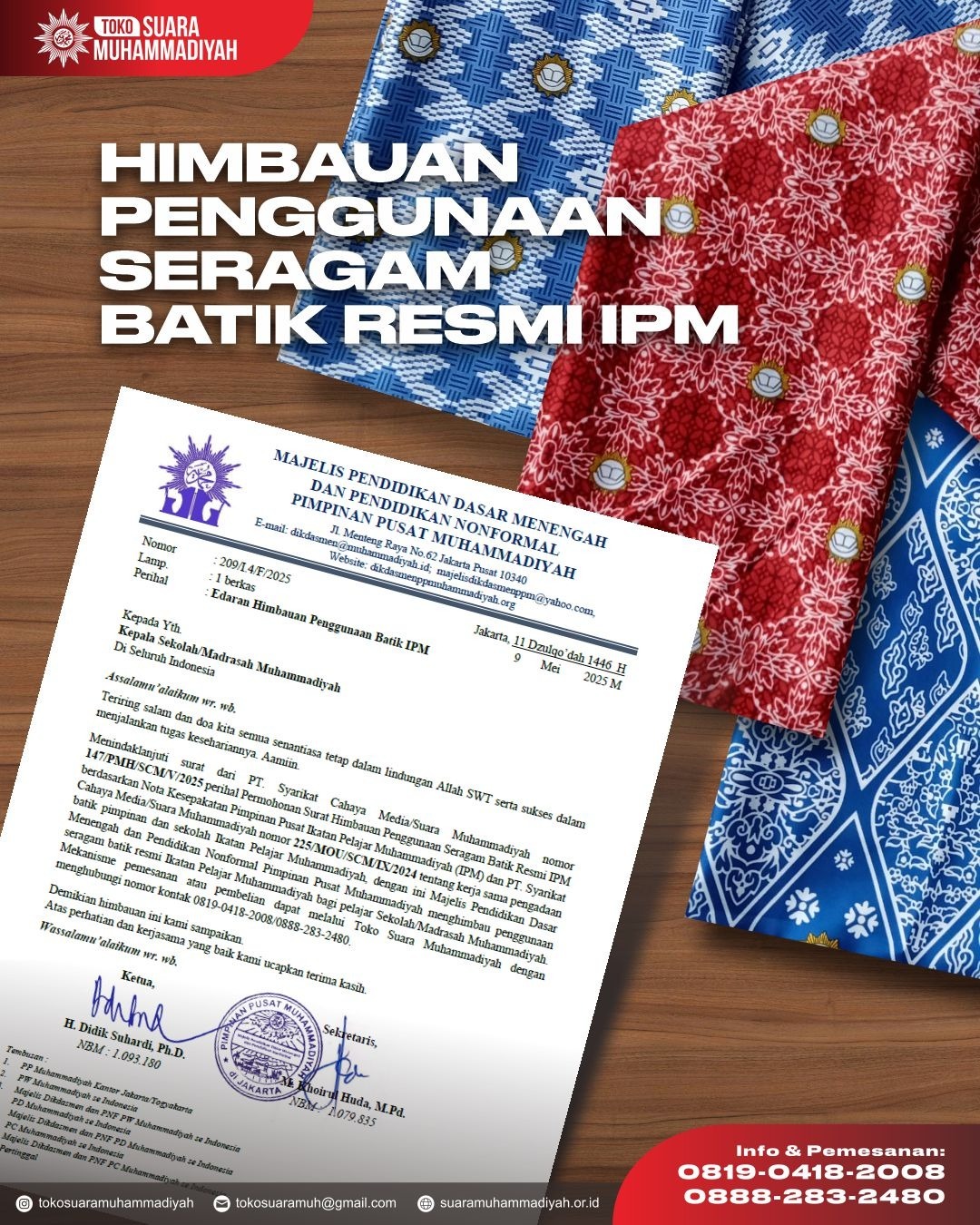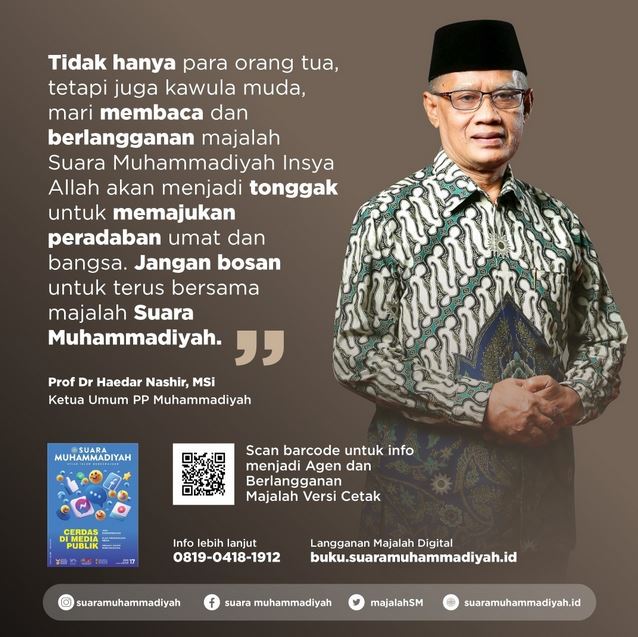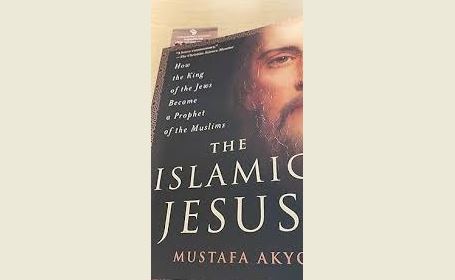Oleh: Muh Akmal Ahsan, Ketua Bidang Ristek DPP IMM
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdiri pada tahun 1964 sebagai salah satu organisasi otonom dalam lingkup Persyarikatan Muhammadiyah. Kehadirannya dimaksudkan untuk memberi ruang artikulasi bagi mahasiswa di perguruan tinggi dengan meneguhkan tiga pilar nilai: religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Namun, perjalanan sejarah IMM memperlihatkan bahwa organisasi ini tidak mungkin steril dari gelanggang politik. Mahasiswa, apa pun latar belakangnya, selalu berada dalam posisi sebagai homo politicus: makhluk politik yang menyadari keberadaannya di tengah masyarakat, berusaha merasionalisasi pengalaman hidupnya secara mandiri, dan berikhtiar untuk mengambil sikap konstruktif demi tercapainya bonum commune, atau kemaslahatan bersama (Kuncahyono, 2018). Dalam pengertian ini, IMM bukan sekadar forum pembinaan kader, melainkan juga laboratorium sosial di mana gagasan dan praksis politik mahasiswa terus diuji dan dimaknai kembali.
Dikotomi Gerakan Intelektual dan Politik
IMM, terutama setelah Reformasi, sebagaimana juga gerakan mahasiswa lain, terlihat kerap terperangkap dalam relasi yang timpang antara negara dan rakyat. Pada satu sisi, ia berusaha memosisikan diri sebagai bagian dari publik yang kritis, yang hendak menyuarakan aspirasi rakyat melalui gerakan intelektual, dakwah, dan kerja-kerja sosial. Namun, pada sisi lain, sebagian elite IMM justru mendorong organisasi ini masuk ke dalam struktur negara, melalui birokrasi, partai politik, atau parlemen, dengan keyakinan bahwa kehadiran di arena kekuasaan akan memberi nilai tawar yang lebih tinggi.
Dilema inilah yang sejak lama membayangi IMM. Sebagian kalangan menolak kehilangan basis kerakyatannya, sementara sebagian lain menganggap kehilangan bargaining power politik akan membuat IMM tidak relevan dalam percaturan nasional. Pertentangan ini merefleksikan suatu problem yang lebih mendasar: kegagalan IMM untuk merumuskan secara konsisten sebuah “jalan ketiga” yang mandiri, yakni posisi yang tidak larut dalam logika negara, namun juga tidak berhenti sekadar menjadi pengkritik tanpa kekuatan praksis.
Ketiadaan jalan ketiga itu membuat IMM mudah terseret dalam orbit negara, atau sebaliknya, terjebak dalam retorika publik yang kritis tetapi tanpa daya intervensi politik yang nyata. Pada titik ini, IMM masih menghadapi tantangan: apakah ia ingin hadir sebagai subjek politik yang otonom dengan daya refleksi kritisnya, ataukah hanya menjadi perpanjangan tangan dari logika yang sudah mapan—baik logika negara maupun logika pasar?
Faktor Struktural dan Kultural
Melemahnya visi intelektual dan politik IMM tidak semata-mata lahir dari kegagalan internal, melainkan merupakan efek samping dari belitan faktor struktural dan kultural yang memenjara organisasi ini. Pertama, dari sisi struktural, IMM kerap terlihat sebagai bagian dari desain politik dan konfigurasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Melalui kooptasi halus, penempatan kader dalam birokrasi, maupun pemberian akses politik tertentu, IMM didorong untuk lebih jinak ketimbang kritis. Situasi semacam ini membuatnya sulit tampil sebagai wakil publik yang independen. Akibatnya, orientasi membangun basis kerakyatan justru melemah. Dalam bahasa yang lebih lugas, IMM lebih sering tampil sebagai serdadu negara ketimbang serdadu rakyat.
Kedua, faktor kultural yang bersumber dari tradisi dan habitus organisasi. Dalam konteks IMM, keterlibatannya yang “latah” dalam politik mungkin merupakan efek langsung dari warisan tradisi politik adiluhung Muhammadiyah. Dari sini, IMM lebih sering dipahami hanya sebagai kekuatan moral (moral force) yang mengusung amar ma’ruf nahi munkar, tetapi jarang berhasil mengartikulasikannya dalam strategi politik yang konkret dan operasional. Dengan demikian, IMM kerap terperangkap dalam peran simbolis: memiliki suara moral, tetapi tanpa daya institusional yang memadai untuk memastikan suara itu berpengaruh dalam ranah kebijakan dan praksis politik.
Jalan Ketiga
Apa yang disebut sebagai jalan ketiga, dalam hal ini, bukanlah sikap netral apalagi pasif. Ia adalah sebuah alternatif, sebuah usaha untuk tetap hadir di tengah ketegangan antara negara yang hegemonik dan rakyat yang rapuh. Jalan ketiga berarti kesanggupan IMM untuk tidak larut dalam logika kekuasaan, tetapi juga tidak tenggelam dalam romantisme kerakyatan yang tanpa strategi.
Dalam kerangka itu, terdapat sejumlah agenda strategis yang perlu diperjuangkan IMM: pertama,IMM dituntut untuk konsisten melancarkan kritik terhadap negara, tanpa jatuh menjadi oposisi buta yang irasional. Kritik yang dimaksud bukanlah sekadar seruan moral yang reaktif, melainkan upaya sistematis untuk membongkar kebijakan negara yang menindas dan, pada saat yang sama, mengajukan alternatif yang masuk akal. Artinya, IMM perlu memosisikan dirinya tidak hanya sebagai “saksi moral” dari kebijakan publik, tetapi juga sebagai produsen gagasan politik. Bentuknya bisa berupa penyusunan policy paper, kerja advokasi, maupun mendorong hadirnya kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat. Dengan demikian, jalan ketiga tidak hanya menjadi retorika, melainkan praksis politik yang menyeimbangkan kritik moral dengan tawaran institusional yang nyata.
Kedua, IMM perlu kembali menapaki akar rumput, sebab di sanalah politik yang paling nyata sedang berlangsung. Politik bukan hanya soal kursi di parlemen atau jabatan dalam birokrasi, tetapi juga soal bagaimana petani, buruh, nelayan, dan masyarakat miskin berjuang mempertahankan hidupnya dari hari ke hari. Jika IMM sungguh ingin meneguhkan dirinya, maka ketekunan untuk hadir bersama mereka menjadi syarat utama.
Dalam kerangka itu, IMM dapat memosisikan diri sebagai intelektual organik yang tidak hanya berbicara tentang rakyat, tetapi hidup bersama rakyat dan menyatu dengan denyut perlawanan mereka. Peran seperti ini tidak cukup dijalankan dengan retorika moral, melainkan harus diwujudkan dalam praksis: advokasi yang konsisten, pendampingan hukum, penyelenggaraan sekolah alternatif, hingga penciptaan ruang-ruang sosial tempat rakyat dapat menemukan kembali martabatnya. Hanya dengan cara itu IMM bisa menghindari godaan menjadi sekadar “penonton kritis” dan sungguh-sungguh hadir sebagai bagian dari energi transformasi sosial.
Ketiga, IMM perlu mengambil peran sebagai mediator antara negara dan rakyat dalam ruang publik. Peran ini bukan perkara sederhana, sebab ia menuntut keberanian untuk berjalan di atas garis tipis antara kritik dan kolaborasi. IMM ditantang untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada negara, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga jarak kritis dari keduanya. Di satu sisi, IMM tidak boleh larut menjadi corong rezim yang sekadar mengulang retorika kekuasaan. Di sisi lain, IMM juga tidak dapat tenggelam dalam radikalisme jalanan yang mudah meledak namun jarang menghasilkan strategi. Posisi ini semakin relevan di tengah situasi media sosial yang serba centang-perenang, di mana suara rakyat kerap tereduksi menjadi riuh rendah tanpa arah.
Keempat, sebagai organisasi mahasiswa yang berbeda dengan partai politik, IMM memiliki ruang unik untuk mengartikulasikan politik nilai Muhammadiyah ke dalam praksis yang lebih konkret. Nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, demokrasi, dan Islam berkemajuan seharusnya tidak berhenti menjadi slogan, melainkan ditransformasikan menjadi pedoman dalam menilai, mengoreksi, dan mengarahkan praktik politik yang sering kali jatuh ke dalam pragmatisme, permisivitas, dan materialisme. Politik nilai ini adalah antitesis dari politik transaksional, sekaligus sebuah upaya menjaga moralitas publik di tengah politik yang kian banal.
Kelima, strategi diaspora politik. IMM tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu arena politik tertentu, melainkan perlu hadir di berbagai sektor: birokrasi, partai, parlemen, maupun masyarakat sipil. Namun kehadiran itu harus dibangun atas kesadaran bahwa politik bukanlah tujuan final, melainkan sarana untuk memperluas ruang perjuangan. Politik yang dimaksud bukan semata perebutan kursi, melainkan arena yang menentukan distribusi sumber daya, arah kebijakan, dan relasi antara negara dengan rakyat. Jika IMM menjauh dari sektor politik formal dengan alasan politik adalah sesuatu yang kotor, maka ruang itu akan segera diisi oleh kekuatan lain yang barangkali jauh lebih tidak peduli pada kepentingan rakyat. Karena itu, IMM dituntut untuk menempatkan politik sebagai arena perjuangan yang digerakkan oleh nilai moral dan intelektual, bukan sekadar sebagai ruang untuk meraih kekuasaan.