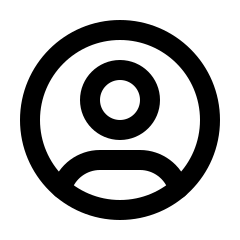Memberi Nilai Ibadah pada Dunia Kerja Kita
Oleh : M. Rifqi Rosyidi, Lc., M.Ag.,
Mudir Pondok Modern Muhammadiyah Lamongan
Dalam rangka menumbuhkan etos (suka) bekerja Rasulullah saw memberikan gambaran tentang prinsip kerja yang baik : “(1) man thalaba al-dunyâ halâlan, (2) wa ta`affufan `an al-mas’alah, (3) wa sa`yan `alâ `iyâlihi, (4) wa ta`âththufan `alâ jârihi, laqiya Allâha wa wajhuhû ka al-qamari laylata al-badri”.
Ungkapan rasulullah di atas secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang bekerja atas dasar empat prinsip tersebut; bekerja dengan cara yang halal, bekerja demi menjaga kehormatan diri dari perilaku meminta-minta, bekerja untuk mencukupi kebutuhan (memberi nafkah) keluarganya dan bekerja karena rasa kasih sayang terhadap tetangganya (untuk tidak menjadi beban bagi mereka), maka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat disamping rizki yang telah diberikan di dunia.
Dengan demikian (etos) kerja dalam Islam sesuai dengan semangat teks-teks agama tidak diletakkan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan duniawi yang bersifat materi, tetapi juga sebagai tugas suci yang mempunyai nilai ibadah atau nilai spiritual (Thalhah Hasan, 2000:183).
Mengacu kepada semangat ungkapan hadits di atas, maka sikap hidup keagamaan yang harus ditanamkan pada setiap orang adalah innerwordly asceticisme (meminjam istilah dalam doktrin Calvinisme) yaitu intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja (sunyoto, 123).
Oleh karena itu (perlu) ada beberapa kriteria dan ciri-ciri yang dijadikan ukuran kerja yang benar menurut pandangan Islam dengan mengacu kepada teks-teks agama di atas;
Pertama-tama, bekerja harus dilandasi oleh niat dan tujuan yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah: “innamâ al-a`mâlu bi al-niyyât…” artinya bahwa setiap pekerjaan (nilainya) tergantung pada niat yang dicanangkan oleh yang mengerjakannya, dan yang mengerjakan akan mendapatkan hasil (nilai) kerjanya sesuai dengan niatnya.
Dengan niat yang benar dan tujuan yang luhur, dalam arti bekerja mencari ridha Allah, maka kita telah memberi makna yang lebih kepada pekerjaan itu. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan tanpa tujuan bagaikan fatamorgana; bayang-bayang yang tiada terwujud (habâ’an mantsûran. Al-Furqân : 23), dalam arti tidak punya nilai substansial apa-apa (q.s. al-nûr:39).
Kalau setiap kerja diorientasikan kepada Allah untuk mencapai ridhanya, dengan berkeyakinan bahwa manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia kerjakan sendiri (al-Najm:36-42), maka tidak ada bentuk pekerjaan di dunia ini yang sepele, tergantung bagaimana cara seseorang memberi makna kepada kerja itu sendiri; pekerjaan harus diberi makna transenden sehingga menjadi bagian menyeluruh dari kehidupan itu sendiri (Nur Kholish Madjid,2001:471).
Langkah awal ini, akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan watak seseorang dalam bekerja, sehingga pada tataran tertentu diharapkan melahirkan suatu sikap al-îtsâr; yaitu suatu sikap dan kepribadian yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Hal ini digambarkan dalam Q.S. al-Hasyr ayat 8 dan 9 :
“(juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan(Nya) dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar (8).
Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan tel;ah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (9)”
Kedua, Al-Itqân; bahwa mengerjakan sesuatu harus dilakukan dengan ketekunan, kesungguhan, profesionalitas. “Allah melakukan (membuat) tiap-tiap sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Naml:88).
Melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang mempunyai dalâlah yang sama (al-Anbiyâ’:16, al-Dukhân:37, al-Mu’minûn:116), Allah ingin memberikan contoh konkrit dan pelajaran bagi manusia bahwa Dia (Allah) tidak pernah main-main (lâ`ibîn), berbuat sia-sia (`abatsan) dan setengah-setengah dalam bekerja menciptakan alam semesta dan isinya ini (Nur Kholish Madjid et.al., 2001:470).
Ketiga al-mujahadah, dalam arti bahwa niat yang benar harus dibarengi dengan kerja keras, optimalisasi kemampuan dan potensi yang dimiliki. “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.” (al-Anfâl : 60). Oleh karena itu paham al-Jabbâriyyah yang selama ini dituding sebagai biang keladi kemiskinan karena menimbulkan sikap menyerah pada nasib dan nerimo ing pandum, hendaknya dipahami secara lebih dalam lagi; yaitu, bahwa memang segala sesuatu sudah ditakdirkan dan kita tidak tahu takdir kita sendiri, karena itu maka masing-masing kita berusaha mendapatkan takdir tersebut.
Dari sini, rekonstruksi pemahaman terhadap taqdir tersebut dimulai dan diharapkan kemudian ada semacam keterpanggilan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang istimewa, yang bersifat mengabdi. Itulah sebetulnya yang merupakan kunci bahwa orang tidak kemudian berperilaku macam-macam, hidup lurus, jujur, bersahaja, menabung, kerja keras untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. (Dawam,1999:264).
Keempat, al-ihsân, dengan pengertian melakukan yang terbaik atau yang lebih baik lagi. Dalam ungkapan hadits al-ihsân ini didefinisikan dengan an ta`buda Allâha ka’annaka tarâhu fa in lam takun tarâhu fa innahû yarâka (sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatNya, tetapi ketika engkau tidak mampu untuk mencapai tingkatan ini dalam ibadahmu , maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu).
Ungkapan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kualitas al-ihsân mempunyai dua makna (Didin,2003;82) :
1. Ungkapan “an ta`buda Allâha ka’annaka tarâhu” mengandung semangat untuk bekerja yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Pesan yang dikandungnya antara lain agar setiap muslim mempunyai komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan.
2. dan ungkapan “fa in lam takun tarâhu fa innahû yarâka” mempunyai makna bahwa pekerjaan yang akan datang harus lebih baik secara kualitas dan kuantitas dari pekerjaan sebelumnya. Makna ini memberi pesan peningkatan yang terus-menerus dengan melakukan kontrol diri dan muhâsabah (meminjam istilah Umar bin Khaththab dalam sebuah ungkapannya; hâsibû anfusakum qabla an tuhâsabû) seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, pengalaman dan sumber daya lainnya.
Hal ini sesuai dengan semangat sebuah ayat “ittaqû Allâha waltandzur nafsun mâ qaddamat li ghadin, wattaqû Allâha inna Allâha khabîrun bimâ ta`malûn”, (Q.S. al-hasyr 18).
Kelima, al-shalâh. Di dalam al-Qur’an al-shalah sering dihadapkan berlawanan makna dengan al-fasâd (kerusakan), al-sayyi’ah (kejelekan), al-ma`ashî (kemaksiyatan) dan al-kufr (kekufuran). Tidak terlepas dari makna lughawynya, al-shalâh di sini dimaksudkan bahwa pekerjaan harus lebih mengedepankan nilai-nilai sosial yang mengandung kebaikan dan perbaikan (bermanfaat) bagi dirinya, tidak berbahaya bagi orang lain serta tidak berdampak pada pencemaran lingkungan hidup sekitar.
“man amila shâlihan min dzakarin aw untsâ wahuwa mu’min falanuhyiyannahû hayâtan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani mâ kânû ya`malûn” (al-nahl: 97).
Keenam, watak-watak luhur dan pribadi-pribadi baik yang dilahirkan dari kelima kriteria etos kerja di atas, diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental yang profesional, optimis, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi setiap tantangan hidup; “dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat allah. Sesungguhnya tiada berputus asa melainkan kaum yang kafir” (Q.S. Yûsûf : 87)