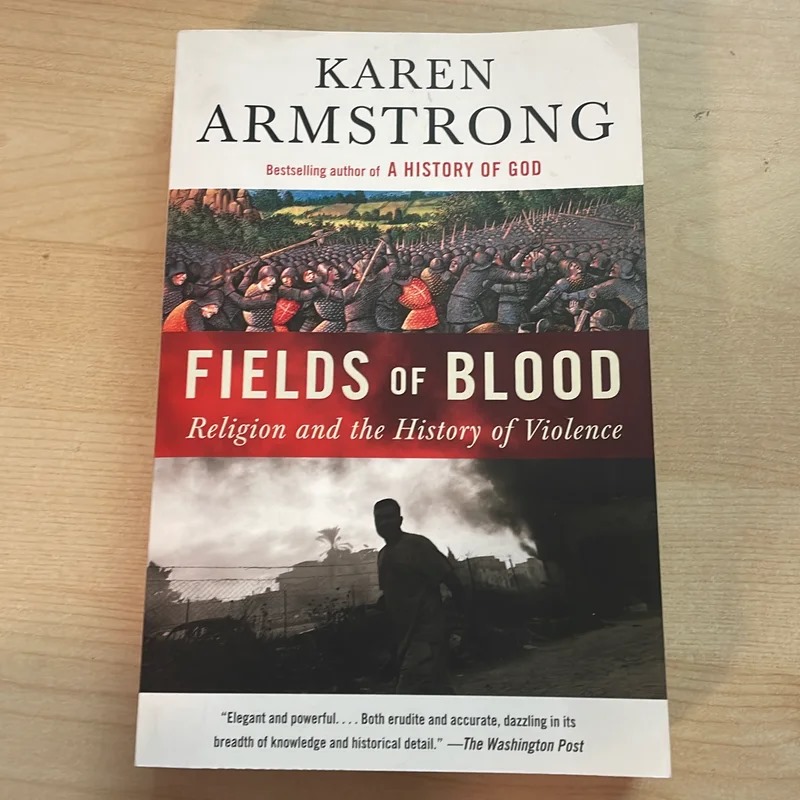Fields of Blood: Mengungkap Hakikat Kekerasan
Oleh: Donny Syofyan
Di tengah arus modernitas yang deras, kita menyaksikan fenomena menarik: religiusitas kian meredup. Gaungnya terdengar sayup-sayup, tergantikan oleh suara-suara sumbang yang mengaitkan agama, termasuk Islam, dengan kekerasan dan agresi. Benarkah agama sedemikian rupa? Karen Armstrong, dalam mahakaryanya Fields of Blood: Religion and the History of Violence (2014), mengajak kita menyelami pertanyaan ini, menelusuri lorong-lorong sejarah untuk mengungkap akar kekerasan yang sesungguhnya.
Armstrong dengan gamblang menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah anak kandung agama. Keduanya lahir dan tumbuh dalam ranah yang berbeda. Jauh sebelum agama-agama besar dunia lahir, manusia telah akrab dengan kekerasan. Naluri purba ini, menurut Armstrong, terukir dalam struktur otak kita. Ia mengibaratkan otak manusia bak piramida tiga tingkat. Di dasar piramida, bersemayam otak reptil, sang pengendali naluri primitif fight-or-flight. Inilah yang mendorong manusia untuk berburu, bahkan membunuh, demi bertahan hidup.
Naik satu tingkat, kita temukan sistem limbik, pusat empati dan kasih sayang. Di sinilah kita belajar merasakan penderitaan sesama, menumbuhkan rasa iba, dan menghindari tindakan yang menyakiti. Puncak piramida dihuni oleh neokorteks, pusat penalaran dan kesadaran diri. Menariknya, Al-Qur'an pun menyiratkan konsep serupa, menjelaskan tentang tingkatan kesadaran di mana manusia mampu melakukan introspeksi dan mengakui kesalahan. Neokorteks inilah yang memungkinkan kita untuk merenungkan tindakan, membedakan benar dan salah, serta mengendalikan naluri hewani yang bersemayam di dasar otak.
Neokorteks, sang pemikir di puncak piramida otak, memberi kita kemampuan untuk merefleksikan diri, menilai tindakan kita, dan belajar dari kesalahan. Namun, di dasar piramida, naluri purba dari otak reptil masih mengintai. Ia tak peduli agama, tak peduli moralitas. Ia adalah warisan dari nenek moyang pemburu kita, yang harus bertarung atau melarikan diri demi kelangsungan hidup. Naluri inilah yang, menurut Armstrong, mendorong manusia ke dalam pusaran konflik dan peperangan.
Bayangkan manusia purba di masa berburu dan meramu. Hidup nomaden, selalu berpindah mencari sumber makanan yang langka. Dalam dunia yang keras dan penuh ancaman, mereka bergantung satu sama lain. Setiap anggota suku memiliki peran penting, seperti sekelompok pemburu yang berani menghadapi macan bertaring tajam demi menghidupi kaumnya. Mereka adalah satu kesatuan, terikat oleh benang kelangsungan hidup bersama.
Namun, revolusi agraris mengubah segalanya. Manusia mulai menetap, bercocok tanam, dan menghasilkan lebih dari yang mereka butuhkan. Lumbung-lumbung penuh dengan biji-bijian, ternak berkeliaran di padang rumput. Kelimpahan ini, yang seharusnya menjadi berkah, justru menabur benih konflik. Perebutan sumber daya, tanah, dan kekuasaan pun tak terelakkan. Seperti kisah Cain dan Habel yang berebut perhatian Tuhan, manusia terjerumus ke dalam lingkaran setan kekerasan demi menguasai sumber daya.
Ironis, bukan? Di masa kelangkaan, manusia justru bersatu. Namun, ketika kelimpahan menyapa, mereka justru terpecah belah. Inilah paradoks sejarah manusia yang diungkap Armstrong. Konflik demi konflik, peperangan demi peperangan, sejatinya berakar pada perebutan sumber daya, yang terkadang dibungkus dengan jubah agama atau ideologi. Mungkin bukan lagi perebutan biji-bijian seperti di masa lalu, tetapi bentuknya bisa bermacam-macam: minyak, gas, mineral, atau bahkan air. Intinya tetap sama: hasrat manusia yang tak pernah puas untuk menguasai sumber daya.
Armstrong, dengan pendekatan komparatifnya yang brilian, mengajak kita menjelajahi peradaban kuno Mesopotamia, jauh sebelum era Alkitab. Di sana, terbentang dilema klasik yang dihadapi umat manusia: mengendalikan kekerasan. Di satu sisi, kedamaian adalah dambaan setiap insan. Namun di sisi lain, tanpa kekuasaan yang menjaga ketertiban, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan. Anarki merajalela, setiap individu berjuang demi diri sendiri, memperebutkan sumber daya yang terbatas.
Dalam situasi demikian, muncullah negara sebagai penjaga ketertiban. Ia bertindak layaknya wasit yang adil, menegakkan aturan, dan menghukum mereka yang menyimpang. Rakyat pun merasa aman, terbebas dari ancaman kekerasan antar sesama. Namun, seiring waktu, negara yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi monster yang menindas. Kekuasaan yang terpusat di tangan penguasa seringkali disalahgunakan untuk menumpas mereka yang berbeda pendapat, menghilangkan lawan politik, dan mempertahankan status quo. Sejarah mencatat berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh negara, dari rezim totaliter hingga otoritarianisme modern.
Di sinilah agama turun tangan, menawarkan jalan keluar dari lingkaran setan kekerasan. Agama, pada hakikatnya, adalah seruan moral untuk mengendalikan naluri hewani, menumbuhkan kesadaran diri, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis, merasakan penderitaan sesama, dan menolak segala bentuk kekerasan. Meskipun terkadang ada penafsiran agama yang menyimpang dan menghasilkan pandangan hidup yang keras, namun sejatinya agama berfungsi sebagai penenang, meredam amarah, dan membawa manusia kembali pada fitrahnya yang penuh cinta dan kasih sayang.
Jika kita menerima premis bahwa kekerasan bersumber dari persaingan memperebutkan sumber daya, bukan dari ajaran agama, lalu bagaimana kita menjelaskan fenomena kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS dan al-Qaeda yang kerap mengatasnamakan agama? Apakah Armstrong menawarkan penjelasan mengenai hal ini?
Meskipun bukunya, yang mencapai ketebalan 512 halaman dan penuh dengan riset mendalam, diterbitkan sebelum kemunculan ISIS, Armstrong menyajikan analisis yang tajam tentang al-Qaeda dan ideologi Osama bin Laden. Ia mengungkapkan bahwa di balik retorika keagamaan, terdapat motif politik dan ekonomi yang mendorong aksi-aksi kekerasan mereka. Bin Laden, misalnya, menentang penjajahan asing di tanah Muslim dan rezim otoriter yang menindas rakyat. Perjuangan mereka, meski dibalut dengan jubah agama, sejatinya adalah perjuangan politik untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan asing dan menegakkan kedaulatan bangsa.
Dengan demikian, Armstrong kembali menegaskan argumen utamanya: konflik dan kekerasan, meski sering dikaitkan dengan agama, sebenarnya berakar pada faktor-faktor non-religius. Perebutan kekuasaan, tanah, dan sumber daya alam adalah pemicu utama kekerasan, sementara agama hanyalah alat untuk memobilisasi massa dan memberikan legitimasi bagi aksi-aksi kekerasan tersebut. Agama, dalam konteks ini, lebih sering dijadikan kambing hitam atas kekerasan yang sebenarnya dipicu oleh faktor-faktor politik dan ekonomi.
Meskipun agama seringkali menjadi panji yang dikibarkan dalam berbagai konflik, Armstrong tidak menampik adanya faktor-faktor lain yang bermain. Ia mengakui bahwa agama memang memiliki peran, namun bukan sebagai akar masalah, melainkan lebih sebagai alat yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Untuk memperjelas argumennya, Armstrong mengambil contoh bom bunuh diri, sebuah taktik yang mengerikan dan dikutuk secara universal. Menariknya, ia menunjukkan bahwa pelopor teknik ini bukanlah kelompok religius, melainkan Macan Tamil, sebuah organisasi separatis di Sri Lanka yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air mereka. Hal ini menegaskan bahwa motivasi di balik kekerasan tidak selalu bersifat religius.
Lebih lanjut, Armstrong menelaah fenomena bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kecil kelompok Muslim. Ia menemukan bahwa aksi-aksi tersebut bukanlah cerminan dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Sebaliknya, tindakan ekstrem ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan yang dialami oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia, seperti konflik Palestina-Israel. Mereka merasa frustrasi karena suara mereka tidak didengar, hak-hak mereka dirampas, dan martabat mereka diinjak-injak.
Armstrong menekankan bahwa keilmuan Islam sepanjang sejarah secara konsisten mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan non-kombatan. Para ulama dan cendekiawan Muslim telah berkali-kali menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, aksi-aksi ekstrem yang dilakukan oleh segelintir individu atau kelompok tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran agama yang sebenarnya.
Bom bunuh diri dalam konteks ini bukanlah manifestasi dari fanatisme agama, melainkan jeritan keputusasaan dari mereka yang terluka dan tertindas. Mereka memilih jalan kekerasan bukan karena agama mengajarkan demikian, melainkan karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Mereka berjuang melawan ketidakadilan dengan cara yang salah, terjebak dalam lingkaran setan kekerasan yang hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan.
Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas