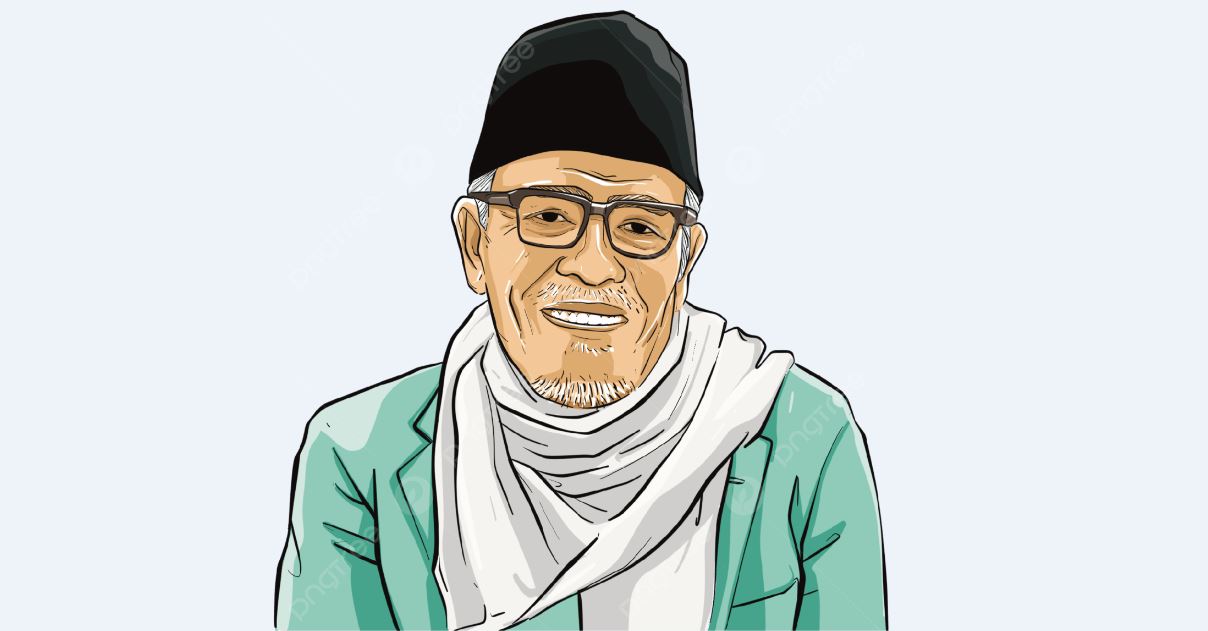Sajadah Kirman
Cerpen Ichsan Nuansa
Asyhadu al Laa Ilaaha Illallah... Suara adzan Rido meluncur ke segala penjuru, menerobos ilalang padi, melingkari telinga serangga di pepohonan, masuk ke sela-sela kayu, menembus dinding telinga semut yang asik mengambil rempah. Suara tersebut mampu memaksa keinginan memacul para petani untuk berhenti.
Masjid itu baru berumur 32 tahun berwarna dinding hijau daun kelapa muda. Beratap cetakan tanah liat matang. Keramik murahan menempel untuk menjaga keindahan. Bila dilihat dari dekat, ada mimbar yang sangat kinclong efek tiner pengrajin warga. Tidak ada ukiran di mimbar itu, warna kayu jati sumbangan Kiai Joko 20 tahun lalu menjadi warna alami.
“Allahu akbar!” Suara takbir Mbah Sastro sebagai imam menjadi tanda kekhusyukan jamaah.
Jumlah jemaah shalat Ashar ada tiga shaf untuk jamaah laki-laki sedangkan jamaah putri hanya satu shaf. Lebar masjid tidaklah besar, hanya delapan kali sembilan meter. Tanah itu wakaf Kiai Alam almarhum yang merupakan ayahanda Mbah Sastro. Desa tersebut dulunya sangat jarang orang mau mendirikan shalat berjamaah di mushala, karena tempatnya kecil dan terlihat kumuh. Tidak ada aktivitas taman kanak-kanak Al-Qur’an yang ramai, justru hanya katak-katak liar menghiasi teras mushala.
Kiai Alam merasa kacau akan pemandangan tersebut, memiliki beberapa meter kubik tanah dan didirikannya sebuah masjid dengan dana tujuh ekor sapi dan dua belas ayam kampung miliknya. Kini sejarah tersebut memiliki obat penyembuh untuk dapat diceritakan kepada anak-anak di desa tersebut yang bandel untuk shalat.
Ada tiga bocah di lapangan bertengkar karena tidak mendapatkan layangan yang dijatuhkan. Lapar menggerogoti naluri dan mencari jalan pulang meminta sedekah dari Rido. Mereka tersadar kepada kehadiran seorang lelaki paruh baya asing menunggang sepeda tua dan melewati ketiga bocah tersebut. Lelaki menghentikan perjalanan untuk menyandarkan sepedanya ke pagar masjid. Rakaat kedua sudah selesai, kekhusyukan Parmin terganggu karena terdengar suara keran yang hidup.
“Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh...” Salam terakhir membuat cepat jamaah pindah ke shaf belakang untuk berzikir. Seperti biasa Mbah Sastro terdiam bermuhasabah dengan doa-doanya. Parmin melirik melihat salah seorang jamaah yang masih melanjutkan shalat. Rido menuju teras masjid dan hendak memarahi ketiga anak yang terdengar berisik mencari dirinya.
“Heh! Shalat dulu! Sana!” tegas Rido sambil memperhatikan anak-anak berwudu.
Selang beberapa waktu setelah shalat Ashar usai Mbah Sastro mendekati Parmin yang masih duduk. Parmin turut menyadari kehadiran beliau lantas siap mendengar apa yang ingin dibicarakan Mbah Sastro.
“Gentengnya sudah diperbaiki Min?” Tanya Mbah Sastro.
“Sudah Mbah, insya Allah tidak bocor lagi. Simbah sehat?” Jawab Parmin sambil mengerutkan wajah karena mengetahui wajah orang di depannya tampak pucat.
“Yo, namanya juga orang tua. Sedikit-dikit masuk angin. Ya sudah saya pulang dulu Min.”
“Nggih Mbah, hati-hati...” semakin kerut wajah Parmin melihat Mbah Sastro pulang. Rido dan ketiga anak tersebut yang telah shalat juga turut berpamitan dengan Mbah Sastro. Mereka pergi ke sebuah warung di ujung jalan masjid.
Mbah Sastro tergelitik melihat tingkah ketiga anak tersebut. Tetapi saat matanya mengarah ke arah lain dirinya terdiam. Kali ini Mbah Sastro penasaran kenapa ada sepeda tua menempel pada pagar masjid. Seperti bernostalgia, dirinya pun meraba setang sepeda tua itu sambil berlalu pulang dengan langkah terbata-bata.
Parmin kembali ke kamar takmir. Sepertinya rasa lapar datang dan ingin memasak air untuk merebus ketela yang Ia dapatkan dari Rido. Berjalanlah ke ruang dapur sambil melirik orang asing yang masih berzikir di dalam masjid. Tetapi setelah sekian detik orang tersebut seperti hendak akan pergi.
Burung-burung kuntul berenang ke arah Timur, tanda senja ingin berpamit. Layangan dari anak-anak sudah tidak lagi menghiasi langit. Langit pun seakan galau dan tak sabar berganti petang. Di bawah atap masjid muncul cicak lapar seraya ingin melahap kupu-kupu yang sedang dibohongi cahaya lampu neon. Berbuka puasalah cicak itu. Tak terasa waktu sudah akan pada petang hari.
“Sajadah siapa ini Mas?” tanya Rido yang baru saja memasuki masjid setelah dari warung.
“Sajadah yang mana? Owalah, itu sepertinya punya salah satu jamaah tadi!” Ujar Parmin.
“Siapa ya Mas?” Rido keheranan, siapa jamaah yang dibicarakan Parmin.
“Adzan maghrib sana Le!” Pinta Parmin sambil melihat sajadah yang diambil oleh Rido. Sajadah tesebut berwana merah dan putih, bergambar kabah dan sangat lembut bahannya. Memang sudah terlihat cukup lusuh karena tak terang lagi warnanya. Parmin mengira sajadah itu sudah sering dipakai.
Setelah adzan Maghrib usai, Rido menghampiri Parmin yang masih asik menilai sajadah tersebut.
”Mas, sepertinya sajadahnya buat shalat Mbah Sastro sudah berbau... Perlu diganti...”
Parmin segera mengganti sajadah tersebut dengan sajadah lain. Tidak tahu mengapa sajadahnya berbau amis. Namun sialnya sajadah-sajadah cadangan terlalu lama disimpan di gudang. Justru yang di gudang lebih pengap dan bau lembab.
Mbah Sastro datang melihat Parmin yang berwajah kebingungan. Ketika sudah memasuki masjid kaki Mbah Sastro menampar sebuah kain. Diambilnya kain tersebut yang ternyata merupakan sajadah yang ditemui Parmin serta Rido. Mata Mbah Sastro tiba-tiba berkaca dan dengan cepat segera mencari sesuatu di suatu bagian sajadah. Tertulis nama Kirman pada sajadah itu. Tulisan tersebut tak asing, bahkan pikiran Mbah Sastro menari-nari ke masa lalu.
Tahun 1974 Mbah Sastro pergi haji bersama rombongannya. Ketika di tenda perkemahaan Sukirman melihat Mbah Sastro kelelahan karena mengalami dehidrasi. Sukirman adalah salah satu rombongan bersama Mbah Sastro yang berasal dari Bantul, memang usia waktu itu masih muda sekitar 30 tahunan dan Mbah Sastro sendirian tidak bersama keluarga ataupun kerabat di satu desa.
“Maaf Mas, Jenengan malah menemani saya...” Ungkap rasa sedih Mbah Sastro.
“Sudah, yang terpenting jenengan pulih!” Kesarehan Sukirman yang 10 tahun lebih tua tersebut membuat tenang Mbah Sastro kala itu. Dan ketika shalat di Masjidil Haram Mbah Sastro kehilangan sajadah. Sukirman memberikan sajadahnya kepada Mbah Sastro, namun sayang umur sajadah tersebut juga tak panjang, sebelum beranjak dari pesawat sajadah tersebut tertinggal entah ke mana.
Lima belas tahun setelah pertemanan mereka, Sukirman meninggal dunia akibat kecelakaan bus waktu perjalanan ke Sragen guna menemui anak perempuannya yang akan melahirkan. Sukirman terjepit di antara tiang kursi dan lantai bus. Mbah Sastro melayat dan menyalatkan jenazahnya, hanya menahan air mata yang Ia mampu untuk melihat temannya itu akan dikubur. Merasa bersalah tidak bisa bertemu dan bercengkrama untuk mengulang kenangan haji mereka.
Tiga puluh tahun berlalu dan sajadah itu tidak bisa Mbah Sastro lupakan. Meski usia kian menua, dirinya hafal betul bentuk, warna, hingga kehalusan sajadah tersebut. Tangannya bergetar karena takjub dengan pertemuan ini. Air mata yang dulunya tertahan saat pemakaman, kini keluar disertai sujud syukur. Jemaah di masjid sontak bergeliat terkesiap akan keadaan itu, Rido mengusap pundak Mbah Sastro yang tetap bersujud di tengah ruangan masjid. Sedang jemaah ibu-ibu berbisik dan bertanya kepada Parmin mengapa dan ada apa.
“Kirman...” Ucap Mbah Sastro yang tiba-tiba semakin terisak. Dirinya menemukan tulisan nama pemilik sajadah tersebut bertuliskan Kirman.•