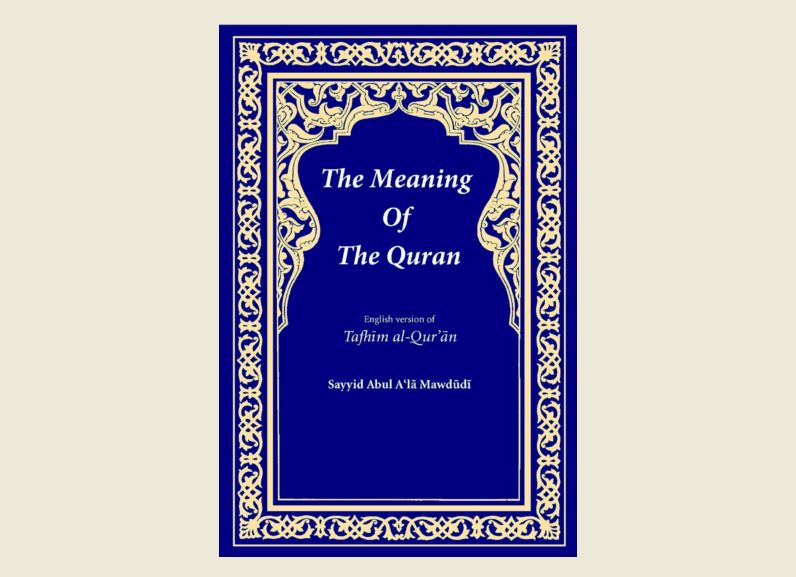Kemunculan Madzhab dan Kedudukan Hadits (Bagian ke-2)
Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Imam Abu Hanifah akan mengutamakan riwayat yang berbasiskan keilmuan. Di masa awal hadits dipahami lewat maknanya, tidak harus kata demi kata, karena siapa yang akan mengingat seluruh kata secara tepat? Bahkan untuk mengingat kata-kata yang utuh dari Al-Qur’an butuh pengulangan (muraja`ah). Tanpa mengulang-ulangnya, kita bisa saja tergelincir mencampurkannya dengan sesuatu yang lain.
Jadi bisa terjadi bahwa orang-orang mencampuadukkan periwayatan, terutama jika mereka bukan yang paham ilmu agama. Jika Nabi SAW mengatakan sesuatu dan seseorang yang memiliki kedalaman ilmu mengulanginya, kita lebih percaya bahwa orang yang berilmu ini menginformasikan kita makna yang dimaksudkan oleh Nabi dengan kata-katanya sendiri. Dia memiliki visi keilmuan untuk memahami makna di balik itu ucapan Nabi SAW sebelum dia mengutarakannya dengan kata-katanya sendiri.
Jika seseorang yang tidak punya kecakapan ilmiah mencoba mengulangi makna yang dia pahami, boleh jadi dia salah memahami. Karenanya Imam Abu Hanifah lebih memilih riwayat yang disampakan oleh orang-orang yang berbasiskan keilmuan. Dia akan menjatuhkan preferensi pada riwayat yang berasal dari orang-orang yang lebih senior alih-alih mereka yang masih muda.
Imam Bukhari pernah menyusun kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh anak-anak. Dalam kitab ini kita bisa membaca, misalnya, ada yang mengatakan bahwa ketika dia masih kecil sesuatu terjadi di hadapan Nabi. Bagi Imam Bukhari, riwayat ini sahih karena diceritakan oleh seseorang yang ada di zaman Rasulullah meskipun dia masih kecil pada saat itu. Sebaliknya, menurut Imam Abu Hanifah, riwayat ini tidak bisa digunakan. Kita harus mengambil riwayat dari orang-orang yang memiliki kecerdasan, yang bisa dipercaya bahwa mereka benar menyaksikan dan mampu memverifikasi apa yang mereka dengar. Bukan berarti Imam Abi Hanifah tidak menerima periwayatan hadits, tapi dia punya prinsip-prinsip sendiri yang mengantarkannya menerima sebagian dan membuang sebagian riwayat lainnya. Jadi kita bisa melihat ada banyak ruang untuk mengevaluasi hadits.
Sekarang kita beralih kepada Imam Malik. Dia meninggal pada tahun 179 Hijrah ketika berusia 87 tahun. Dia tinggal di Madinah. Oleh karenanya, Imam Malik menikmati keuntungan hidup di mana sejumlah besar sahabat Nabi pernah hidup. Di situlah Nabi SAW menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya, di sana beliau meninggal dan dimakamkan. Masyarakat Islam awal juga tumbuh dan berkembang di Madinah. Masyarakat paham apa yang Rasululah praktikkan.
Imam Malik menggunakannya sebagai dasar untuk mendirikan madzhabnya. Sebetulnya beliau tidak berniat mendirikannya, tetapi itu adalah prinsip-prinsipnya yang dia pegang. Imam Malik menyebutnya 'al-amr al-mujtama` `alaih `indanaa (praktik kami yang umumnya disepakati [di Madinah]). Dia berpendapat bahwa praktik-praktik masyarakat Islam di Madinah jauh lebih kokoh dan dapat diandalkan daripada riwayat yang disampaikan seseorang dari Nabi. Orang bisa saja lupa atau salah ketika meriwayatkan. Bagi Imam Malik, orang mengerti Islam lebih baik karena ia dipraktikkan di tengah masyarakat. Kita tidak perlu menerima semua yang orang katakan. Kita akan berurusan dengan apa yang ada di sini (kota Madinah), sesuatu yang sudah kita ketahui sebagai praktik-praktik keimanan terbaik. Jadi iman dulu baru hadits.
Jadi ada keseimbangan ini antara penggunaan akal di satu sisi dan penerimaan hadits di sisi lain. Begitu hadits diterima, tentu saja tidak ada alasan untuk menentangnya, sebab ia bersumber dari Nabi SAW. Beliau dibimbing oleh Allah. Maka, bila Imam Abu Hanifah menerapkan akal atau rasionalitas dalam mengevaluasi hadits, maka Imam Malik tidak mengutamakan rasio tapi lebih merujuk kepada amalan orang-orang Madinah. Lalu datanglah Imam Syafi'i, beliau wafat tahun 204 Hijriah. Pada masanya, para ulama sibuk mengumpulkan dan memilah-milah hadits, membedakan gandum dan sekam, menerima hadits yang asli, membuang hadis yang jelas-jelas palsu, dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i tumbuh di era di mana dia lebih percaya kepada hadits.
Baginya, untuk mengetahui mana hadits yang otentik tidak butuh kerja keras. Begitu kita mengetahui hadis otentik dari Nabi SAW, mengapa repot-repot mengikuti yang lain? Jika kita berbicara tentang praktik orang-orang di tempat tertentu, bisa saja mereka mengubah satu hal dalam satu tahun, dan kemudian satu hal lagi di tahun kedua, dan kemudian hal lain di tahun ketiga. Begitu banyak yang telah diubah—bersambung.