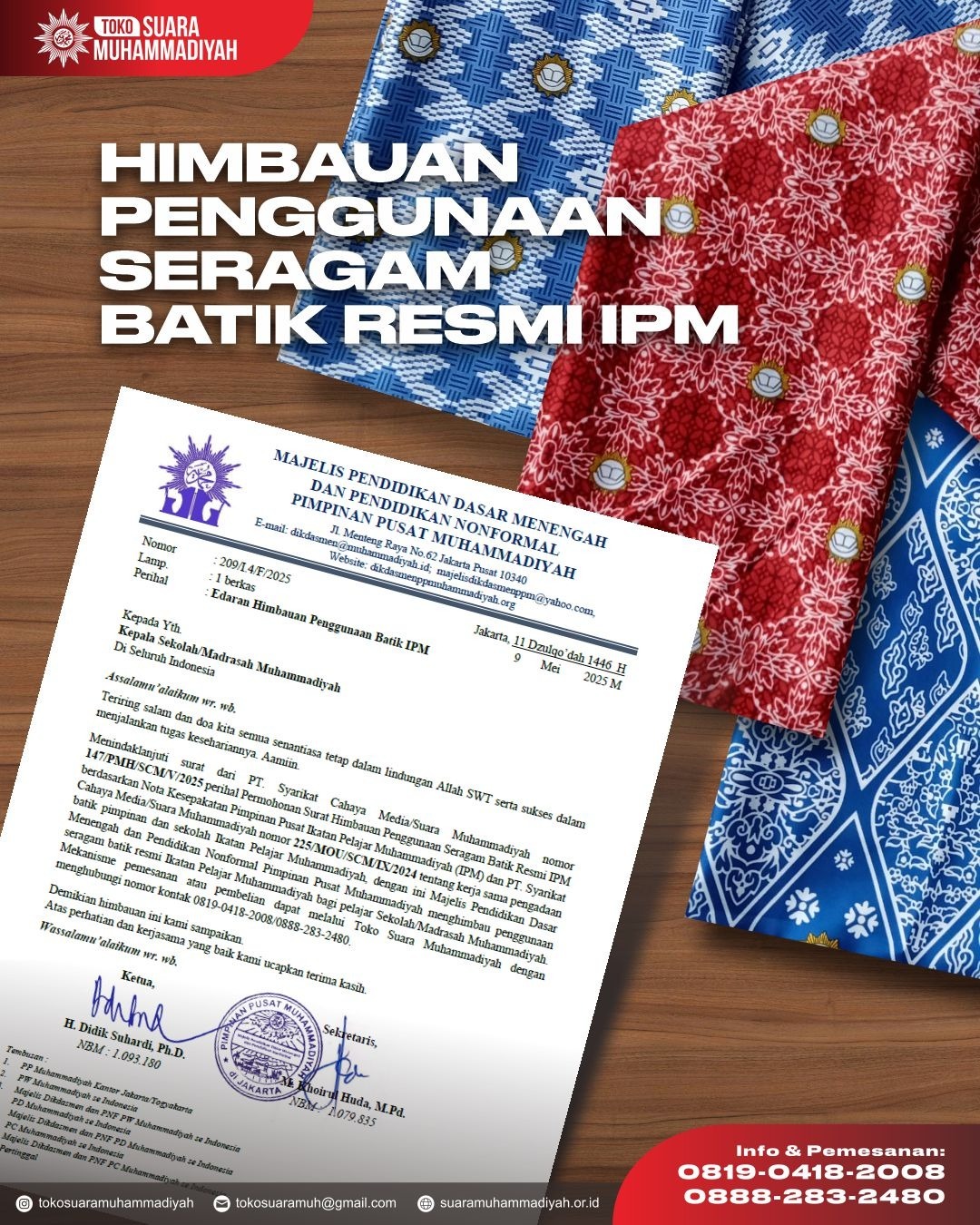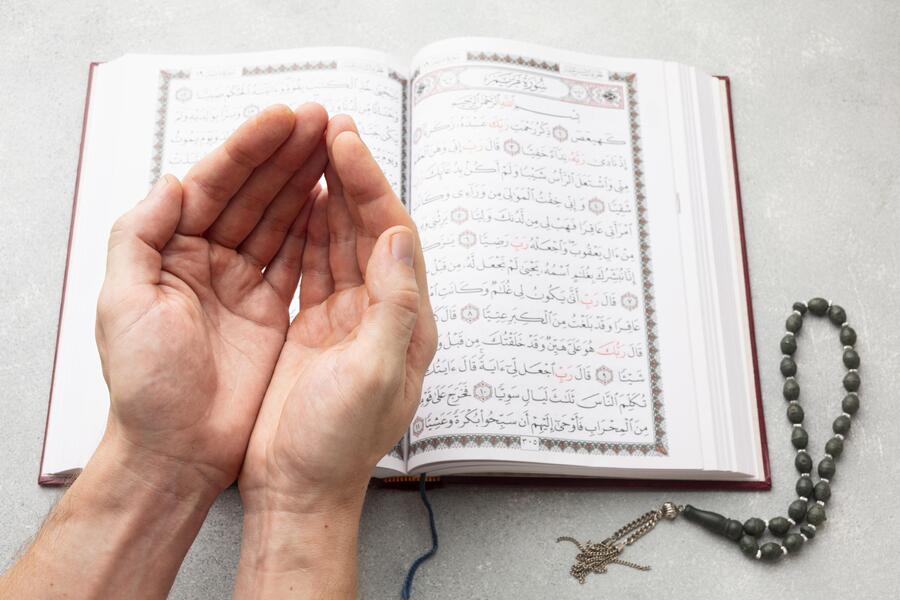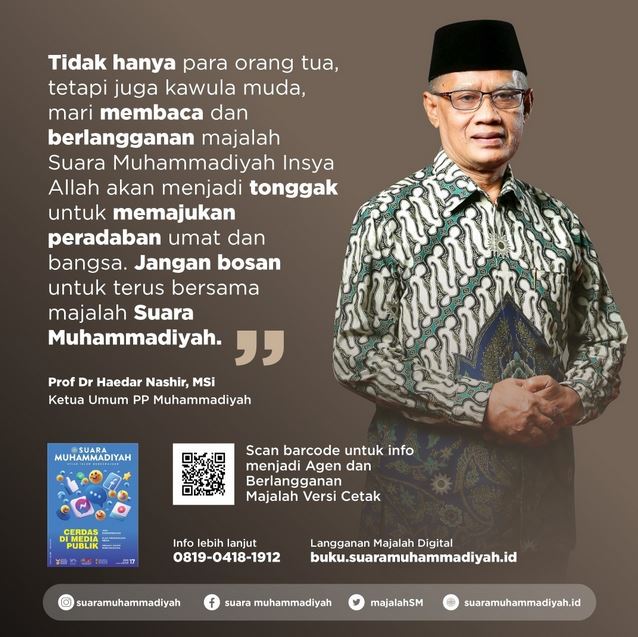Ketika Kita Semakin Lupa (Pentingnya) Membaca
Oleh: Dr Husamah, SPd, MPd, Wakil Dekan I FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, baru saja bikin gebrakan: murid SD sampai SMA akan wajib membaca buku dan menulis resensinya. Komisi X DPR menyambut dengan tepuk tangan, kebijakan ini disebut sebagai “angin segar” untuk menguatkan literasi di sekolah.
Di atas kertas, ini kelihatan seperti berita bagus. Tapi ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu: “Kalau murid diwajibkan membaca, gurunya sudah membaca belum?”
Dan kita, orang dewasa yang sibuk berdebat di media sosial soal pendidikan, terakhir kali khatam satu buku kapan?
Melek Huruf, tapi Tidak Benar-Benar “Hidup” dengan Bacaan
Data nasional menunjukkan tingkat melek huruf Indonesia pada 2025 sudah menembus sekitar 96,6–96,7%. Artinya, mayoritas warga kita bisa membaca. Masalahnya, “bisa membaca” beda jauh dengan “suka membaca”. Survei GoodStats (2025) menunjukkan hanya sekitar 20,7% responden di Indonesia yang membaca buku setiap hari. Selebihnya? Ada yang hanya seminggu sekali, sebulan sekali, sesekali saja, bahkan hampir tidak pernah.
Di sisi lain, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) nasional memang naik—dari sekitar 55-an pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024, kategori “sedang menuju baik”. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga bergerak pelan naik. Artinya, ada progres. Tapi ya itu: pelan. Sementara dunia lari.
Kita sering bangga: “Alhamdulillah, buta huruf tinggal di bawah 1%.” Tapi kalau melek huruf hanya dipakai buat baca caption, chat, dan hoaks yang lewat di grup WhatsApp keluarga, maka sama saja: kita melek huruf, tapi tidak tumbuh sebagai pembaca.
Dunia di Luar Sana Lagi Giat Baca, Bukan Cuma Scroll
Sebuah survei yang dirangkum CEOWORLD dan berbagai sumber internasional mencatat: rata-rata orang Amerika membaca sekitar 17 buku per tahun, sedangkan orang India sekitar 16 buku per tahun. Sementara itu, pasar buku global nilainya sekitar 144,67 miliar dolar AS pada 2023, dan masih diproyeksi tumbuh dengan laju sekitar 1,8% per tahun hingga 2030.
Artinya apa? Di tengah serbuan TikTok, Netflix, dan semua hal yang serba instan, dunia tetap menganggap buku sebagai barang berharga—bukan sekadar pajangan estetik di rak belakang saat Zoom meeting. Jadi ketika dunia sedang naik kelas dalam budaya baca, Indonesia masih berkutat dengan debat klasik: “Anak-anak sekarang kok susah banget disuruh baca buku, ya?”
Guru Tidak Membaca, Murid Ikut Tidak Merasa Perlu
Jujur saja: di banyak sekolah, membaca itu identik dengan tugas, bukan kesenangan. Membaca sering muncul dalam format: “Baca bab 3, nanti ada ulangan.” “Ringkas halaman 10–20, dikumpulkan besok.” Jarang sekali kita dengar: “Ini buku yang Bapak/Ibu suka banget, kalian coba baca ya, nanti kita ngobrol soal isinya.”
Padahal, literasi itu tidak bisa hanya disuruh. Ia butuh ditularkan. Beberapa pegiat literasi sudah lama mengingatkan: di sekolah, guru juga harus membaca buku dan menulis—bukan hanya menyuruh murid membaca dan menulis.
Bayangkan bedanya: (1) Versi lama. Guru: “Anak-anak, kalian wajib baca satu buku dan bikin resensi.” Murid (dalam hati): “Bu guru sendiri baca nggak, ya?” Versi baru (ideal). Guru: “Bulan ini Bapak lagi baca buku tentang petualangan ilmuwan muda. Seru banget. Kalian bebas pilih buku apa saja, nanti kita bikin Book Talk di kelas. Bapak juga bakal presentasiin satu buku.”
Saat guru membaca, murid melihat contoh. Saat guru bercerita tentang buku dengan mata berbinar, murid menangkap bahwa membaca itu bisa bikin bahagia.
Dari Wajib Baca ke Sekolah yang Lebih Manusiawi
Kebijakan mewajibkan murid membaca lalu menulis resensi datang di saat lain: Kemendikdasmen juga sedang menyiapkan aturan baru penanganan kekerasan di sekolah, yang ditargetkan berlaku mulai semester II tahun pelajaran 2025–2026 (Januari 2026).
Ada benang merah di situ. Sekolah yang sehat bukan cuma yang bebas bullying, tapi juga yang kaya bacaan. Bacaan fiksi melatih empati dan kemampuan membayangkan sudut pandang orang lain. Bacaan nonfiksi melatih berpikir kritis dan kemampuan memeriksa fakta.
Anak yang terbiasa membaca, cenderung lebih mudah diajak berdialog daripada meledak dengan kekerasan. Reading doesn’t solve everything, tapi ia menjadi fondasi penting untuk karakter dan nalar.
Kalau aturan anti-kekerasan adalah “pagar”, maka budaya baca adalah “tanah subur” tempat karakter anak tumbuh. Kita butuh dua-duanya.
Meneladani Para Tokoh: Sukses yang Dimulai dari Buku
Gramedia pernah merangkum kisah tujuh tokoh dunia yang sukses dan sangat dekat dengan buku: Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates, Oprah Winfrey, Mark Cuban, Elon Musk, dan Jeff Bezos. Mark Zuckerberg membiasakan diri membaca satu buku setiap dua minggu untuk memahami teknologi, sejarah, sampai budaya. Warren Buffett menghabiskan 5–6 jam per hari hanya untuk membaca surat kabar dan dokumen. Bill Gates membaca sekitar 50 buku per tahun—kurang lebih satu buku per minggu. Oprah Winfrey menyebut membaca sebagai “jalan menuju kebebasan” dan punya Oprah’s Book Club. Elon Musk kecil menghabiskan lebih dari 10 jam sehari membaca, terutama fiksi ilmiah; pengetahuannya soal roket bahkan banyak ia dapat dari buku. Jeff Bezos pun dikenal sebagai pembaca berat dan punya “reading list” sendiri.
Mereka ini bukan malaikat, tapi ada pola menarik: Orang-orang yang mengubah dunia, sangat jarang yang alergi buku. Kalau kita ingin Indonesia punya generasi yang bukan sekadar pengguna teknologi, tapi pencipta dan pemikir di baliknya, maka kebiasaan membaca bukanlah pilihan tambahan. Itu fondasi.
Kita Tidak Kekurangan Aturan, Kita Kekurangan Teladan
Mendikdasmen sudah memulai dengan dua langkah penting. Mewajibkan murid membaca buku dan menulis resensi. Menyiapkan regulasi baru penanganan kekerasan di sekolah.
Tapi sekencang apa pun aturan, kalau orang dewasa di sekitar anak tidak memberi teladan membaca—guru, orang tua, pejabat, tokoh publik—kebiasaan itu akan berhenti di spanduk dan hashtag.
Judul tulisan ini sengaja berbunyi, “Ketika Kita Semakin Lupa (Pentingnya) Membaca”, karena masalahnya memang bukan cuma di “mereka” (murid, generasi Z, anak sekolah), tapi di kita semua.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, “Kenapa anak-anak sekarang malas baca?”
dan mulai menggantinya dengan, “Sudahkah saya, orang dewasa, memberi contoh bahwa membaca itu penting dan menyenangkan?”
Kalau hari ini 96–97 persen warga Indonesia sudah melek huruf, langkah berikutnya adalah membuat angka itu bermakna. Bukan sekadar bisa mengeja dan menandatangani formulir, tapi betul-betul hidup bersama buku, ide, dan gagasan.
Mungkin kita tidak akan langsung menjadi Bill Gates yang membaca 50 buku setahun. Tapi kalau satu keluarga di negeri ini mau mulai dengan satu buku sebulan, satu kelas satu buku bersama, satu sekolah satu klub baca… pelan-pelan, Indonesia bisa bergerak dari “sekadar melek huruf” menuju bangsa pembaca yang berpikir.
Dan siapa tahu, dari halaman yang kita baca malam ini, lahir generasi yang kelak menulis bab baru peradaban Indonesia. (hanan)