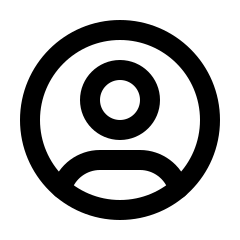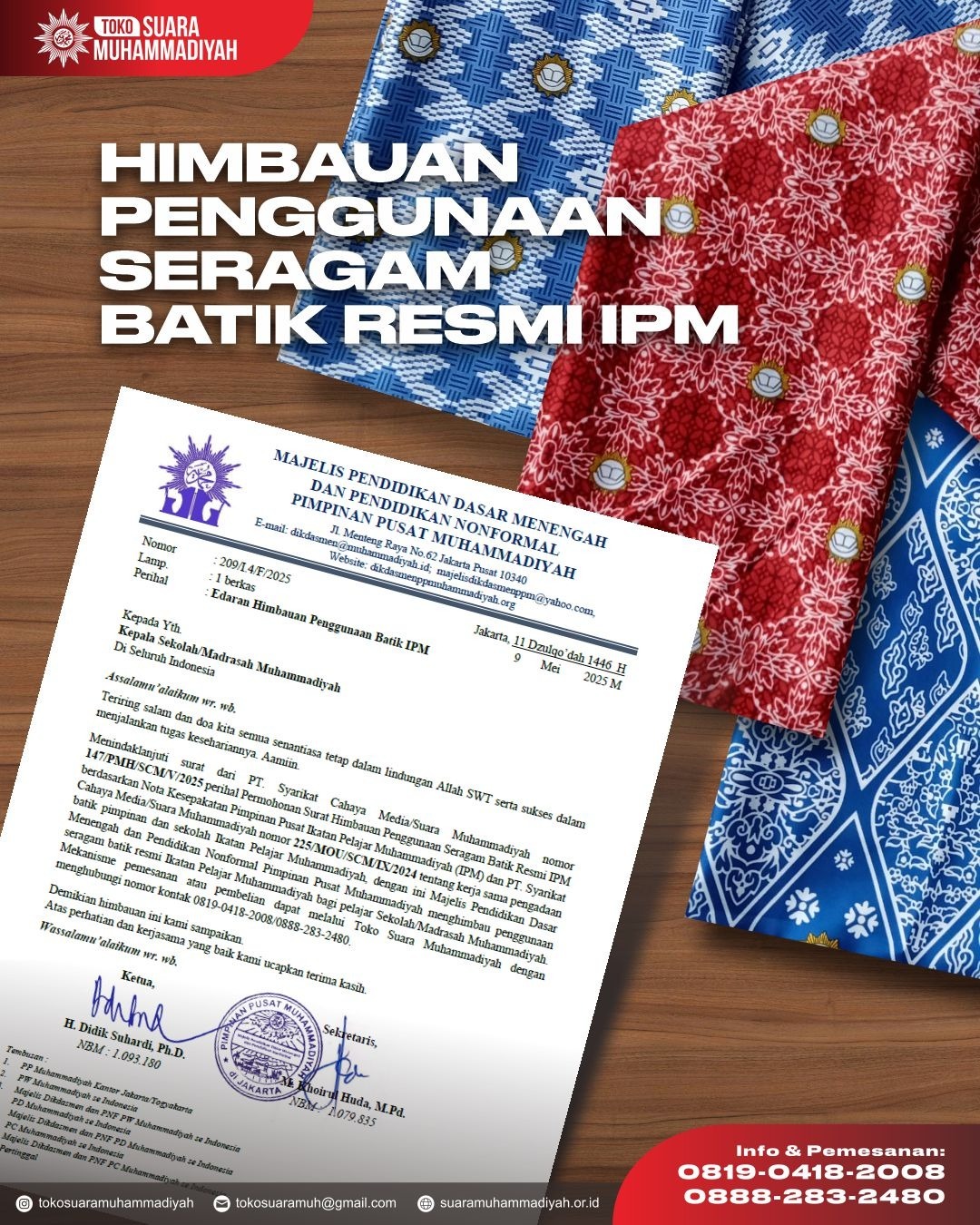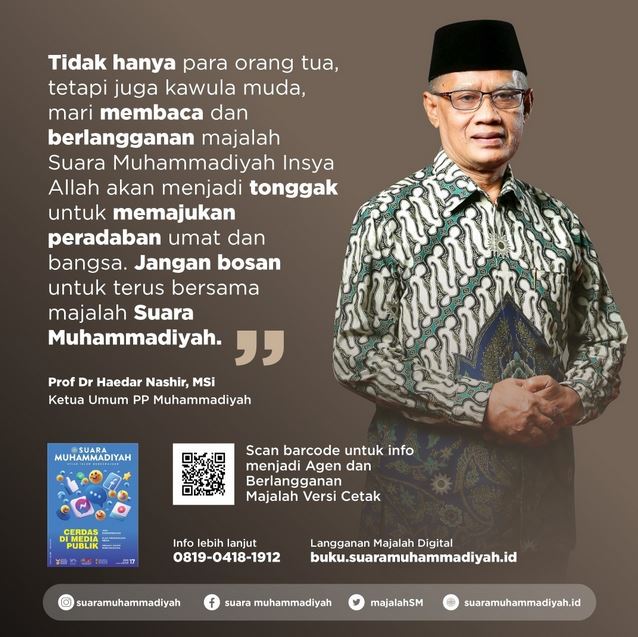Klik Cepat, Berpikir Lambat: Filsafat Terabaikan oleh Masyarakat Instan
Oleh: Riki Saputra, Pengajar Filsafat Program Doktor Studi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Beberapa minggu belakangan ini pernyataan dari salah satu influencer Ferry Irwandi mengguncang dunia maya atau cyberspace yang mengusulkan penghapusan institusi filsafat di perguruan tinggi yang menimbulkan perdebatan sengit di media sosial. Menurut Ferry, lulusan filsafat dinilai sulit bersaing di pasar kerja karena dianggap tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Ia juga berpendapat bahwa jurusan filsafat tidak lagi relevan, karena mempelajari filsafat, menurutnya, memerlukan pendekatan keilmuan yang lebih empiris dan bersifat spesialis. Pernyataan semacam ini tidak hanya menyederhanakan persoalan kompleks antara dunia pendidikan dan dunia kerja, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap fungsi dan kontribusi filsafat dalam kehidupan sosial, budaya, dan keilmuan bangsa. Pernyataan seperti ini, ketika diungkapkan oleh figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial, berpotensi membentuk opini publik secara serampangan dan memperkuat narasi utilitarianisme sempit dalam pendidikan tinggi.
Di era digital yang serba tergesa, ketika jempol lebih cepat dari akal dan notifikasi lebih sakral daripada perenungan, filsafat justru dipandang usang oleh kaum instan. Mereka ingin jawaban cepat, solusi instan, dan kesimpulan tanpa proses berpikir yang mendalam. Bagi mereka, refleksi dianggap membuang waktu, dan mempertanyakan hidup hanya memperlambat "progres". Padahal, kemajuan tanpa kedalaman adalah ilusi yang menyesatkan. Seperti mencoba menulis novel lewat tweet, atau memahami makna hidup dari potongan video lima detik. Kaum instan ini lupa, bahwa dunia yang cepat bukan alasan untuk menjadi dangkal.
Mereka menyingkirkan filsafat seolah tak relevan lagi untuk dipelajari, padahal filsafatlah yang mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kebisingan permukaan. Filsafat mengasah keberanian untuk bertanya di tengah arus jawaban yang seragam, untuk meragukan di tengah fanatisme data, dan untuk diam sejenak di tengah dunia yang tak berhenti berbicara. Ironisnya, mereka yang paling lantang mengatakan filsafat tidak lagi relevan untuk dipelajari dizaman era digital justru sering terjebak dalam dogma algoritma. Maka tak heran, klik mereka cepat tetapi pikirannya lambat, rapuh, dan mudah dibentuk serta tidak mempunyai prinsip dalam menjalani kehidupan.
Pertama, perlu diluruskan bahwa filsafat bukanlah disiplin ilmu yang secara langsung mencetak tenaga kerja teknis, melainkan ilmu yang melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Dalam filsafat, seseorang tidak hanya belajar berpikir logis dan sistematis, tetapi juga diajak untuk mempertanyakan asumsi dasar, menilai validitas argumen, serta menyelami dimensi etis, metafisik, dan epistemologis dari berbagai aspek kehidupan. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks, tidak pasti, dan penuh dilema moral. Oleh karena itu, meskipun tidak secara langsung menghasilkan “pekerja siap pakai,” filsafat justru mencetak pemikir, pengambil keputusan, dan inovator yang mampu melihat masalah secara mendalam dan menyeluruh. Perlu digarisbawahi bahwa filsafat adalah metode berpikir, bedakan filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran, banyak orang tidak suka filsafat bahkan mengakafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikiran mereka tidak melihat bahwa filsafat itu adalah sebagai alat metode berpikir. Jadi filsafat itu adalah sebuah alat dengan alat filsafat yang sama bisa membuat orang jadi anti agama dengan alat filsafat yang sama juga bisa membuat orang menjadi sangat religius.
Dan Nietche-pun pernah berdebat tentang eksistensialisme, yang satu eksistensialisme-nya religius dan yang satunya lagi eksistensialisme ateis, sama-sama berbicara eksistensialisme dalam hal ini ada yang membawa kita kepada cara berpikir lebih baik dan kritis dan ada juga membawa kita kepada cara berpikir yang keliru bahkan sesat, mungkin cara berpikir Ferry Irwandi ini bagian dari yang akan membawa kita kepada cara berpikir yang keliru. Lalau kenapa ada sebagian orang yang anti filsafat karena orang melihat filsafat sebagai produk pemikiran bukan melihat filsafat sebagai alat metode berpikir.
Kedua, realitas dunia kerja saat ini tidak sekaku yang dibayangkan. Banyak alumni filsafat yang sukses berkarier di berbagai bidang seperti media, jurnalisme, kebijakan publik, pendidikan, teknologi, bahkan sektor bisnis dan korporasi. Tokoh-tokoh besar seperti Peter Thiel (pendiri PayPal) dan Carly Fiorina (mantan CEO Hewlett-Packard) merupakan lulusan filsafat. Di Indonesia pun, banyak akademisi, cendekiawan, dan tokoh publik dengan latar belakang filsafat yang memberikan kontribusi besar dalam wacana kebangsaan dan pembangunan moral bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan filsafat memiliki fleksibilitas intelektual dan daya adaptasi yang tinggi.
Ketiga, menghapus institusi filsafat karena dianggap tidak “menguntungkan” secara dunia pasar hal ini adalah bentuk pandangan instrumentalis terhadap pendidikan. Pendidikan tinggi tidak semata-mata bertujuan mencetak pekerja, tetapi juga bertugas membentuk manusia yang utuh yang berpikir, merasa, dan bertindak secara etis. Dalam konteks demokrasi dan kehidupan berbangsa, filsafat berperan penting dalam menjaga semangat berpikir kritis terhadap kekuasaan, membangun diskursus publik yang sehat, serta membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan dimensi reflektifnya, dan masyarakat akan kehilangan perangkat untuk mengkritisi status quo.
Filsafat dalam Kehidupan Masyarakat
Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat sebenarnya telah meresap secara mendalam dalam cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan memaknai kehidupan, meski sering kali tidak disadari. Seorang petani yang merenungi musim dan kesuburan tanah, dan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih dan pertimbangan moral, bahkan seorang pemuda yang mempertanyakan arah hidupnya—semuanya itu sedang menerapkan bentuk refleksi filosofis. Ketika masyarakat berdiskusi tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, atau makna kebahagiaan, sesungguhnya mereka sedang memasuki wilayah filsafat, yakni wilayah yang mempertanyakan dan menimbang nilai-nilai dasar kehidupan. Dalam konteks demokrasi, filsafat politik hadir dalam wacana publik tentang hak rakyat, kekuasaan negara, dan etika kepemimpinan. Tanpa filsafat, para pemimpin hanya akan menjadi penguasa tanpa nurani. Bahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, filsafat moral memainkan peran ketika seseorang mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah, bukan hanya untung dan rugi. Filsafat bukan sekadar ranah akademik yang bertele-tele, melainkan napas berpikir kritis dan jernih yang membimbing manusia agar tidak terjerumus dalam kepicikan dan dogma yang menyesatkan.
Bagi mereka yang anti filsafat karena dianggap tidak praktis, para filsuf besar telah lama memberi peringatan dan refleksi yang tajam. Socrates, pernah mengatakan, “The unexamined life is not worth living”—kehidupan tanpa perenungan tidak layak dijalani. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tanpa refleksi filosofis, kehidupan manusia hanya akan berjalan secara mekanis tanpa makna. Sementara itu, Immanuel Kant menegaskan bahwa “Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan.” Artinya, filsafat melatih kebebasan berpikir secara sistematis, sebuah bekal penting dalam menghadapi dunia yang penuh manipulasi dan kepalsuan. Bertrand Russell pun mengingatkan bahwa “Nilai dari filsafat harus terutama dicari bukan pada jawaban-jawabannya, melainkan pada pertanyaan-pertanyaannya.” Di tengah arus informasi yang serba cepat dan dangkal, filsafat mengajak manusia berhenti sejenak untuk bertanya lebih mendalam tentang siapa dirinya, apa yang benar, dan ke mana ia menuju.
Kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang hari ini mengalami krisis makna dan kehampaan eksistensial, meskipun secara materi terlihat sukses. Filsafat eksistensialisme, seperti yang dikembangkan Viktor Frankl dan Nietzsche, menawarkan jalan untuk memahami tujuan hidup, menghadapi penderitaan, dan menemukan makna di tengah absurditas dunia modern. Filsafat memberi manusia kekuatan untuk bertahan hidup dalam ketidakpastian dengan memahami "mengapa" mereka hidup. Dalam tradisi Islam sendiri, Al-Farabi menegaskan bahwa filsafat adalah ilmu tertinggi karena membimbing manusia pada kebahagiaan sejati. Filsafat bukanlah menara gading yang terpisah dari kenyataan. Ia adalah cahaya reflektif yang membentuk cara berpikir yang jernih, etis, dan bermakna. Menghapus filsafat adalah sama dengan mencabut akar kebijaksanaan dari generasi masa depan.
Di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma, propaganda, dan kekuasaan tanpa nurani, filsafat menawarkan daya tahan batin dan keberanian berpikir. Ia membentuk warga yang tidak hanya patuh, tetapi juga bertanya, menimbang, dan bertanggung jawab sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan bangsa yang beradab dan bermartabat. Dengan demikian, menhapus filsafat berarti menghapus kemampuan untuk berpikir secara mendalam, kritis, dan manusiawi. Dalam masyarakat yang kerap terjebak dalam polarisasi, kekerasan simbolik, dan konsumerisme buta, filsafat hadir sebagai lentera nurani yang menuntun kita pada kebijaksanaan yang membumi.
Maka pernyataan Ferry Irwandi itu secara tidak langsung mencerminkan cara pandang pragmatis yang terlalu menekankan pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Cara pandang ini mengabaikan nilai-nilai intrinsik dalam pendidikan dan cenderung memposisikan manusia sebagai alat produksi semata. Sikap seperti ini dapat melanggengkan budaya konsumtif, anti-intelektualisme, dan menurunkan mutu diskursus publik. Terlebih lagi, menyampaikan pendapat tentang sebuah disiplin ilmu tanpa pemahaman yang mendalam atau basis data yang akurat adalah tindakan tidak bertanggung jawab, terutama bagi seseorang yang memiliki platform besar dan bisa mempengaruhi masyarakat luas. Munculnya figur-figur publik yang merasa bebas berbicara tentang segala sesuatu, tanpa memahami secara mendalam substansi permasalahan. Ini adalah gejala dari krisis otoritas keilmuan, di mana opini populer dianggap lebih sahih daripada pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui studi serius. Dalam hal ini, kita bukan hanya sedang membicarakan filsafat, tetapi juga mempertaruhkan nilai dan masa depan dunia pendidikan dan generasi masa depan kita secara keseluruhan.
Solusi dan Langkah Konstruktif
Daripada menghapus institusi filsafat, langkah yang lebih konstruktif adalah mereformulasi kurikulum filsafat agar lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Misalnya, filsafat dapat dikaitkan lebih erat dengan isu-isu kontemporer seperti etika teknologi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, keadilan sosial, hingga filsafat publik. Pendidikan filsafat juga dapat diperkaya dengan keterampilan tambahan seperti penulisan kreatif, komunikasi publik, serta berpikir desain (design thinking) agar lulusannya memiliki daya saing di dunia kerja modern. Selain itu, perlu dilakukan kampanye literasi publik untuk memperkenalkan kembali nilai dan manfaat ilmu humaniora, termasuk filsafat, kepada masyarakat luas. Universitas, media, dan tokoh intelektual perlu berperan aktif mengedukasi publik bahwa dunia pendidikan bukan semata-mata investasi ekonomi, tetapi juga pembangunan peradaban. Pemerintah pun sebaiknya mendukung keberadaan institusi filsafat sebagai bagian dari ekosistem intelektual bangsa yang sehat dan berkelanjutan.
Jika ada pernyataan atau usulan penghapusan institusi filsafat karena filsafat tidak lagi relevan. Hal itu tidak hanya mencederai martabat keilmuan, tetapi juga menunjukkan kekeliruan cara berpikir terhadap pendidikan. Filsafat bukan ilmu yang gagal ia adalah fondasi dari semua ilmu dan instrumen penting dalam membentuk generasi masa depan dan masyarakat yang adil, reflektif, dan beradab. Di tengah krisis etika, polarisasi sosial, dan kebisingan digital, kehadiran filsafat justru semakin dibutuhkan, bukan dihapuskan. Maka, alih-alih menghapus, marilah kita revitalisasi filsafat agar tetap menjadi suluh ditengah kegelapan bagi kemanusiaan dalam menghadapi zaman yang serba kabur dan penuh ambiguitas.
“Jika ada orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran karena filsafat itu yang dikejar adalah kebenaran, dan orang yang anti kebenaran katanya al-Kindi adalah orang kafir. Jika kita cermati lebih dalam, sebenarnya orang tidak akan menolak filsafat, kanapa? Orang yang suka filsafat maka dia akan menerima dan bahkan mempelajari filsafat, begitu juga dengan orang yang menolak atau tidak suka filsafat maka dia harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran argumentasinya”.