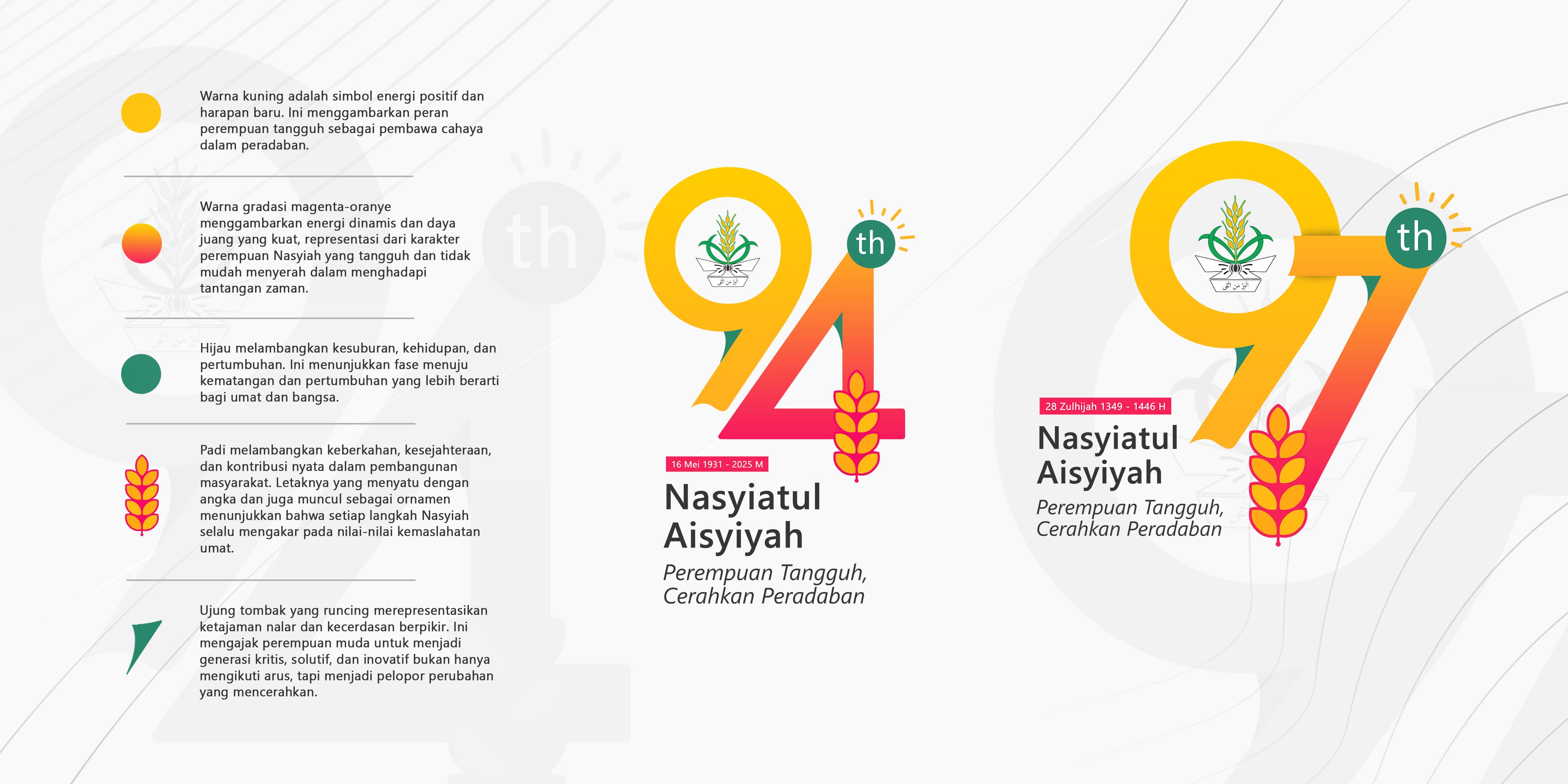Mau Boikot? Jangan Lupa Hitung Siapa yang Sebenarnya Rugi
Oleh: Rusydi Umar, Dosen S3 Informatika UAD, Anggota MPI PP Muhammadiyah (2015-2022)
Beberapa bulan terakhir, ajakan untuk memboikot berbagai merek internasional kembali ramai di media sosial. McDonald’s, Starbucks, KFC, hingga Unilever menjadi sasaran. Alasannya: dugaan keterlibatan atau dukungan tidak langsung terhadap Israel. Gelombang boikot ini kerap dikampanyekan dengan nada emosional: siapa yang membeli, dianggap mendukung penjajahan.
Namun, di tengah hiruk-pikuk seruan moral itu, kita perlu sejenak menarik napas panjang. Betulkah persoalannya sesederhana "beli berarti mendukung"? Siapa sebenarnya yang akan paling terdampak jika benar-benar dilakukan pemboikotan massal?
Di Indonesia, McDonald’s mempekerjakan sekitar 15 ribu karyawan langsung. Itu belum termasuk ribuan peternak ayam, petani sayur, pabrik roti, supir truk logistik, hingga perusahaan kemasan yang menopang operasional mereka. Satu gerai cepat saji bisa melibatkan puluhan pekerja harian, sementara pemasok lokal menggantungkan hidup pada pembelian rutin dalam skala besar.
Jika kita geser ke Unilever Indonesia (UNVR), angkanya tak kalah mengejutkan. Perusahaan ini memiliki sekitar 6 ribu karyawan langsung. Lewat program kemitraan, Unilever membina lebih dari 10 ribu petani kedelai hitam, teh, dan cabai lokal. Para petani ini bukan sekadar mitra bisnis, tetapi tulang punggung ekonomi keluarga mereka masing-masing. Ditambah ribuan warung kelontong yang menjual sabun, sampo, hingga bumbu masak, maka dampak ekonomi Unilever menyentuh jutaan orang secara berantai.
Saat narasi boikot digaungkan, tak sedikit yang berseru, "Biar saja bangkrut! Nanti akan tumbuh perusahaan lokal baru yang merekrut orang Indonesia." Sekilas terdengar heroik. Tetapi, pertanyaannya: kapan? Siapa? Dengan modal dan jaringan distribusi sebesar apa?
Sebuah perusahaan multinasional tidak dibangun dalam semalam. Butuh puluhan tahun, teknologi, jaringan pemasok yang solid, serta standar mutu yang terjaga. Jika McDonald’s atau Unilever tiba-tiba tutup, bukan hanya ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Para petani lokal akan kehabisan pembeli, pabrik roti dan saus kehilangan pesanan, sopir truk kehilangan muatan. Rantai kerugian ini bergerak cepat dan merembet ke banyak lapisan ekonomi yang kadang luput dari kesadaran publik.
Selain kerugian sosial-ekonomi, negara pun kehilangan sumber pajak besar. Unilever termasuk pembayar pajak korporasi terbesar di Indonesia. Pajak yang mereka setorkan membantu membiayai sekolah, rumah sakit, subsidi kesehatan, hingga infrastruktur. Tanpa disadari, boikot yang tidak cermat justru bisa memukul masyarakat sendiri, bukan negara atau pihak yang kita protes.
Sementara itu, narasi yang menyebut bahwa perusahaan-perusahaan ini "mengirim dana ke Israel" sering kali berdasar asumsi yang sangat lemah. Dalam struktur perusahaan terbuka (go public) seperti Unilever Indonesia, keuntungan pertama-tama digunakan untuk menggaji karyawan, membayar supplier, menutupi biaya operasional, lalu membayar pajak. Hanya jika ada laba bersih, barulah dividen dibagikan kepada pemegang saham. Pemegang saham pun adalah pihak paling akhir yang menerima sisa keuntungan, setelah semua komponen lain terpenuhi. Jadi kalaupun ada dugaan kiriman keuntungan ke Israel, porsinya super kecil. Sehingga jika Unilever rugi atau bangkrut, tidak akan berdampak pada Israel. Artinya, risiko terbesar justru ditanggung oleh masyarakat Indonesia yang bergantung pada kelangsungan bisnis sehari-hari.
Prinsip fiqh muamalah memberikan kerangka yang bijak. Islam mengajarkan bahwa segala urusan muamalah pada dasarnya mubah, kecuali jika ada dalil yang jelas dan pasti (qath’i) yang mengharamkannya. Selain itu, kaidah penting dalam fiqh menyebut: "Apabila dua mafsadah (kerusakan) bertemu, maka diambil yang lebih ringan, dan apabila mafsadah bertemu dengan maslahat (kemaslahatan), maka diambil yang maslahatnya lebih besar."
Menolak produk asing dengan alasan moral memang sah, bahkan bisa menjadi ekspresi solidaritas. Namun, jika mudarat yang dihasilkan justru lebih besar — yaitu hilangnya pekerjaan bagi rakyat kecil, matinya usaha petani lokal, dan keruntuhan ekonomi turunan — maka pilihan itu perlu dipertimbangkan ulang. Dalam konteks ini, kita tidak sedang membicarakan halal-haram semata, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan keberlanjutan hidup orang banyak.
Umat Islam diajarkan untuk berpikir jernih, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah secara proporsional. Pernah disebutkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa pada sesuatu yang dilarang, terkadang terdapat manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Di sini kita belajar pentingnya neraca pertimbangan yang tidak sekadar emosional, tetapi juga rasional dan sosial.
Kita boleh saja mendukung Palestina, bahkan wajib dalam bentuk kemanusiaan dan diplomasi. Namun, mematikan sumber nafkah petani kita, menutup lapangan kerja ribuan orang, dan memiskinkan UMKM lokal demi sekadar simbol, adalah sebuah kemudaratan nyata. Sebaliknya, kita justru bisa memperkuat solidaritas lewat jalur yang lebih konstruktif: edukasi publik, penggalangan donasi langsung, diplomasi politik, serta memperkuat lembaga-lembaga kemanusiaan resmi.
Di saat emosi kolektif memuncak, sikap rasional sering dianggap tidak populer. Namun dakwah Islam bukanlah dakwah emosi, melainkan dakwah yang mencerahkan (tanwir). Dakwah yang mengajak umat untuk berpikir jernih, tidak mudah tergiring narasi provokatif, dan tetap memelihara keberkahan ekonomi bersama.
Maka, sebelum kita meneriakkan "boikot" dengan lantang, mari kita hitung ulang: siapa yang sebenarnya rugi? Apakah benar Israel yang akan menderita? Atau justru petani cabai di Indramayu, peternak ayam di Blitar, karyawan pabrik sabun di Rungkut, hingga sopir truk yang mengangkut logistik ke berbagai kota?
Menjaga maslahat umat jauh lebih besar nilainya daripada sekadar memuaskan emosi sesaat. Karena pada akhirnya, boikot bukan sekadar soal menghentikan konsumsi, melainkan soal arah perjuangan yang benar dan bertanggung jawab. Gerakan dakwah Islam berkemajuan mengajarkan kita untuk mempertimbangkan maslahat yang lebih luas, bukan sekadar emosional. Mari terus mengedepankan rasionalitas dan keadilan demi terwujudnya masyarakat utama.