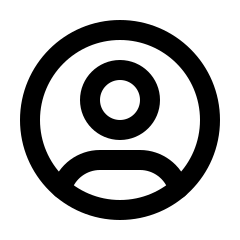NGAJI YANG MENJADI AMAL: Pelajaran dari Kesederhanaan Muhammadiyah
Oleh: Jabrohim
Di sebuah ruang pengajian kecil, di tengah kampung yang tak ramai, seorang Kyai tua membacakan Surat Al-Ma’un kepada murid-muridnya. Bukan tafsir panjang atau perdebatan istilah yang terjadi, tapi pertanyaan sederhana yang menampar: “Sudah kamu amalkan?” Itulah gaya pengajaran Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang hingga kini mengalirkan ruh kesederhanaan dalam gerak dan amal organisasi yang dibangunnya.
Satu surat, satu pertanyaan, satu dunia yang berubah. Banyak orang hari ini menganggap ilmu sebagai menara gading. Ngaji dijadikan kompetisi istilah, ajang debat tentang siapa paling benar, siapa paling lurus. Namun Muhammadiyah— dalam jejak historis dan praksis sosialnya —menawarkan wajah lain dari mengaji: sebagai laku, bukan sekadar tahu. Mengaji yang mengakar, bukan sekadar mengawang.
Surat Al-Ma’un, surat pendek yang akrab di telinga anak-anak TPA, menjadi titik mula revolusi sunyi dari Kyai Dahlan. Ia tak pindah-pindah surat, karena satu surat saja cukup jika dijadikan nyata. Dari situlah lahir panti asuhan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai amal sosial lain. Seolah Kyai Dahlan ingin berkata: “Apa gunanya tahu banyak, jika satu pun tak dijalani?”
Saya tumbuh di lingkungan yang dikelilingi orang Muhammadiyah. Mereka bukan pendebat di media sosial, bukan pengkhotbah keras, bukan pula peragu identitas. Mereka para penyusun meja kelas, para penjaga kebersihan masjid, para guru honorer yang mengajar tanpa banyak suara. Mereka orang biasa yang bekerja dalam senyap, tetapi hasil kerjanya membentuk fondasi peradaban.
Ngaji mereka sederhana, kadang hanya satu surat atau satu tema sebulan. Namun dari sana mereka bergerak: merintis klinik kesehatan, menyambangi anak jalanan, memperbaiki mushala, membebaskan lahan untuk pendidikan. Mereka tak punya waktu untuk bertengkar karena terlalu sibuk membangun.
Di sinilah saya paham, bahwa kekuatan Muhammadiyah bukan pada slogannya, melainkan pada konsistensinya. Dalam diam, mereka menanamkan nilai Al-Ma’un: keberagamaan yang berpihak pada yang lemah, beriman dengan merawat yang ditinggalkan. Di mana ada ketimpangan, di situ ada ladang amal. Di mana ada kebodohan, di situ ada ruang dakwah dengan buku dan sekolah.
Bandingkan dengan tren sebagian pengajian hari ini. Ngajinya “ndakik-ndakik” seperti kata orang Jawa—berbelit, tinggi, dan jauh dari bumi. Banyak bicara tentang akhirat, tapi lupa bahwa jalan ke akhirat itu melewati kemiskinan tetangga dan kelaparan anak yatim. Lalu kita heran mengapa pengajian ramai tapi masjid tetap kosong dari gerak, negeri tetap lemah dari sistem.
Kita terlalu banyak mengkafirkan dan menyesatkan, tapi jarang memeriksa diri: adakah satu ayat saja yang benar-benar sudah kita jadikan perbuatan? Kita lebih sibuk membenarkan posisi duduk dalam shalat daripada memastikan tetangga bisa makan sahur. Kita lebih suka memenangkan perdebatan teologis daripada mengajak orang lain memanen padi.
Padahal, jika kita mau menengok kembali semangat awal Muhammadiyah, kita akan menjumpai keindahan Islam yang membumi: Islam yang membangun bukan menjatuhkan, yang mengajak bukan mengejek, yang mendidik bukan mencaci.
Kyai Dahlan tahu, zaman terus berubah. Maka pengajian bukan hanya tempat mencari pahala, tetapi peta jalan bagi pembaruan sosial. Muhammadiyah menginstitusikan ngaji menjadi gerakan: ada struktur, ada tujuan, ada kerja nyata. Di sinilah letak kekuatannya yang jarang disadari.
Saat orang lain berhenti pada seruan, Muhammadiyah bergerak pada pelayanan. Saat yang lain bicara tentang umat, Muhammadiyah membentuk institusi yang menghidupi umat. Sekolah, rumah sakit, universitas, bahkan ambulans gratis dan respon bencana—semuanya lahir dari semangat ngaji yang diamalkan.
Sikap seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh kesadaran mendalam bahwa agama bukan identitas yang ditampilkan, melainkan jalan yang dijalani. Kesederhanaan dalam berpikir dan bertindak menjadi kekuatan tersembunyi yang membuat Muhammadiyah terus relevan. Bukan karena sensasi, tetapi karena kontribusi.
Saya kira, inilah tantangan kita hari ini: mengembalikan ruh kesederhanaan dalam mengaji. Kita tak butuh lebih banyak ustadz viral, tapi lebih banyak guru TK Islam yang sabar mendidik. Kita tak butuh lebih banyak debat sunnah-bid’ah, tapi lebih banyak relawan yang hadir saat banjir datang. Kita tak butuh lebih banyak hafalan, tapi lebih banyak perwujudan nilai-nilai dalam tindakan.
Apa artinya ilmu jika tidak menjadi jalan pengabdian? Apa arti dakwah jika tidak menjadi jembatan kasih? Apa guna mengaji jika hanya menjadi senjata menyerang sesama?
Muhammadiyah, dalam diam dan konsistensinya, menjawab semua itu dengan tindakan. Tanpa banyak bicara, mereka membangun. Tanpa harus tampil, mereka hadir. Tanpa merasa paling benar, mereka menjadi yang paling bermanfaat.
Mengkaji dan mengamalkan surat Al-Ma’un bukan sekadar penghormatan pada satu surat Al-Qur’an. Ia adalah pengingat bahwa ajaran yang benar itu cukup satu ayat, jika satu ayat itu membuat kita bergerak. Cukuplah kita menjadi orang Muhammadiyah dalam semangat—sederhana dalam ngaji, besar dalam amal.
Karena pada akhirnya, bukan banyaknya ayat yang akan ditanya di akhirat. Tapi: sudahkah kamu amalkan?