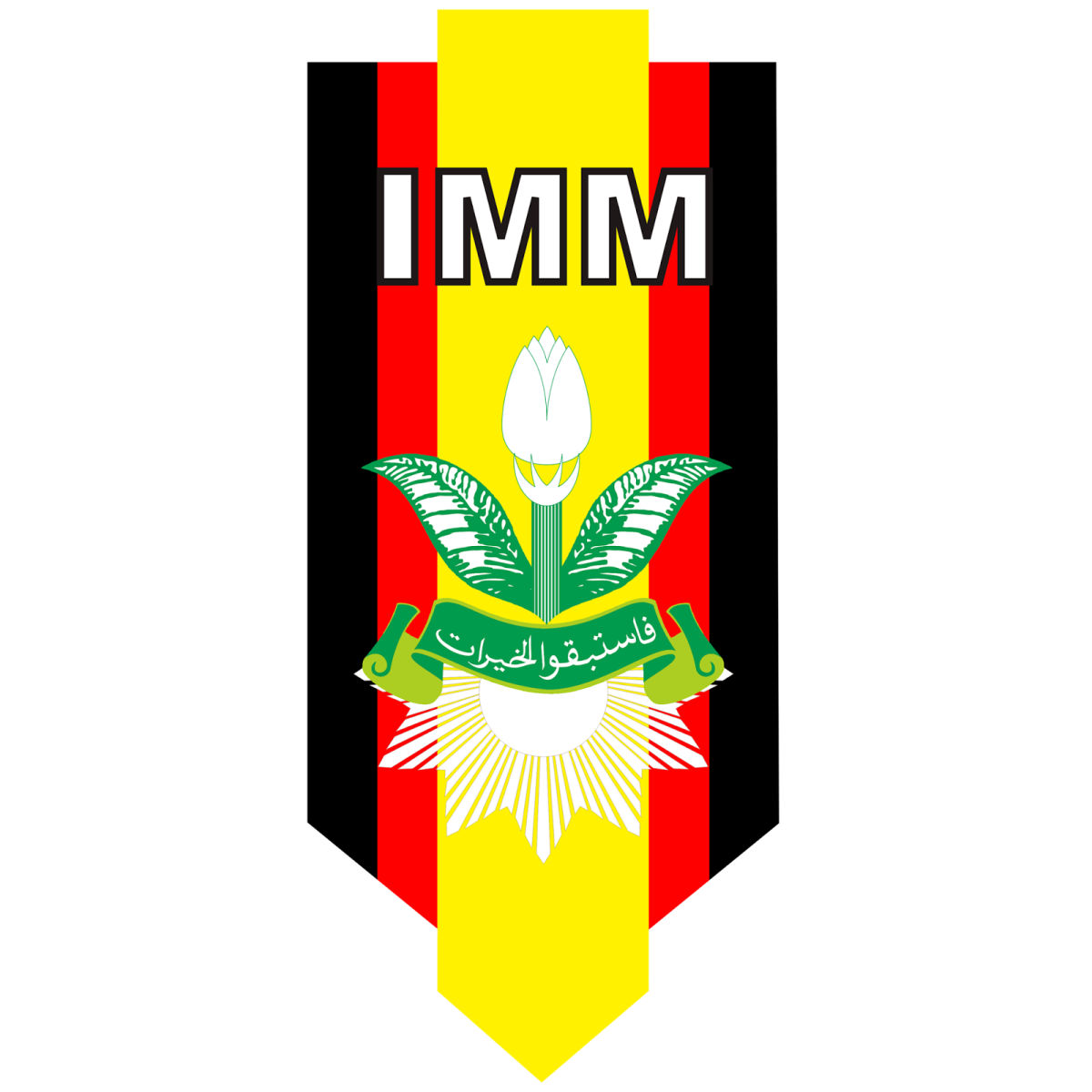Persentase Muslim Shalat dan Perkembangan Islam di Indonesia: Plus atau Minus?
Oleh: Ahwan Fanani, Sekretaris MTT PWM Jateng, Guru Besar UIN Walisongo Semarang
Beberapa bulan lalu orang meributkan persentase muslim di Indonesia yang mengerjakan shalat fardhu lima waktu. Ahad kemarin saat dan selesai acara pengajian di masjid, ada jamaah yang mengungkapkan baik kesetujuan atau penolakan terhadap kesimpulan penelitian di atas. Kesimpulan tersebut bersumber pada Moslem Report yang dikeluarkan oleh Avara Research pada tahun 2019.
Kesimpulan penelitian tersebut adalah persentase muslim yang mengerjakan shalat hanyalah 38,9%. Persentase tersebut menjadi high-light dari kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dan diviralkan sebagai kondisi memprihatinkan. Mungkin niatnya baik, agar muslim punya kesadaran akan shalat, tetapi penggambaran itu juga kurang fair.
Kesimpulan pembacaan data demikian menimbulkan distorsi yang serius. Menurut survei tersebut ada 2% umat Islam yang selalu mengerjakan shalat Lima waktu berjamaah, 7,7% yang mengerjakan shalat Lima waktu sering berjamaah, 29,2% menunaikan shalat Lima waktu terkadang berjamaah, 33,8% sering melaksanakan shalat Lima waktu, 26,8% kadang melakukan shalat Lima waktu, dan hanya 0,4% tidak pernah menjalankan shalat. Jika data itu dibaca seharusnya berbunyi 99,6% muslim di Indonesia mengerjakan shalat Lima waktu, bukan 38,9%. Dan hanya 0,4% yang tidak pernah menjalankan shalat.
Memang dari data di atas, muslim yang menyatakan diri selalu mengerjakan shalat dan terkadang atau selalu melakukannya secara jamaah mencapai persentase 38,9%. Tetapi jika memasukkan data muslim yang sering mengerjakan shalat 5 waktu maka angka muslim yang menjalankan shalat dalam kategori selalu dan sering mencapai 72,7%. Persentase ini cukup tinggi jika melihat secara flashback kondisi umat Islam di Indonesia beberapa puluh tahun lalu.
Pada akhir tahun 1950-an, Clifford Geertz membagi muslim di Jawa ke dalam tiga kategori yaitu santri, priyayi, dan abangan. Santri adalah muslim yang menjalankan syariat Islam, seperti shalat fardhu 5 waktu, shalat Jumat dan puasa Ramadhan.
Abangan lebih fokus pada ritus-ritus Jawa. Sedangkan priyayi lebih menekankan aspek filosofis dengan pengaruh filsafat Hinduisme maupun mistik Islam.
Meski penelitian Geertz dilakukan di Jawa, khususnya Jawa Timur, tetapi fenomena muslim terbagi atas yang saleh dan yang tidak menjalankan syariat dasar itu sebenarnya berlaku secara luas di Indonesia. Di berbagai wilayah, selalu ada kelompok muslim yang rajin menjalankan shalat 5 waktu dan ada yang tidak atau jarang mengerjakan.
Orang kadang mengacu pada klaim bahwa jumlah muslim di Indonesia adalah 90% pada sekitar zaman kemerdekaan. Namun persentase tersebut tentu lebih bersifat klaim, dengan tanpa mempertimbangkan kualitas keagamaan. Bagaimanapun, di wilayah kerajaan Islam, ambil contoh di kerajaan Islam Mataram Jawa, hampir seluruh rakyatnya mengidentifikasi diri sebagai muslim, meski tidak pernah menjalankan ibadah shalat, karena mengikuti Raja.
Tetapi persentase itu tidak menggambarkan keislaman nyata dari penduduk yang mengaku beragama Islam. Perkembangan agama lain mungkin mempengaruhi persentase umat Islam, tetapi tidak berarti mempengaruhi kualitasnya. Ambil contoh, saat misionaris mulai memasuki wilayah kerajaan Islam di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, muncul pula respon dari kalangan muslim, bahkan yang termasuk tidak saleh. Berdirinya Muhammadiyah dan dukungan dari para priyayi Budi Utomo terhadapnya punya kaitan tertentu dengan perkembangan aktivitas misionaris di wilayah Selatan Jawa tersebut.
Sebenarnya sejak masa Orde Baru telah terjadi perubahan besar dalam pola keberagamaan di Indonesia. Dahulu persentase terbesar umat Islam adalah abangan atau muslim yang tidak rajin menjalankan kewajiban shalat dan puasa. Namun sejak runtuhnya PKI dan kewajiban pembelajaran agama di sekolah-sekolah maka dengan sendirinya persentase abangan menurun. Saat ini di berbagai wilayah desa, pemilahan santri dan abangan semakin berkurang di masyarakat.
Terlebih pada tahun 1990-an, Pemerintah Orba mulai menunjukkan dukungan terhadap keagamaan Islam, seperti banyak pejabat masuk ICMI, Presiden Soeharto semakin Islami, dukungan terhadap pembangunan masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pengiriman da'i ke wilayah transmigrasi, dan pendirian Bank Muamalat dengan dukungan Presiden.
Bersamaan dengan tren tersebut, jilbab semakin marak dikenakan kaum muslimah, masjid-masjid berdiri di kampung-kampung dan kantor pemerintahan, masjid-masjid kampus semakin marak kegiatan keislamannya. Pada paruh akhir tahun 1990-an, simbol keislaman semakin marak muncul di televisi maupun lembaga pemerintahan. Warga mulai melakukan shalat di mall-mall, di mushola yang disediakan pengelola mall.
Mulai ada acara menjelang sahur dan berbuka di televisi, penyiar membuka berita dengan Assalamualaikum, dan kesenian Islam berkembang, seperti nasyid dan lagu Islami. Kelas menengah yang sebelumnya diwarnai oleh kultur priyayi semakin bergeser kepada penemuan kembali kesalehan dan simbol keislaman sebagai lambang kemapanan.
Pada awal era Reformasi, pendidikan agama semakin diakui dengan pengakuan terhadap MI/MTs dan MA di UU Sisdiknas. Alumni madrasah bisa mendaftar di perguruan tinggi umum tanpa harus ikut ujian nasional di sekolah menengah umum. Pesantren semakin dikenal berkat sinetron-sinetron bertema pesantren. Belakangan, sekolah-sekolah Islam semakin naik gengsinya, utamanya sejak muncul trend Sekolah Islam Terpadu, yang mendorong penguatan branding sekolah Islam.
Orang kadang tanpa melihat perkembangan dakwah Islam membandingkan bahwa persentase muslim di Indonesia sekarang hanya 85% saja, turun dari 90%. Namun, orang lupa bahwa persentase 90% itu mungkin lebih besar diisi oleh muslim yang tidak menjalankan shalat. Sementara itu, persentase 85% pada tahun 1990-an itu berkembang menjadi 87,2% pada tahun 2024 atau bertambah sekitar 2,2%. Pertambahan persentase itu tampak kecil tapi jika dikonversi menjadi angka bisa mencapai 4.000.000 orang.
Kultur Islam juga semakin kuat membentuk peri kehidupan masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini bahkan pemeluk agama lain terekam melakukan ibadah dengan berpakaian ala Islam, berkopiah dan berjilbab, bahkan menggunakan mukena. Hal itu dilakukan karena begitu kuatnya simbol kultural Islam mengakar di Indonesia.
Bahkan untuk urusan klenik, seperti dalam Primbon Betaljemur Adammakna terdapat simbol-simbol keislaman. Dalam kesenian Jawa, yaitu macapat, ada sosok agamawan yang dianggap sebagai penggubahnya. Hingga dalam pengobatan "suwuk" atau pengobatan ala mantra pun akan selalu ditemui ungkapan "semua karena Allah Taala" atau ucapan "bismillah" sebagai permulaan.
Keterhambatan missi di kalangan non-muslim adalah kesulitan mereka untuk menembus simbol-simbol kultural Islam yang kuat di masyarakat. Apalagi, awal perkembangan missi mereka berangkat dari kalangan elit atau priyayi yang dekat dengan pendidikan Barat.
Sebaliknya, Islam sejak dulu justru mewakili agama rakyat kebanyakan hingga agama para raja lokal. Hal itu sudah menjadi pemikiran di kalangan elit agama lain sehingga ada upaya untuk menggunakan tembang Jawa hingga simbol budaya sebagai sarana liturgi.
Oleh karena itu, ketika jilbab seolah menjadi simbol Islam, padahal orang-orang non-muslim di Timur Tengah maupun Eropa sejak dulu sudah biasa mengenakan jilbab maka timbullah pemikiran untuk turut merebut simbol jilbab agar tidak diklaim sepihak oleh umat Islam. Hal itu juga dilakukan agar pengikut agama tersebut lebih tampak familier dan tidak mengalami perasaan terasingkan dalam perhubungan sosial di berbagai wilayah se Indonesia, yang sangat kuat kultur Islamnya.