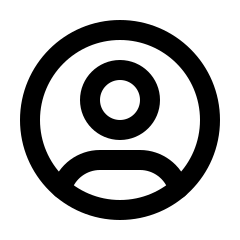Cerpen Diko Ahmad Riza Primadi
Titik dan detik paling aman dunia adalah ketika matahari terbenam. Setelah hujan menghantam aspal kering di musim kemarau. Aura kehidupan kembali menggeliat ketika uap-uap mengepul dan kemudian melayang menembus mukosa, permukaan hidung bagian dalam. Merangsang ingatan tentang orang-orang yang dipinggirkan kemajuan, dilupakan kemapanan dan kemudian dibuang ke lumpur hidup kemelaratan.
Dari posisi waktu dan tempat terjauh itu. Aku pernah duduk di atas tumpukan jerami yang terikat kuat di sadel belakang sepeda unta milik petani miskin. Kronologinya bermula saat petani itu datang dari belakang. Menyusul dan menghampriku. Memungutku tanpa izin. Menaikkan tubuhku di atas tupukan jerami dengan tinggi sekitar satu meter. Mungkin karena aku masih anak kecil yang tak memiliki hak untuk menentukan keputusan penting atau pun remeh dalam hidup. Karena alasan itulah ia berani membawaku tanpa izin dan sepengetahuan ibuku.
Belum selesai helaan nafas pertama setelah berada di atas tumpukan jerami. Petani itu langsung bertanya alamat rumahku. Nama ibuku dan tentang pekerjaan ayahku. Lucunya tak satu pun pertanyaan bisa ku jawab dengan kata-kata. Aku hanya bisa menunjuk dengan jari telunjuk arah rumahku. Dan kemudian petani itu menuntun sepedanya untuk mengantarku pulang. Melawati jalan bebatuan yang dihimpit area persawahan. Air mengalir, angin berhembus tenang. Rasanya seperti terbang di atas lautan.
Di sepanjang perjalanan pulang aku belum dihinggapi perasaan ingin membalas budi. Mungkin karena saat itu aku masih anak ingusan yang selalu menangis jika tidak dibelikan mainan, menggerutu jika tidak dituruti kemauan. Egois. Meski begitu, hal terpenting yang aku sadari saat dewasa bahwa duduk di atas tumpukan jerami yang terikat kuat di sadel belakang sepeda petani itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, menentramkan dan mengagumkan.
Di dalam hati aku berani mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan momentum paling langka di dunia. Bisa disamakan dengan peristiwa alam komet Halley yang terlihat dari bumi setiap 76 tahun sekali. Mungkin hanya satu berbanding satu juta anak yang mujur merasakan momentum langka seperti ini.
Aku hanya bisa menerka-nerka, mungkin petani itu tak tega melihatku berjalan kaki di atas jalan bebatuan agak terjal. Jika mengingat masa-masa itu, aku mulai menggerutu pada diriku. Agak menyesal. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Banyak hal yang telah ku lewatkan. “Dulu aku adalah anak yang tak tahu diri dan tidak tahu berterimakasih.”
Penyesalan tetap ada namun perasaanku sekarang berbeda. Aku selalu merasa berutang budi ketika ada seseorang yang tak lebih baik nasibnya dariku justru datang membantuku. Menawarkan bantuan tenaga, pikiran atau fasilitas miliknya. Besar atau kecil bagiku bukan masalah. Di mataku mereka adalah orang-orang baik. Di banyak kasus, kebaikan selalu datang dari mereka yang secara materi tak memiliki apa-apa.
“Pernahkah kau mencoba mengingat orang-orang yang pernah menolongmu tapi kau sendiri tak mengenalinya?” tanyaku kepada angin yang berhempus menerpa tubuh di tepian sungai. “Aku sering kawan. Jika kau pernah mengalaminya, kita sama” jawakbku dalam hati.
Aku coba mengingat dengan jelas wajah-wajah orang baik. Khususnya petani yang mengatarku pulang 20 tahun silam. Namun banyak variabel telah hilang dari ingatan. Mungkin karena pertemuan yang tak disengaja. Dan karena kelalaian mengacuhkan sesuatu yang sangat penting seperti nama, tempat tinggal dan nomor handphone jika ada. Dampak tindakan kebetulan di luar kehendak pribadi biasanya bisa lebih besar daripada tindakan yang dilakukan secara sengaja. Itulah yang terjadi kepadaku. Dan jika dicari sekarang, fisiknya mungkin sudah sangat sulit dikenali karena efek penuaan yang terjadi pada setiap manusia.
Aku ingin mencarinya walau sampai ke ujung dunia. Oleh karenanya aku memilih masuk jurusan matematika. Tidak salah lagi. Untuk mencari rumus ke masa lalu. Karena ku dengar angka bisa membuat manusia berpergian ke mana saja. Membentuk lorong waktu. Para ilmuwan terus menelitinya. Mencari jawaban pastinya. Bagi para ilmuwan, waktu yang di dalamnya mengandung kumpulan detik-detik umpama garis yang tersusun dari banyak titik yang ingin mereka lipat dan putar-putar. Atau lorong, yang dapat melemparkan manusia dari masa ke masa, maju atau mundur.
“Ya, kuncinya ada pada kecepatan kawan. Aku bayangkan seperti sebuah lorong berkecepatan tinggi yang bisa mengantar manusia ke mana saja,” kataku dalam hati berdasar kesimpulan dari film-film action yang pernah aku tonton. Membiarkan pikiran melayang. Dibawa angin selatan.
…
Tak tahu akhir-akhir ini aku suka menyendiri. Merenung. Bukan karena benci pada keramaian. Tapi karena kesendirian bisa mendorongku lebih produktif dan jeli melihat keadaan, peluang serta tantangan. Dan yang tak kalah penting adalah untuk mengingat-ingat kebaikan orang lain yang hanya bisa aku lakukan dalam kesendirian. Berbicara sendiri. Bertanya sendiri. Bahkan menjawab pertanyaan itu sendirian. Tanpa ada yang mengintervensi. Merdeka. Dambaan semua manusia yang ditekan keadaan. Selain itu memecahkan permasalah sendiri sebenarnya lebih praktis dalam kesunyian.
Dalam kesendirian itu waktu melambat. Hukum relativitas yang digagas Einstain pun terbukti. Berlaku. Gerak sejarah mulai dapat dikendalikan. Laju masa depan mulai dapat dibaca arahnya. Semua ini harus dibaca dengan kesadaran dan ketenangan. Dan seringkali kesadaran dan ketenangan seperti ini berada di tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Bersama Tuhan.
Meski begitu dan sambil menunggu hadirnya transportasi ke masa lalu, aku mencoba mencari alamat orang yang bersangkutan. Menanyakannya kepada ibu. Sayangnya ibuku juga sulit mengingat petani pembawa jerami yang pernah mengantar anaknya pulang sekolah dua dekade lalu.
Dalam hati aku terus menanyakan kabar, keadaan, kondisi tempat tinggal, kebutuhan pokok makanan, pendidikan anak-anak petani itu. Semuanya masih menjadi pertanyaan besar yang belum bisa dijawab. Pertanyaan itu hanya bisa ku tampung sendirian tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan.
Meski dengan cara matematika aku belum menemukan titik koordinat posisi tempat petani itu berpijak. Aku selalu berharap ia selalu dalam keadaan sehat dan kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Aku juga selalu berdoa agar segera dipertemukan dengan petani baik itu. Aku masih merasa berhutang karena aku pernah diantarkannya ke masa depan dengan sepeda unta tua “di atas tumpukan jerami”. Mewah dan menggembirakan.
Yogyakarta, November 2021
Diko Ahmad Riza Primadi, lahir di Blitar, 02 Mei 1994. Seorang sarjana Matematika yang hobi membaca, menulis dan sekaligus bersepeda. Semasa kuliah hingga sekarang aktif berkecimpung di dunia jurnalistik. Kini sedang menempuh S2 di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan bekerja sebagai wartawan di Majalah Suara Muhammadiyah.