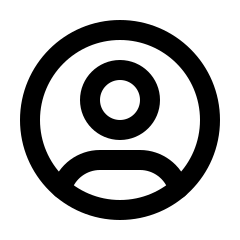Psychozoic, Evolusi Kesadaran di Tengah Krisis Bumi
Oleh : Ratna Arunika, Anggota LLHPB Pimpinan Wilayah A’isyiyah Jawa Timur
Manusia adalah paradoks terbesar yang pernah lahir dari rahim alam semesta. Kita adalah makhluk yang mampu menatap bintang-bintang dan bertanya tentang asal-usulnya, namun di saat yang sama, kita menggali bumi tanpa henti hingga kehilangan pijakan. Tidak ada makhluk lain yang menyadari kefanaannya, tetapi bertindak seolah akan hidup selamanya.
Kita adalah ciptaan yang penuh keajaiban, tetapi juga sumber dari banyak kehancuran. Dalam diri manusia bersemayam dua kekuatan yang saling bertentangan welas asih dan kekejaman, penciptaan dan perusakan, kesadaran dan kealpaan. Dengan tangan yang sama, kita menulis puisi dan menyalakan perang; kita menanam pohon dan menebang hutan; kita menciptakan kehidupan dan merusaknya demi keuntungan sesaat.
Selama 250.000 tahun keberadaan spesies manusia telah menjadi kekuatan geologis yang menubah wajah planet ini lebih cepat dari proses alam manapun. Kini kita hidup di era Antroposen, masa ketika bumi tidak lagi diatur oleh siklus alami, melainkan oleh keputusan-keputusan manusia. Ribuan spesies lenyap, hutan menyusut, iklim bergeser, dan laut kehilangan napasnya.
Namun krisis ini bukan semata krisis ekologi. Ia adalah krisis kesadaran, kehilangan keseimbangan antara kecerdasan dan kebijaksanaan. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar bagaimana menyelamatkan bumi, tetapi bagaimana menyelamatkan kemanusiaan dari dirinya sendiri.
Antroposen, Ketika Manusia Menjadi Bencana bagi Bumi
Para ilmuwan menyebut era kita sebagai antroposen, masa ketika manusia telah menjadi kekuatan geofisik yang menandingi proses bumi itu sendiri. Di Indonesia, wajah Antroposen tampak nyata dan telanjang dampak ini terlihat jelas melalui deforestasi yang begitu. Hutan-hutan tropis yang dahulu menjadi paru dunia kini terbentang sebagai lahan gundul, sungai-sungai berubah warna, laut menjadi tempat pembuangan limbah industri, dan tanah adat yang selama b ertahun-tahun dijaga dengan kearifan, berubah menjadi konsesi tambang dan perkebunan. Setiap hektar hutan yang hilang bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga kehilangan doa, cerita, dan kebijaksanaan lokal yang selama ini menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Kita menyaksikan satu demi satu spesies endemik yang menjadi warisan alam kita seperti: gajah dan harimau Sumatera, orangutan dan bekantan Kalimantan, anoa dan langur Sulawesi, badak Jawa, hingga burung cenderawasih Papua berjalan menuju kepunahan, seolah menjadi korban bisu dari ambisi manusia. Kepunahan mereka bukan sekedar hilangnya makhluk hidup. Setiap spesies yang punah, adalah satu huruf yang hilang dari puisi panjang kehidupan
Paradigma ekonomi modern, alam direduksi menjadi sekedar “bahan mentah”, sesuatu yang boleh digali, dijual, dan ditinggalkan. Paradigma ekstraktivistik atau dalam diksi yang lebih mudah dipahami, ekonomi perampasan, telah menjadikan bumi sebagai tubuh yang bisa diiris tanpa rasa. Pandangan ini memisahkan manusia dari lamnya, seolah keduanya entitas berbeda, padahal kehidupan saling menopang seperti simpul dalam jaring yang sama.
Ironinya, di balik jargon “pembangunan berkelanjutan”, kita justru menyaksikan kontradiksi yang semakin nyata. Kebijakan lingkungan sering berhenti pada tataran dokumen dan seremoni, sementara kesadaran ekologis belum tumbuh dalam cara berpikir kita. Antroposen bukan hanya menandai kerusakan ekologis, tetapi juga kemunduran spiritual saat manusia kehilangan kemampuan untuk melihat alam sebagai sesama kehidupan, bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi.
Maka, bencana terbesar di era ini bukan semata badai tropis, longsor, atau kebakaran hutan, melainkan manusia itu sendiri, ketika ia lupa siapa dirinya di antara makhluk lain. Kita terlalu berkuasa untuk menciptakan kehancuran, namun tidak cukup bijak untuk menanggung akibatnya. Dan mungkin di situlah tragedi terbesar antroposen, ketika makhluk paling sadar di bumi justru menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan.
Kesadaran yang Belum Berevolusi
Era Psychozoik, istilah yang diutarakan oleh Le Conte pada 1877, menandai babak baru dalam sejarah bumi, masa di mana manusia bukan lagi sekedar bagian dari alam, melainkan kekuatan yang mempengaruhi arah evolusi kehidupan itu sendiri. Di era ini, kesadaran menjadi kekuatan paling dominan di planet ini. Namun, ironisnya, kesadaran itu belum sepenuhnya berevolusi. Ia tumbuh dalam kecerdasan yang tajam, tetapi sering kehilangan kelembutan hati; ia rasional, tetapi belum welas asih.
Krisis ekologis yang kita hadapi sejatinya bukan semata masalah fisik, tetapi krisis makna, nilai, dan empati. Kita hidup di zaman di mana keberhasilan diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, bukan keseimbangan ekosistem. Ketika bumi diukur seperti neraca laba rugi, kehidupan kehilangan ruhnya. Alam tidak lagi dipandang sebagai rumah bersama, melainkan sekadar sumber daya yang dapat dikuras tanpa batas, tanpa menghargai keseimbangan ekosistem, dan hidup kehilangan jati dirinya.
Sebagai penyeimbang dari era Psychozoik, Thomas Berry memperkenalkan konsep Ecozoic Era, zaman di mana manusia hidup selaras dengan bumi melalui kesadaran ekologis yang mendalam. Ini bukan utopia yang idealis, melainkan panggilan moral dan spiritual untuk menyelaraskan kembali manusia dengan kehidupan yang lebih luas. Ecozoik bukan seruan untuk mundur ke zaman primitif, tetapi ajakan untuk maju dengan kesadaran yang lebih dalam, yang menyatukan rasio dan rasa, sains dan spiritualitas, kemajuan dan keheningan.
Berry menyebut misi manusia di zaman ini sebagai The Great Work adalah tugas suci manusia modern: mentransformasi kesadaran kolektif agar bumi bisa pulih dan terus berkelanjutan. Hubungan ini bukan sekadar romantisisme, melainkan hakikat biologis dan spiritual dimana segala makhluk saling bergantung.
Namun sebelum bumi pulih, manusia harus lebih dulu menyembuhkan kesadarannya sendiri. Sebab, kerusakan ekologis yang kita saksikan hari ini adalah pantulan dari keretakan batin manusia modern. Kita terlalu cepat menaklukkan alam, tetapi terlalu lambat memahami jiwanya. Barangkali inilah saatnya untuk berhenti merasa sebagai pusat dari segalanya, dan mulai kembali mendengarkan denyut kehidupan di luar diri sebelum bumi berhenti berbisik kepada kita.
Geopuitika dan Kearifan Lokal
Konsep geopuitika, yang ditulis oleh Umbgrove, menekankan keterpaduan jiwa, bumi, galaksi, dan pikiran sebagai satu kesatuan ritmis harmonis bukan mesin buta, melainkan simfoni yang hidup. Melalui geopuitika, manusia diajak untuk “membaca” bumi bukan hanya dengan logika data, melainkan juga dengan perasaan dan intuisi.
Kearifan lokal Nusantara menawarkan pelajaran berharga meski ilmu modern sering memisahkan diri dari tradisi, kearifan adat seperti konsep Jawa "Hamemayu Hayuning Bawana" (menjaga keseimbangan alam sebagai tugas spiritual) dan prinsip Sunda "Tri Tangtu di Bumi", “leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” (hancurnya alam berarti sengsaranya manusia). Kehancuran alam adalah penderitaan umat manusia sendiri, seperti juga yang disampaikan dalam adigium masyarakat Minang, “Alam takambang jadi guru”, manusia harus belajar dari alam.
Contoh konkrit seperti Kalender Pranata Mangsa di Jawa yang menyesuaikan pertanian dengan siklus alam dan Subak di Bali yang mengelola irigasi dengan prinsip keadilan serta spiritualitas menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam.
Kisah-kisah bumi adalah dongeng kosmik yang terus kita tulis bersama, mengingatkan bahwa alam bukan sesuatu yang statis, melainkan entitas yang bernapas dan berdenyut. Tempat kita belajar tentang rapuh dan kuatnya kehidupan. Manusia harus belajar menyelaraskan diri, bukan mendominasi.
Eksploitasi dan Politik Ekologis di Indonesia
Eksploitasi alam yang dibungkus dengan narasi pembangunan kerap menjadi wajah lain dari ketimpangan. Di balik jargon kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, tersembunyi paradigma yang menempatkan alam semata sebagai “sumber daya” bukan sebagai ruang hidup bersama. Inilah wajah dari apa yang oleh banyak pemikir disebut sebagai ekstraktivisme, atau dalam bahasa yang lebih mudah, logika eksploitasi sumber daya, sebuah cara pandang yang melihat bumi hanya sebagai gudang bahan mentah yang bisa ditambang, ditebang, dan dijual tanpa batas.
Di Indonesia, dampak paradigma ini tampak begitu jelas. Konflik agraria yang tak kunjung usai, perampasan tanah adat, ekspansi perkebunan skala besar, hingga bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang kian sering terjadi, semuanya berakar pada hubungan yang timpang antara manusia dan alam. Hutan-hutan yang dahulu menjadi penopang kehidupan kini berubah menjadi area konsesi; sungai-sungai yang dahulu menjadi nadi komunitas kini mengalirkan lumpur dan limbah industri. Semua atas nama pembangunan.
Namun, persoalan ini bukan semata kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan kesadaran. Politik yang mengatur hubungan manusia dengan alam selama ini lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek ketimbang kelestarian hidup jangka panjang. Perlindungan lingkungan sering dijadikan simbol administratif, tersangkut dalam dokumen rencana, tetapi terpinggirkan dalam tindakan nyata.
Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan bentuk politik ekologis baru, politik yang tidak hanya berurusan dengan regulasi, tetapi tumbuh dari kesadaran ekologis yang hidup dalam masyarakat. Politik yang menempatkan manusia bukan sebagai penguasa bumi, melainkan penjaga yang bertanggung jawab.
Politik ekologis yang sejati adalah politik yang menolak ilusi kemajuan yang dibangun di atas kehancuran ekosistem. Ia mengakui bahwa kesejahteraan manusia tidak bisa dicapai dengan mengorbankan keseimbangan alam. Ia berpihak pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Sebab pada akhirnya, krisis lingkungan bukan hanya masalah ekosistem yang rusak tetapi gejala dari kesadaran yang terputus dari bumi. Dan selama paradigma eksploitasi masih menjadi dasar berpikir, pembangunan hanya akan menjadi lingkaran penderitaan yang mengulang dirinya sendiri.
Masa Depan yang Berkabut, Antara Kehancuran dan Harapan
Masa depan memang penuh ketidakpastian, menghadirkan suasana kelam sekaligus harapan. Krisis iklim membuka ruang bagi adaptasi kreatif dan kerja sama antar makhluk hidup.
Sebagaimana kata Octavia Butler, “Takdir dari benih bumi adalah berakar di bintang-bintang” manusia ditakdirkan untuk tumbuh dan berubah, menanamkan kesadaran yang melampaui batas planet ini, bukan untuk melarikan diri, tetapi memahami tempatnya dalam alam semesta.
Jalan Pulang ke Kesadaran
Manusia sebagai khalīfatul fīl arḍ adalah wakil Tuhan di bumi dengan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga alam semesta dengan bijaksana. Tugas ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang tidak berlebihan, menciptakan keseimbangan, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Menjadi khlaifah bukan berarti menaklukkan bumi, melainkan merawatnya sebagai rumah bersama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam alam Al-Qur’an surat Al-Baqrah ayat 30 yaitu:
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ ِانِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
“Ingatlah ketika Tuhanmu befrirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, pada hal kami senangtiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.
Ayat ini menyiratkan paradoks eksistensial manusia, antara potensi kebaikan dan kerusakan yang berjalan beriringan. Dan barangkali disitulah letak ujian terbesar peradaban ini, kita terlalu bekuasa untuk membuat kerusakan, namun belum cukup bijak untuk menanggung akibatnya.
Krisis ekologis yang melanda dunia saat ini sejatinya juga merupakan krisis identitas. kita lupa bahwa kita adalah satu bagian dari jaringan kehidupan yang rapuh dan saling bergantung, bukan penguasa tunggal di atasnya. Ketika kesadaran ini pudar, keseimbangan pun terganggu. maka gtugas kita bukan sekedar bertahan hidup di tengah perubahan, melainkan menemukan kembali jiwa sejati kita sebagai bagian dari semesta.
Perubahan adalah keniscayaan yang tak dapat dihindari, namun arah perubahan itu dapat kita pilih bersama. The Great Work, sebagaimana disebut Thomas Berry, menuntut transformasi kesadaran kolektif agar bumi dapat sembuh. Prinsip saling ketergantungan, bukan dominasi, harus menjadi fondasi baru bagi keberlangsub-ngan hidup.
Dalam kebijaksanaan Nusantara, prinsip itu sesungguhnya telah lama dijaga. Pawukon, Pepali, dan Pepakem adalah warisan etika ekologis, contoh aturan hidup leluhur yang mengikat manusia pada alam menjadi penuntun agar kita bisa hidup harmonis. Para pendahulu kita mengajarkan bahwa hutan bukan sekadar tanah, melainkan leluhur yang hidup; sungai bukan sekadar air yang mengalir, melainkan nadi yang menghubungkan semua kehidupan.
Masa depan boleh samar, tetapi tidak kosong. Ia dipenuhi oleh jejak pilihan yang kita tanam hari ini. Tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan keberanian mengakui bahwa manusia sekaligus ancaman terbesar bagi kehidupannya. Namun di balik kesadaran itu, tersimpan pula harapan—bahwa kita masih bisa belajar untuk bertahan bukan dengan menguasai, melainkan dengan menyatu.
Mari menjadi spesies yang belajar berjalan bersama alam, bukan di atasnya. Kita tahu kita fana, namun biarlah kefanaan itu bermakna, biarlah jejak kita menjadi akar yang tumbuh dan menjalar, menghidupkan bumi, bahkan mungkin suatu hari menembus bintang-bintang.
Sebab harapan ecozoik bukan utopia, ia adalah keniscayaan bagi kelangsungan hidup bersama. “Kita cukup berkuasa untuk menghancurkan dunia, tapi belum cukup bijak untuk menyelamatkannya. Dan mungkin, perjalanan sejati kita adalah menemukan jalan pulang menuju kebijaksanaan itu, jalan kembali ke kesadaran, ke harmoni, dan ke cinta yang memelihara seluruh kehidupan. (hanan)