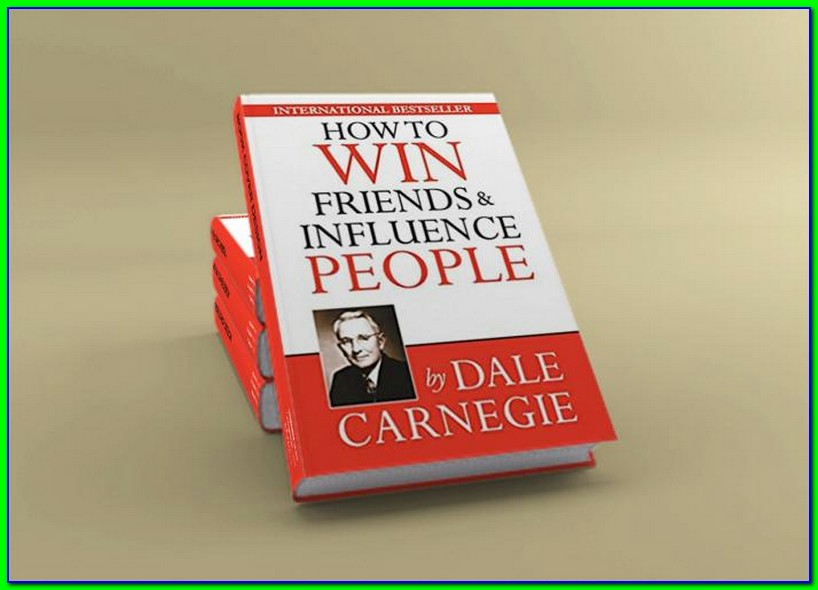Tragedi Ballpoin: Cermin Retak Sistem Pendidikan Dasar Kita
Oleh: Syahnanto Noerdin*)
Surat perpisahan dari seorang anak berusia 10 tahun menjadi saksi bisu kegagalan kita semua. Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang siswa kelas IV SD mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli ballpoin dan buku tulis. Dalam surat yang ditinggalkannya, tergambar jelas keputusasaan seorang anak yang seharusnya masih polos bermain dan belajar, namun sudah terbebani oleh tekanan yang tak sanggup dipikulnya.
Tragedi ini bukan sekadar kisah sedih tentang kemiskinan, melainkan tamparan keras yang mempertanyakan esensi sistem pendidikan dasar di Indonesia. Bagaimana mungkin di era yang mengklaim pendidikan gratis, seorang anak berusia 10 tahun merasa begitu terpojok hingga memilih mengakhiri masa kecilnya? Surat yang ditinggalkannya adalah teriakan sunyi yang terlambat kita dengar.
Program pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah sejak lama ternyata masih menyimpan celah yang fatal. Meski SPP ditiadakan, biaya operasional pendidikan masih merembes ke kantong orangtua dalam berbagai bentuk: seragam, sepatu, tas, alat tulis, hingga berbagai iuran yang "sukarela" namun implisit wajib. Bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke atas, ini mungkin nominal kecil. Namun bagi keluarga miskin di daerah seperti Ngada—salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di NTT—ini bisa menjadi beban yang mencekik.
Kasus di Ngada ini mengungkap ironi yang menyakitkan: anak SD kelas IV itu meninggal bukan karena tidak ingin sekolah, tetapi justru karena sangat ingin sekolah namun tidak punya sarana paling dasar. Ballpoin dan buku—dua benda yang bagi banyak orang begitu sepele—menjadi penghalang yang begitu besar hingga seorang anak merasa tidak ada jalan keluar lain.
Tragedi ini juga mengungkap bahwa kita gagal memahami kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang martabat. Seorang anak yang tidak punya ballpoin di tengah teman-temannya yang lengkap perlengkapan sekolah mengalami tekanan psikologis yang luar biasa. Rasa malu, merasa berbeda, dan takut diejek adalah beban mental yang tidak terlihat namun sangat nyata—begitu nyata hingga bisa merampas nyawa.
Fakta bahwa anak ini meninggalkan surat menunjukkan bahwa keputusannya bukan impulsif, melainkan hasil dari tekanan berkepanjangan yang tidak ada yang menyadari atau merespons. Seorang anak 10 tahun seharusnya menulis tentang cita-cita, bukan surat perpisahan. Ini menandakan sistem deteksi dini kita terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan—baik ekonomi maupun psikologis—benar-benar gagal.
Di mana guru-gurunya ketika anak ini berjuang tanpa alat tulis? Di mana teman-temannya ketika dia menderita dalam diam? Di mana sistem pendidikan yang seharusnya melindungi setiap anak, apapun kondisi ekonominya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus mengganggu tidur kita semua, karena ini adalah kegagalan kolektif.
Sistem pendidikan kita terlalu fokus pada capaian akademik dan melupakan aspek psikososial anak. Guru-guru kita, yang juga terbebani oleh administrasi berlebihan dan kurikulum yang padat, seringkali tidak punya waktu atau pelatihan memadai untuk mendeteksi anak-anak yang mengalami tekanan mental. Konselor sekolah, jika ada, jumlahnya sangat terbatas—di daerah seperti NTT, kemungkinan besar sekolah-sekolah bahkan tidak memiliki konselor sama sekali.
Di Ngada, dengan kondisi geografis yang menantang dan akses terhadap layanan psikososial yang minimal, anak-anak rentan seperti korban praktis tidak punya jaring pengaman. Mereka berjuang sendirian melawan tekanan yang bahkan orang dewasa pun kesulitan menghadapinya.
Budaya sekolah yang masih cenderung menekankan kompetisi daripada kolaborasi juga memperparah situasi. Anak-anak yang tertinggal, baik secara ekonomi maupun akademik, mudah terstigma. Mereka tidak mendapat dukungan yang cukup untuk bangkit, melainkan justru semakin terpinggirkan.
Potret Kesenjangan yang Menganga
Indonesia menghadapi paradoks: di satu sisi ada sekolah dengan fasilitas mewah dan teknologi canggih di kota-kota besar, di sisi lain masih banyak sekolah di daerah seperti NTT yang kekurangan guru, gedung rusak, dan siswa yang tidak punya alat tulis dasar. Kesenjangan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang akses terhadap martabat yang sama dalam menempuh pendidikan.
NTT, sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, menjadi representasi dari daerah-daerah terpinggirkan yang tidak mendapat perhatian memadai. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang seharusnya menutup celah ini ternyata masih belum optimal. Mekanisme penyalurannya yang birokratis, penggunaannya yang terbatas pada pos-pos tertentu, dan lemahnya pengawasan membuat banyak kebutuhan riil siswa tidak tercover.
Program bantuan sosial seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) juga belum menjangkau semua anak yang membutuhkan. Kasus di Ngada ini mempertanyakan: apakah anak korban terdata sebagai penerima bantuan? Jika tidak, mengapa sistem pendataan kita gagal menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan? Jika ya, mengapa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti ballpoin dan buku?
Reformasi yang Harus Dimulai Sekarang
Tragedi ini harus menjadi titik balik. Pertama, kita perlu mendefinisikan ulang "pendidikan gratis" secara komprehensif—bukan hanya bebas SPP, tetapi juga mencakup semua kebutuhan dasar pendidikan termasuk alat tulis, seragam, hingga makan siang. Beberapa negara telah membuktikan bahwa menyediakan semua kebutuhan ini justru meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jika negara bisa mengalokasikan miliaran untuk berbagai proyek, mengapa tidak untuk memastikan setiap anak punya ballpoin?
Kedua, sekolah harus menjadi zona aman secara psikologis. Ini berarti melatih guru untuk lebih sensitif terhadap kondisi mental siswa, menambah jumlah konselor terutama di daerah-daerah terpencil, dan membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif. Anak-anak harus merasa bahwa sekolah adalah tempat mereka bisa tumbuh tanpa rasa takut atau malu. Guru harus diberdayakan untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendeteksi anak-anak yang membutuhkan bantuan.
Ketiga, sistem pelaporan dan respons cepat untuk anak-anak dalam kesulitan ekonomi atau psikologis harus diperkuat, terutama di daerah-daerah terpencil. Guru dan sekolah harus punya jalur yang jelas untuk segera membantu siswa yang menghadapi masalah, dengan akses langsung ke sumber daya dan dana darurat. Tidak boleh ada lagi birokrasi yang menghambat penyelamatan nyawa anak.
Keempat, perlu ada perhatian khusus terhadap daerah-daerah tertinggal seperti kabupaten-kabupaten di NTT. Pemerataan pendidikan bukan hanya soal membangun gedung, tetapi memastikan setiap anak—di Jakarta atau di Ngada—punya kesempatan yang sama untuk belajar dengan bermartabat.
Namun reformasi sistem saja tidak cukup tanpa perubahan mindset masyarakat. Kita perlu membangun empati kolektif bahwa setiap anak, apapun latar belakangnya, berhak mendapat pendidikan dengan martabat yang sama. Stigma terhadap kemiskinan harus dikikis, dan solidaritas sosial harus diperkuat.
Orangtua, guru, teman sebaya, bahkan tetangga—kita semua punya peran. Terkadang hal sekecil meminjamkan ballpoin atau membagikan buku bisa menyelamatkan seorang anak dari keputusasaan. Namun lebih dari itu, kita perlu menciptakan lingkungan di mana tidak ada anak yang merasa sendirian menghadapi kesulitannya, di mana seorang anak merasa aman untuk bercerita tentang kesulitannya sebelum terlambat.
Anak SD kelas IV di Ngada itu tidak seharusnya mati karena ballpoin. Surat yang ditinggalkannya seharusnya adalah karangan tentang liburan atau cita-citanya menjadi dokter, bukan surat perpisahan. Dia seharusnya masih bermain, belajar, bermimpi, dan tumbuh menjadi apa yang dia inginkan. Tragedi ini adalah pengingat bahwa di balik statistik pencapaian pendidikan yang kita banggakan, masih ada anak-anak yang jatuh di celah sistem yang gagal melindungi mereka.
Setiap kali kita melihat ballpoin atau buku tulis, kita harus mengingat anak 10 tahun di Ngada yang nyawanya terampas karena tidak punya akses pada benda-benda sederhana itu. Ingatannya harus menjadi cambuk bagi kita untuk terus memperbaiki sistem, untuk terus berjuang memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami nasib serupa.
Jika kita benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas, maka tidak boleh ada lagi anak yang merasa hidupnya tidak berharga hanya karena tidak punya alat tulis. Sistem pendidikan yang baik bukan yang hanya mencetak lulusan pintar, tetapi yang memastikan setiap anak—dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Ngada—merasa dihargai, didukung, dan punya harapan untuk masa depan.
Ballpoin dan buku adalah benda kecil, tetapi bagi anak itu, mereka adalah segalanya. Surat terakhirnya adalah pesan untuk kita semua: sudah saatnya kita memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang harus memilih antara martabat dan hidup. Sudah saatnya kita mendengarkan teriakan sunyi anak-anak kita sebelum mereka memilih untuk selamanya diam. (***)
*) Penulis adalah Ketua Bidang Kerjasama dan hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI Pusat) 2021-2026 dan Alumni Mikom Fisip UMJ