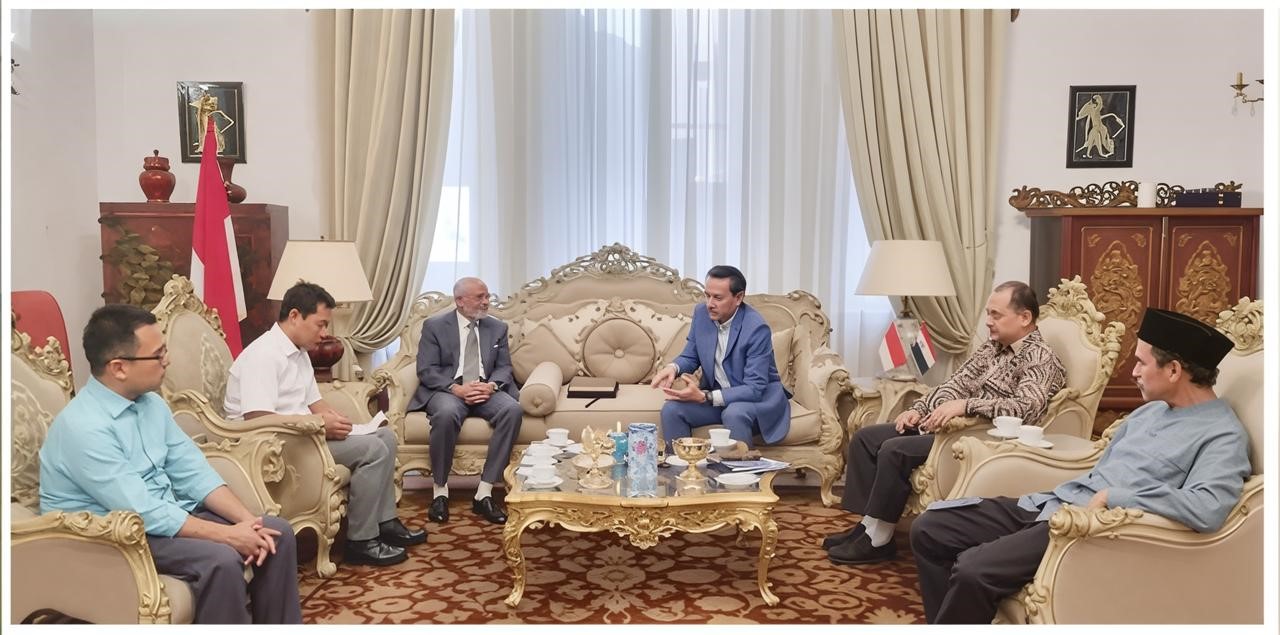Umar Melarang Anaknya Dicalonkan Jadi Khalifah
Oleh: Abdul Hafiz, Wakil Ketua PWM Bengkulu
“Jika deadlock, minta anakku Abdullah bin Umar menentukan siapa yang jadi khalifah tetapi anakku itu tidak boleh dicalonkan jadi khalifah.” Demikian pesan Khalifah Umar bin Khathab kepada enam orang Sahabat yang ia tunjuk menjadi tim formatur untuk memilih dan mengangkat seseorang pengganti dirinya. Dalam keadaan sakit akibat tikaman belati, menjelang kematiannya, Umar masih memikirkan keberlangsungan negara. Ia masih cawe-cawe dalam urusan pemilihan penggantinya. Namun, cawe-cawenya Umar jauh dari ambisi pribadi dan ambisi keluarga. Untuk menjadi anggota tim, ia tunjuk Sahabat-sahabat Nabi saw terkemuka yaitu mereka yang mendapat kabar gembira bahwa mereka masuk surga.
Sahabat-sahabat Nabi saw yang diberi kabar gembira masuk surga berjumlah sepuluh orang; Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khathab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, al-Zubair bin al-‘Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Sa’ad bin al-Waqqash, dan Sa’id bin Zaid. Namun, yang menjadi anggota tim formatur hanya enam orang karena dua orang yang disebut pertama sudah meninggal dan dua orang yang disebut terakhir berhalangan. Oleh karena komposisi anggota formatur berjumlah genap maka untuk mengantisipasi deadlock Umar meminta supaya anaknya—Abdullah bin Umar—menjadi penentu, tetapi ia bukan anggota tim formatur. Bilamana ada dua calon khalifah mendapat dukungan berimbang, maka yang menjadi khalifah adalah calon yang ditunjuk oleh Abdullah bin Umar.
Tampaknya pedoman yang dibuat Umar itu tidak diikuti. Atas inisiatifnya sendiri, ketika terjadi deadlock, Abdurrahman bin Auf mendatangi secara terpisah dua calon yang memperoleh dukungan yang sama besar untuk meminta komitmen masing-masing terhadap tradisi kepemimpinan yang telah dibangun oleh dua khalifah terdahulu. Usman bin Affan setuju dengan tuntutan Abdurrahman bin Auf. Sementara Ali bin Abi Thalib menolaknya karena baginya setiap khalifah harus memaksimalkan ijtihadnya. Abdurrahman bin Auf menentukan Usman menjadi khalifah setelah Umar. Abdurrahman tampaknya tidak menyadari bahwa tindakannnya itu telah membuka pintu bagi nepotisme dan politik dinasti masuk ke dalam Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, tidak ada lagi pemerintahan yang demokratis di dunia Islam dan tidak ada lagi kepala negara yang lahir dari pemilihan.
Dalam pikiran orang sekarang, tindakan Umar melarang anaknya dicalonkan sebagai khalifah dianggap tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Namun, anggapan itu tidak sesuai dengan kehidupannya secara umum. Ia sering sekali dikritik. Alih-alih memarahi pengritik, ia justru merubah kebijakannya mengikuti aspirasi pengkritik. Diceritakan, seorang perempuan yang merintih di tengah malam dalam senandung menggugat keadilan Umar. Karena kebijakan Umar, ia mesti berpisah berbulan-bulan dari suaminya yang menjalankan tugas ketentaraan. Segera ia kumpulkan para isteri. Dari saran mereka ia memutuskan bahwa seorang suami yang terpaksa berpisah dari isteri karena menjalankan tugas, penugasannya tidak boleh lebih dari empat bulan.
Pernah pula Umar melindungi hak asasi seorang Yahudi dalam kepemilikan lahan. Gubernur Mesir, Amr bin al-‘Ash, bermaksud memperluas bangunan masjid yang untuk itu mesti membebaskan lahan di samping masjid itu. Bukan soal agama, tetapi kebetulan lahan itu milik seorang Yahudi. Berkali-kali Amr melakukan negosiasi dengan pemilik lahan tetapi pemilik lahan kukuh tidak mau melepaskan haknya atas tanah itu. Amr tidak punya jalan lain untuk meneruskan upaya perluasan masjid selain penggusuran secara paksa. Ketika menerima pengaduan dari pemilik lahan, Umar langsung memerintahkan Amr untuk mengembalikan hak atas lahan kepada orang Yahudi itu.
Dalam sebuah pemerintahan yang masih sangat muda—di tengah kawasan yang telah memiliki peradaban, Persia dan Romawi—dan wilayah yang tidak diperhitungkan, Umar telah melahirkan konsep pemerintahan yang sangat modern. Konsep itu disebut amῑrul-mu`minῑn yang lahir sekedar untuk menyelesaikan problem sebutan kepala negara. Abu Bakar al-Shidiq, sebagai kepala negara, disebut Khalifah Rasulillah (Pengganti Rasulullah). Sebagai kepala negara berikutnya, Umar bin Khathab, disebut Khalifah Khalifah Rasulillah (Pengganti penggantinya Rasulullah). Kepala negara setelah Umar bin Khathab disebut Khalifah khalifahnya khalifah Rasulillah saw. Sangat tidak efisien dan menyulitkan. Umar menampilkan istilah baru sebutan kepala negara yaitu amῑrul-mu`minῑn.
Amῑrul-mu`minῑn terdiri dari dua kata yaitu amῑr dan mu`minῑn. Amῑr berasal dari kata amara yang berarti memerintahkan dan menyuruh. Dari segi bentuk kata (shighah), amῑr berarti “yang disuruh dan yang diperintah” atau pelayan. Amῑrul-mu`minῑn dengan demikian berarti orang disuruh-suruh oleh orang-orang beriman atau pelayan rakyat. Atas dasar itu, menjadi pemimpin bagi Umar bukanlah kenikmatan yang harus disyukuri. Memimpin itu bukan menjadi pejabat yang minta dilayani; dilengkapi dengan fasilitas kemewahan, dibukakan pintu mobilnya, dibawakan tasnya, dipayungi supaya tidak terkena sinar matahari, dst. Bagi Umar, memimpin adalah beban dan penderitaan. Kata Umar, “Cukuplah satu Umar yang menanggung beban berat ini.”
Sikap Umar seperti itu diteladani oleh banyak founding fathers kita. Mereka gambarkan sikap Umar itu dengan pepatah kuno bangsa Belanda, leiden is lijden. Pepatah itu diucapkan oleh Kasman Singodimejo di hadapan H. Agus di rumah kontrakannya di Gang Tanah Tinggi Jakarta tahun 1925. Dengan pikiran bahwa memimpin itu menderita, umumnya founding fathers tidak mewariskan penderitaan itu kepada anak-anak mereka. Mungkin itu sebabnya, pascafounding fathers, daftar nama-nama pemimpin negara yang mereka dirikan tidak diisi oleh nama-nama anak-anak mereka. Di mana anak-anak H. Agus Salim? Di mana anak-anak Kasman Singodimejo? Di mana anak-anak Moh Yamin? Di mana anak-anak Ahmad Subardjo? Di mana anak-anak Moh Natsir? Di mana anak-anak IJ Kasimo? Di mana anak-anak Jenderal Soedirman?
Zaman sudah berubah. Dewasa ini para pemimpin berlomba-lomba mempromosikan anak-anak mereka untuk jadi pemimpin. Mereka berlomba-lomba mendirikan dinasti. Bukan hanya di pusat, di daerah-daerah banyak gubernur, bupati, dan walikota yang sudah membentuk dinasti. Mungkin bagi mereka memimpin tidak lagi menderita tapi menyenangkan. Ya, tentu menyenangkan. Menjadi pemimpin dilayani dengan berbagai fasilitas. Kadang-kadang pemimpin sudah seperti raja. Apapun kehendaknya dipenuhi orang. Ia ingin menumpuk hutang, terpenuhi. Ia ingin anaknya mewarisi kekuasaan, terpenuhi meskipun dengan menekuk aturan. Bertambah kesenangan si pemimpin ketika kehendaknya untuk mewariskan kekuasaan disetujui oleh guru besar hukum tata negara yang dulunya sering mencercanya. Didukung pula oleh para politikus yang tidak pernah mencalonkannya dan dulu menentangnya. Adapun kritikan dan penyesalan para guru besar di kampus-kampus dan budayawan terkemuka hanya dianggapnya sebagai “bagian dari demokrasi”.
Lihatlah di berbagai kejadian, ia berkunjung ke suatu daerah, rakyat menyambutnya. Lebih menyenangkan baginya, senyumnya tersungging, ketika melihat rakyat berebutan mendapatkan kaos yang ia lemparkan dari jendela mobil mewahnya. Pemimpin memberi sesuatu kepada rakyat adalah baik. Tapi lihatlah Umar. Seringkali di malam hari ia, tanpa diketahui orang, menelusup ke perkampungan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Di suatu ketika ia dengar rintihan seorang perempuan mempertanyakan kepedulian Khalifah. Perempuan itu merebus batu hanya sekedar memberikan harapan kepada anak-anaknya yang kelaparan bahwa mereka akan segera makan dan meminta mereka untuk tidak menangis lagi. Umar segera ke baitul-mal untuk mengambil gandum. Karung gandum ia panggul sendiri. Pulang ke rumah, Umar menangis. “Tuhan, Umar yang dipuji banyak orang karena keadilan dan kebijaksanaannya, ternyata hanyalah seorang hamba yang hina.”
Bukan hanya sekadar tidak ingin menjerumuskan Abdullah bin Umar ke dalam penderitaan, larangan Umar kepada anaknya itu untuk dicalonkan menjadi khalifah didasari oleh keadilan yang telah tertanam kuat dalam jiwanya. Hukum Alquran sekalipun tidak serta merta ia terapkan manakala berakibat pada munculnya ketidakadilan. Demikianlah, misalnya, Umar tidak menerapkan hukum menyangkut harta rampasan perang. Menurut Qs 8: 41, empat per lima dari harta rampasan perang dibagikan untuk masing-masing tentara yang ikut perang. Dalam perang al-Qadisiyah, Umar tidak menerapkan hukum ini karena menimbulkan ketidakadilan. Di satu pihak, para tentara semakin kaya raya karena mereka banyak ikut perang dan setiap perang menghasilkan tambahan kekayaan. Di lain pihak, penduduk al-Qadisiyah jatuh miskin karena tanah yang menjadi sumber penghasilan mereka dirampas.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Abdullah bin Umar mendapat keuntungan dari kedudukan bapaknya bila ia ikut kontestasi pemilihan khalifah. Andaikan Abdullah bin Umar ikut pemilihan, para pemilih sedikit banyak melihat Umar pada dirinya. Rasa keadilan Umar terusik. Jiwanya tidak kuat melihat rakyatnya yang gagal menjadi khalifah karena dikalahkan anaknya. Tidaklah adil bila seseorang yang bukan siapa-siapa diadu dengan seorang anak kepala negara dalam sebuah pemilihan pemimpin. Padahal boleh jadi seseorang itu jauh lebih mampu memimpin dibandingkan anak khalifah.
Barangkali karena prokeadilan Umar menjadi antinepotismen sebagaimana Nabi dan juga pendahulu Umar, Abu Bakr al-Shiddiq. Tidak ada dalam catatan sejarah yang menunjukkan bahwa mereka menunjuk anak cucunya menjadi khalifah, gubernur, dan pejabat lainnya. Negara Madinah menjadi sangat kuat. Hanya dalam tempo tidak lebih dari lima belas tahun sejak Rasulullah saw mendirikan negara itu, wilayah kekuasaan Madinah sudah meliputi kawasan yang sangat luas yaitu wilayah yang sekarang disebut Timur Tengah. Namun setelah Umar wafat, perkembangan negara Madinah melambat menyusul masuknya nepotisme ke dalam pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.
Setelah Umar wafat dunia Islam mengalami perpecahan yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Pemerintahan khilafah yang demokratis di masa Abu Bakr dan Umar bagaikan kilat di tengah kegelapan abad pertengahan. Muncul sekilas untuk kemudian menghilang berabad-abad. Barangkali kekhalifahan yang demokratis terlalu modern untuk masa itu. Akibatnya nyaris sepanjang sejarah perjalanannya dunia Islam diperintah oleh berbagai dinasti silih berganti. Pergantian kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya selalu diwarnai oleh pertumpahan darah dan saling menghabisi.
Larangan Umar terhadap pencalonan anaknya untuk menjadi khalifah merupakan tonggak penting dalam perkembangan peradaban manusia. Pada masa itu, rasanya belum ada bangsa yang memiliki pemimpin melalui pemilihan. Pemimpin selalu lahir dari istana. Namun, hal itu adalah wajar karena negara adalah dinasti dan tidak relevan berbicara nepotisme dalam negara semacam itu. Umar merubah secara fundamental sistem politik yang tidak memberlakukan asas equalitas bagi rakyatnya.
Kendati berasal dari masyarakat Arabia yang terkebelakang, Umar berhasil menujukkan kualitasnya sebagai pemimpin kelas dunia. Michael H. Hart, sejarawan Amerika, menempatkanya sebagai salah seorang tokoh, di antara 100 tokoh, yang berpengaruh di dunia. Setelah Umar meninggal, secara perlahan dunia Islam masuk ke dalam masa kegelapan. Di masa moderen, negara-negara demokrasi muncul di dunia Islam. Secara perlahan dunia Islam bangkit. Dalam politik, terbuka pintu bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin. Namun, dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang mempromosikan nepotisme belakangan ini akankah dunia Islam kembali ke zaman kegelapan? Wallahu a’lam bish-shawab.