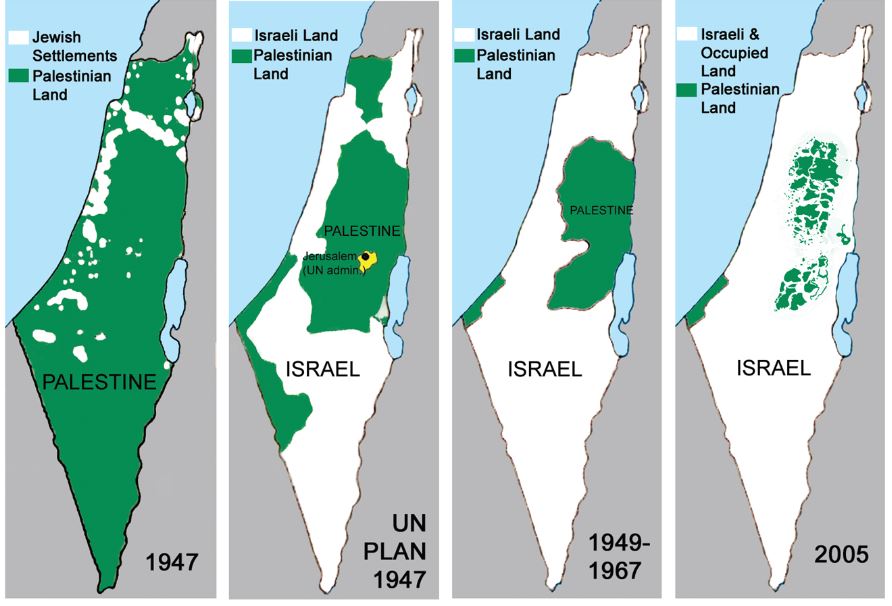Banjir Sumatra dan Pentingnya Hablum Minal ‘Alam
Oleh: Raihan Muhammad, Pegiat HAM, Direktur Amnesty UNNES, Pemerhati Politik dan Hukum
Banjir dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem, melainkan krisis kemanusiaan yang menelanjangi rapuhnya tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana.
Ratusan nyawa melayang, ratusan orang belum ditemukan, dan jutaan penduduk terdampak dalam situasi keterputusan—akses jalan terputus, listrik padam, logistik menipis, layanan dasar tersendat. Pada saat yang sama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penderitaan tidak semata lahir dari “hujan deras”, melainkan dari rangkaian keputusan pembangunan yang bertahun-tahun menggerus daya dukung alam dan memperbesar risiko bagi warga.
Pemicunya memang disebut Siklon Senyar—fenomena langka di dekat khatulistiwa—yang mendorong hujan ekstrem dan berkepanjangan. Namun, hujan ekstrem tidak otomatis berubah menjadi bencana mematikan tanpa kondisi yang sudah disiapkan sebelumnya: hutan yang menipis, kawasan resapan yang berubah fungsi, sungai yang dangkal karena sedimentasi, dan ekspansi aktivitas ekstraktif yang merusak bentang alam.
Ketika perbukitan kehilangan penutup vegetasi dan aliran sungai berubah, air tidak lagi tertahan dan terserap; air berlari kencang membawa lumpur, kayu, dan batu, lalu menghantam permukiman. Dalam kerangka ini, banjir Sumatra memperlihatkan bahwa “bencana” sering kali merupakan gabungan antara bahaya alam dan kegagalan manusia mengelola risiko.
Di sinilah urgensi hablum minal ‘alam menjadi terang: relasi etis dengan alam bukan tambahan wacana, melainkan prasyarat keselamatan sosial. Islam mengenal amanah pengelolaan bumi, larangan membuat kerusakan (fasad), dan tuntutan menegakkan kemaslahatan.
Relasi yang rusak dengan alam pada akhirnya berbalik menjadi mudarat bagi manusia—terutama kelompok rentan yang paling dulu kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan nyawa. Maka pembahasan banjir Sumatra semestinya melampaui simpati sesaat dan seremonial bantuan; fokus harus bergeser pada koreksi arah pembangunan, pemulihan ekosistem, penertiban izin-izin yang merusak, dan pembentukan kebijakan yang menghormati batas alam sebagai bentuk nyata menjaga kehidupan.
Hablum Minal ‘Alam sebagai Amanah Peradaban
Hablum minal ‘alam sejatinya bukan sekadar istilah indah dalam ceramah, melainkan ukuran etik yang menentukan arah peradaban: merawat atau merusak. Relasi dengan alam menuntut sikap amanah—memperlakukan hutan, sungai, dan tanah sebagai titipan yang memiliki fungsi penyangga kehidupan. Ketika amanah ini dilanggar melalui pembiaran deforestasi, alih fungsi kawasan resapan, dan eksploitasi tanpa batas, yang muncul bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi juga kerusakan sosial: warga kehilangan ruang hidup, kepastian ekonomi, dan keselamatan.
Ajaran Islam menolak fasad—kerusakan yang sengaja atau dibiarkan terjadi—karena dampaknya merusak kemaslahatan umum. Banjir besar yang berulang dapat dibaca sebagai peringatan keras bahwa kebijakan yang mengizinkan kerusakan lingkungan berarti menempatkan nyawa manusia dalam risiko. Di titik ini, pendekatan keagamaan tidak berhenti pada ajakan bersabar atau sekadar mendoakan korban, melainkan mendorong koreksi struktural: pengetatan evaluasi izin, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, serta pemulihan daerah tangkapan air dan bantaran sungai.
Hablum minal ‘alam juga menuntut keberpihakan pada kelompok rentan. Warga kurang mampu, masyarakat adat, petani, dan nelayan sering menjadi pihak pertama yang menanggung dampak dari banjir, longsor, dan krisis air bersih, padahal kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan paling kecil.
Maka, pemulihan pascabencana harus dibarengi keadilan ekologis: memastikan pembangunan tidak memindahkan risiko ke kampung-kampung, memastikan distribusi bantuan berjalan cepat, dan memastikan kebijakan tata ruang serta proyek ekonomi tidak menambah luka baru. Tanpa perubahan itu, bencana serupa akan terus menjadi “rutin tahunan” yang sebetulnya bisa dicegah.
Fikih Lingkungan sebagai Ukuran Tanggung Jawab
Dalam perspektif Islam, relasi manusia-alam tidak berhenti sebagai pesan moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum-etik yang tegas. Al-Qur’an mengingatkan bahwa kerusakan ekologis berkelindan dengan ulah manusia: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia…” (Q.S. Ar-Rum: 41). Ayat ini bukan sekadar narasi “azab”, melainkan penjelasan sebab-akibat: ketika tata kelola, produksi, dan konsumsi berjalan tanpa batas, dampak buruk tampil ke permukaan dan menimpa yang paling lemah terlebih dahulu.
Peringatan senada muncul dalam larangan merusak setelah perbaikan dilakukan: “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya …” (Q.S. Al-A’raf: 56). Dalam konteks banjir Sumatra, dua ayat tersebut menuntut evaluasi yang serius terhadap kebijakan ruang, praktik ekstraktif, dan pembiaran pelanggaran lingkungan—bukan hanya seruan kesabaran.
Dalil-dalil itu bertemu langsung dengan kaidah besar fikih: lā ḍarar wa lā ḍirār—tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Kaidah ini relevan saat pembukaan hutan, penambangan, pemotongan lereng, atau alih fungsi lahan dilakukan sedemikian rupa hingga meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor ke hilir.
Jika tindakan ekonomi atau kebijakan perizinan menambah bahaya bagi warga, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pencegahan mudarat dan kewajiban menjaga jiwa (hifz al-nafs). Islam pun sejatinya menegaskan nilai amal yang memulihkan: “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu dimakan burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya.” (H.R. Bukhari). Hadis ini memberi arah: perbaikan ekosistem—revegetasi, rehabilitasi daerah tangkapan air, pemulihan sempadan sungai—bukan proyek pinggiran, melainkan ibadah sosial yang dampaknya meluas.
Maka, hablum minal ‘alam perlu diterjemahkan menjadi agenda yang terukur dan tegas. Pertama, penataan ulang tata ruang berbasis daya dukung: kawasan resapan, lereng rawan, dan sempadan sungai harus dipulihkan fungsinya, bukan dinegosiasikan melalui dispensasi. Kedua, audit dan penertiban izin—terutama yang berada di hulu DAS dan wilayah rawan—harus menjadi langkah korektif, disertai penegakan hukum terhadap perusakan.
Ketiga, mitigasi berbasis komunitas: sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta pelindungan kelompok rentan wajib diutamakan. Pada titik ini, amar ma’ruf nahi munkar menemukan bentuk yang sangat konkret: mendorong kebijakan yang mencegah kerusakan, menolak normalisasi pelanggaran, dan memastikan keselamatan warga tidak dikorbankan demi keuntungan sesaat.
Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Negara
Banjir dan longsor tidak berhenti sebagai tragedi alam, karena dampaknya langsung menyasar hak-hak dasar manusia: hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, hak atas air bersih, hak atas pendidikan (ketika sekolah terhenti), hingga hak atas rasa aman.
Dalam kerangka HAM, lingkungan hidup yang baik dan sehat dipahami sebagai prasyarat terpenuhinya hak-hak tersebut. Ketika degradasi hutan, rusaknya daerah tangkapan air, dan penyempitan ruang sungai dibiarkan, risiko kebencanaan meningkat, lalu korban berjatuhan. Pada titik itu, persoalan bergerak dari sekadar “musibah” menuju persoalan tanggung jawab—terutama tanggung jawab kebijakan publik yang seharusnya mencegah bahaya sebelum menjadi petaka.
Konsekuensi etik dan hukum dari hablum minal ‘alam menuntut perubahan cara pandang: bencana berulang bukan “rutinitas cuaca”, melainkan indikator kegagalan memenuhi amanah perlindungan. Amanah tersebut sejalan dengan larangan memakan harta dan sumber daya secara batil, serta kewajiban menjaga kemaslahatan umum.
Al-Qur’an menegaskan larangan merusak keseimbangan yang telah ditakar: “Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan (keseimbangan), agar jangan melampaui batas dalam mizan.” (QS. Ar-Rahman: 7–8). Ayat ini memberi dasar kuat untuk menolak model pembangunan yang melampaui batas daya dukung. Ketika mizan dilanggar melalui ekspansi ekstraktif dan alih fungsi yang ugal-ugalan, yang hadir bukan hanya kerusakan ekologis, melainkan juga ketimpangan risiko: kampung-kampung di hilir menjadi “penampung” mudarat, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Maka, agenda pascabencana tidak cukup berupa rekonstruksi fisik semata, tetapi juga rekonstruksi kebijakan. Ukurannya jelas: pencegahan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Peninjauan izin di wilayah hulu dan kawasan rawan harus bersandar pada data ilmiah, bukan kompromi politik; pemulihan DAS dan sempadan sungai harus memiliki target yang terukur; penegakan hukum lingkungan harus menyasar pelaku utama, bukan berhenti pada kambing hitam di lapangan.
Di atas semuanya, prinsip keadilan ekologis harus ditegakkan: korban dan kelompok rentan memperoleh pemulihan yang layak, informasi risiko dibuka secara jujur, serta partisipasi warga—termasuk masyarakat adat—dihormati dalam penataan ruang. Dengan langkah semacam itu, hablum minal ‘alam menemukan bentuk paling nyata: menjaga kehidupan melalui tata kelola yang adil, disiplin, dan berpihak pada keselamatan.