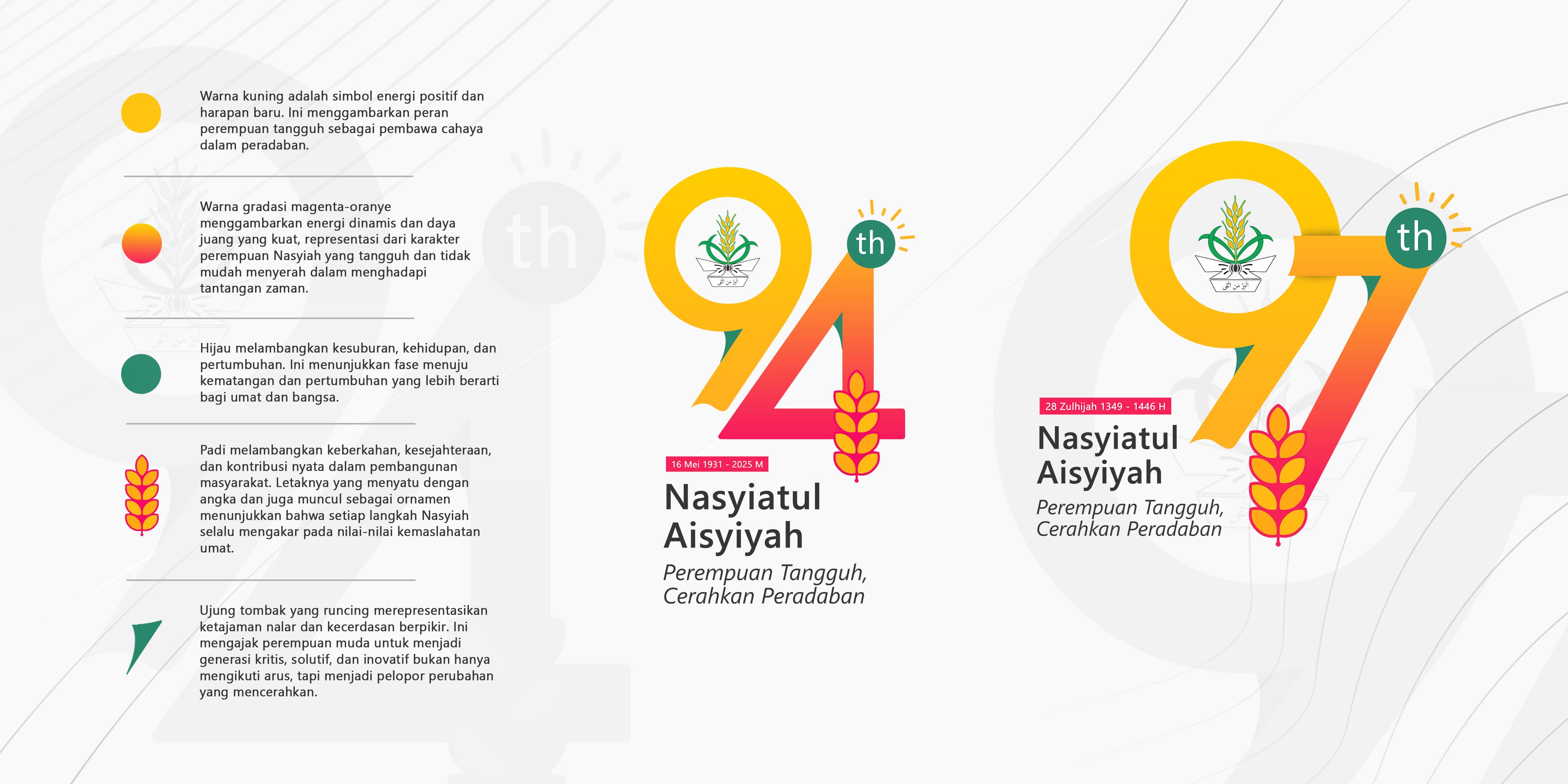Budi Pekerti dalam Rimba Homo Digitalis
Oleh: Al-Faiz MR Tarman, Dosen Universitas Muhammadiyah Klaten
Pendidikan akhlak pada era kontemporer ‘belum berani’ menyentuh persoalan-persoalan yang aktual. Muncul pada benak saya segudang pertanyaan, “bagaimana ber-akhlak pada era digital?”, “kiranya apakah cukup mengajarkan pendidikan lingkungan dengan anjuran tidak membuang sampah sembarangan kepada peserta didik?”
Apa yang muncul kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan itu, buruknya perilaku netizen kita di media sosial serta lingkungan hidup yang rusak akibat pembangunan menjadi persoalan serius jika diabaikan.
Kegelisahan ini bermula ketika saya santap Jumat berkat bersama di serambi masjid. Seorang bapak paruh baya rupanya menghampiri saya, “Mas, sudah lama saya ingin bilang begini, tidak banyak anak muda yang punya kesantunan seperti Mas-nya,” ujarnya dengan tiba-tiba.
Rupanya bapak ini mendaku kerap mengamati sikap saya sebagai jemaah masjid ketika melewati jemaah lain. Beliau melihat saya agak membungkukkan badan sembari memberi isyarat melalui tangan kanan ke bawah pertanda permisi, “Saya suka gusar, Mas, ngga mudah ngajarin anak zaman sekarang soal tata krama,” akunya.
Obrolan kian mengalir dimulai membahas akhlak secara normatif hingga fenomena homo digitalis. Di antara sekian pembahasan, saya tertegun ketika beliau menceritakan tentang pendidikan budi pekerti yang dahulu dipelajarinya di bangku sekolah dasar.
“Para siswa berbaris sebelum masuk, periksa kuku, sampe guru ngajarin sikap duduk yang benar lho, Mas, se-detail itu. Bahkan diajarkan mengucap maaf, tolong dan terima kasih, sikap baik terhadap orang tua, guru, keluarga, teman sebaya,” ungkapnya.
Kemudian istilah budi pekerti ini cukup mengganggu pikiran saya. Secara barangkali karena memiliki keresahan yang sama perihal tata krama.
Budi pekerti pernah menjadi salah satu mata pelajaran dalam pendidikan di Indonesia sekitar akhir 1960-an. Namun tidak berlangsung lama, pada pertengahan 1980-an mata pelajaran ini digantikan mata pelajaran kewarganegaraan dan agama.
Lantas, bagaimana merespon dekadensi akhlak pada masa kini, yang sejatinya bukanlah isu baru. Pada jagat media sosial, tidak sedikit netizen yang mengeluhkan etika mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih.
Saat yang sama, dalam konteks memasuki ruang digital, permasalahan lain muncul, misalnya tentang etika menghubungi guru atau dosen, etika mengenalkan diri kepada seorang yang asing, hingga memasuki grup aplikasi chatting dan meninggalkan grupnya sekaligus.
Upaya merespon permasalahan yang nampak sepele di atas memantik saya untuk berpikir terkait solusi. Apakah menjadi penting untuk kembali menggalakkan mata pelajaran budi pekerti?
Di samping itu, kompleksnya permasalahan rasanya tidak bisa kita merujuk kepada kitab-kitab akhlak normatif. Misalnya dalam kitab yang sering menjadi rujukan di pesantren, akhlak lil banin dan akhlak lil banat karya Umar bin Ahmad Baraja. Sebab tentu saja latar kitab itu disusun perkembangan teknologi belum se-masif sekarang.
Lebih jauh, rumitnya soal tambang dan dampaknya terhadap lingkungan, izin pembangunan yang menabrak kawasan hijau, apakah dapat direspon dengan larangan membuang sampah sembarangan, dalam kitab akhlak yang belum terbarukan?
Landasan-landasan normatif dalam kitab-kitab akhlak tetap menjadi penting. Namun merespon permasalahan-permasalahan kontemporer menjadi tidak kalah penting.
Dalam hemat saya, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah berani untuk berdialog dengan kitab suci dengan bekal kualifikasi pendidik. Sepertinya ini suatu hal yang sangat idealis. Pada kenyataannya hal ini sebagai konsekuensi logis keimanan terhadap kitab suci yang selalu relevan pada setiap zaman.
Pendidik dengan kualifikasinya mestinya berani untuk menerjemahkan nilai-nilai normatif kitab suci ke dalam suatu keadaan zamannya.
Dalam Islam, dengan terang al-Qur’an mengajarkan agar tidak saling membully antar satu sama lain (QS. al-Hujurat: 11). Pada saat yang sama apa yang kerap terjadi hari ini adalah maraknya cyber-bullying. Sikap tersebut merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Ayat tersebut secara jelas, tanpa perlu membuka kitab tafsir sekalipun, dapat dipahami maksud tujuan ayat.
Persoalan lain, al-Qur’an juga mengingatkan agar tidak berperilaku fasik, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi dan gemar memutus silaturahmi (QS. al-Baqarah: 27).
Saya tergugah ketika mendialogkan ayat tersebut dengan tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, di dalamnya dengan keras lontaran kritik tentang perilaku-perilaku merusak bumi di antaranya adalah, “illegal logging (penebangan hutan secara liar), pencemaran lingkungan, emisi gas buang, yang akhirnya menciptakan global warming (pemanasan global).”
Maka, apakah kiranya berani untuk berdialog dengan kitab suci, tentu saja tidak lepas menggunakan perangkat keilmuan lain yang relevan.
Tak kalah penting juga terkait strategi pengemasan materi secara sederhana agar diinternalisasikan kepada peserta didik. Harapannya agar peserta didik menyadari nilai-nilai normatif pada satu sisi, serta kenyataan aktual yang dihadapinya pada sisi yang lain.
Dengan demikian, budi pekerti sebagai pelajaran tidak mesti juga dimunculkan kembali secara harfiah. Namun, fokus untuk membenahi akhlak peserta didik dan homo digitalis, adalah sejauh mana seorang pendidik mengkontekstualisasikan ajaran kitab suci sehingga berdialog dengan problem zaman.
Dalam hemat saya, budi pekerti tiada lain merupakan salah satu instrumen dalam internalisasi nilai terhadap peserta didik. Ruhnya terletak kepada mental pendidik yang secara terbuka menafsirkan kitab sucinya dengan situasi zaman. Wallahu a’lam bishawab.