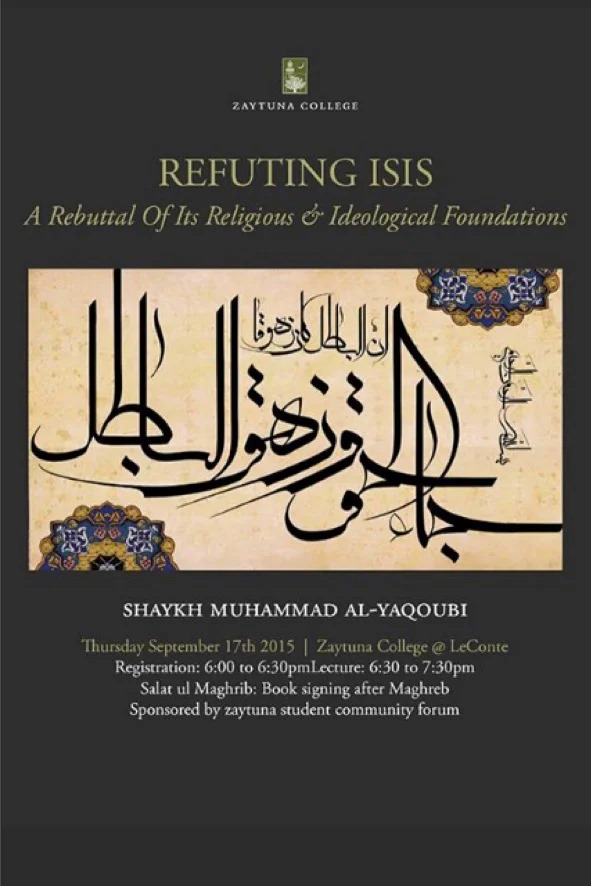Catatan Perjalanan Pulang di Akhir Tahun
Oleh; Ahsan Jamet Hamidi
Menjelang akhir tahun 2025, saya dan keluarga kecil memutuskan untuk pulang kampung. Kepulangan ini bukan semata untuk berlibur, melainkan juga untuk menyampaikan rasa duka atas berpulangnya suami dari keponakan saya. Saya memeluk erat keponakan dan kakak perempuan saya yang kini hampir berusia 75 tahun. Keduanya larut dalam tangis saat menceritakan kisah kebaikan suami dan menantu mereka.
Renungan Kematian
Setiap menemui peristiwa kematian, saya enggan membahas musabab yang mengantarkan seseorang pada ajalnya. Bagi saya, sakit hanyalah perantara. Banyak yang meyakini bahwa sakit menjelang kematian sejatinya merupakan pertanda bahwa Tuhan sedang memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat. Selama masih sadar, seseorang masih memiliki ruang untuk menyampaikan pesan belum sempat diselesaikan, baik berupa janji maupun utang.
Karena itu, sakit bukanlah penyebab kematian. Betapapun bonafidenya rumah sakit dan mahalnya pengobatan yang bisa dipenuhi seseorang, semua itu tak akan mampu menunda kedatangan malaikat pencabut nyawa. Bahkan, ada pula orang yang tak merasakan sakit sama sekali, namun ketika ajal menjemput, waktu itu tak pernah bisa ditawar.
Peristiwa ini membuat saya terus merenung di tengah keramaian suasana liburan. Kematian adalah penutup perjalanan hidup. Ia bisa datang kepada siapa saja, baik untuk mereka yang berada di puncak pencapaian hidup, ataupun yang tengah terpuruk di titik terendah, maupun yang menjalani hidup biasa-biasa saja tanpa gejolak, kematian tetap akan datang.
Dari setiap peristiwa kematian, saya terdorong untuk memperlakukan hidup ini dengan sikap yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena pada akhirnya, dalam kondisi apa pun saya berada, kematian akan mengakhiri segalanya. Usaha maksimal yang dapat saya lakukan hanyalah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi saat itu ketika ia tiba.
Kepekaan yang Tumpul
Peristiwa lain yang saya jumpai selama perjalanan jauh kemarin pun masih sama. Banyak kendaraan berpelat dinas milik instansi negara yang digunakan untuk keperluan liburan. Saya tidak mengetahui secara pasti, apakah kendaraan tersebut memang digunakan oleh pejabat yang berhak, atau hanya digunakan oleh oknum yang memakai pelat nomor palsu, atau kendaraan dinas itu sedang disalahgunakan.
Apa pun itu, seharusnya pengemudi dan pengguna kendaraan dinas itu menyadari bahwa mobil dinas itu dibeli dari uang pajak rakyat. Karena itu, cara mengendarainya semestinya mencerminkan keteladanan dalam berlalu lintas. Bukan justru sebaliknya. Dengan dalih menggunakan mobil dinas, ada oknum pengemudi yang berkendara secara arogan: memanfaatkan bahu jalan tol, menggunakan lampu sorot khusus untuk meminta keistimewaan, dan seolah merasa kebal aturan. Perilaku semacam ini hanya menunjukkan ketidakpekaan terhadap perasaan publik. Mungkin, karena ada pengabaian sehingga kepekaannya tumpul, rasa malunya terkikis oleh pangkat dan jabatan yang hanya sementara.
Pemandangan rutin lain yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah kondisi toilet umum di sepanjang rest area, tempat wisata, bahkan tempat ibadah yang saya jumpai selama perjalanan. Para perempuan—mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga nenek-nenek—terlihat mengantre dengan wajah gelisah. Mereka menahan ketidaknyamanan, bahkan rasa nyeri, demi segera buang air, namun terhalang oleh antrean panjang yang mengular.
Sementara itu, toilet laki-laki justru dapat digunakan dengan relatif leluasa tanpa harus menunggu lama. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana dan mudah diatasi. Andai para pengembang dan pengelola memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan hakiki, persoalan ini tak perlu terus terjadi. Jumlah toilet seharusnya dibangun secara proporsional: jika toilet laki-laki tersedia sepuluh bilik, maka toilet perempuan idealnya berjumlah tiga puluh atau bahkan lebih.
Secara alami, perempuan membutuhkan waktu lebih lama dalam menggunakan toilet. Durasi yang dibutuhkan bisa mencapai tiga kali lipat dibanding laki-laki. Karena itu, wajar jika antrean toilet perempuan hampir selalu panjang. Kepekaan batin dan pola pikir para pengembang serta pengelola perlu “di-reset” agar lebih peka terhadap persoalan sederhana yang solusinya pun sangat mudah.
Performa Seorang Kepala
Akhir tahun ini, saya pulang ke Ngawi, kampung halaman tempat saya lahir. Kota para pensiunan ini selalu menyimpan cerita tersendiri. Salah satu yang paling terasa adalah kondisi jalan menuju kampung halaman. Dulu jalannya bergelombang, namun kini perlahan mulai diperbaiki. Setelah sekian lama, diterapkan solusi sederhana: jalanan dengan tanah labil itu dicor agar lebih rata dan aman dilalui.
Ngawi juga memiliki beberapa tempat wisata menarik. Salah satunya adalah Benteng Pendem, atau nama resminya Benteng Van den Bosch, peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1841. Disebut “pendem” karena sebagian bangunannya berada lebih rendah dari permukaan tanah. Bertahun-tahun, tempat ini tampak terbengkalai dan terkesan angker. Kini suasananya jauh berbeda. Benteng telah ditata ulang menjadi bangunan tua yang tetap megah dan enak dipandang.
Di depan area benteng terdapat Migunani Café, tempat yang pas untuk nongkrong santai atau mengajak teman dari luar kota. Pilihan kopinya beragam dan unik, dengan rasa yang nikmat. Kafe ini menempati rumah tua dengan halaman cukup luas, suasananya sejuk, toiletnya bersih, dan tertata rapi. Bagi yang ingin duduk di ruangan ber-AC, tersedia pula area indoor yang nyaman.
Selain Ngawi, saya juga mengunjungi beberapa kota lain: Madiun, Yogyakarta, dan Semarang. Setiap pagi, saya membiasakan diri berjalan kaki mengelilingi kota sekadar untuk berolahraga. Dari aktivitas sederhana itu, saya justru menemukan cara paling jujur untuk menilai kualitas kepemimpinan sebuah daerah.
Trotoar adalah cermin paling dekat dari wajah kekuasaan. Jika jalur pejalan kaki bisa dilewati, terawat, rata, bersih dari sampah, dan bebas dari bau pesing, hampir bisa dipastikan pemerintah daerah hadir dan bekerja. Ruang publik dijaga, aturan ditegakkan, dan warganya dididik untuk tertib.
Sebaliknya, ketika trotoar berlubang dan membahayakan, dipenuhi pedagang kaki lima yang mengokupasi ruang pejalan kaki, sampah berserakan tanpa pengelolaan, dan sudut-sudut jalan berbau pesing, masalahnya bukan sekadar soal estetika. Itu adalah tanda kelalaian: negara, dalam hal ini pemerintah daerah, tidak hadir di ruang publiknya sendiri.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar mengapa pedagang kaki lima ada di trotoar, tetapi mengapa pelanggaran itu dibiarkan berlangsung lama. Apakah karena pembiaran, lemahnya pengawasan, atau praktik pungutan ilegal yang membuat pelanggaran terasa “resmi”? Ketika hukum bisa dinegosiasikan, yang dirugikan selalu sama: pejalan kaki, warga biasa, dan rasa keadilan. Pada akhirnya, kota bukan dinilai dari baliho pencitraan atau slogan di sudut jalan, melainkan dari hal-hal paling sederhana: trotoar yang bisa dilalui dengan aman, udara yang bersih, dan ruang publik yang benar-benar milik bersama.
Di pojok sebuah alun-alun, saya melihat pedagang balon, tukang becak, dan tukang parkir sedang asyik berdiskusi. Sesekali mereka menghirup kopi dan mengisap rokok sambil menatap secarik kertas dan bolpoin di tangan masing-masing. Dari gerak-gerik mereka, tampak seperti sedang menghitung angka-angka serius. Karena penasaran, saya mendekat, dan baru tahu ternyata mereka sedang meramal nomor keramat yang diyakini akan keluar nanti malam minggu.
“Beli nomor memang tidak membuat kita kaya, Mas,” kata salah satu dari mereka sambil menyeruput kopi. “Kalah atau menang itu biasa saja, tapi yang pasti, ini membuat kita bahagia. Kebahagiaan kecil seperti ini, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan lho...”
Ketiganya terkekeh sambil mengisap rokok dan meneguk kopi pahit. Ada semacam kehangatan sederhana dalam tawa itu, sebuah kebahagiaan yang lahir dari hal-hal kecil di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota.
Kesan cukup mendalam dari perjalanan ini adalah bahwa kematian akan mengakhiri siapa pun. Baik mereka yang berada di puncak pencapaian maupun yang sedang terperosok di dasar kehancuran. Kualitas seorang pemimpin terlihat dari kemampuannya menangani hal-hal sederhana: toilet, trotoar, sampah, dan ruang publik. Sebagai penutup, kebahagiaan sejati sering lahir dari hal-hal kecil, tumbuh dari kualitas hubungan antar manusia yang saling menghargai. Menjalani hidup dengan kesederhanaan menjadi penting, karena pada akhirnya, semua akan berakhir dengan kematian.