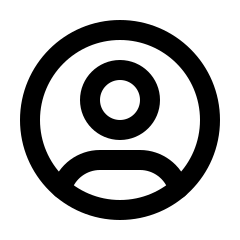Oleh: Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Ada empat aliran pemikiran besar tentang hukum Islam dalam tradisi Sunni. Umumnya kita menyebutnya madzhab. Bagaimana berbagai madzhab ini menafsirkan atau memahami hadits? Untuk itu, kita perlu melihat hubungan antara hukum Islam, Al-Qur’an, dan hadits. Hukum Islam tidak mungkin ada tanpa Al-Qur’an. Tanpa Al-Qur’an maka kita tak akan mengenal hukum Islam kecuali kita mengambil pemahaman yang lebih luas dan generik tentang Islam, yang berarti penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi tanpa Al-Qur’an, hukum Islam tidak akan ada. Fakta menunjukkan hukum Islam memang sudah tegak sebelum kompilasi hadits ditulis.
Hal ini sangat penting untuk dipahami. Munculnya berbagai madzhab dalam Islam merupakan bukti positif atas hal ini. Madzhab sudah ada sebelum kompilasi buku hadis, yang hari ini kita kenal sebagai enam kitab hadits (Kutubus Sittah) yang sahih—Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Al-Jami' Imam At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah.
Mari kita berbicara waktu. Yang paling awal dari enam kitab hadits ini ditulis oleh Imam Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. 256 minus 11, artinya Imam Bukhari meninggal 245 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Jika Imam Bukhari menulis bukunya menjelang akhir hidupnya, maka beliau menulis dua abad setelah Nabi SAW meninggal.
Kita mulai dengan gagasan ini. Ada empat madzhab dalam yurisprudensi Islam. Sekali lagi, madzhab ini muncul lebih awal dari penulisan koleksi hadits. Semuanya tak akan lahir tanpa Al-Qur’an namun eksis tanpa kompilasi kitab-kitab hadits. Ini bukan berarti tanpa hadits karena masyarakat Islam sudah mengenal hadits yang menyebar secara lisan. Mereka mengingat atau memiliki kenangan tentang apa yang dikatakan, dilakukan dan hal-hal yang terjadi di hadapan Nabi SAW. Semua preseden ini membentuk hukum Islam. Tetapi mereka tidak mendasarkan hukum Islam pada kitab-kitab hadits. Mereka melandaskan pada apa yang mereka ketahui tentang hadits, sedikit atau banyak.
Sering dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak memiliki sedikit akses ke hadits. Banyak sarjana Muslim yang tidak percaya ini, bahwa dia memiliki kendala mengakses hadits. Isu ini kerapkali menjadi ciri khas aliran pemikiran Hanafi yang tidak terlalu bedasarkan hadits. Pendapat ini sukar diterima. Mereka bukan tidak memiliki sirkulasi hadits karena pada waktu orang suka bepergian. Masyarakat bepergian untuk melakukan ziarah ke Makkah dan berkunjung ke Madinah untuk melihat, shalat dan beribadah di masjid Nabawi.
Ketika bepergian, biasanya mereka menghabiskan waktu yang lama. Tidak seperti kita sekarang. Kita naik pesawat lalu menghabiskan satu hari dan kembali. Waktu itu perjalanan yang dilakukan kaum Muslimin relatif panjang. Begitu sampai di Makkah atau Madinah, misalnya, mereka menetap di sana beberapa hari bahkan berbulan-bulan sebelum kembali. Saat menetap di sana, mereka berinteraksi dengan banyak ulama yang juga melakukan haji dari berbagai belahan dunia. Jadi mereka semua memiliki berbagai informasi. Mereka berbagi satu sama lain. Jadi informasi itu tidak kurang.
Namun Imam Abu Hanifah memiliki cara khusus ketika berhubungan dengan riwayat tentang Nabi SAW. Imam Abu Hanifa meninggal sekitar tahun 150 Hijrah. Jadi 139 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Dia menulis karyanya dalam 20 tahun terakhir hidupnya, itu berarti seabad setelah kematian Nabi SAW. Ini dilakukan sebelum kompilasi kitab-kitab Hadis.
Lalu apa yang menjadi prinsip-prinsip Imam Abu Hanifah? Mengapa dia menolak hadits tertentu, yang kemudian dikumpulkan dalam kompilasi kitab-kitab hadits seperti yang kita miliki sekarang? Boleh jadi dia menolak hadits tertentu karena hadits ini hanya terkait oleh beberapa orang dan terkait dengan fenomena yang akan disaksikan oleh banyak orang. Ini menyangkut hal-hal yang diriwayatkan oleh sebagian besar orang. Ini memiliki implikasi terhadap cara berpikir.
Sebagai misal, kita ingin mengetahui awal Ramadhan. Ada satu orang yang mengatakan dia melihat hilal, bulan sabit yang menandai awal bulan baru, tetapi saat itu langit cerah. Tentu kita berharap bukan hanya satu orang yang melihatnya, tetapi banyak orang. Tentu saja, tidak semua orang, seperti mereka yang memiliki penglihatan yang buruk atau yang menderita penyakit mata. Tetapi kita berharap kerumunan orang yang menyaksikan adanya bulan sabit dengan jelas. Tetapi jika langit mendung maka hanya mereka yang punya kehati-hatian melihatnya. Maka mungkin kita bisa memaafkannya, “Baiklah. Ada satu orang melihatnya dan pandangannya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan.”
Kembali kepada pembicaraan tentang hadits, jika satu orang meriwayatkan dan kita tahu ini seharusnya diriwayatkan sebagian besar pihak, maka ini mencurigakan. Dalam konteks ini, Imam Abu Hanifah tidak memercayai orang seperti ini. Ini sama saja dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seseorang yang bukan ahli agama atau ulama, dan juga bertentangan dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh seseorang yang dikenal sebagai sarjana Muslim atau ulama—bersambung. *