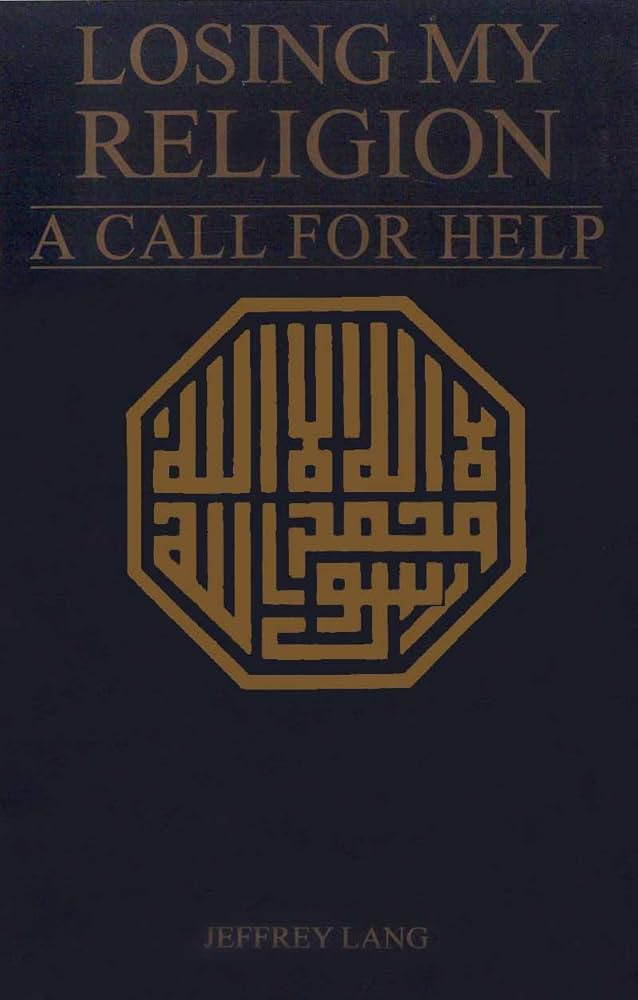Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Imam Syafi'i memberi banyak penekanan pada hadits. Beliau menulis sebuah buku yang sebenarnya menguraikan prinsip-prinsip ini berjudul Al-Risalah. Karya ini telah menjadi karya klasik karena untuk pertama kalinya teori hukum Islam dipaparkan secara tertulis.
Imam Syafi'i berbicara lebih dari sekadar keaslian hadits. Dia menyinggung tingkat otoritas hadits tertentu sebagai argumen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab dan hikmah kepada Nabi SAW, artinya Al-Qur’an dan kebijaksanaan. Beliau menegaskan bahwa kebijaksanaan di sini merujuk kepada hadits, karena dua hal ini diwahyukan kepada Nabi SAW, kitab dan hikmah. Kitab tidak diragukan lagi adalah Al-Qur’an dan hikmah di sini adalah hadits.
Tentu saja kata ‘hikmah’ di sini tidak harus berarti hadits. Al-Qur’an sendiri bahkan menyebut dirinya sendiri ‘kebijaksanaan’—wal Qur’ânul hakîm (QS 36: 2). Al-Qur'an sendiri disebut hikmah. Itu bukan sesuatu yang lain. Kita dapat mengatakan bahwa Nabi SAW adalah orang yang bijaksana. Dan itulah sebabnya Allah memilihnya sebagai kendaraan untuk menjadi pengajar dan pembimbing bagi umatnya dan melaluinya Al-Qur'an diturunkan.
Kita dapat mengatakan bahwa Allah mengilhami dan membimbing Nabi SAW sehingga secara internal beliau mengatakan dan melakukan hal-hal yang penting untuk membimbing masyarakat, sebagai ‘oposan’ dari orang lain yang mendorong dosa dan menyesatkan masyarakat. Jadi dalam hal itu kita bisa mengatakan bahwa tindakan dan ucapan Nabi SAW adalah bagian dari kebijaksanaan jika dipahami secara lebih luas.
Namun jika kita berpikir bahwa Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk mengikuti hadits sebagai sebuah korpus yang disebut hikmah dalam ayat ini, maka tidak semua ulama dan sarjana Muslim yang sepakat dengan Imam Syafi'i dengan argumennya bahwa Al-Qur’an menggunakan kata ‘hikmah’ yang merujuk kepada hadits sebagai sebuah korpus yang disusun.
Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi setelah Imam Syafi'i memberikan penekanan besar pada hadis, muncullah Ahmad bin Hanbal. Dia meninggal di awal abad ketiga hijriah. Jadi beliau hidup beberapa ratus tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Dia lebih menekankan pada hadits. Baginya, lebih baik mengandalkan hadits yang lemah daripada bergantung kepada rasio atau pertimbangan manusia yang lemah.
Jadi lagi-lagi kita menyaksikan upaya menyeimbangkan antara penggunaan akal dan ketergantungan pada hadits. Jika kita merenungkan sesuatu dan tiba-tiba seseorang datang dan berkata bahwa Nabi mengatakan sebaliknya, tentu kita akan meninggalkan apa yang kita pikirkan demi mengikuti apa yang diucapkan Nabi SAW. Jadi begitu hadits masuk, maka pemikiran terhenti. Karenanya, pada zaman Ahmad bin Hanbal terjadi bentrokan antara pemikiran (`aql) dan penggunaan hadits (naql), antara dirayah (penilaian/pertimbangan manusia) dan riwayah (informasi yang diceritakan), yakni hadits. Di era Ahmad bin Hanbal, dirayah atau rasio dipinggirkan dan riwayah atau informasi yang ditransmisikan (hadits) sangat ditekankan. Bagi Ahmad bin Hanbal, jika kita memiliki hadis yang lemah, ini lebih baik daripada menggunakan akal. Mungkin saja Nabi mengatakannya, mungkin saja tidak mengatakannya. Ini lebih baik dengan segenap kemungkinannya daripada mengikuti akal pikiran manusia yang mungkin menyesatkan orang.
Perlu dicatat bahwa Ahmad bin Hanbal berkontribusi menyusun koleksi 30.000 hadits. Riwayat hadits ini meliputi apa saja—makan, minum, pergi ke kamar mandi, tidur dan lain-lain. Semua ini dimaktub dalam kitab-kitab hadits ini. Kitab-kitab hadits yang terkenal saat ini kemudian disusun di pertengahan dan menjelang akhir abad ketiga hijriah. Ahmad bin Hanbal telah meletakkan landasan bagi kita untuk menerima hadits, bahkan yang lemah sekalipun. Para sarjana Muslim kemudian berusaha untuk membedakan mana hadits yang asli dan yang tidak asli, yang sahih dan yang lemah.
Meskipun madzhab lain menekankan akal atau rasio, berkat kekuatan buku cetak, sarjana Muslim mencoba untuk menyelaraskan rasionalitas dan hadits. Jadi ada upaya untuk menyesuaikan pemahaman sesuai dengan hadits. Satu hal yang perlu disyukuri bahwa madzhab dalam Islam ini sudah hadir mendahului kompilasi kitab-kitab hadits yang utama.
Madzhab ini berkembang dan tertanam kuat lewat praktik-praktik tertentu yang bertentangan dengan perkembangan hadits di masa berikutnya. Itulah mengapa kita menemukan, misalnya, madzhab Hanafi, yang merupakan yang paling awal dari empat madzhab, dalam keyakinan dan praktik keagamannya memiliki banyak perbedaan dengan apa yang termaktub dalam koleksi kitab-kitab hadits yang utama. Perbedaan ini dapat mengingatkan kita akan fakta bahwa madzhab dalam Islam sudah berdiri mapan sebelum penulisan kitab-kitab hadits yang utama. Artinya, umat Islam bisa survive tanpa kitab-kitab hadits, tetapi tidak akan mampu hidup tanpa Al-Qur’an—Tamat. *