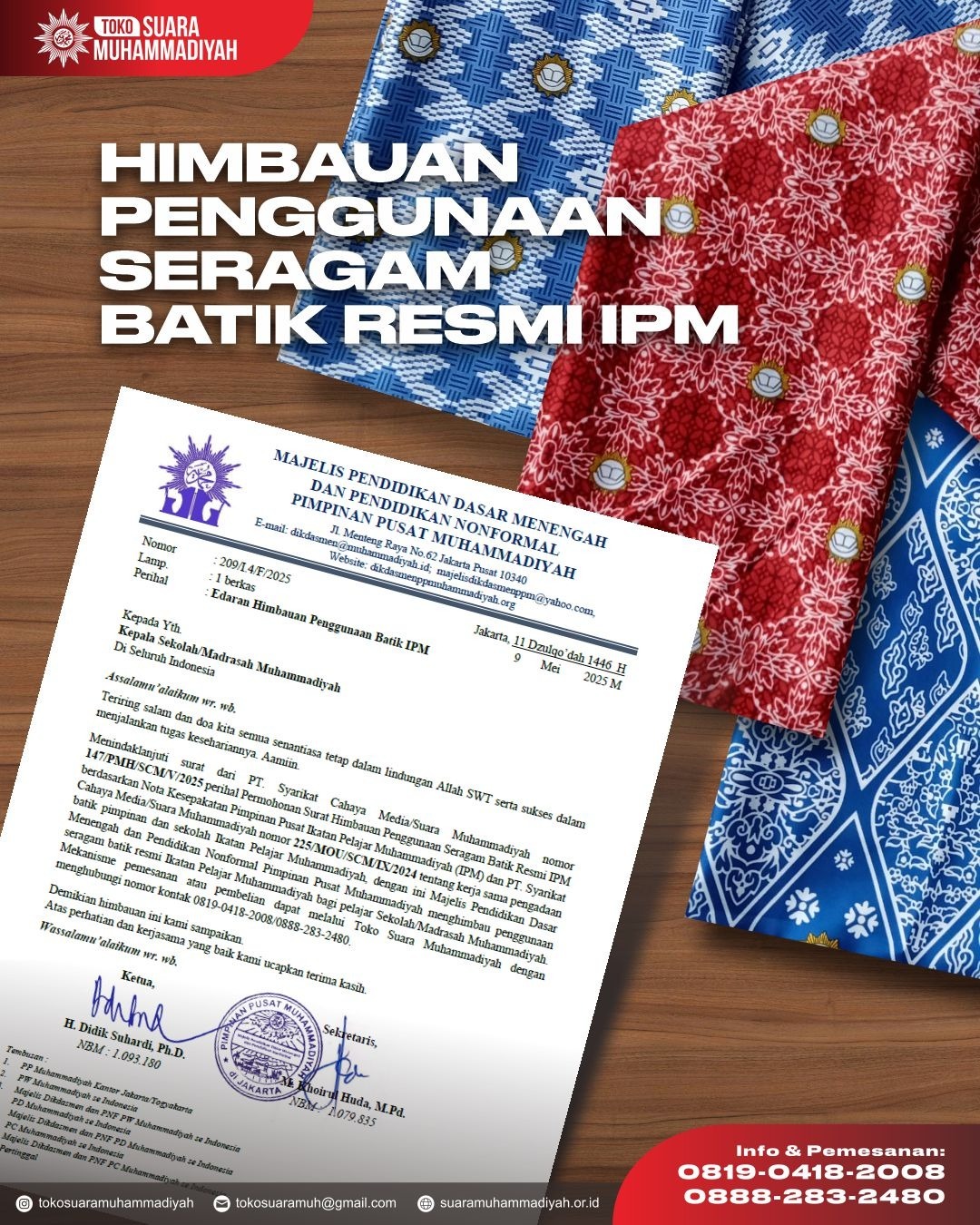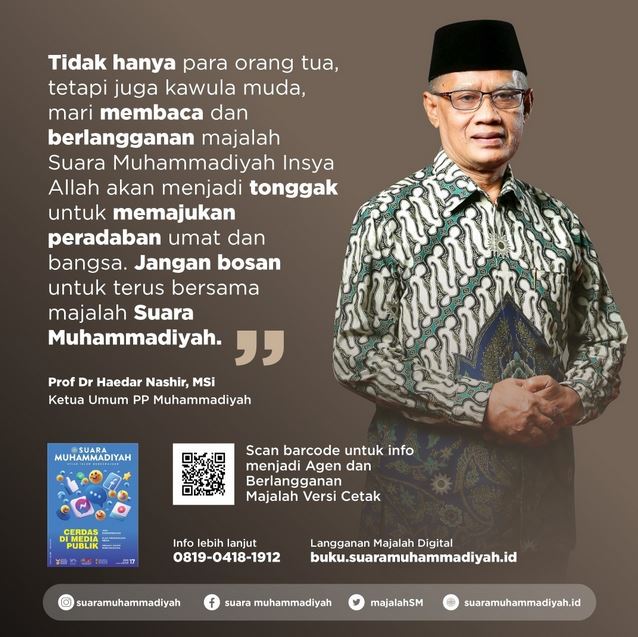Kesucian, Kebersihan, dan Keragaman: Potret Ibadah di Masjidil Haram
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Legoso, Wakil Sekretaris LPCRPM PP Muhammadiyah
Pernahkah pembaca menonton konser Bon Jovi pada tahun 2015 di Jakarta? Saat itu, kurang lebih 40 ribu orang berkumpul di satu tempat, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Bisa dibayangkan bagaimana keriuhan para penonton saat memasuki area pertunjukan dan mencari tempat duduk sesuai tiket yang dimiliki, serta ketika mereka keluar dari gedung setelah pertunjukan usai.
Suasana di dalam stadion tentu sangat dinamis. Para penonton berjubel keluar-masuk dengan kondisi emosional yang berbeda-beda. Aksi senggol-menyenggol antarpengunjung kadang bisa menyulut emosi dan berpotensi menjadi keributan. Kesamaan niat untuk menikmati pertunjukan musik sama sekali tidak menjamin adanya komitmen bersama yang dapat menumbuhkan perilaku baik dan santun selama pertunjukan berlangsung.
Bayangkan pula bagaimana kondisi toilet di stadion tersebut. Biasanya, tidak terjadi antrean panjang di toilet laki-laki karena aktivitas buang air kecil bagi laki-laki relatif sederhana. Berbeda halnya dengan perempuan, yang secara alamiah membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, antrean di toilet perempuan bisa mengular panjang. Perilaku pengguna toilet pun sangat beragam. Ada yang membersihkan bekas pakainya dengan siraman air yang cukup hingga kembali bersih, namun ada juga yang tidak melakukannya.
Keriuhan serupa juga dialami para jemaah haji saat melaksanakan salat di Masjidil Haram pada musim haji. Bedanya, niat para jemaah adalah untuk beribadah. Namun demikian, niat itu pun tidak menjamin akan nihilnya aksi saling senggol—kadang juga saling sikut—yang terjadi antarsesama jemaah. Saya, yang berpostur pendek dan relatif kecil, sering kali menjadi korban: tersenggol, tersikut, kaki terinjak, hingga tubuh terdorong dan terpental jauh oleh jemaah lain yang bertubuh jauh lebih besar dan kuat.
Kesucian Tempat Suci
Awalnya, saya kaget saat pertama kali memasuki Masjidil Haram, yang disebut sebagai tempat suci bagi umat Muslim di seluruh dunia. Lazimnya, ketika masuk masjid di Indonesia, saya pasti akan melepaskan sandal atau sepatu karena dianggap kotor, dan masjid haruslah suci. Jika tidak, hampir pasti akan mendapat teguran dari jemaah lain. Namun, etika melepas alas kaki ternyata tidak berlaku di Masjidil Haram. Banyak orang tetap mengenakan sandal atau sepatu, bahkan saat mereka melakukan tawaf dan sai. Para polisi dan tentara yang bertugas pun tetap memakai sepatu militer. Area yang mereka pijak tetap digunakan oleh jemaah lain untuk salat.
Andaikan saya menerapkan prinsip fikih secara kaku bahwa tempat tersebut tidak suci dan tidak layak untuk salat, maka saya akan sangat kesulitan untuk bisa melaksanakan salat. Di sisi lain, jika saya meyakini bahwa bersentuhan dengan kulit perempuan membatalkan wudu, maka saya bisa mengalami puluhan hingga ratusan kali batal saat hendak salat. Sebab, untuk menuju area masjid, saya pasti akan berdesak-desakan hingga berisiko bersentuhan dengan banyak perempuan.
Demikian pula jika saya meyakini bahwa salat berjemaah di belakang perempuan tidak sah, maka salat saya bisa batal. Kenyataannya, saya tidak bisa melarang ketika, di tengah salat, tiba-tiba ada perempuan yang ikut salat di depan atau di samping saya—bahkan sangat dekat. Saya memakluminya karena memang sedang dalam keadaan darurat. Saya menerapkan kaidah dalam ushul fikih bahwa “ad-dharurat tubihu al-mahdzurat”, yang berarti “keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”
Kebersihan dan Etika di Toilet Masjid
Di Masjidil Haram, semestinya ada kesadaran standar dari para pengguna toilet, yaitu menyiram setelah digunakan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa “kebersihan adalah bagian dari iman.” Maka, menjaga kebersihan toilet adalah bagian dari ukuran harga diri seseorang dan bisa menjadi standar untuk menilai kualitas kemanusiaan seorang Muslim yang beriman.
Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Bukan hanya tidak membersihkan kotoran, sebagian orang bahkan tidak punya etika dalam antrean. Mereka tahu ada orang yang menunggu di depan pintu, tapi tetap menerobos tanpa peduli. Keributan sering terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap aturan antre, yang seharusnya menjadi kesadaran kolektif.
Keragaman Cara Beribadah
Saat bersembahyang di Masjidil Haram, saya mendapati begitu banyak ragam praktik salat. Ada yang meletakkan tangan di bawah dada sambil bersedekap setelah mengucapkan “Allahu Akbar”, ada pula yang membiarkan tangan lurus ke bawah. Ada yang matanya fokus pada tempat sujud, namun ada pula yang menoleh ke kanan, kiri, bahkan ke atas saat mengikuti salat berjemaah. Saat duduk pada tasyahud akhir, ada yang mengacungkan jari, ada yang tidak. Ada yang mengacungkan dari awal, ada pula yang di tengah. Bahkan, cara duduk antara dua sujud dan saat tasyahud pun berbeda-beda.
Melihat ragam cara bersembahyang umat Islam dari berbagai belahan dunia, saya bertanya dalam hati: manakah sejatinya yang paling benar di antara sekian banyak variasi itu? Jika saya bersikap fanatik, merasa paling benar, lalu gemar menyalahkan praktik salat orang lain, apakah ada jaminan bahwa kebenaran yang saya yakini saat ini juga diakui sebagai kebenaran oleh Allah kelak di hari pengadilan?
Saya menyadari bahwa meskipun kita sama-sama merujuk pada Al-Qur’an dan hadis yang sama, peluang perbedaan dalam praktik tetap terbuka lebar. Saya pun berkesimpulan bahwa level kebenaran tertinggi saya hanyalah sebatas upaya untuk meraih kebenaran menurut versi yang saya yakini. Namun, kebenaran hakiki hanya akan saya temukan di akhirat kelak.
Semoga saya dan para pembaca senantiasa diberi ampunan dan keridaan Allah dalam setiap upaya menegakkan kebenaran yang sama-sama kita yakini. Aamiin.