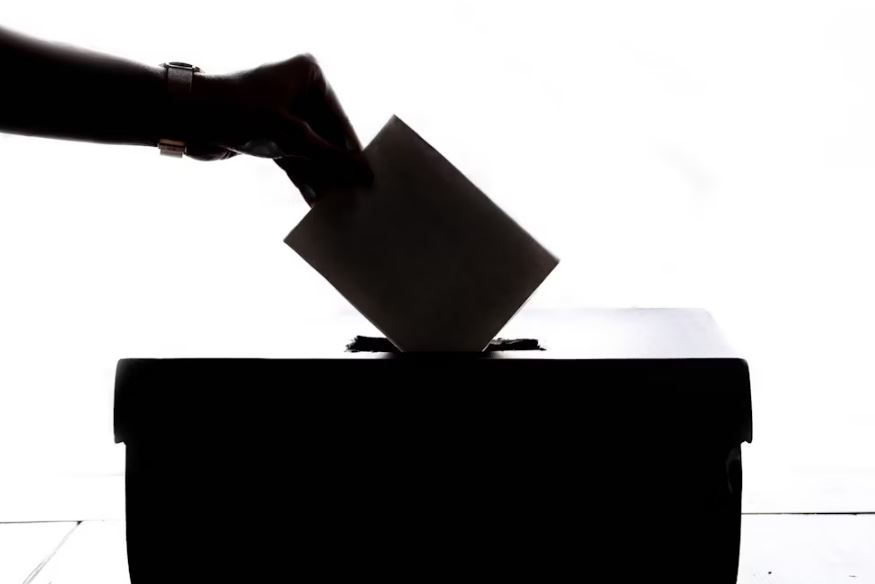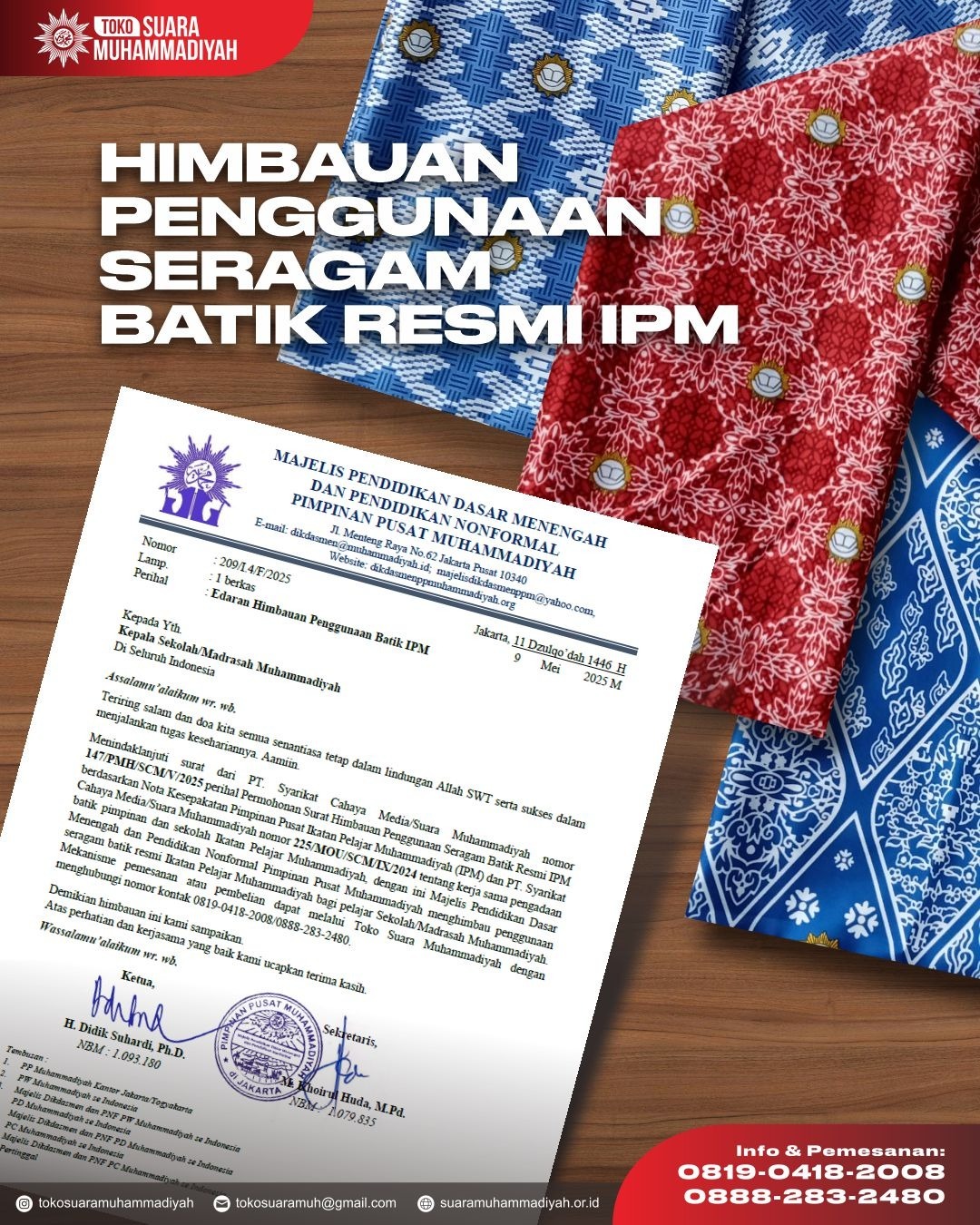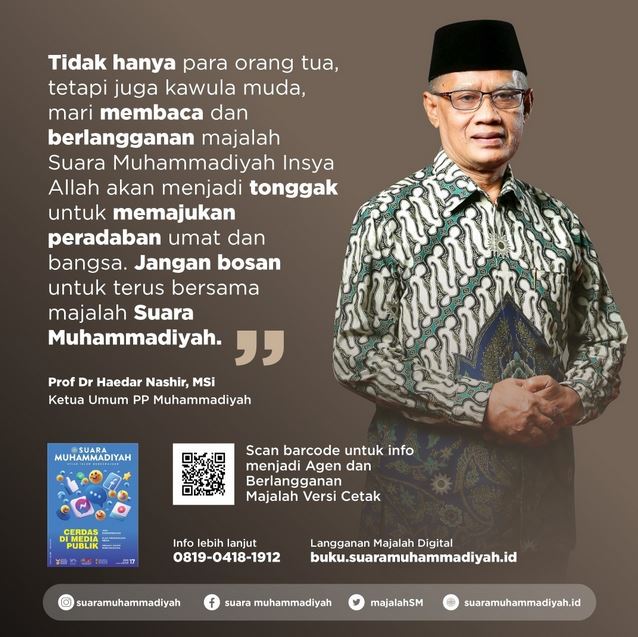Hujan deras terus turun seperti tidak pernah berniat reda. Pada 26 November pagi, saya mendapat pesan dari ibu tentang air yang mulai naik di depan dan belakang rumah kami di Pante Gajah, Peusangan, Bireuen. Sementara di banyak rumah warga lainnya, air sudah mulai masuk sejak dini hari. Siangnya, ibu mengabari bahwa air dan lumpur telah merangsek ke dalam rumah, dan volumenya terus naik. Menjelang sore, ibu mengabari bahwa ia, tante, dan nenek kami yang sudah berusia hampir 90 tahun, mulai mengungsi ke masjid yang letaknya lebih tinggi. Kabar itu menjadi yang terakhir. Setelah pesan itu, tak ada lagi akses komunikasi, berhari-hari.
Memang, sejak pertengahan November 2025, langit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menggelap, menumpahkan air dari sistem cuaca yang dipengaruhi Siklon Tropis Senyar: siklon yang lahir dari Bibit Siklon 95B pada 26 November 2025. Fenomena ini jarang terjadi tepat di perairan dekat Indonesia, dan ketika terjadi oleh karena iklim yang turut berubah, ia membawa dampak masif pada kawasan yang secara geografis sudah rentan terhadap banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor. Banjir dan longsor juga menghantam Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Sri Lanka.
Siklon Senyar menciptakan kombinasi buruk antara curah hujan ekstrem, angin kencang, dan kejenuhan tanah. Tiga provinsi di ujung barat Sumatra menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Sungai dan segala isi perutnya tumpah ruah. Ratusan ribu warga terdampak. Jalan raya putus. Pasokan logistik tersendat. Akses bantuan terbatas dan tak mampu menjangkau semua korban. Diperparah dengan padamnya listrik dan internet. Lengkap sudah. Ditambah lagi, di balik tragedi itu, tampak ketimpangan tentang bagaimana bencana besar di provinsi pinggiran sering berjalan dalam sunyi panjang, tak sepenuhnya masuk dalam radar nasional.
Di Aceh, sejak 19–20 November 2025, hujan turun seperti tirai tebal yang tak bisa disibak. Sungai-sungai meluap dan menerjang permukiman di Aceh Utara dan Langsa. Air bah menghantam perkampungan, menenggelamkan rumah dan memaksa warga mengungsi dalam gelap. Ribuan rumah terendam lumpur. Sebagian besar warga terpaksa mengungsi hanya dengan pakaian di badan dan kelaparan yang entah sampai kapan. Sebagian masih ada yang bertahan dan terjebak di atap rumah bersama bayi dan lansia. Mereka yang rumahnya hanya bisa dicapai dengan melewati jembatan, kini benar-benar terisolasi. Beberapa jembatan ambruk, sebagian lagi tidak bisa dilewati karena arus air masih tinggi.
Sering berulang, listrik padam total berhari-hari, bahkan ketika tidak ada bencana. Terlebih saat situasi seperti ini, gardu induk di beberapa kecamatan terendam air. Lima tower SUTT 150 KV milik PLN roboh diterjang banjir dan longsor. Sinyal telepon dan internet hilang. Banyak warga yang bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar desa mereka. Di daerah yang sejak dulu berada jauh dari hiruk-pikuk nasional, bencana terasa berbeda dan menuntut solidaritas sesama warga semata. Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana pada 28 November hingga 2 pekan ke depan.
Sumatera Utara juga mengalami dampak besar. Data Pusdalops PB Sumut menyebut 13 kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan longsor. Bencana kali ini bukan kejadian lokal; ia merentang dari pesisir ke dataran tinggi, dari perbatasan Aceh hingga kaki-kaki gunung di wilayah Tapanuli. Di beberapa titik, longsor memutus sepenuhnya akses jalan. Badan jalan tertimbun lumpur dan bebatuan. Sementara itu, banjir bandang di desa-desa sekitar Daerah Aliran Sungai menggerus rumah-rumah kayu hingga rata tanah.
Laporan sementara, pada 27 November 2025 siang, menyebut 34 orang meninggal dan 52 orang hilang. Angka yang mungkin bertambah, karena pencarian terkendala medan dan cuaca. Para relawan yang sangat terbatas itu tidak bisa masuk ke desa-desa terdampak, sehingga warga harus bertahan sendiri tanpa makanan, tanpa pakaian kering, dan tanpa kepastian. Ada warga yang menggunakan rakit darurat dari batang pisang untuk menyeberangi arus demi mencari pertolongan. Pohon-pohon tumbang menutup jalan selama berjam-jam, membuat ambulans tidak bisa lewat. Kisah-kisah seperti ini sering hanya menjadi cerita lokal, padahal menggambarkan betapa gentingnya situasi sebenarnya.
Sumatera Barat, yang wilayahnya didominasi perbukitan dan lembah sempit, mengalami serangkaian longsor yang tidak kalah mengerikan. Pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat bencana sejak 25 November hingga 8 Desember 2025. Di beberapa ruas jalan nasional, alat berat harus bekerja siang-malam untuk membersihkan material tanah dan batu yang terus turun akibat curah hujan yang belum mereda. Di sejumlah kecamatan, warga harus mengungsi ke masjid atau sekolah yang berada di lokasi lebih tinggi.
Sampai 27 November malam, lebih dari lima jembatan utama yang menghubungkan jalan nasional Aceh-Sumut putus. Artinya, semua jalur pasokan logistik ke Aceh terhenti. Berbeda dengan di pulau Jawa yang punya akses mudah, jalan darat di provinsi pinggiran hanya punya satu jalur utama dan menjadi satu-satunya. Tak ada laternatif transportasi yang bisa diakses. Ketika jalur itu putus, maka semua nasib hidup mereka di seberang jalur itu ikut terhenti. Jutaan orang terdampak situasi ini.
Pada 28 November pagi, jumlah korban meninggal sudah mencapai angka 79 orang (47 di Sumatera Utara, 13 di Aceh, sisanya di Sumatera Barat) serta 115 orang hilang (95 di Sumatera Barat, 5 orang di Aceh, dan 15 di Sumatera Barat). Data ini masih terus bertambah di tengah terputusnya jalur komunikasi dan terbatasnya personil relawan.
Di tengah berbagai situasi mengerikan itu, pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional. Luasnya dampak banjir di tiga provinsi di Sumatera itu belum menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Padahal, data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tentang banjir pada 18-27 November 2025, terdapat 16 Kabupaten/Kota di Aceh yang terdampak langsung (Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan). Di Sumatera Utara, data BNPB menunjukkan bahwa bencana terjadi di 13 Kabupaten/Kota. Demikian halnya di Sumatera Barat, ada 13 Kabupaten/Kota yang terdampak langsung.
Ada paradoks tentang bencana sebesar ini tidak mendapat perhatian nasional sebesar dampaknya. Mengapa? Isolasi fisik dan digital membuat informasi terlambat keluar. Ketika listrik padam, jalan terputus, dan internet hilang, suara warga tidak bisa menembus batas-batas kabupaten. Selain itu, media nasional cenderung memprioritaskan pusat-pusat urban, tempat kamera bisa dengan mudah datang dan sinyal internet tidak pernah mati. Mungkin juga ada faktor bias historis bahwa provinsi-provinsi di pinggiran sering dilihat sebagai wilayah yang jauh secara geografis, juga secara politis dan kultural. Bayangkan jika bencana sebesar ini terjadi di Jakarta atau daerah yang lebih dekat.
Sementara itu, linimasa media sosial lebih riuh memperbincangkan kasus perselingkuhan selebgram syariah, tumbler, ijazah palsu, dan konflik pucuk pimpinan ormas Islam. Mungkin di mata sebagian mereka, bencana demi bencana di pulau-pulau yang isi perutnya terus dikeruk dan menanggung beban emisi itu dianggap suratan takdir biasa, dan terhadap orang-orang yang peduli dipandang sebagai “wahabi lingkungan” yang tidak moderat dan tidak toleran. Ya, tidak toleran terhadap pengrusakan alam. (Muhammad Ridha Basri)