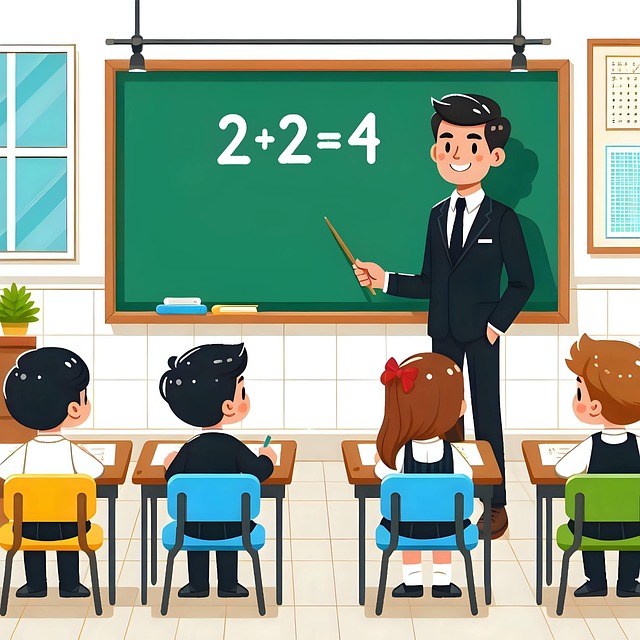Memahami Impian Rakyat
Oleh: Sobirin Malian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Ketika rakyat hanya dijadikan obyek pendulang suara maka berhati-hatilah para anggota dewan! Apalagi kalau rakyat sekadar dijadikan untuk legitimasi kekuasaan. Pada saatnya, akan terjadi arus balik dimana wakil rakyat justru tidak lagi dipercaya rakyat. Fenomena itulah yang terjadi tatkala demo besar-besaran terjadi pada 22 Agustus 2024 kemarin.
Demonstrasi besar-besaran di berbagai kota kemarin memberi pesan, mereka sulit menerima bentuk demokrasi yang dibegal. Rakyat__dari kalangan manapun__ selama ini sering dimanipulasi untuk berbagai kepentingan kekuasaan. Dan biasanya diakhiri dengan opini berupa pertanyaan, “lantas rakyat mana yang sebenarnya yang diperjuangkan?”
Mendefinisikan siapakah rakyat dan apa yang diperlukannya memang tidak mudah. Rakyat dalam pengertian umum merujuk pada penduduk suatu negara,titik. Namun, dalam kajian filosofis sosial, ia adalah suatu entitas yang abstrak sehingga Pierre Rosanvallon, dalam sebuah penelitiannya tentang representasi di Perancis melukiskan rakyat sebagai entitas “tak terjumpa” (unfounded). Artinya, rakyat sebagai suatu kesatuan, sebagai identitas, atau sebagai suatu totalitas tidak dapat dijumpai secara konkret. Makna ini sebenarnya yang “dipermainkan” oleh para anggota dewan atau penguasa itu sehingga berujung pada pertanyaan, “rakyat yang mana?”. Termasuk di DPR kita manakala mereka segera merespon Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70 itu.
Masih terkait dengan keadaan di atas, konsep “perwakilan” (representasi) sendiri sering menjadi bahan perdebatan. “Perwakilan rakyat” mengandung dua makna yang terbedakan satu dengan yang lainnya dan perlu mendapatkan perhatian. Di satu sisi ia menunjuk pada “penghadiran simbolik” rakyat dan di sisi lain ia pahami sebagai “perutusan” atau pemberian mandat politik (Free Merriam-Webster Dictionary, 2012). Dalam sistem pemerintahan demokratis, mereka yang disebut wakil rakyat menghadirkan secara simbolik rakyat yang “tanpa wajah” itu dan juga secara yuridis mendapatkan legitimasi untuk berkuasa atasnama rakyat.
Narasi “tanpa wajah” itu telah menempatkan rakyat dalam posisi rawan untuk terabaikan atau ia terpajang sekadar sebagai “penguasa simbolik”, sedangkan kekuasaan yang sesungguhnya ditentukan oleh mereka yang “terlanjur” diberi mandat sebagai “wakil atau penyambung lidah.” Adakah jalan untuk merajut keterkaitan antara rakyat yang diwakili dan pejabat yang mewakili, antara rakyat yang memberi mandat dan penguasa yang diberi mandat?
Dalam rezim pemerintahan demokratis, kehendak atau aspirasi rakyat merupakan “tali perajut” yang menghubungkan rakyat dan wakil rakyat. Giovanni Sartori, membantu mendeskripsikan hakikat demokrasi modern dengan penegasannya bahwa kata ”demokrasi” pertama-tama dan terutama adalah sebuah kata normatif dan bukan deskriptif. Demokrasi tidak mendeskripsikan suatu hal tertentu, tetapi lebih pada meletakkan/ menetapkan sebuah ideal. Yang harus dipahami juga, demokrasi dalam dirinya menyimpan potensi utopis bagi masa depan, kata Giovanni Sartori (1968).
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam demokrasi representatif para calon kepala daerah atau calon anggota legislatif justru “menjual impian”. Oleh karena itu, parta-partai politik pun berlomba “menangkap aspirasi” sebagai kendaraan mendapat mandat kekuasaan. Kampanye lalu menjadi ajang “menjual impian” demi legitimasi kekuasaan.
Teladan dan Populisme
Kesulitan menghadirkan aspirasi sesungguhnya berakar dari ketiadaan penjelasan yang mampu menyepakati apa yang sedang diperjuangkan terutama untuk rakyat konstituennya. Disinilah seperti dikatakan Mohammad Hatta, demokrasi bisa memakan rakyatnya sendiri. Mustahil mampu menangkap dan merumuskan apa yang diinginkan rakyat itu jika para wakil rakyat hanya berorientasi pada kekuasaan seperti dibentuknya koalisi KIM (koalisi Indonesia maju) itu. Tampak jelas bahwa partai maupun politisinya telah kehilangan teladan ideologis dan teladan elit. Mereka sangat miskin apresiasi kepada rakyat.
Di era modern ini, salah satu bentuk dominan penafsiran impian, kerinduan atau aspirasi rakyat adalah ide populisme. Dalam bentuknya yang kuno aspirasi dapat hadir dalam wujud yang sangat kejam seperti praktik di masa kaisar Romari sebelum Konstantinus (274-337), yang dalam rangka menggembirakan rakyat__Kaisar mempertontonkan penganiayaan kelompok minoritas (Kristiani) di arena pertarungan manusia melawan hewan buas__seperti singa.
Dalam platform modern, populisme bisa sangat halus, misalnya, Ketika Gubernur Anies mengubah kawasan kumuh menjadi perumahan yang layak huni lengkap dengan segala legalitasnya. Atau pernah juga terjadi di Italia ketika Silvio Berlusconi (Perdana Menteri Italia) memberikan tiket gratis bagi para manula yang ingin menonton pertandingan sepakbola seri A Italia.
Sejatinya, demokrasi modern telah memaksa setiap rezim pemerintahan untuk menafsirkan dan “memuaskan” impian rakyat melalui keputusan-keputusan populis. Namun, jangan dilupakan peringatan keras Moh. Hatta dan Sartori, bahwa demokrasi menyimpan daya utopis yang bisa saja mengarah kepada pembegalan demokrasi itu sendiri.
Atas dasar itulah, menjadi tanggungjawab politik (wakil rakyat/penguasa) untuk menjaga keseimbangan dan tidak mempermainkan aspirasi rakyat. Mereka harus pandai dan jujur menerjemahkan tafsiran atas kehendak rakyat__bukan sebaliknya membegal aspirasi rakyat demi kekuasaan an sich.
Adalah menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia untuk sungguh-sungguh mengemplementasikan ide-ide populis sesuai bunyi Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat: mensejahterakan rakyat. Sebaliknya segera menghentikan merebaknya bentuk politik tanpa imajinasi (baca: daya utopis) yang akhirnya menjebak para pelaku politik/elit/penguasa jatuh dalam pragmatisme politik. Daya utopis demokrasi yang selama ini dikembangkan adalah “tidak cawe-cawe”, “menyandera lawan politik” dengan kasus-kasus hukum, “politik dinasti itu tidak masalah” atau melalui pembunuhan karakter lawan politik.
Akhirnya, harus disadari sekali lagi bahwa potensi bangsa ini sangat besar; luas wilayah, SDA, keberagaman agama, budaya, etnisitas, dan bahasa. Mari kita kembangkan semua potensi itu sebagai kekayaan memajukan bangsa.
Jika kita masih saja terjebak pada pragmatisme politik, maka pada akhirnya akan memandulkan seluruh bangsa dalam melahirkan impian besar masa depan.