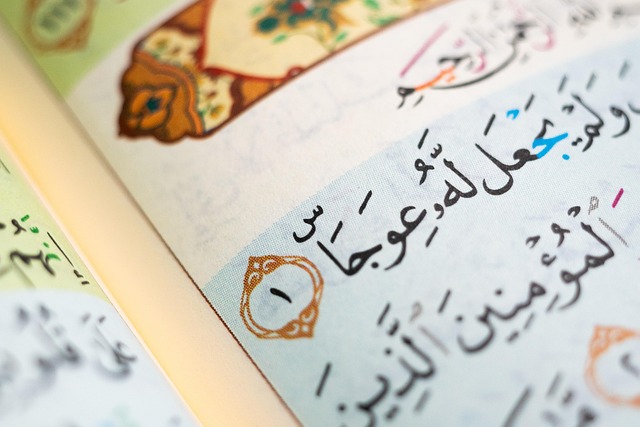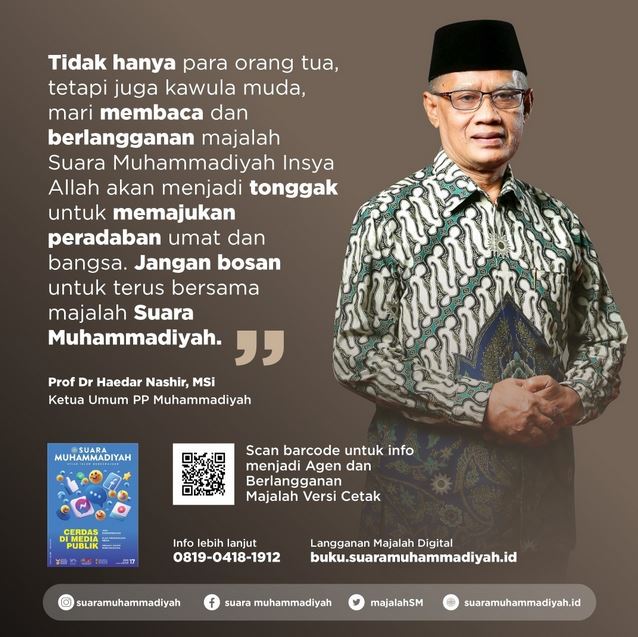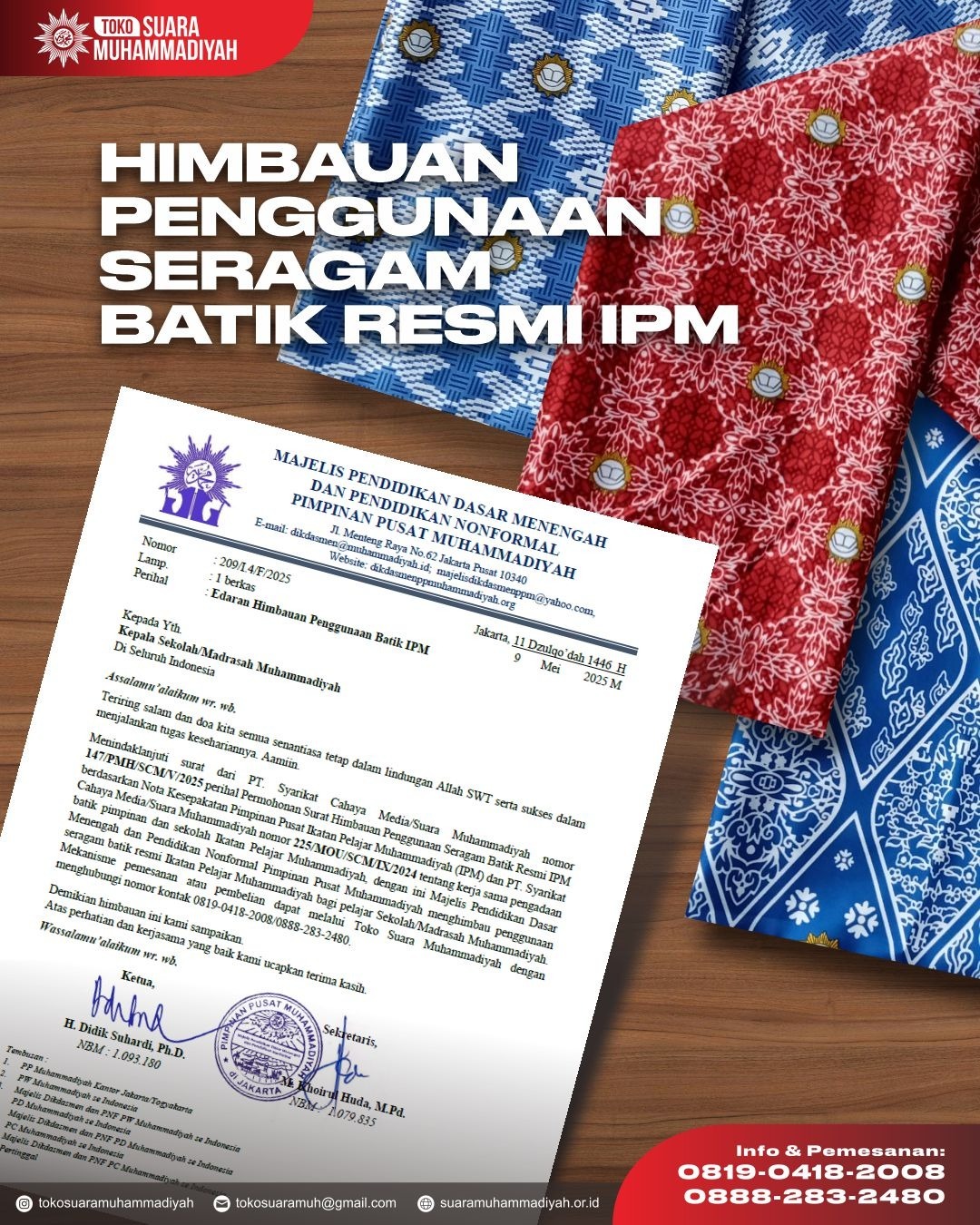Membaca Paceklik Gerakan Mahasiswa dan Jalan Keluar Menuju Politik Emansipatoris
Oleh: Figur Ahmad Brillian/PK IMM Muhammad Abduh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, PC IMM Sukoharjo
Selepas gemuruh demonstrasi menolak RUU TNI yang berlangsung antara tanggal 20 hingga 29 Maret 2025 dan mencatatkan 72 titik aksi di seluruh Indonesia, suasana politik gerakan mahasiswa tiba-tiba kembali senyap. Tak ada kelanjutan aksi, tak ada konsolidasi besar, bahkan gema tagar di media sosial pun perlahan redup. Kondisi ini kembali membangkitkan kritik lama yang terus menghantui wajah pergerakan mahasiswa bahwa mereka cenderung reaktif, moralis, dan sangat bergantung pada viralitas isu. Energi yang membuncah di satu momen dengan cepat menguap di bulan berikutnya, memperlihatkan watak gerakan yang tak berkesinambungan dan gagal menjaga nyala perlawanan.
Gerakan menolak RUU TNI memang tidak lahir dari mahasiswa semata. Hampir seluruh elemen masyarakat sipil bersatu menolak undang-undang cacat tersebut. Namun, dari sekian banyak unsur, mahasiswa tetap diposisikan sebagai wajah moral dari gerakan sosial. Sayangnya, peran itu justru kian kehilangan taji. Dalam beberapa tahun terakhir, yang disebut “gerakan mahasiswa” telah bertransformasi menjadi viral-based movement, bukan lagi moral force. Mereka bukan yang mempopuliskan tuntutan-tuntutan kerakyatan, melainkan yang terpopulasikan oleh logika viralitas media sosial.
Akibatnya, seperti yang dikatakan Coen Husain Pontoh dalam artikelnya di Indoprogress berjudul “Membangun Gerakan Sosial Baru: Sebuah Usul”, pola gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah diprediksi: kekecewaan, kemarahan, perlawanan, lalu kekalahan. Sebuah rantai siklik yang tak kunjung diputus karena desain dasarnya tidak pernah dibangun di atas kesadaran politik yang matang, melainkan pada kehebohan yang sesaat.
Gerakan mahasiswa yang berbasiskan viralitas tidak hanya mudah meledak, tapi juga mudah padam. Tanpa keberlanjutan strategi, tanpa jaringan basis massa, dan tanpa ideologi yang mengakar, gerakan hanya menjadi event, bukan proses sejarah. Bahkan dalam kasus Maret 2025, tidak ada forum rakyat atau konsolidasi lanjutan yang mampu memperkuat gerakan. Semua usai begitu saja setelah trending topic reda. Ini bukan hanya soal lemahnya manajemen aksi, tapi lebih dalam lagi: soal nihilnya arah politik dan keberanian untuk membangun proyek perubahan yang konsisten.
Dalam konteks inilah, kita dapat membaca ulang pemikiran Tan Malaka sebagai fondasi strategis untuk keluar dari masa paceklik. Tan dalam Madilog menekankan pentingnya logika materialisme dalam membaca realitas sosial. Bagi Tan, perjuangan tidak bisa dibangun di atas ilusi, melainkan atas dasar analisis terhadap struktur penindasan yang konkret. Mahasiswa, dengan posisinya sebagai kaum terpelajar namun tetap bagian dari kelas tertindas dalam sistem pendidikan neoliberal, harus memulai perjuangannya dari situ. Kesadaran sebagai subjek tertindas menjadi batu loncatan pertama menuju politik emansipatoris.
Pemikiran Tan Malaka lainnya yang relevan adalah keyakinannya pada pentingnya pendidikan revolusioner, sebagaimana ditegaskan dalam Sekolah Republik. Di sini, pendidikan bukanlah alat reproduksi kelas elite, melainkan alat pembebasan rakyat. Bila mahasiswa masih terjebak dalam sistem pendidikan yang melayani pasar, maka perjuangan menolak komersialisasi pendidikan adalah awal paling logis untuk menyusun gerakan.
Isu pendidikan tidak hanya inheren dengan nasib mahasiswa, tapi juga dengan nasib kelas buruh dan tani yang anak-anaknya dikorbankan oleh sistem pendidikan yang mahal dan diskriminatif. Dengan mengangkat isu neoliberalisme pendidikan, mahasiswa tak hanya memperjuangkan dirinya, tapi juga mengangkat agenda politik kelas tertindas yang lebih luas.
Dalam Naar de Republiek Indonesia, Tan juga menekankan pentingnya organisasi massa yang kuat dan ideologis. Tan tak pernah percaya pada kekuatan gerakan sporadis yang lahir dari kemarahan sesaat. Maka dari itu, mahasiswa perlu membangun organisasi yang tahan lama, tidak hanya organisasi kampus yang terjebak pada agenda administratif, tetapi organisasi kerakyatan yang berakar pada massa dan memiliki arah politik jangka panjang.
Namun demikian, perjuangan Tan tidak lengkap bila tak dibaca berdampingan dengan suara-suara kontemporer yang menyuarakan hal serupa. Salah satunya adalah A. Fadhil Aprilyandi Siltan, dalam artikelnya “Agar Gerakan di Kampus Tidak Mampus” (Indoprogress). Siltan menawarkan pembacaan kritis terhadap realitas hari ini bahwa kegagalan gerakan mahasiswa tidak semata-mata akibat kurangnya konsolidasi atau kemerosotan moralitas aktivis, melainkan karena krisis politik di dalam kampus itu sendiri. Kampus telah menjadi ruang steril dari pertarungan ide. Politik dilarang tampil terang-terangan. Diskusi ideologi dicurigai sebagai potensi radikalisme. Mahasiswa dikondisikan untuk menjadi teknokrat, bukan pejuang sosial.
Siltan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “depolitisasi ganda.” Pertama, depolitisasi oleh rezim kampus melalui regulasi yang mengebiri hak bersuara mahasiswa. Kedua, depolitisasi oleh mahasiswa sendiri yang menjauh dari konflik ide, karena terlalu nyaman dengan dunia pelatihan, seminar, lomba, dan karier. Alhasil, gerakan mahasiswa kehilangan jiwanya: keberanian untuk melawan. Aktivisme digantikan manajerialisme. Kritik digantikan presentasi. Perlawanan digantikan proposal sponsorship.
Jika Tan Malaka menekankan pentingnya membangun basis ideologis dan organisasi kerakyatan, Siltan melengkapi dengan seruan untuk merebut kembali ruang politik di dalam kampus. Bagi Siltan, kampus tidak boleh dibiarkan menjadi ruang netral. Ia harus dikembalikan sebagai ruang hidup politik: tempat konflik wacana, pertarungan ide, dan produksi kesadaran kritis. Gerakan tidak akan lahir dari seminar dan pelatihan, melainkan dari pertarungan nilai di ruang-ruang kelas dan sekretariat. Mahasiswa harus merebut ruang-ruang organisasi mahasiswa, BEM, DEMA, hingga UKM, dan mengubahnya dari alat karier menjadi alat perjuangan.
Dari sinilah transformasi politik gerakan mahasiswa dapat dimulai: bukan dengan menunggu isu viral berikutnya, tapi dengan menyusun arah politik yang organik dari bawah. Mahasiswa harus memulai dari kampusnya sendiri, dari ketertindasan yang dialaminya sendiri, dengan membangun kembali diskusi ideologis, membaca buku-buku kiri yang dibungkam, membuka forum kelas filsafat pembebasan, dan merebut ruang-ruang strategis organisasi mahasiswa untuk kepentingan politik emansipatoris.
Apa yang diperjuangkan Tan Malaka—pendidikan sebagai alat pembebasan, organisasi sebagai alat perjuangan, dan kesadaran kelas sebagai fondasi politik—masih sangat relevan dalam konteks hari ini. Dan seperti yang diingatkan Siltan, perjuangan itu harus dimulai dari keberanian mahasiswa untuk menghidupkan kembali konflik ide di dalam kampus. Karena hanya dengan begitu, gerakan mahasiswa bisa keluar dari paceklik sejarahnya, dan kembali menjadi lokomotif perubahan sosial yang visioner dan revolusioner.