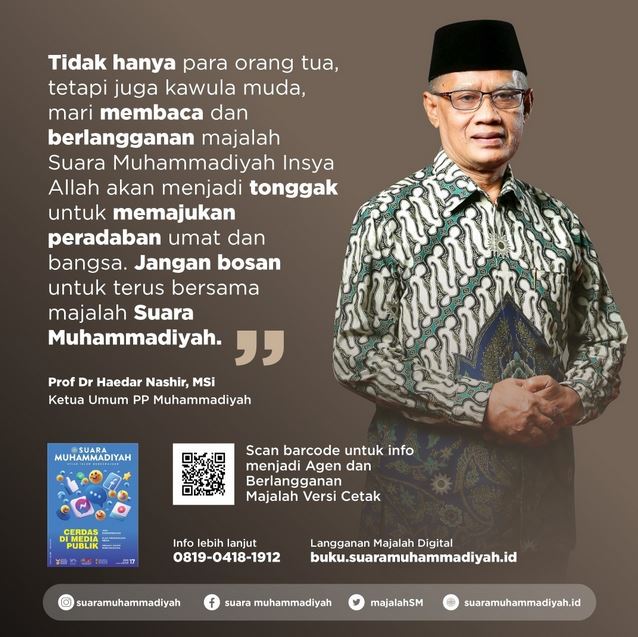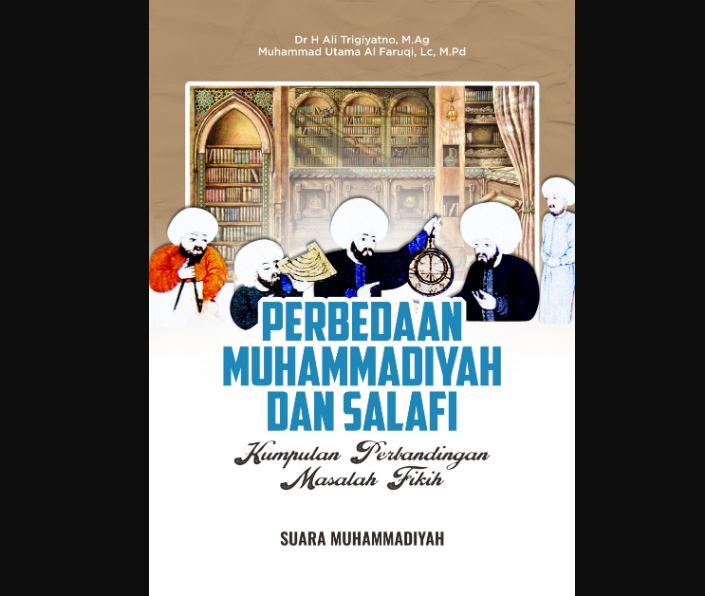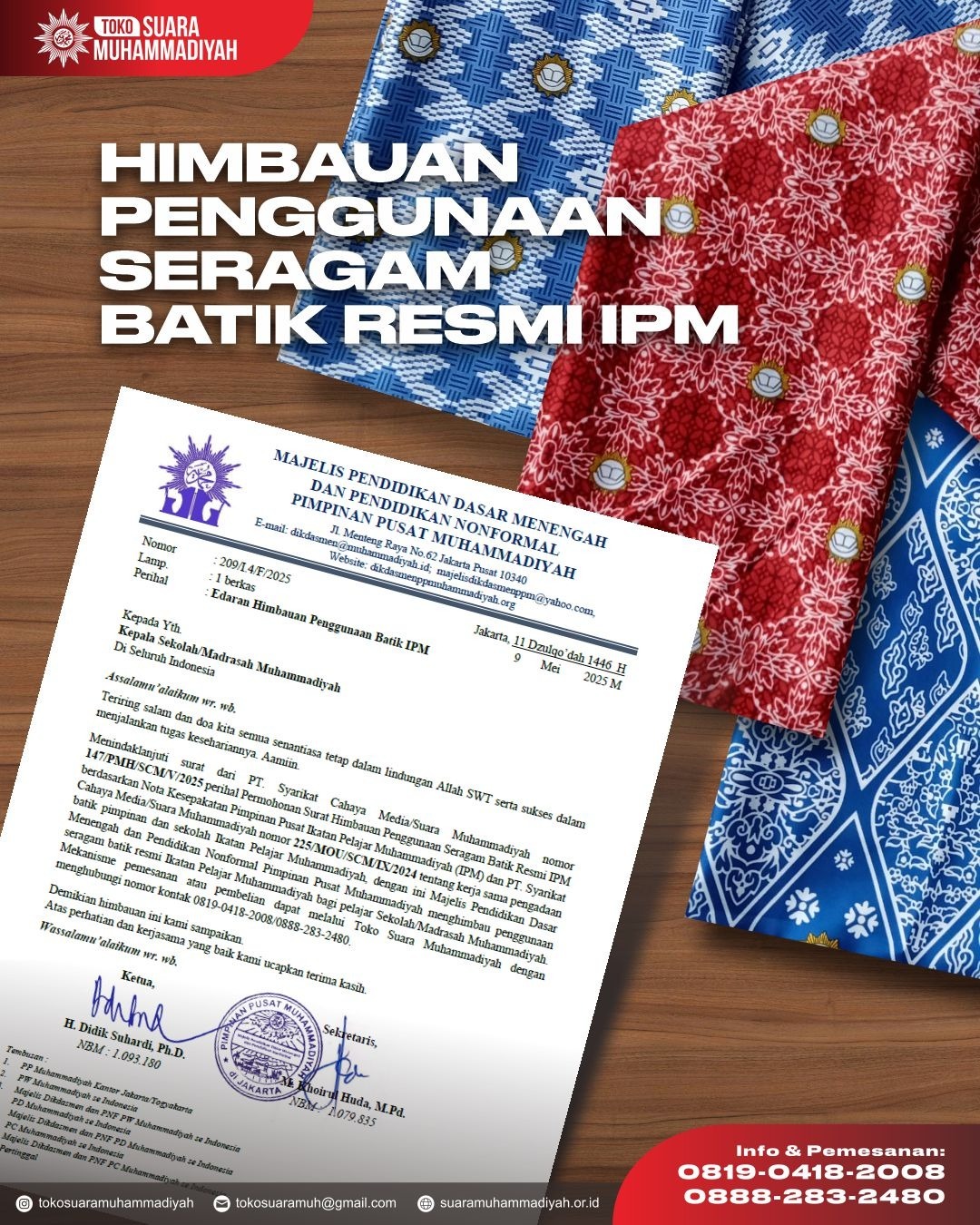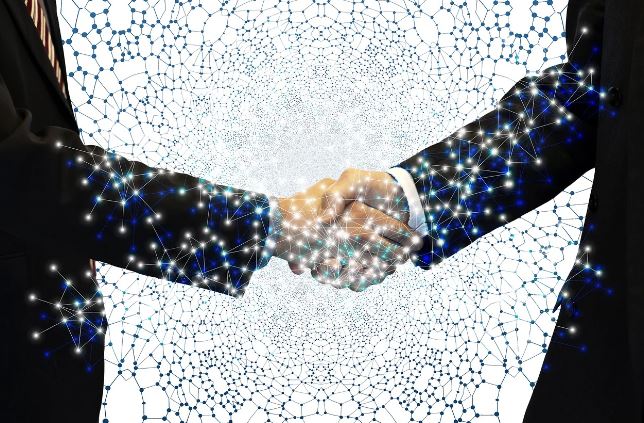Membangun Karakter Syukur dalam Praksis Hamdalah di Era Kontemporer
Piet Hizbullah Khaidir, Ketua STIQSI Lamongan; Sekretaris PDM Lamongan; Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur
Dalam era kontemporer yang ditandai oleh percepatan teknologi, mobilitas informasi, dan dinamika sosial yang kian kompleks, karakter syukur semakin menemukan urgensi baru. Banyak manusia modern hidup dalam limpahan fasilitas material, namun justru mengalami kekeringan spiritual dan krisis makna. Dalam konteks ini, konsep hamdalah—yakni ungkapan al-ḥamdu lillāh (segala puji bagi Allah)—tidak sekadar menjadi ucapan ritual, melainkan landasan etis dan spiritual dalam membangun karakter syukur yang aktif, reflektif, dan produktif.
Hamdalah bukanlah ekspresi pasif dari penerimaan takdir, tetapi cerminan kesadaran ilahiah (God-consciousness) yang menghidupkan nilai-nilai positif seperti kerendahan hati, penghargaan terhadap nikmat, dan orientasi hidup yang berimbang antara dunia dan akhirat. Dengan demikian, membangun karakter syukur melalui praksis hamdalah berarti menghidupkan kembali ruh spiritualitas dalam setiap dimensi kehidupan manusia modern—dalam belajar, bekerja, berteknologi, dan berinteraksi sosial.
Secara etimologis, ḥamd berarti “pujian yang disertai pengagungan terhadap pihak yang dipuji karena kesempurnaan sifat atau perbuatannya.” Dalam terminologi teologis, al-ḥamdu lillāh berarti mengakui dan menegaskan bahwa segala bentuk kebaikan dan kesempurnaan bersumber dari Allah semata. Ucapan ini menandai kesadaran manusia akan posisi dirinya sebagai hamba yang lemah di hadapan Tuhan yang Mahaagung.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Madārij al-Sālikīn menyebut bahwa ḥamd mengandung dua unsur: pengakuan (ma‘rifah) dan pengagungan (‘ibādah). Artinya, hamdalah bukan sekadar pengakuan verbal, tetapi manifestasi intelektual dan spiritual yang menuntut kesadaran penuh atas nikmat dan kebesaran Allah. Dengan demikian, hamdalah menjadi titik temu antara pengetahuan, iman, dan perilaku.
Al-Qur’an sendiri membuka seluruh sistem wahyunya dengan al-ḥamdu lillāh (QS. al-Fātiḥah: 2), menandakan bahwa seluruh perjalanan kehidupan manusia dan petunjuk Ilahi berpangkal dari kesadaran syukur. Para mufassir seperti al-Rāzī dan al-Qurṭubī menegaskan bahwa hamdalah adalah fondasi teologis dari hubungan manusia dengan Tuhan—suatu relasi yang dimulai dari pujian dan berakhir dengan penghambaan.
Hamdalah sebagai Karakter Imani
Karakter syukur yang dibangun dari hamdalah tidak berhenti pada pengucapan lisan, melainkan menuntut pembentukan habitus spiritual. Dalam perspektif iman, syukur adalah reaksi etis terhadap kesadaran nikmat: semakin dalam pengetahuan seseorang terhadap nikmat Allah, semakin tinggi pula tingkat pengabdiannya.
Al-Qur’an mengaitkan syukur dengan kecerdasan ruhani:
"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur" (QS. Saba': 13).
Ayat ini mengisyaratkan bahwa syukur bukanlah kemampuan umum, tetapi hasil dari kesadaran yang terlatih dan berilmu. Menurut al-Ghazālī, syukur mencakup tiga dimensi: pengenalan nikmat dengan akal, pengakuan nikmat dengan lisan, dan pemanfaatan nikmat dengan perbuatan yang diridhai Allah. Dengan demikian, hamdalah merupakan sintesis dari tiga lapis kesadaran tersebut.
Karakter syukur menjadikan individu berorientasi pada nilai-nilai transendental, tidak terjebak pada materialisme. Seseorang yang terbiasa mengucap al-ḥamdu lillāh bukan sekadar berterima kasih, tetapi menempatkan segala pencapaian dalam kerangka kehendak Ilahi. Inilah bentuk tertinggi dari etika tauhid yang melahirkan keseimbangan antara usaha (ikhtiar) dan penerimaan (ridhā).
Praksis Hamdalah di Era Kini
Dalam konteks era kontemporer, hamdalah dapat diimplementasikan sebagai praksis spiritual yang membentuk kepribadian resilien, optimis, dan berorientasi nilai. Di tengah tekanan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan banjir informasi, hamdalah menjadi bentuk meditasi singkat yang menenangkan sekaligus memurnikan motivasi manusia.
Pertama, dalam dunia pendidikan, hamdalah menumbuhkan etos belajar yang berorientasi lillāh—belajar bukan untuk popularitas atau keuntungan semata, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Mahasiswa atau peneliti yang membuka dan menutup aktivitas ilmiahnya dengan bismillāh dan al-ḥamdu lillāh sejatinya sedang meneguhkan kesadaran bahwa ilmu adalah amanah, bukan komoditas.
Kedua, dalam dunia kerja, hamdalah membentuk etika profesional yang produktif dan jujur. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh, karena setiap tantangan dianggap sebagai peluang peningkatan diri. Dalam perspektif psikologi Islam, hal ini menumbuhkan growth mindset berbasis iman—bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mengokohkan karakter.
Ketiga, dalam interaksi sosial dan politik, hamdalah menjadi simbol kesantunan publik. Dalam budaya digital yang sarat ujaran kebencian dan keluhan, membiasakan hamdalah berarti menanamkan positive discourse berbasis spiritualitas. Ucapan al-ḥamdu lillāh di media sosial, misalnya, bisa menjadi strategi dakwah kultural yang menebarkan optimisme dan adab berbahasa.
Dengan demikian, praksis hamdalah bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga tindakan sosial yang berdampak luas—membangun masyarakat yang bersyukur, beretika, dan berkeadaban.
Syukur sebagai Jalan Adab dan Masa Depan
Hamdalah adalah simpul antara iman, ilmu, dan adab. Ia membentuk cara berpikir yang positif, hati yang tenang, serta perilaku yang santun. Dalam kerangka spiritualitas Islam, syukur bukan sekadar respon emosional terhadap nikmat, tetapi prinsip eksistensial yang membentuk pandangan hidup (weltanschauung).
Orang yang bersyukur tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi menggunakannya dengan adab. Ia tidak menentang dunia, tetapi menundukkan dunia dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian, membangun karakter syukur melalui praksis hamdalah merupakan strategi kebudayaan sekaligus pendidikan spiritual bagi masyarakat modern.
Hamdalah mengajarkan bahwa setiap keberhasilan adalah amanah, setiap nikmat adalah ujian, dan setiap kesulitan adalah peluang untuk bertumbuh dalam iman. Dalam tataran sosial, masyarakat yang berkarakter hamdalah akan tumbuh menjadi peradaban yang damai, berdaya, dan penuh kasih.
Akhirnya, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah:
"Jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat-Ku kepada kalian" (QS. Ibrahim: 7).
Ayat ini bukan sekadar janji, melainkan prinsip universal bagi keberlanjutan moral dan spiritual umat manusia. Maka, al-ḥamdu lillāh bukan hanya akhir dari doa, tetapi juga awal dari seluruh proses membangun kehidupan yang bermakna.