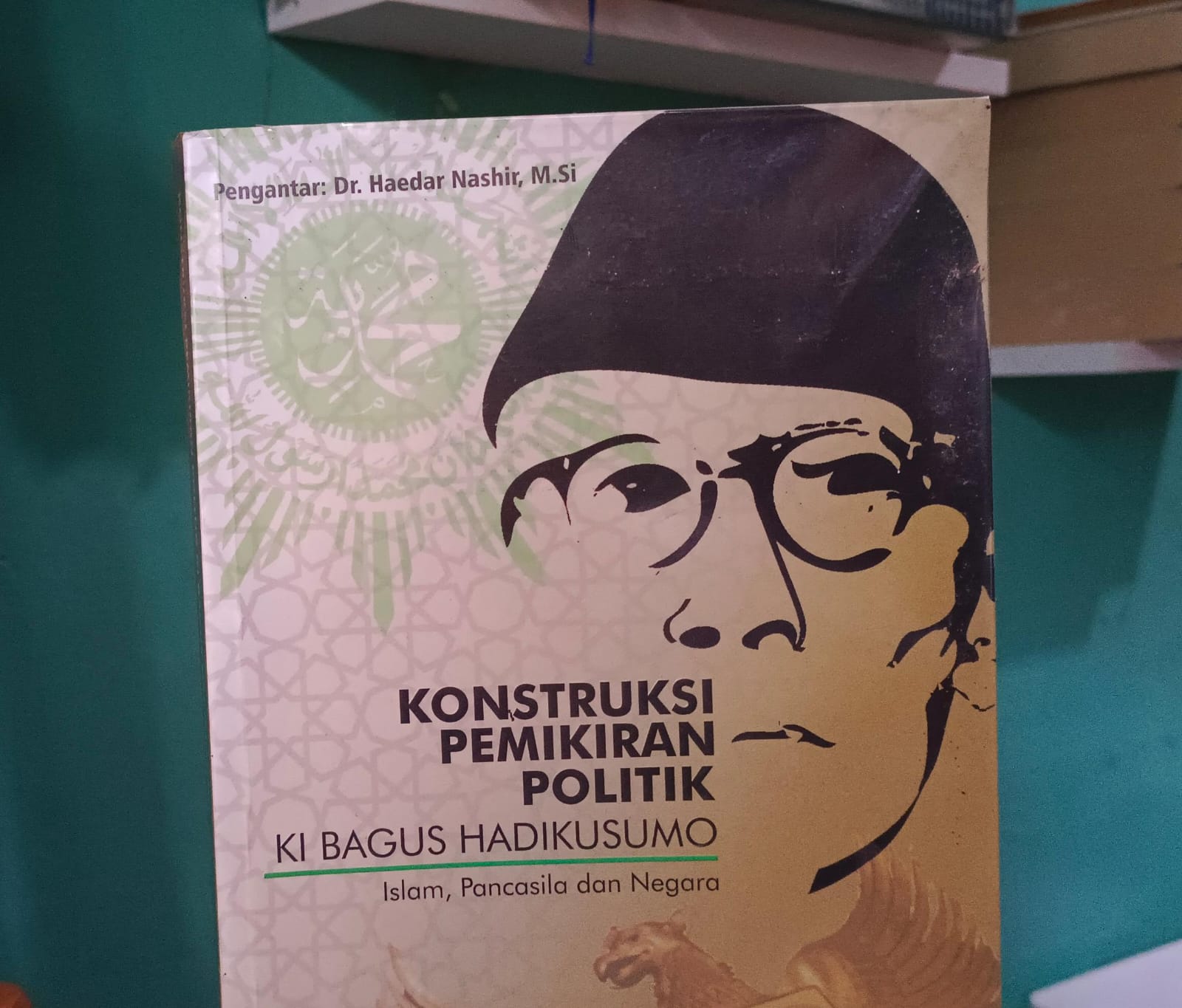Menjaga Nyala Tajdid; Refleksi untuk Jiwa-jiwa Pengabdi di Jalan Muhammadiyah
Oleh: Dr. Jaharuddin, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta
Ada satu pertanyaan sunyi yang kadang datang justru ketika aktivitas sedang ramai-ramainya, untuk apa kita bergerak? Di antara rapat yang padat, agenda yang bertumpuk, laporan yang harus disusun, dan program yang harus dituntaskan, ada ruang batin yang sering luput kita kunjungi. Ruang yang seharusnya menjadi tempat kita menegakkan niat, meluruskan arah, dan menghidupkan kembali ruh dakwah.
Muhammadiyah tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kegelisahan yang jujur, kegelisahan melihat umat tertinggal, terbelenggu kebodohan, terjepit kemiskinan, dan pada saat yang sama jauh dari kemurnian tauhid. Dari kegelisahan itulah tajdid menemukan tempatnya—bukan sebagai slogan, melainkan sebagai jalan. Tajdid bukan sekadar pembaruan gagasan; ia adalah keberanian untuk kembali pada kemurnian ajaran, lalu melangkah menjawab zaman dengan hikmah, ilmu, dan amal yang nyata.
Kita sering mendengar bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid. Kalimat itu begitu akrab, begitu sering diulang, hingga kadang terasa seperti frasa yang berjalan otomatis. Tetapi sesungguhnya kalimat itu adalah sumpah sejarah. Ia adalah mandat peradaban. Ia bukan hanya identitas; ia adalah tanggung jawab. Sebab amar ma’ruf nahi munkar, jika hanya berhenti pada ucapan, akan menjadi retorika. Tajdid, jika hanya berhenti pada teks, akan menjadi arsip. Padahal Muhammadiyah adalah gerakan hidup—dan gerakan yang hidup hanya bisa bertahan jika ruhnya tetap menyala.
Di titik inilah kita perlu kembali mengingat, kekuatan Muhammadiyah sejak awal bukan semata pada bangunan, struktur, atau reputasi sosialnya. Kekuatan Muhammadiyah bertumpu pada satu hal yang lebih halus namun lebih menentukan, kehadiran dakwah yang membumi. Dakwah yang turun ke realitas. Dakwah yang tidak alergi pada luka sosial. Dakwah yang tidak sekadar menasihati dari jauh, tetapi mendekat—menyentuh, menolong, menemani, lalu mengangkat martabat manusia.
Sejarah mengajarkan kita pelajaran yang tidak pernah usang. KH. Ahmad Dahlan tidak memulai Muhammadiyah dengan panggung megah. Ia memulai dengan ayat-ayat yang mengguncang nurani, surat Al-Mā‘ūn. Ayat-ayat itu dibaca berulang-ulang bukan untuk memamerkan hafalan, melainkan untuk membongkar cara beragama yang hanya berhenti pada ritual. Jika ada yatim yang diabaikan, jika ada miskin yang tak dipedulikan, maka ada yang rapuh dalam kesalehan kita. Dari kesadaran itulah lahir “teologi amal”, agama yang membentuk tindakan, bukan sekadar pengetahuan.
Maka, ketika hari ini Muhammadiyah telah berjejak melalui sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, panti asuhan, lembaga sosial, dan beragam amal usaha, kita patut bersyukur. Namun bersamaan dengan syukur, kita juga harus menjaga kewaspadaan. Karena di balik capaian besar, ada ujian yang lebih halus, ujian kenyamanan dan rutinitas. Rutinitas yang membuat gerakan terasa sekadar “pekerjaan organisasi”, bukan lagi “tugas peradaban”. Kenyamanan yang membuat kita lupa pada akar, pada masyarakat kecil yang sering tak punya suara, pada orang-orang lemah yang tak punya akses, pada masalah-masalah sunyi yang tak pernah viral.
Tajdid harus kita jaga agar tidak padam di tengah kemapanan. Sebab tajdid adalah api yang membuat Muhammadiyah terus muda. Ia yang mencegah kita menjadi institusi yang hanya sibuk mempertahankan diri. Ia yang menghidupkan keberanian untuk berbenah, memperbaiki, dan memperbarui. Tajdid mengajarkan bahwa memurnikan tidak berarti mengeringkan, dan memajukan tidak berarti melupakan akar. Tajdid adalah keseimbangan, kokoh pada prinsip, cerdas pada strategi, lembut pada manusia.
Jika kita menengok realitas masyarakat hari ini, tantangan dakwah semakin kompleks. Kemiskinan tidak lagi hanya soal tidak punya uang, tetapi juga soal tidak punya akses dan tidak punya harapan. Kebodohan tidak lagi sekadar tidak sekolah, tetapi juga soal banjir informasi yang membuat orang kehilangan daya pilih. Kerusakan moral tidak selalu tampil kasar, justru sering hadir halus—melalui normalisasi kebiasaan yang mengikis adab. Konflik sosial kadang tidak meledak keras, tetapi menyusup melalui prasangka, polarisasi, dan rasa saling curiga.
Dalam situasi seperti ini, dakwah berkemajuan menuntut lebih dari sekadar ceramah. Ia menuntut solusi sosial, penjagaan kemaslahatan, dan pembangunan sistem yang beradab. Dakwah harus mampu mengobati luka yang terlihat, menjaga kebaikan yang telah ada, dan menumbuhkan peradaban yang melahirkan kebaikan secara berkelanjutan. Artinya, kita tidak cukup hanya mengadakan kegiatan; kita harus merawat ekosistem.
Inilah makna tajdid yang sesungguhnya, ia mengubah dakwah dari “peristiwa” menjadi “peradaban”. Ia menggeser orientasi kita dari sekadar “program” menjadi “dampak”. Ia mengajak kita tidak hanya bangga pada jumlah, tetapi jernih pada mutu. Karena ukuran keberhasilan gerakan bukan semata statistik, melainkan seberapa jauh ia menghidupkan manusia.
Ada ukuran yang sering tidak tertulis dalam laporan, tetapi sebenarnya paling menentukan, apakah dakwah kita menyentuh jiwa? Apakah ia membuat seseorang yang jauh dari Allah menjadi dekat kembali? Apakah ia membuat keluarga yang rapuh menjadi lebih utuh? Apakah ia membuat pemuda yang gelisah menemukan arah? Apakah ia membuat yang lemah merasa dilindungi? Jika jawaban-jawaban itu hadir, maka Muhammadiyah sedang berada di jalurnya.
Di sinilah kita memahami mengapa Muhammadiyah sejak awal meletakkan amal usaha sebagai instrumen dakwah. Sekolah/kampus bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi jalan memuliakan akal dan membangun masa depan. Rumah sakit bukan sekadar layanan kesehatan, tetapi ekspresi kasih sayang dan amanah kemanusiaan. Panti asuhan bukan sekadar tempat tinggal anak yatim, tetapi bukti bahwa iman tidak tega membiarkan yang lemah sendirian. Semua itu adalah dakwah yang menjejak bumi—dakwah yang membuat Islam terasa sebagai rahmat, bukan hanya wacana.
Namun amal usaha yang besar juga mengandung risiko, ia bisa berubah menjadi sekadar “sistem administrasi” jika ruhnya tidak dijaga. Karena itu kader Persyarikatan perlu memelihara satu hal yang tidak boleh hilang, kesadaran bahwa setiap amal usaha adalah amanah dakwah. Setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap pelayanan, setiap rapat, bahkan setiap konflik internal sekalipun, pada akhirnya harus kembali pada satu pertanyaan, apakah ini membawa kita lebih dekat pada misi?
Tajdid juga berarti menumbuhkan kader yang berkarakter, ikhlas, ilmiah, dan tangguh. Ikhlas membuat amal tidak bergantung pada tepuk tangan. Ilmiah membuat gerakan tidak dikuasai emosi, tetapi dituntun data, akal sehat, dan hikmah. Tangguh membuat kader tidak mudah patah oleh dinamika. Kader yang demikian tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai panggung untuk diri sendiri, melainkan sebagai jalan untuk memperbesar manfaat.
Di saat yang sama, tajdid mengajarkan bahwa gerakan yang besar tidak boleh kehilangan kelembutannya. Peradaban yang kuat tidak lahir dari kekerasan jiwa, tetapi dari keluhuran akhlak. Karena itu, Muhammdiyah yang berkemajuan adalah Muhammadiyah yang menegakkan prinsip dengan tegas, namun tetap memeluk manusia dengan hangat. Ia berani menyampaikan kebenaran, tetapi tidak gemar merendahkan. Ia berani mengoreksi, tetapi tidak kehilangan kasih sayang. Di sinilah tajdid menjadi indah, ia tidak menjauhkan kita dari umat, tetapi mendekatkan.
Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan awal, untuk apa kita bergerak? Jawabannya mungkin tidak perlu rumit. Kita bergerak agar agama tidak berhenti sebagai kalimat. Kita bergerak agar Islam benar-benar menjadi cahaya. Kita bergerak agar masyarakat kecil merasakan bahwa Persyarikatan ini bukan sekadar nama, tetapi rumah pengabdian. Kita bergerak untuk menjaga nyala tajdid—agar Muhammadiyah terus muda, terus hidup, terus relevan, dan terus menjadi rahmat bagi semesta.
Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa pulang bukan jabatan, bukan pujian, bukan catatan prestasi. Yang akan kita bawa adalah jejak. Jejak kebaikan yang mungkin tampak kecil, tetapi di sisi Allah bisa menjadi cahaya besar. Seorang anak yang terbantu pendidikannya. Seorang pasien yang merasakan pelayanan penuh empati. Seorang pemuda yang menemukan arah. Seorang keluarga yang terselamatkan. Seorang masyarakat yang pelan-pelan menjadi lebih beradab.
Semoga tulisan ini menyalakan sesuatu di dalam diri kita, rasa haru yang jernih, rasa syukur yang dewasa, dan tekad yang baru. Agar kita tidak sekadar menjadi bagian dari struktur, tetapi menjadi penjaga ruh. Agar kita tidak hanya mengisi organisasi, tetapi meneruskan misi. Agar kita tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar menghidupkan.
Dan jika suatu hari nanti kita merasa lelah, ingatlah, nyala besar selalu bermula dari api kecil. Tajdid pun begitu. Ia dimulai dari hati yang jujur, dari niat yang bersih, dan dari langkah yang setia.
Menjaga nyala tajdid berarti menjaga agar Muhammadiyah tetap menjadi cahaya—cahaya yang lahir dari akar rumput, namun mampu menerangi peradaban.