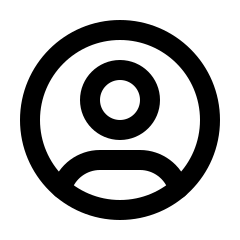Menunggu Sikap TNI dalam Absurditas Politik
Oleh: Sobirin Malian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Mengapa militer berpolitik? Pertanyaan ini mengusik siapapun terutama manakala militer ternyata tak mampu menjadi “penyuluh” atau penuntun politik yang benar baik menurut konstitusi maupun menurut demokrasi. Huntington dalam Political Orde in Canging Societies (1969) mengemukakan, bahwa masuknya militer ke dalam ranah politik tidaklah berbeda dengan keterlibatan mahasiswa, pemuka agama, buruh, petani, dan wanita dalam politik. Militer di mana pun di dunia ini umumnya terlibat dalam politik, itu hal lumrah.
Amos Perlmutter dalam The Political Roles and Military Rulers (2014) menyebut beberapa alasan mengapa militer terjun ke politik praktis, diantaranya karena lemahnya pelembagaan dan struktur negara, ketidakmampuan pengaruh masyarakat kelas menengah, dan pertentangan antar kelompok. Konkretnya, militer masuk ke arena politik terutama karena didukung oleh iklim kelembagaan internal militer yang kohesif. Dalam kaitan ini, ada delapan kohesi atau pun kesenjangan internal tentara menurut Janowit Frederich yakni (1) latar belakang etnik, (2) latar belakang agama, (3) usia, (4) latar belakang sosial, (5) pengalaman pendidikan, (6) pengalaman kerja, (7) ikatan ideologis atau politik, dan (8) pengalaman keberhasilan dalam tugas (Janowitz, 1964).
Ditambahkan Huntington (1969) militer terlibat dalam politik karena telah terjadi kemerosotan politik dalam negara itu, misalnya karena rezim yang korup, otoriter, melakukan dinasti politik atau menyimpangi demokrasi sehingga orientasi penguasa lebih pada kekuasaan an-sich, disitu ada peluang militer terjun dalam politik. Kehadiran militer dalam hal itu mengambil alih pemerintahan (kekuasaan) kadang melalui kudeta atau dengan cara damai untuk mengembalikan fungsi pemerintahan (kekuasaan) agar kembali sesuai dengan konstitusi atau demokrasi.
Keterlibatan militer dalam politik, seperti diuraikan secara panjang lebar oleh Huntington_ sejatinya tidak secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap. Ia menjelaskan tentang “masyarakat Pretoria” sebagai kondisi yang melahirkan pretorianisme__selanjutnya pretorianisme ini membuka jalan bagi tentara (militer) terlibat dalam politik dan pada titik tertentu ketika telah menjadi kekuatan utama, tentara membentuk lembaga politik atau politik melembaga dalam militer (di masa Orba, terbentuknya Golkar karena alasan ini).
Pertama, “Masyarakat Pretoria” dalam narasi Huntington yaitu suatu keadaan masyarakat dimana seluruh kekuatan sosial yang ada dipolitisasi. Kekuatan-kekuatan sosial, besar ataupun kecil, berupaya masuk ke dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan meskipun bangunan politik belum mapan. Dalam keadaan demikian, tidak hanya militer tetapi setiap kekuatan sosial berjuang masuk dalam politik.
Kedua, Pretoria Oligarkis mengacu pada kondisi dimana kelompok tertentu, seperti tuan tanah, pemuka agama, dan golongan pemegang pedang, dalam masyarakat menguasai politik hingga kekuatan sosial lain dibatasi untuk terlibat didalamnya. Dominasi oligarki ini yang disebut Huntington sebagai Pretorianisme Oligarkis. Salah satu ciri yang utama dari Pretorianisme Oligarkis adalah adanya pencampuran secara sekaligus urusan politik, militer, agama, sosial dan ekonomi. Pada titik tertentu, pretorianisme oligarkis cenderung berubah menjadi pretorianisme radikal.
Ketiga, Pretorianisme Radikal. Pretorianisme oligarkis akan lenyap ketika dalam masyarakat terjadi perkembangan kekuatan sosial, muncul banyak kelompok yang berbeda-beda lalu sama-sama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi politik. Dalam keadaan seperti ini akan terbentuk pretorianisme karena kekuatan yang mempengaruhi politik dalam masyarakat cenderung radikal.
Keempat, Pretorianisme Rasial. Pada titik tertentu dalam perkembangannya, masyarakat bisa saja dikuasai oleh ras tertentu sehingga urusan politik diambil-alih ditangan ras tertentu dan melahirkan apa yang disebut pretorianisme rasial. Pernah terjadi di Afrika Selatan tahun 80-an di masa Presiden Botha (kulit putih melahirkan politik apartheid/rasis) yang kemudian memunculkan perlawanan Nelson Mandela.
Kelima, Pretorianisme Massa. Karena hakikatnya kekuatan sosial dalam masyarakat terus berkembang maka besar peluang dominasi kekuatan sosial tertentu akan digantikan oleh dominasi berbagai kekuatan sosial yang dirangkum dalam istilah “massa””. Pretorianisme massa ini menurut Huntington ditandai oleh adanya suatu kekuatan massa dalam jumlah besar yang tergabung dalam satu wadah seperti kelompok buruh dalam masyarakat modern. Kekuatan ini akan berhadapan dengan pemerintah atau dengan militer atau bisa juga bekerjasama untuk melawan satu kekuatan yang sedang mendominasi. Model ini yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi saat ini.
Keenam, Prajurit Pembentuk Lembaga. Huntington menyatakan bahwa militer memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan kekuatan sosial yang lain dalam suatu masyarakat Pretoria untuk mendirikan lembaga politik, misalnya karena militer memiliki kemampuan manajerial dan terorganisasi dengan baik.
Militer dalam Politik Indonesia
Bagaimana militer terlibat dalam politik di Indonesia ? Bagi Janowitz, keterlibatan tentara bukan semata karena institusi sipil yang lemah (faktor masyarakat Pretoria) tetapi justru karena tendensi (interest) internal tentara yang begitu kuat untuk terlibat dalam politik atau tepatnya militer paham betapa nikmatnya kekuasaan.
Boni Hargens (2006) menilai, faktornya terkait dengan latar belakang sejarah tentara (TNI) yang adalah pejuang republik, dimana terbentuknya militer secara otonom. Artinya, tanpa campur tangan negara. Atas dasar itulah, sepanjang periode kekuasaan Orde Baru bahkan hingga kini, militer sangat sulit dibersihkan dari arena politik. Hal ini pun tak dapat dipungkiri karena faktor internal bahwa tentara kohesif, dan berjiwa kepemimpinan yang kuat dibandingkan kelompok sipil dalam negara.
Problem mendasarnya dalam konteks Indonesia adalah, dominasi tentara dalam politik tidak disertai dengan suatu platform atau format politik yang mendorong terciptanya suatu pola pemerintahan demokratis yang taat pada substansi konstitusi (living constitution). Problem mendasar ini sejatinya telah membuat negara seolah lepas kendali. Negara seakan tak lagi dapat dikoreksi atau dikritik agar dapat kembali sejalan dengan ruh negara hukum, konstitusi dan Pancasila.
TNI yang diharapkan berjiwa patriotis, berintegritas kuat seharusnya menjadi penuntut apabila jalannya pemerintahan dianggap keluar jalur. Sejauh ini TNI justru terjebak dalam pragmatisme politik. Beberapa menteri yang dijabat oleh militer terkesan tak memiliki tanggungjawab untuk kembali mengembalikan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi (negara hukum) dan ideologi negara. Jiwa korsa, jiwa patriot, integritas kemiliteran yang telah menempa mereka bertahun-tahun seolah tak membekas di saat mereka ikut dalam arus politik rezim.
Pemerintahan yang jelas-jelas mengusung dinasti politik (tak sejalan dengan nilai demokrasi), masifnya korupsi, kolusi dan nepotisme, mengacak-acak lembaga hukum (MK,MA,Kejagung) tak mampu dikontrol oleh jiwa korsa (TNI). Kalau pun ada perwira TNI yang bersuara lantang sifatnya perseorangan (pribadi) bukan sebagai kelembagaan yang mampu mengontrol jalannya pemerintahan negara tetapi lebih bersifat pribadi yang oleh karena itu tidak efektif__bak bebek lumpuh (lame duck). Padahal yang diperlukan dalam kondisi pemerintahan yang makin jauh dari ruh konstitusi adalah gerakan kontrol secara kelembagaan, intens dan masif.
Keterlibatan TNI dalam politik sebenarnya bukanlah hal yang keliru, anggaplah itu sebagai bagian dari proses dan peran militer dalam menuju Indonesia yang maju. Namun yang perlu ditegaskan dalam konteks itu adalah, bagaimana agar TNI tetap menjaga marwahnya sebagai penjaga stabilitas negara dalam arti pemerintah tidak menyimpangi hukum secara terang-terangan. TNI seharusnya mampu menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol jalannya pemerintah agar tidak makin jauh dari suasana demokratis dan tetap dalam koridor konstitusi (negara hukum) dan Pancasila sebagai ideologi negara.
Pada akhirnya, perlu ditunggu sikap TNI__bukan dalam arti mengembalikan mereka dalam barak yang sempit, melainkan bagaimana agar TNI mampu mengembalikan absurditas politik kembali on the track. TNI harus mengambil posisi yang benar, efektif sebagai kekuatan penjaga politik demokratis dan sesuai dengan koridor bernegara yang benar yaitu dalam kerangka konstitusi yang dinamis (living constitution).
Jiwa korsa harus dikembalikan dalam arti konsep daya juang dalam hal strategi memajukan negara; bahwasanya TNI satu korps saling setia, bahu-membahu dan melindungi negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri seperti penyimpangan KKN, politik dinasti, otoriterian; maupun dari luar yaitu intervensi negara lain.