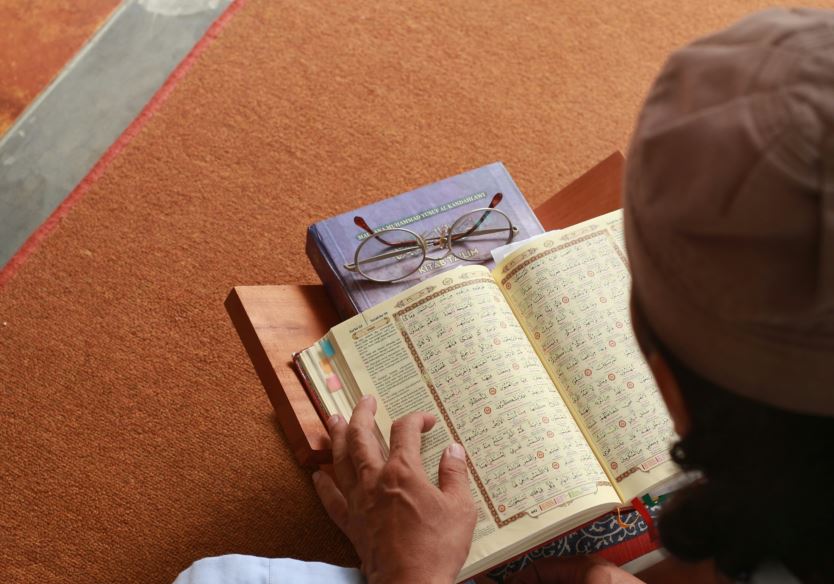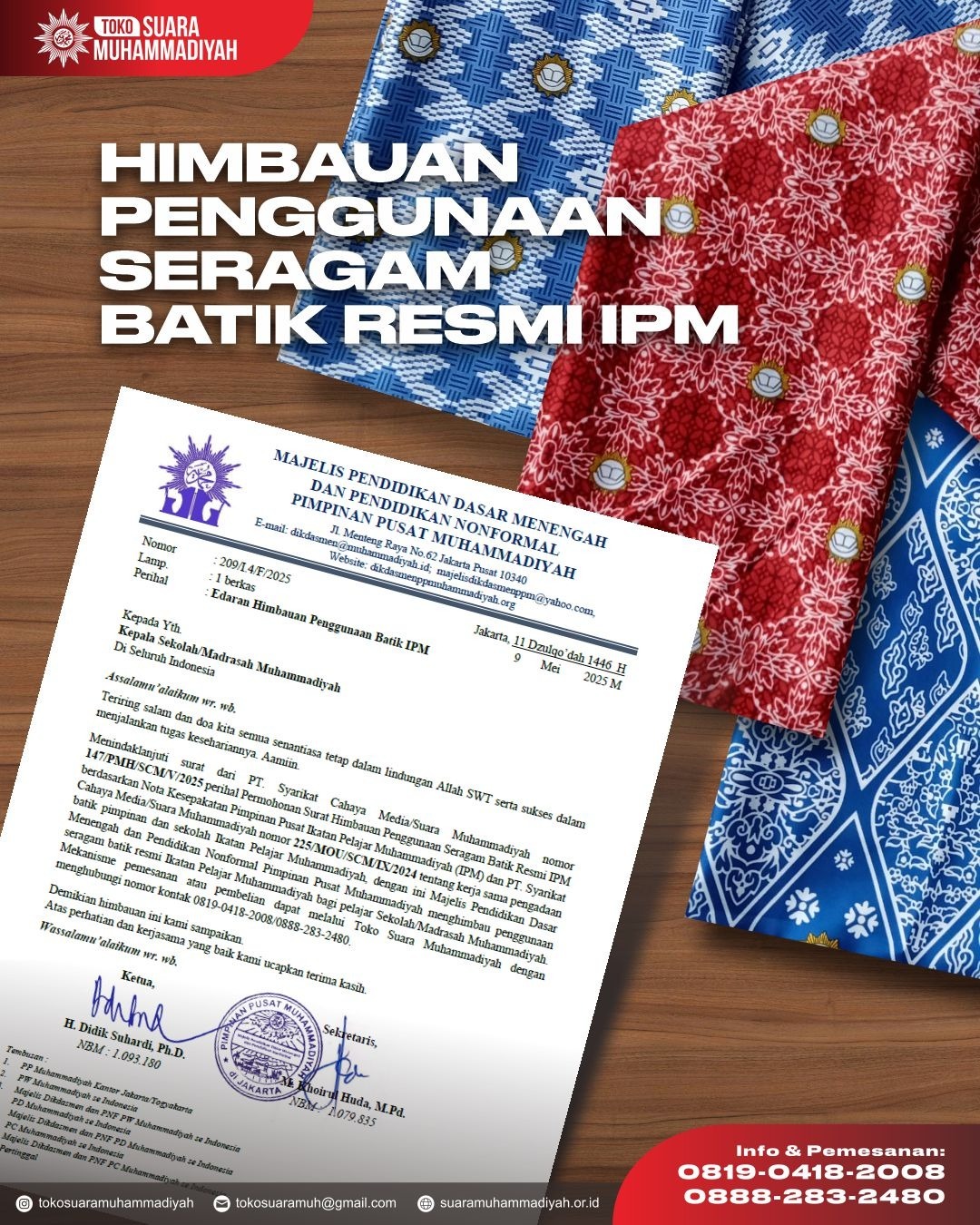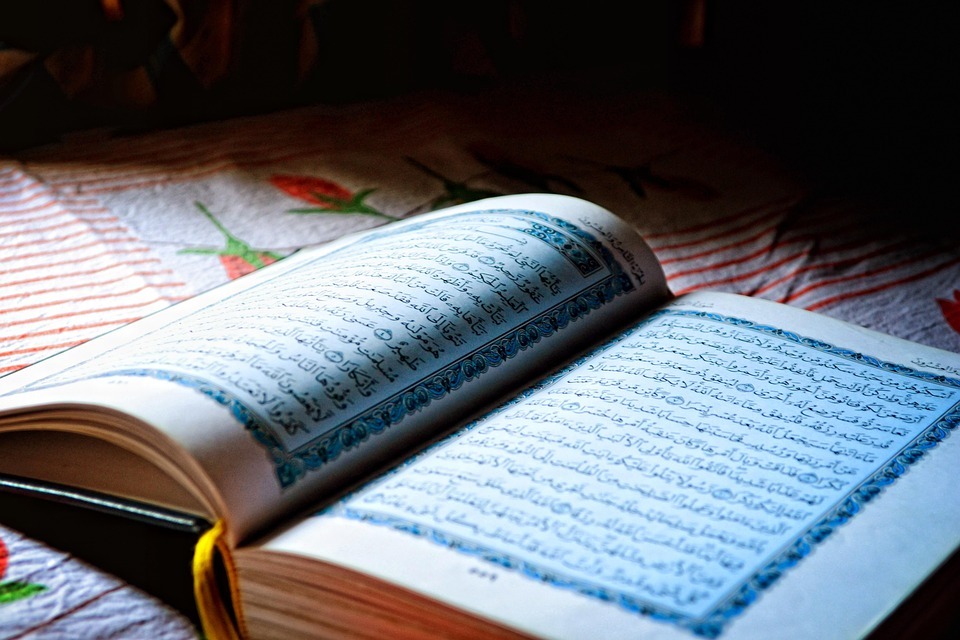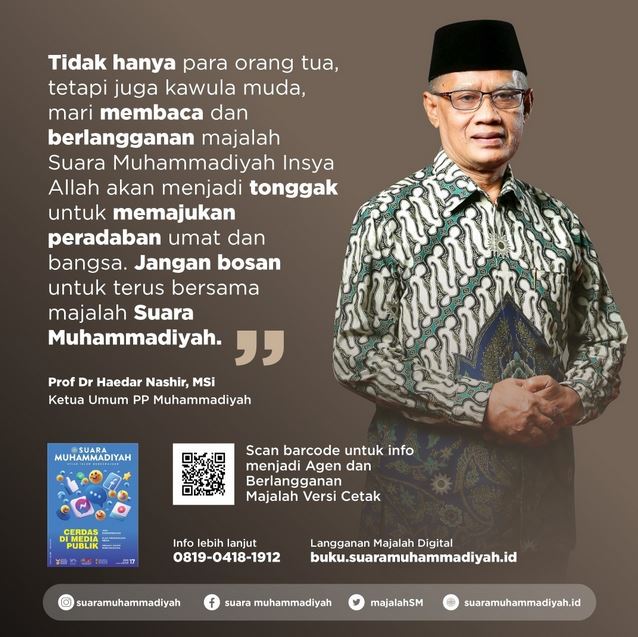Menyembah dalam Yakin, Meminta Pertolongan dalam Pasrah: Tafsir Filosofis-Sufistik QS. Al-Fātiḥah [1]: 5 sebagai Pedoman Pergaulan di Masyarakat Digital
Oleh: Piet Hizbullah Khaidir, Ketua STIQSI Lamongan; Sekretaris PDM Lamongan; dan Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur
Masyarakat digital hari ini hidup dalam paradoks spiritual yang tajam. Fenomena post-truth, fear of missing out (FOMO), dan budaya clipper—yakni potongan-potongan realitas dari video atau tulisan yang diambil tanpa konteks dan makna utuh, disertai framing dengan maksud tertentu—menjadikan relasi sosial serba instan, dangkal, dan terfragmentasi. Dalam ruang semacam itu, menyembah Tuhan seringkali hanya menjadi formalitas spiritual yang kehilangan substansi transendennya. Sementara itu, permohonan pertolongan kepada Allah terkadang berubah menjadi sekadar instrumen pragmatis untuk mengejar ambisi duniawi. Maka muncul pertanyaan yang menyentak nurani: apakah manusia digital masih merasa membutuhkan Tuhan, ataukah ia telah menuhankan algoritma, data, dan pengakuan sosial?
QS. al-Fātiḥah [1]:5, iyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn (“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan”), menawarkan sebuah kearifan filosofis-sufistik yang melampaui sekadar ritus. Ayat ini mengandung uslūb (struktur retoris dan gaya bahasa) yang unik dan dalam: penggunaan iyyāka (إِيَّاكَ) yang mendahului fi‘il, serta pengulangan yang menegaskan orientasi eksistensial manusia kepada Allah. Lafal na‘budu dan nasta‘īn berbentuk fi‘il muḍāri‘ (kata kerja kini dan akan datang), yang menandakan kesinambungan ibadah dan permohonan dalam kesadaran eksistensial yang berkelanjutan.
Ayat ini bukan sekadar ajaran tauhid ritual, tetapi fondasi etis bagi adab al-‘āsyirah—tata pergaulan di tengah masyarakat digital yang rentan kehilangan kesadaran ilahiah. Dalam konteks ini, tafsir para mufassir besar seperti al-Zamakhsyarī dalam al-Kashshāf, Ibn ‘Arabī dalam Tafsīr Ibn ‘Arabī, dan Muhammad Husein Ṭabāṭabā’ī dalam al-Mīzān memberikan horizon penafsiran yang dalam, memadukan ketepatan linguistik, kedalaman metafisika, dan kehalusan spiritual.
Uslub Iyyāka yang Diulang Dua Kali
Al-Zamakhsharī dalam al-Kashshāf menjelaskan bahwa struktur taqdīm maf‘ūl bih (mendahulukan objek) dalam iyyāka menandakan pembatasan mutlak (ḥaṣr), yakni hanya kepada Allah semata ibadah dan permohonan itu tertuju. Menurutnya, pengulangan iyyāka dua kali menunjukkan pemisahan antara dua dimensi yang tidak identik: ibadah sebagai bentuk penghambaan, dan isti‘ānah sebagai dimensi pengakuan kelemahan. Ibadah tanpa isti‘ānah akan menjelma kesombongan spiritual, sedangkan isti‘ānah tanpa ibadah akan menjadi kelemahan eksistensial tanpa arah.
Ibn ‘Arabī dalam Tafsīr Ibn ‘Arabī menafsirkan pengulangan iyyāka sebagai isyarat dua maqām ruhani: maqām ‘ubūdiyyah (penghambaan murni) dan maqām tafwīḍ (penyerahan diri sepenuhnya). Menurutnya, hamba yang sejati tidak hanya menyembah dalam yakin (yaqīn), tetapi juga meminta pertolongan dalam pasrah (taslīm). Dalam ibadah, manusia menyadari kehadiran Ilahi (ḥuḍūr), sementara dalam isti‘ānah, ia mengakui kelemahannya sendiri (faqr). Kedua sikap ini bersenyawa dalam satu kesadaran: bahwa segala daya hanyalah milik Allah (lā ḥawla wa lā quwwata illā billāh).
Sementara itu, Muhammad Husein Ṭabāṭabā’ī dalam al-Mīzān menegaskan bahwa pengulangan iyyāka merupakan refleksi hubungan dua arah antara Tuhan dan hamba. Dalam na‘budu, manusia menegaskan eksistensinya di hadapan Tuhan; dalam nasta‘īn, manusia mengakui ketergantungannya kepada Tuhan. Hubungan ini menegaskan tawḥīd fi‘lī (keesaan dalam perbuatan), yang menjadi dasar bagi etika sosial Islam: tidak ada kekuatan otonom selain Allah. Dengan demikian, setiap bentuk interaksi sosial, digital sekalipun, harus tunduk pada kesadaran bahwa segala daya, kuasa, dan keberhasilan adalah anugerah Ilahi, bukan hasil rekayasa manusia semata.
Fi‘il Muḍāri‘ dalam Menyembah dan Meminta Pertolongan
Al-Zamakhsharī menyoroti bentuk fi‘il muḍāri‘ pada na‘budu dan nasta‘īn sebagai indikasi kontinuitas (istimrār). Menyembah dan memohon pertolongan bukanlah tindakan sesaat, tetapi keadaan eksistensial yang terus diperbarui. Dalam konteks masyarakat digital, hal ini bermakna bahwa spiritualitas sejati tidak berhenti pada ritual, tetapi mewujud dalam kontinuitas kesadaran ilahiah di tengah dinamika teknologi dan interaksi virtual.
Al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghayb menafsirkan bentuk muḍāri‘ ini sebagai penegasan bahwa ibadah adalah pergerakan dinamis jiwa menuju kesempurnaan. Ia menulis, “al-‘ibādah ḥaqīqatu sayr al-insān ilā Allāh bi ikhtiyārihi wa ikhlāṣihi”—ibadah adalah perjalanan sadar manusia menuju Allah melalui pilihan dan keikhlasannya. Dalam era digital, di mana manusia mudah teralihkan oleh notifikasi dan validasi sosial, fi‘il muḍāri‘ mengingatkan bahwa ibadah sejati adalah proses penyucian diri yang tidak pernah berhenti.
Ibn ‘Arabī menambahkan bahwa nasta‘īn dalam bentuk muḍāri‘ menunjukkan tajdīd al-‘ahd (pembaruan janji spiritual). Setiap kali seseorang memohon pertolongan, ia memperbarui janjinya kepada Tuhan bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Maka, dalam dunia yang dipenuhi kecerdasan buatan dan teknologi otonom, kesadaran isti‘ānah menjadi benteng agar manusia tidak tergelincir dalam ilusi kemandirian digital.
Pedoman dalam Pergaulan Masyarakat Digital
QS. al-Fātiḥah [1]:5 mengajarkan etika spiritual yang sangat relevan bagi masyarakat digital modern. Pertama, iyyāka na‘budu mengingatkan manusia agar tidak menuhankan likes, followers, atau popularitas. Penyembahan sejati bukan kepada algoritma, melainkan kepada Allah yang Maha Mengatur.
Kedua, wa iyyāka nasta‘īn mengajarkan pasrah dalam perjuangan. Di tengah kompetisi digital, permohonan pertolongan sejati bukan kepada sistem, tetapi kepada sumber daya tertinggi: Allah SWT.
Tafsir filosofis-sufistik ini mengandung nilai tawḥīd al-‘amal (kesatuan orientasi tindakan). Setiap interaksi di ruang digital harus mencerminkan kesadaran spiritual: menulis dengan kejujuran, berbagi dengan niat kebaikan, dan berdialog dengan adab. Menyembah dalam yakin berarti tetap berpegang pada prinsip ilahiah di tengah arus informasi yang menipu. Meminta pertolongan dalam pasrah berarti menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman etik yang menyeimbangkan antara kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial di dunia maya. Iyyāka na‘budu menegaskan orientasi vertikal manusia kepada Tuhan, sementara iyyāka nasta‘īn menegaskan relasi horizontal manusia dengan sesama, yang dibingkai dalam kesadaran ilahiah.
QS. al-Fātiḥah [1]:5 adalah kristalisasi kesadaran eksistensial manusia: yakin dalam penyembahan, pasrah dalam permohonan. Dalam tafsir filosofis-sufistik, ayat ini tidak hanya memandu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengarahkan etika dalam pergaulan sosial, termasuk dalam ruang digital. Ketika manusia modern menempatkan Tuhan kembali sebagai pusat orientasi hidupnya, maka pergaulan digital tidak lagi menjadi arena pertarungan ego, tetapi ruang pengabdian yang penuh makna.
Menyembah dalam yakin berarti menegakkan keimanan di atas kesadaran; meminta pertolongan dalam pasrah berarti menegakkan harapan di atas kerendahan hati. Dua sikap ini menjadikan manusia digital bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi ‘ābid—penyembah yang sadar, dan musta‘īn—pemohon yang tunduk. Dengan itulah, kehidupan digital kembali bermakna sebagai jalan menuju Allah, bukan pelarian dari-Nya.