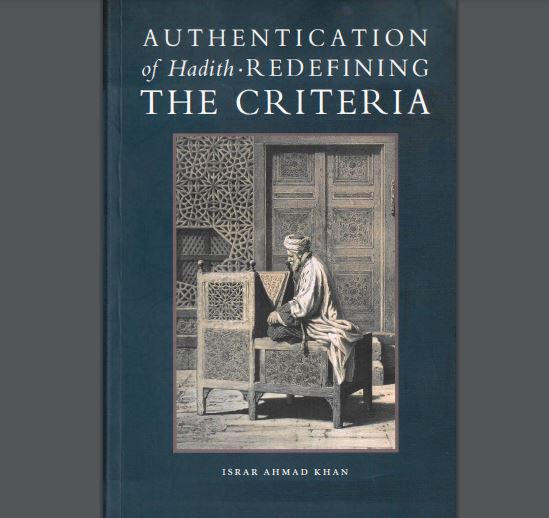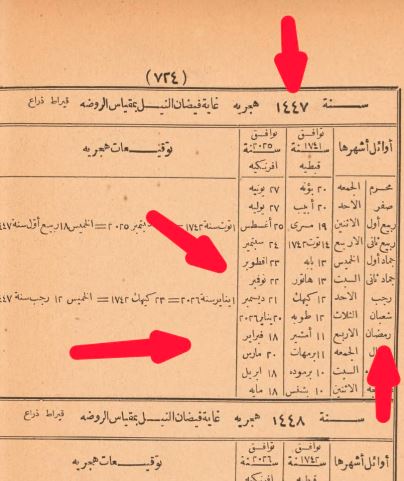Pendekatan Kritis dalam Otentikasi Hadits
Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Saya sedang membaca sebuah buku yang berjudul Authentication of Hadith: Redefining the Criteria (2010) karya Israh Ahmad Khan. Apa sebenarnya yang dibahas dalam buku ini? Buku ini mengupas secara mendalam tentang hadits dan kriteria yang digunakan oleh para ulama Muslim terdahulu untuk menilai keabsahan sebuah hadits. Para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan hadits, yang berisi catatan kecil tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Setiap hadits mengandung rekaman tentang apa yang beliau katakan, lakukan, atau saksikan, yang kemudian menjadi landasan hukum dalam Islam. Namun, tidak semua informasi dapat diterima begitu saja. Oleh karena itu, para ulama meneliti setiap hadits dengan sangat teliti. Mereka akan bertanya kepada orang yang menyampaikan hadits tersebut, "Siapa yang memberitahu Anda? Anda hidup di zaman saya, Anda tidak bertemu Nabi SAW dan saya juga tidak. Jadi, dari mana Anda mendapatkan informasi ini?"
Selanjutnya, orang tersebut akan menyebutkan nama guru atau orang yang menjadi sumber informasinya, dan proses verifikasi terus berlanjut. "Jangan hanya beritahu kami siapa yang Anda kenal, dari siapa guru Anda mendapatkannya? Karena dia juga tidak bertemu Nabi SAW, maka dari mana dia mendapatkannya?" Pertanyaan ini berlanjut, sehingga rantai narasi terus diusut hingga mencapai sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad SW. Dengan cara ini, sebuah hadits dikonfirmasi melalui rantai informan yang terhubung langsung hingga ke Nabi.
Pada masa awal pengumpulan hadits, fokus utama para kolektor adalah pada keaslian rantai perawi. Keterbatasan pemahaman pada zaman itu membuat mereka kurang kritis terhadap isi hadis itu sendiri. Namun, buku ini mengajak kita untuk melihat kembali hadis-hadis tersebut dan menilai kewajaran isinya.
Apakah ada contoh dari pendekatan ini? Tentu saja. Beberapa sahabat Nabi, terutama Aisyah, juga melakukan hal serupa. Ketika mendengar hadits yang dirasa tidak masuk akal, Aisyah akan mempertanyakannya. Bukan mempertanyakan Nabi, melainkan mempertanyakan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Aisyah memahami bahwa manusia bisa saja salah mengingat atau lupa. Oleh karena itu, tidak semua perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi bisa langsung diterima begitu saja, terutama jika tidak masuk akal. Salah satu tolok ukurnya adalah Al-Qur`an. Aisyah seringkali membandingkan hadits dengan Al-Qur`an. Jika ada pertentangan, ia berani menyangsikan kesahihan hadis tersebut.
Ia tidak pernah meragukan Nabi, melainkan meragukan perawi hadis. Sebagai contoh, ketika ada sahabat yang meriwayatkan bahwa orang yang meninggal akan dihukum jika ada orang yang menangisi mereka, Aisyah menolaknya. Ia berargumen bahwa Al-Qur`an telah menegaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tangisan orang yang hidup adalah dosa mereka sendiri, bukan dosa orang yang telah meninggal.
Inilah contoh bagaimana pentingnya menggunakan akal sehat dan penilaian kritis dalam memahami hadis. Kita perlu memahami konteks zaman dan keterbatasan manusia dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam menerima dan mengamalkan ajaran Nabi SAW.
Para ulama terdahulu, selain menyusun kitab-kitab hadits sahih, juga menyusun kitab-kitab yang memuat hadis-hadis palsu. Ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk upaya menjaga kemurnian ajaran Islam. Kitab-kitab tersebut berfungsi sebagai referensi cepat untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang perlu diwaspadai.
Ibnu al-Jawzi, misalnya, menyusun kitab Al-Maudhu'at yang berarti hadits-hadits palsu. Dalam menyusun kitab ini, ia dan ulama lainnya tidak hanya meneliti rantai perawi, tetapi juga menggunakan kriteria rasional. Misalnya, jika sebuah hadits menyebutkan seseorang terlibat dalam suatu peristiwa sebagai seorang Muslim, padahal diketahui dari sumber lain bahwa orang tersebut belum masuk Islam pada saat itu, maka hadits tersebut patut diragukan.
Selain itu, hadis yang bertentangan dengan akal sehat atau Al-Qur`an juga harus ditolak, meskipun diriwayatkan dalam kitab hadis yang terkenal. Al-Qur`an harus selalu menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesahihan sebuah hadis.
Dengan adanya kitab-kitab hadits palsu dan penerapan kriteria rasional, kita dapat lebih berhati-hati dalam menerima hadis. Ini penting untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam narasi palsu yang dapat menyesatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam. Salah satu contoh penting adalah hadis tentang hukuman rajam bagi pezina. Al-Qur`an secara jelas menyebutkan hukuman cambuk, sementara hadits tersebut menyebutkan rajam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ayat tentang rajam pernah ada dalam Al-Qur`an, tetapi kemudian dihapus.
Pendapat semacam ini tentu saja tidak bisa diterima karena akan meragukan keaslian Al-Qur`an itu sendiri. Al-Qur`an telah sampai kepada kita melalui jalur periwayatan yang sangat kuat, dihafal dan dibaca oleh banyak sahabat Nabi di setiap generasi. Sebaliknya, hadits diriwayatkan oleh satu atau dua individu yang mungkin saja melakukan kesalahan. Meskipun kemudian diriwayatkan oleh banyak orang, kesalahan tersebut tetap bisa menyebar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menerima hadis.
Sebelum kita menolak atau menerima suatu hadits, kita perlu memahami bahwa tidak semua hadis itu otentik. Penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang cara membedakan antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam memahami dan mengamalkan ajaran Nabi.
Satu hal yang saya rasa kurang dari buku ini adalah pembahasan mengenai predestinasi atau takdir. Meski penulis mengkritik beberapa hadis terkait topik tersebut, namun belum ada pandangan alternatif yang komprehensif ditawarkan. Saya memahami bahwa isu takdir adalah masalah yang kompleks dan sulit dipahami, namun saya berharap ada penjelasan lebih mendalam tentangnya.