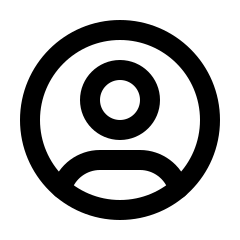Politik Bahasa dan Ilusi Kekuasaan
Oleh: Suko Wahyudi, PRM Timuran Yogyakarta
Bahasa pada hakikatnya adalah medium komunikasi, sarana penyampaian pikiran, serta jembatan untuk membangun pemahaman bersama. Namun dalam praktik politik, bahasa tidak jarang berubah fungsi. Ia tidak lagi berperan untuk menjernihkan realitas, melainkan untuk menyamarkannya.
Kata-kata dipoles hingga tampak menawan, sehingga kebijakan yang keras terdengar lunak, dan tindakan yang merugikan tampil sebagai langkah penuh kepedulian. Dengan strategi semacam itu, masyarakat diarahkan menerima sesuatu yang sesungguhnya menyakitkan, seolah-olah itu pilihan yang tak terelakkan.
Kekuasaan memahami betul bahwa manusia lebih mudah dipengaruhi oleh narasi daripada data mentah. Statistik sering kali terasa kaku, tetapi bahasa memiliki daya sugestif. Ia dapat membungkus kepahitan fakta dengan kemasan yang menenteramkan.
Karena itu, istilah yang terdengar ramah kerap dipilih untuk menutupi konsekuensi kebijakan. Penggusuran diubah menjadi penataan, pemotongan subsidi disebut efisiensi, sementara tindakan represif diberi nama penertiban. Bahasa menjadi tameng yang membentuk ilusi, seakan-akan tindakan yang sulit dipertanggungjawabkan adalah sesuatu yang wajar.
Fenomena ini begitu terasa di Indonesia hari ini. Ketika harga bahan bakar naik, masyarakat tidak diajak menyebutnya beban tambahan, melainkan “penyesuaian harga”. Ketika lahan masyarakat tergusur oleh proyek infrastruktur, istilah yang dipakai bukan perampasan, melainkan “relokasi”. Ketika aparat membubarkan demonstrasi dengan kekerasan, kata yang digunakan adalah “pengendalian situasi”. Kata-kata menjadi kosmetika bagi kebijakan, dan realitas yang pahit disembunyikan di balik kamuflase retoris.
Bahaya dari praktik semacam ini adalah terbentuknya kebiasaan untuk tidak lagi mempertanyakan makna kata-kata. Lama-kelamaan, masyarakat terbiasa menerima istilah yang membius tanpa daya kritis. Batas antara benar dan salah, adil dan zalim, menjadi kabur. Realitas yang merugikan bisa tampak seolah-olah sebagai kebaikan, hanya karena bahasa dipelintir untuk meyakinkan. Pada titik inilah pembusukan makna terjadi: kata-kata kehilangan daya moralnya sebagai penunjuk kebenaran.
Bahasa, Kuasa, dan Normalisasi Ilusi
Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, situasi ini diperparah dengan arus informasi digital. Media sosial mempercepat penyebaran narasi resmi, sementara suara kritis sering dilemahkan dengan stigma. Pihak yang berbeda pandangan mudah sekali dicap “anti-pembangunan”, “provokator”, bahkan “ancaman bagi stabilitas”.
Label semacam itu bukan sekadar permainan kata, melainkan instrumen kuasa yang efektif untuk membungkam oposisi. Padahal demokrasi menuntut keterbukaan, bukan pengaburan.
Perspektif Michel Foucault memberi pendasaran yang lebih dalam untuk memahami gejala ini. Bagi Foucault, bahasa bukanlah instrumen netral, melainkan bagian dari jaringan kuasa-pengetahuan (power/knowledge).
Melalui bahasa, kekuasaan tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap kenyataan. Siapa yang menguasai wacana, ia berhak mendefinisikan apa yang disebut pembangunan, siapa yang disebut musuh, bahkan apa yang dimaknai sebagai kebenaran. Dengan demikian, politik bahasa bukan sekadar soal retorika, melainkan bagian dari strategi kuasa yang halus tetapi efektif.
Sejarah mengajarkan bahwa manipulasi bahasa selalu membuka jalan bagi manipulasi yang lebih besar. Totalitarianisme, baik di Eropa maupun Asia, tidak hanya bertumpu pada kekerasan, melainkan juga pada kontrol kata-kata. Kata menjadi instrumen ideologi, propaganda menjadi bahasa resmi, dan kritik kehilangan legitimasi.
Indonesia memang bukan negara totaliter, tetapi gejala pengaburan bahasa tetap kentara. Ketika kritik diubah menjadi ancaman, ketika keberatan masyarakat diterjemahkan sebagai gangguan, bahasa telah diperalat untuk menyingkirkan kejujuran.
Menjaga Kejernihan Bahasa sebagai Tanggung Jawab Moral
Karena itu, menjaga kejernihan bahasa adalah tugas mendesak. Masyarakat perlu berani bertanya: apakah “penyesuaian harga” sungguh demi kesejahteraan, atau sekadar memindahkan beban? Apakah “relokasi” benar-benar berarti peningkatan kualitas hidup, atau hanya pemindahan penderitaan? Pertanyaan semacam ini adalah jalan awal untuk menyingkap selubung ilusi.
Menjaga kejernihan bahasa tentu bukan perkara ringan. Ia menuntut keberanian moral untuk berbicara apa adanya, meskipun terasa keras. Dalam iklim politik yang sering alergi terhadap kritik, keberanian ini berisiko. Namun, kejujuran kerap bermula dari kata-kata sederhana yang terang. Menyebut penggusuran sebagai penggusuran, pemotongan sebagai pemotongan, adalah bentuk kecil dari perlawanan terhadap manipulasi. Dari langkah kecil itulah kesadaran kolektif dapat tumbuh.
Pada akhirnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cermin keberpihakan. Apakah kita berpihak pada kekuasaan yang memoles kenyataan, atau pada masyarakat yang berhak mengetahui kebenaran? Politik mungkin penuh kompromi, tetapi bahasa tidak boleh kehilangan integritasnya. Begitu kata-kata kehilangan makna, masyarakat kehilangan kompas moral untuk membedakan yang benar dari yang salah.
Menjaga kejernihan bahasa berarti menjaga akal sehat bangsa. Bahasa yang jernih adalah cahaya, bahasa yang dipelintir adalah kabut. Di tengah kabut, rakyat bisa tersesat. Tetapi dengan cahaya kata-kata yang jujur, arah kebenaran akan tetap terlihat.