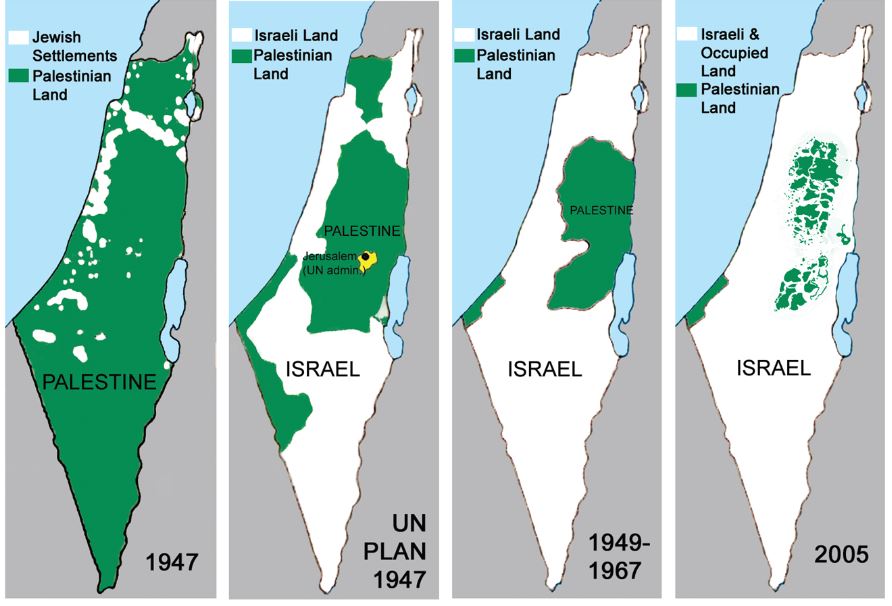TKA, Kesehatan Mental Siswa, dan Pendidikan yang Mencerahkan
Oleh: Nabigh Shorim Faozan, Mahasiswa Kedokteran Universitas Mataram dan Alumni MBS Ki Bagus Hadikusumo Bogor
Setiap tahun, jutaan pelajar Indonesia menghadapi berbagai bentuk evaluasi akademik. Salah satunya adalah Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang dirancang sebagai instrumen pelaporan capaian belajar individu secara terstandar. Secara konseptual, TKA diharapkan menjadi alat ukur yang objektif dan adil.
Namun dalam praktiknya, ujian tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral. Ia selalu bersinggungan dengan realitas psikologis, sosial, dan kultural peserta didik yang beragam, sehingga memungkinkan hasil yang tak sama.
TKA lahir dari kebutuhan akan data capaian akademik individu yang reliabel, setelah beberapa tahun sistem penilaian terstandar tidak berjalan optimal. Pada 2026, pendaftaran TKA untuk jenjang SD dan SMP dibuka sejak 19 Januari hingga 26 Februari. Meski tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan, TKA tetap dipersepsi sebagai momen penting dalam perjalanan pendidikan siswa. Persepsi inilah yang kerap memicu tekanan psikologis, terutama pada anak-anak dan remaja.
Bagi banyak siswa, TKA bukan sekadar pengujian pengetahuan. Ia sering dimaknai sebagai penentu masa depan: peluang melanjutkan pendidikan, pengakuan sosial, hingga kebanggaan keluarga. Tekanan datang dari berbagai arah—orang tua, guru, dan sistem pendidikan yang masih menempatkan prestasi kognitif sebagai indikator utama keberhasilan.
Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekspektasi akademik yang tinggi tanpa dukungan emosional memadai berkontribusi pada meningkatnya kecemasan siswa menjelang ujian (Putwain & Daly, 2014). Karena itu perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Data hasil TKA jenjang SMA/SMK/MA tahun 2025 memperlihatkan tantangan serius. Sebanyak 44,7 persen peserta memperoleh nilai Matematika dalam kategori kurang, sementara 33,8 persen berada pada kategori kurang untuk Bahasa Inggris. Sebaliknya, lebih dari 80 persen siswa mencapai kategori baik dan istimewa dalam Bahasa Indonesia.
Ketimpangan ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh kesiapan mental dan lingkungan belajar yang kondusif. Sehingga apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya akan berdampak positif pada prestasi siswa.
Dari sudut pandang kesehatan, keluhan seperti jantung berdebar, sakit kepala, mual, atau nyeri perut menjelang ujian merupakan manifestasi stres. Stres akut maupun kronis mengaktifkan sumbu hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis) yang meningkatkan kadar hormon kortisol.
Dalam jangka pendek, respons ini membantu tubuh beradaptasi. Namun, jika berlangsung berlebihan, kortisol justru mengganggu fungsi hipokampus dan korteks prefrontal—bagian otak yang berperan dalam memori, konsentrasi, dan pengambilan keputusan (McEwen, 2007; Lupien et al., 2009; Arnsten, 2009).
Kondisi ini dikenal sebagai test anxiety, yaitu kecemasan yang muncul pada situasi evaluasi akademik dan ditandai oleh kekhawatiran berlebihan, ketegangan fisik, serta gangguan perhatian (Spielberger & Vagg, 1995). Meta-analisis Zeidner (1998) menunjukkan bahwa kecemasan ujian berkorelasi negatif dengan prestasi akademik. Artinya, dua siswa dengan kemampuan yang relatif setara dapat memperoleh hasil berbeda hanya karena perbedaan tingkat ketenangan batin.
Menariknya, tingkat partisipasi TKA tahun 2025 mencapai sekitar 3,56 juta siswa dari total 4,1 juta murid jenjang SMA, SMK, MA, dan Paket C. Angka ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya evaluasi akademik. Dalam psikologi, motivasi semacam ini disebut motivasi intrinsik, dan terbukti lebih sehat serta lebih bertahan lama (Ryan & Deci, 2000).
Namun, objektivitas penilaian tidak cukup diukur dari keseragaman materi, soal dan waktu. Keadilan substantif menuntut perhatian pada kondisi psikologis siswa, karena dukungan emosional terbukti mampu menurunkan respons biologis terhadap stres (Heinrichs et al., 2003).
Penelitian lain menunjukkan bahwa dukungan dari orang tua, guru, dan teman sebaya berperan sebagai faktor protektif yang signifikan terhadap kecemasan akademik dan berdampak positif pada prestasi belajar (Suldo et al., 2008; Yamamoto & Holloway, 2010). Dalam nilai-nilai Islam yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah, pendidikan sejatinya adalah proses tarbiyah yang menumbuhkan manusia secara utuh—akal, jiwa, dan akhlaknya.
Sayangnya, praktik pendidikan kita masih cenderung menekankan aspek teknis persiapan ujian. Try out diperbanyak, jam belajar ditambah, dan target nilai diperketat, sementara layanan konseling sering bersifat reaktif.
Padahal, OECD (2015) menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan prasyarat utama pembelajaran yang efektif. Pendidikan modern di berbagai negara mulai mengintegrasikan social-emotional learning sebagai bagian dari kurikulum (Durlak et al., 2011).
Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang angka dan peringkat. Mutu pendidikan suatu bangsa tercermin dari sejauh mana sistemnya mampu menjaga kesehatan mental generasi mudanya.
TKA akan menjadi lebih bermakna jika diposisikan bukan sekadar alat ukur akademik, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif membangun pendidikan yang adil, berkeadaban, dan mencerahkan—sejalan dengan spirit dakwah Muhammadiyah dan cita-cita Islam berkemajuan.