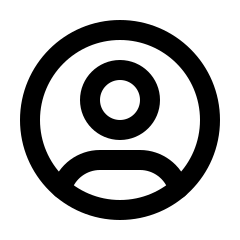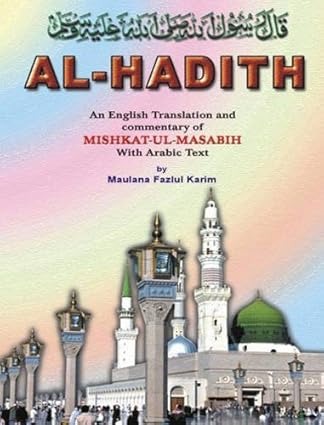Ya’qub dalam Al-Qur`an dan Alkitab
Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Ketika membahas Nabi Ya’qub, seringkali perhatian kita tertuju pada kisah putranya, Nabi Yusuf, yang penuh warna dan keagungan. Namun, di balik sorotan kisah Yusuf, terdapat sosok Ya’qub yang juga memiliki peran penting dan layak untuk kita dalami lebih jauh. Mari kita telusuri bagaimana Ya’qub digambarkan dalam dua kitab suci besar, Alkitab dan Al-Qur`an, serta apa persamaan dan perbedaan yang menarik di antara keduanya.
Baik Alkitab maupun Al-Qur`an sama-sama mengakui Ya’qub sebagai sosok penting dalam sejarah agama. Keduanya mencatat bahwa ia memiliki dua nama, Ya’qub dan Israel, yang terakhir diberikan oleh Tuhan sendiri. Dalam Alkitab, Ya’qub adalah bapa bangsa Israel, memiliki 12 putra yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Sementara itu, Al-Qur`an menggambarkan Ya’qub sebagai seorang nabi yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Ia digambarkan sebagai sosok yang berilmu karena telah diajarkan oleh Allah.
Namun, terdapat perbedaan menarik dalam bagaimana karakter Ya’qub ditampilkan dalam kedua kitab suci tersebut. Dalam Al-Qur`an, Ya’qub, sebagaimana para nabi lainnya, digambarkan sebagai sosok yang saleh dan bertakwa. Ia menjadi teladan bagi umat manusia, sosok yang patut dicontoh dan diikuti dalam menjalani kehidupan.
Dalam Alkitab, Ya’qub sering digambarkan sebagai sosok yang cerdik dan licik. Salah satu contohnya adalah ketika ia memanfaatkan rasa lapar saudaranya, Esau, untuk mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Dalam kisah tersebut, Esau yang sedang kelaparan bersedia menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkuk sup yang ditawarkan Ya’qub.
Tentu saja, dari sudut pandang penulis Alkitab, tindakan Esau ini dianggap kurang terpuji karena ia merelakan hak istimewa yang penting demi memuaskan kebutuhan sesaat. Namun, jika kita mencoba memahami dari sudut pandang Esau, mungkin kita bisa bersimpati dengan keputusannya. Saat itu, ia sedang sangat lapar dan merasa bahwa hak kesulungan tidak ada artinya jika ia harus mati kelaparan.
Selain itu, ada juga kisah lain yang menggambarkan kecerdikan Ya’qub. Ketika ayahnya, Ishak, yang sudah tua dan buta, hendak memberikan berkat kepada Esau, Ya’qub menyamar sebagai Esau dan berhasil mendapatkan berkat tersebut.
Ya, dan ternyata Ishak telah memberikan berkat kepada putra yang salah. Tentu saja, cara penggambaran kisah ini dalam Alkitab mungkin sulit diterima oleh mereka yang cenderung skeptis. Alkitab menggambarkan Esau dilahirkan dengan tubuh berbulu lebat, nyaris seperti tertutup lapisan bulu hewan. Ini jelas merupakan hiperbola yang dilebih-lebihkan, karena tidak mungkin manusia memiliki rambut sebanyak itu.
Ketika Ishak telah lanjut usia dan kehilangan penglihatannya, ia berniat memberikan berkat kepada putranya. Pilihannya tentu saja antara Esau atau Ya’qub. Sebagai anak sulung, Esau seharusnya menjadi pewaris berkat tersebut. Namun, Ribka, ibu Ya’qub, menyusun rencana licik. Ia menyuruh Ya’qub mengenakan kulit binatang agar terasa berbulu ketika disentuh oleh Ishak. Dengan tipu muslihat ini, Ishak yang buta akan mengira Ya’qub adalah Esau dan memberikan berkat kepadanya. Ya’qub pun mengikuti rencana ibunya, dan akhirnya Ishak memberikan berkat yang berharga itu kepada Ya’qub, bukan Esau, sang putra sulung yang seharusnya menerimanya.
Dan ternyata, berkat yang telah diberikan itu bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Sekali terucap, meskipun diberikan karena kesalahan, berkat itu tetap berlaku. Sepertinya berkat khusus semacam itu memang hanya bisa diberikan kepada satu putra saja. Jadi, ketika Esau kembali dari berburu dengan penuh semangat untuk menyenangkan ayahnya, ia mendapati kenyataan pahit bahwa berkat tersebut telah diberikan kepada Ya’qub. Padahal, Esau telah bersusah payah pergi berburu dan menyiapkan hidangan kesukaan ayahnya. Namun, Ribka, dengan cerdiknya, telah mendahului Esau dengan menyiapkan hidangan yang sama dan menyuruh Ya’qub membawanya kepada Ishak.
Dengan penuh kekecewaan, Esau menghadap ayahnya dan bertanya, "Ayah, di mana berkatku? Akulah Esau, putramu!" Namun, Ishak hanya bisa menjawab dengan sedih, "Maafkan aku, anakku. Aku telah memberikan seluruh berkat kepada saudaramu, dan itu tidak bisa dibatalkan."
Situasi ini mungkin terasa janggal bagi sebagian orang. Jika kita menganggap berkat sebagai doa atau harapan baik, tentu kita berpikir bahwa Tuhan lebih mengetahui niat sebenarnya di balik ucapan tersebut. Meskipun Ishak keliru mengira Ya’qub sebagai Esau, bukankah seharusnya Tuhan tetap memberikan berkat itu kepada Esau yang memang menjadi tujuan doa Ishak? Namun, dalam kisah ini, hal tersebut tidak terjadi.
Bagi para sejarawan, kejadian ini menimbulkan dugaan bahwa kisah tersebut ditulis dari sudut pandang keturunan Ya’qub. Dengan kata lain, penulis berusaha mengangkat derajat nenek moyang mereka, Ya’qub, dibandingkan dengan Esau.
Meskipun Ya’qub adalah nenek moyang mereka, penulis Alkitab tidak selalu menggambarkannya dalam citra yang paling positif, bukan? Kita mungkin berharap bahwa seorang pahlawan atau tokoh penting akan selalu ditampilkan dalam sudut pandang yang mengagungkan. Namun, bagi seorang Muslim yang membaca kisah-kisah tersebut, Ya’qub mungkin terkesan kurang terpuji karena tindakannya yang licik.
Ini menimbulkan pertanyaan menarik: mengapa penulis Alkitab memilih untuk menggambarkan nenek moyang mereka sendiri dengan cara seperti itu? Mungkin saja pada masa itu, kecerdikan dan kemampuan untuk mengakali orang lain dianggap sebagai sifat yang menguntungkan. Konsep tentang benar dan salah bisa berubah seiring waktu dan budaya. Mungkin saja para penulis Alkitab tidak sepenuhnya menyadari bagaimana kisah tersebut akan ditafsirkan oleh generasi di masa depan, sehingga mereka menggambarkan Ya’qub sebagaimana adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Kita mengagumi bagaimana Al-Qur`an melukiskan sosok Ya’qub, terutama dalam hal kesabaran dan keteguhan imannya kepada Tuhan. Apakah ada kisah serupa dalam Alkitab yang menggambarkan kualitas-kualitas tersebut? Tentu, kita akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk membahas hal ini secara mendalam ketika kita menelaah kisah Nabi Yusuf. Namun, untuk saat ini, saya ingin menegaskan bahwa Al-Qur`an memang menggambarkan Ya’qub sebagai sosok yang memiliki kesabaran luar biasa. Kita akan melihat lebih detail mengenai hal ini di lain waktu.
Selain itu, Al-Qur`an juga menyoroti kepedulian Ya’qub terhadap tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Ia bahkan mengajarkan konsep ini dengan sungguh-sungguh kepada anak-anaknya. Al-Qur`an menceritakan momen mengharukan ketika Ya’qub, menjelang wafatnya, mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, "Siapa yang akan kalian sembah setelah aku tiada?" Mereka pun berjanji untuk hanya menyembah satu Tuhan yang benar.
Ini sedikit berbeda dengan penggambaran dalam Alkitab, di mana Ya’qub mengumpulkan putra-putranya dan membicarakan tentang masa depan mereka di dunia, termasuk siapa yang akan memerintah wilayah mana. Tampaknya ada perbedaan fokus antara narasi Alkitab yang lebih bersifat duniawi, dan Al-Qur`an yang lebih menekankan aspek spiritual dan akhirat.
Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, baik Alkitab maupun Al-Qur`an sama-sama mengakui Ya’qub sebagai sosok yang agung, salah satu nenek moyang penting dalam sejarah keyakinan kita. Penghargaan kita terhadapnya semakin bertambah ketika kita memahami lebih dalam tentang kehidupannya dan nilai-nilai yang ia perjuangkan.