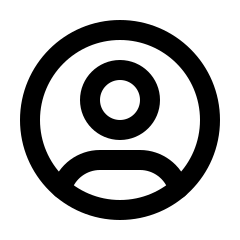Kebaikan Tanpa Tuhan: Apakah Moralitas Diciptakan atau Ditemukan?
Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Jawaban atas pertanyaan apakah seseorang bisa menjadi orang baik tanpa percaya kepada Tuhan hampir pasti adalah ya, sebab banyak dari kita mengenal individu yang sangat baik meskipun mereka tidak beriman. Hal ini kemudian mengarahkan kita pada pertanyaan yang lebih menarik: bagaimana seseorang yang tidak percaya Tuhan mendefinisikan dirinya sebagai orang baik?
Bagi non-agamis, kebaikan seringkali diukur secara horizontal, berakar pada kepatuhan pada aturan dan norma sosial. Ini mencakup kepatuhan pada hukum negara, seperti menjadi pengemudi yang taat, dan kesesuaian sosial, yaitu bertindak sebagai warga negara yang baik yang hidup damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, dalam pandangan ini, menjadi orang baik berarti mengikuti dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, di mana kebaikan adalah cerminan dari ekspektasi masyarakat dan keyakinan internal seseorang tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam lingkungan sosial.
Namun, definisi kebaikan memiliki dimensi yang berbeda bagi orang yang religius. Ketika seorang yang beriman menyatakan dirinya sebagai orang baik, mereka mendasarkan pernyataan itu pada lapisan moralitas yang lebih dalam. Meskipun mereka juga mematuhi norma sosial dan hukum yang berlaku - seperti mengemudi dengan benar dan tidak mengganggu tetangga - mereka menambahkan lapisan kewajiban vertikal: menjadi baik sesuai dengan cara yang Tuhan inginkan.
Dalam pandangan ini, kebaikan tertinggi bukan ditentukan oleh diri sendiri, melainkan oleh kehendak Ilahi. Ini berarti berusaha menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Tuhan, dan yang lebih fundamental, mengakui bahwa Tuhan adalah benih atau dasar dari segala kebaikan. Oleh karena itu, konsepsi mereka tentang "orang baik" berakar pada apa yang Tuhan yakini sebagai deskripsi kebaikan sejati, bukan hanya pada keyakinan manusia. Ketika orang yang beragama berusaha menjadi baik, mereka berusaha menyesuaikan diri dengan citra atau deskripsi sempurna tentang orang baik yang ada dalam pikiran Tuhan. Perbedaan ini krusial: sementara pandangan sekuler mendasarkan kebaikan pada kemauan sendiri, definisi sosial, dan kepatuhan norma, orang yang beriman memiliki ide yang berbeda, yang bersumber dari entitas transenden.
Perbedaan mendasar antara pandangan sekuler dan religius dalam mendefinisikan kebaikan terletak pada sifat permanensi dan sumber otoritas moral tersebut. Dalam pandangan sekuler, definisi "orang baik" bersifat relatif dan dapat berubah, di mana apa yang dianggap baik hari ini dapat bergeser besok, karena kebaikan adalah fungsi dari norma-norma sosial yang cair. Contoh nyatanya adalah perbedaan aturan lalu lintas di Kanada (kanan) dan Inggris (kiri), kebaikan hanya berarti menyesuaikan diri dengan tren atau adat setempat, yang memicu pertanyaan, "Mengapa harus melakukan apa yang orang lain harapkan?" Seseorang yang melanggar norma sosial hanya dianggap sebagai pemberontak terhadap konsensus sosial saat itu. Sebaliknya, meskipun interpretasi kebaikan religius juga dapat bervariasi, definisinya selalu berakar kuat pada konsepsi Tuhan tentang orang baik. Setiap tindakan moral baru selalu kembali pada pertanyaan: Apa yang Tuhan ingin orang baik lakukan dalam situasi ini? Bagi orang beriman, menentang konsepsi kebaikan moral bukan sekadar pemberontakan sosial, tetapi merupakan keputusan yang sangat signifikan yang menentukan apakah individu tersebut tetap "berada di pihak Tuhan" atau "memberontak melawan Tuhan," sehingga konsekuensinya jauh melampaui sanksi sosial dan menjadi penentu keputusan yang mengubah hidup.
Perbedaan pandangan moral ini berpuncak pada pertanyaan tentang otoritas dan kewajiban. Dalam pandangan sekuler, individu menikmati kelonggaran moral yang luas. Meskipun seseorang dapat memilih untuk menjadi "orang baik" dengan mengikuti norma sosial, pada dasarnya tidak ada kata 'harus' yang mengikat. Jika seseorang diperintahkan untuk mengikuti aturan masyarakat, ia berhak bertanya: "Siapa masyarakat yang berhak mendikte saya? Saya adalah individu dengan norma-norma saya sendiri." Kebaikan, pada akhirnya, adalah pilihan sukarela, bukan keharusan yang mengikat secara fundamental.
Sebaliknya, dalam pandangan religius, ruang gerak untuk menentukan kebaikan secara mandiri menjadi sangat terbatas. Meskipun Tuhan memberikan kebebasan dalam batas-batas tertentu, perilaku baik harus tetap berada dalam paradigma Ilahi. Ketika seseorang berkata, "Anda seharusnya menjadi baik sesuai perintah Tuhan," pertanyaan balik yang menantang otoritas tersebut ("Siapa Tuhan yang berhak mendikte saya?") menjadi tidak logis dalam kerangka keyakinan itu sendiri. Jika entitas tersebut benar-benar adalah Tuhan (Sang Pencipta), maka otoritas-Nya untuk mendikte kebaikan adalah mutlak dan tak terbantahkan.
Inilah yang menciptakan jurang pemisah yang besar: pandangan sekuler menyediakan otonomi moral yang rentan terhadap nihilisme, sementara pandangan religius menancapkan kebaikan pada kewajiban Ilahi yang fundamental.
Kontras paling tajam antara moralitas sekuler dan religius terletak pada pertanyaan mendasar: Apakah kita menciptakan kebaikan, ataukah kita menemukannya? Dalam pandangan sekuler, dimana norma-norma terus berubah lintas generasi dan budaya, sering kali kita secara radikal mengubah definisi kebaikan. Hal ini digambarkan dengan metafora yang mencolok: kita menembakkan panah terlebih dahulu, baru kemudian menggambar sasaran tembak di sekelilingnya.
Artinya, kita bertindak, memutuskan apa yang ingin kita bayangkan sebagai "orang baik" setelah fakta, dan baru kemudian kita melabelinya sebagai moralitas. Kebaikan adalah konstruksi yang selalu beradaptasi dengan tindakan dan keinginan kita.
Sebaliknya, pandangan yang meyakini Tuhan sebagai sumber moralitas menempatkan sasaran tembak di tempatnya sejak awal. Kebaikan adalah objek eksternal yang sudah ada - sebuah konsepsi yang dimiliki Tuhan. Kita tidak menciptakan kebaikan; kita berusaha memukul sasaran yang sudah ditetapkan. Kebaikan adalah upaya untuk meniru dan mengikuti citra "orang baik" yang telah Tuhan bayangkan dan definisikan, menjadikan perilaku baik sebagai sebuah kewajiban ('seharusnya') untuk menyesuaikan diri dengan citra Ilahi tersebut.
Inilah mengapa di zaman modern, sulit mencapai konsensus moral. Ketika setiap orang menjadi arsitek moralitasnya sendiri, masing-masing memiliki konsepsi yang berbeda tentang apa itu 'baik'. Situasi ini melahirkan anarki moral, di mana beberapa orang bahkan mengangkat tangan dan bertanya: "Mengapa saya harus menjadi baik sama sekali?" Hanya dalam pandangan religius kita dapat memberikan jawaban yang otoritatif dan mengikat, yang menyatakan: "Ya, Anda seharusnya menjadi baik." Kebaikan ini dijelaskan melalui Kitab Suci dan dicontohkan melalui para Nabi - seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad - yang berfungsi sebagai teladan hidup dari "orang baik" yang Tuhan inginkan. Ini memberikan fondasi yang kokoh bagi moralitas, berbeda dengan fondasi sekuler yang terus bergeser.
Bagi umat Islam, Al-Qur'an memberikan kesimpulan yang jelas mengenai sumber dan tujuan kebaikan. Surah Al Ahzab ayat 21 menyatakan: "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat." (Laqad kâna lakum fî rasûlillâhi uswatun hasanah, liman kâna yarjûllâha wal-yawmal-âkhira).
Ini berarti, bagi seorang Muslim, tujuan kebaikan adalah menyesuaikan diri dengan citra sempurna yang telah Tuhan tetapkan dan wahyukan - sebuah gambar yang dicontohkan dalam kehidupan Nabi. Ini adalah upaya untuk memukul sasaran tembak yang telah ditetapkan secara objektif di luar diri kita.
Maka, kesimpulannya adalah seseorang memang bisa menjadi orang baik tanpa percaya Tuhan, tetapi kebaikan itu akan terbatas pada norma sosial, adat istiadat, atau konsepsi pribadi, dan tidak ada keharusan untuk menjadi baik. Pada pandangan religius, ada keharusan moral yang mengikat: seseorang seharusnya menjadi baik, dan cara untuk menjadi baik sudah ditetapkan oleh pandangan objektif Tuhan. Dalam pandangan sekuler, kita bebas berkeliaran tanpa sasaran, sedangkan dalam pandangan religius, kita memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk mengenai sasaran mutlak dari kebaikan yang telah Dia niatkan.
(Vivi)