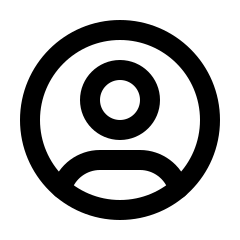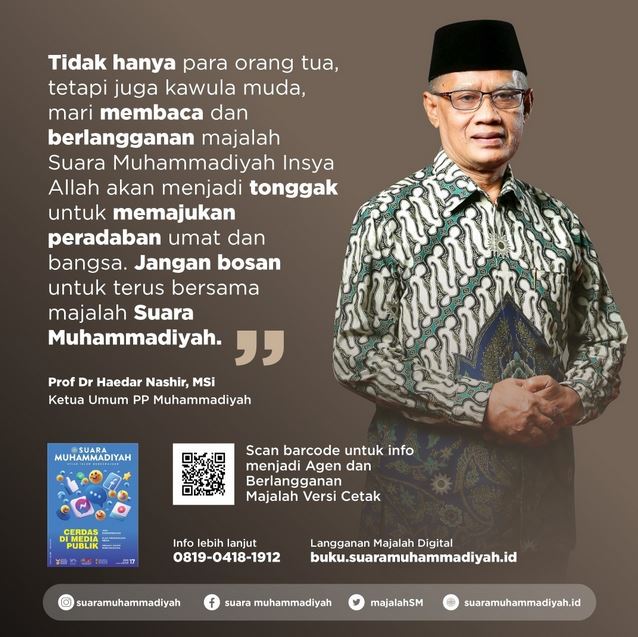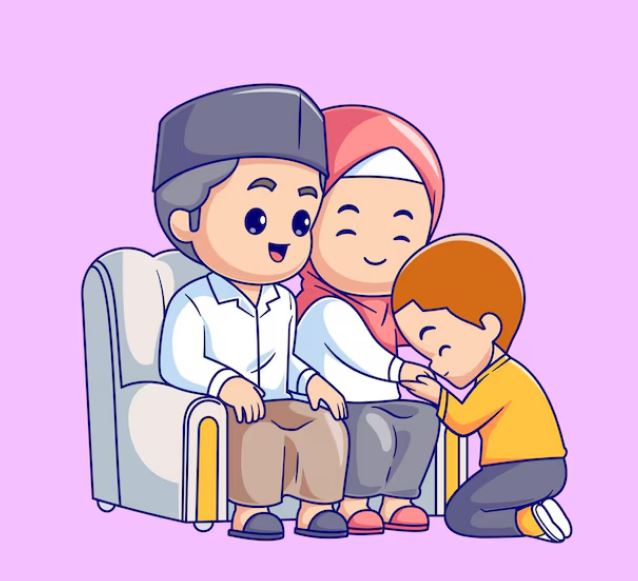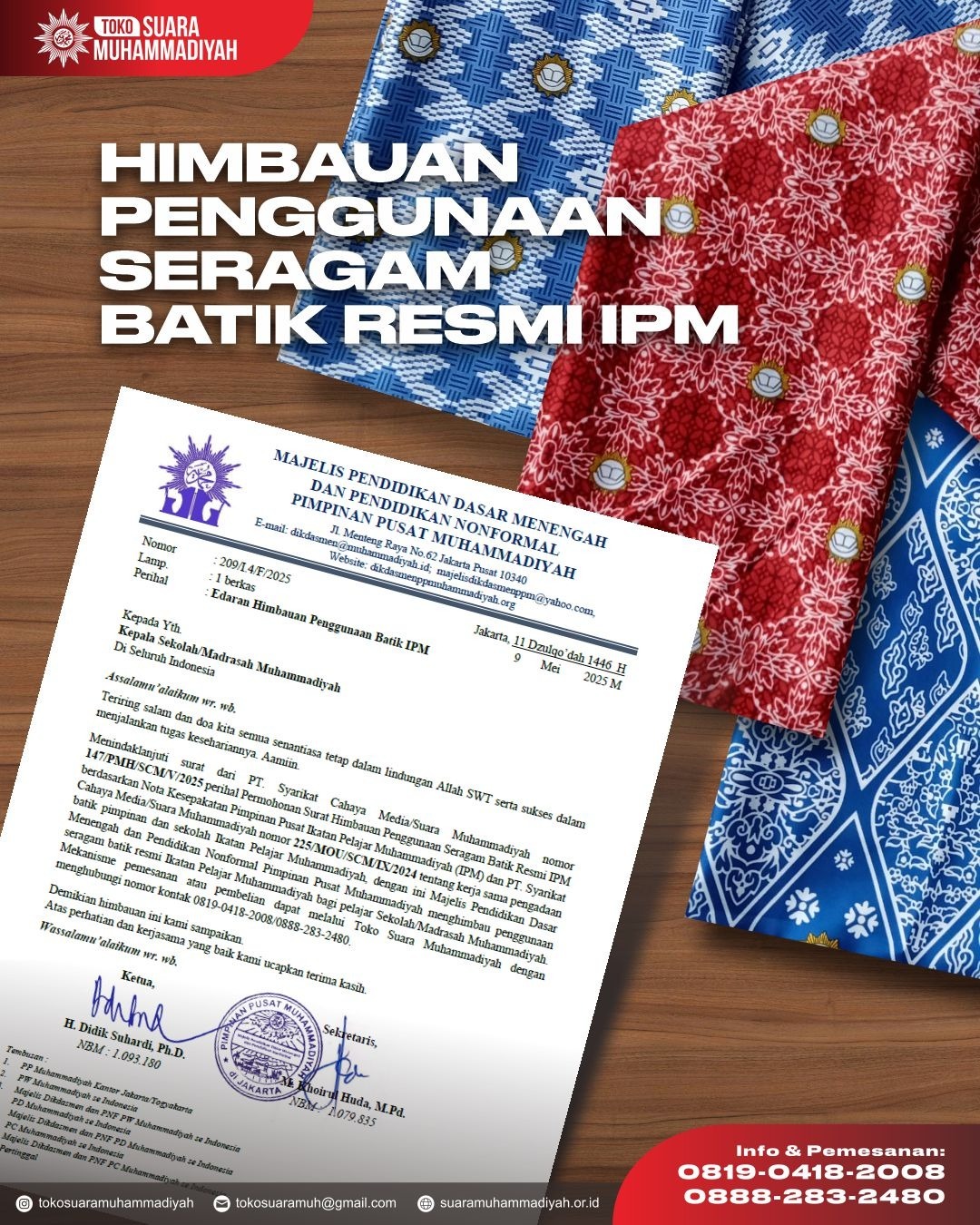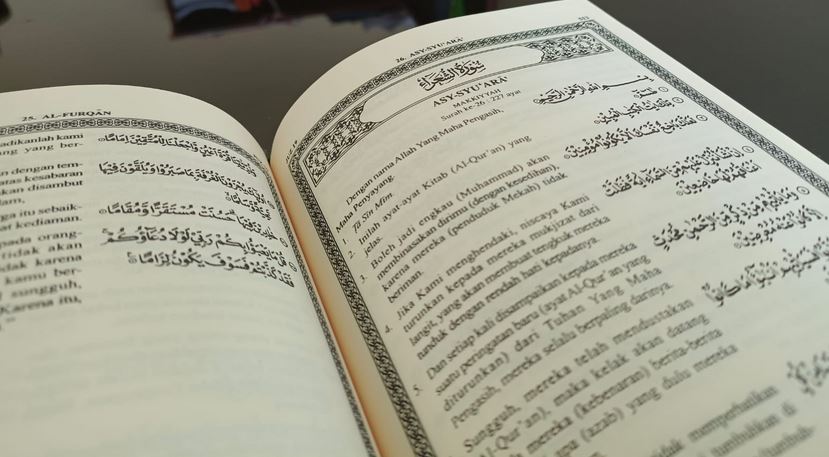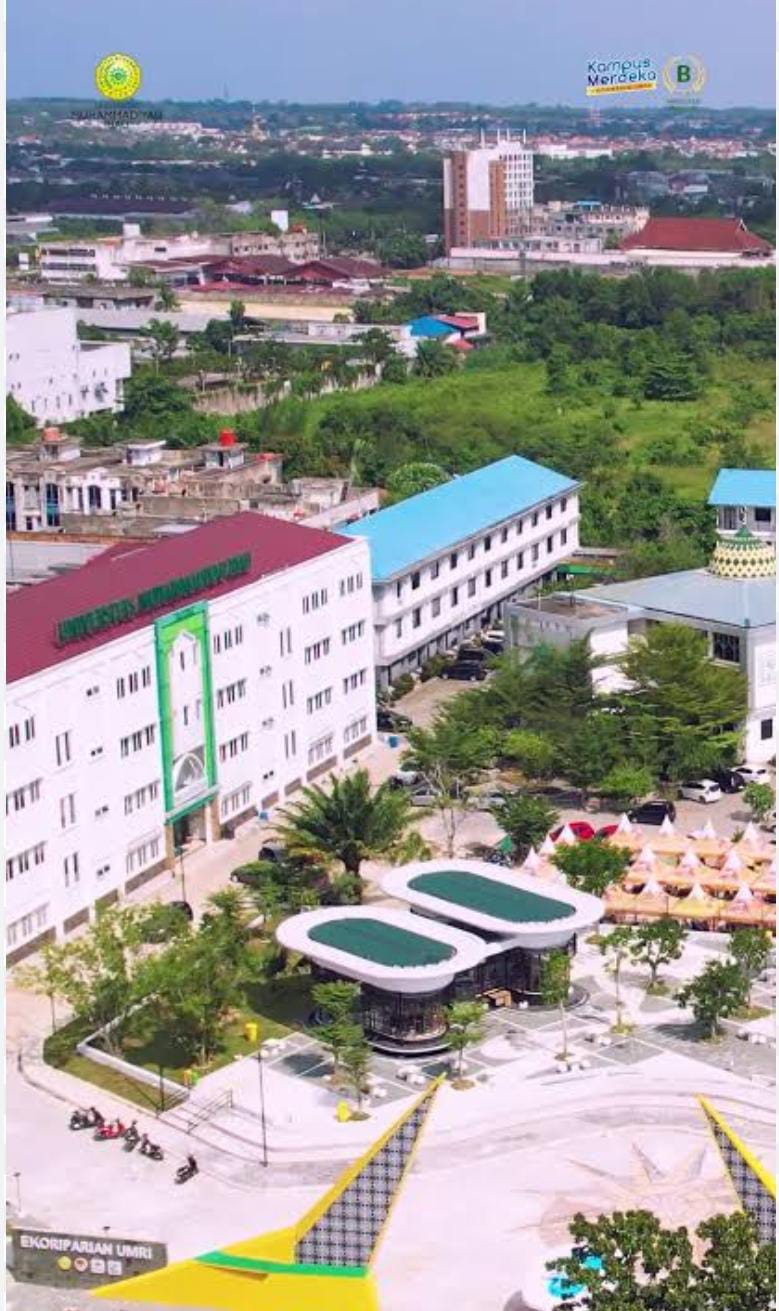Kekuasaan: Antara Amanah dan Alat Distribusi Keuntungan
Oleh: Suko Wahyudi, PRM Timuran Yogyakarta
Kekuasaan dalam sejarah umat manusia senantiasa menjadi pusat perhatian, karena ia tidak hanya menyangkut persoalan politik praktis, melainkan juga menyentuh dimensi moral, spiritual, bahkan eksistensial.
Dalam dirinya, kekuasaan memiliki daya ganda: ia dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial, tetapi sekaligus dapat berubah menjadi sumber kerusakan, ketidakadilan, dan kehancuran bila dikelola dengan keliru. Realitas politik di tanah air memperlihatkan betapa sering kekuasaan direduksi menjadi sekadar alat distribusi keuntungan.
Politik yang pada hakikatnya lahir sebagai ruang ideal untuk menata kehidupan bersama, dalam kenyataannya berubah menjadi arena perebutan akses terhadap sumber daya, tempat para pemegang kekuasaan sibuk mengatur aliran pendapatan, sementara rakyat yang mestinya menjadi tujuan utama justru ditinggalkan di pinggiran.
Fenomena ini membuka mata kita terhadap akar dari berbagai problem bangsa: korupsi yang merajalela, kebijakan yang berpihak kepada segelintir kelompok, hingga jurang ketimpangan sosial yang semakin menganga.
Kekuasaan yang seharusnya dipandang sebagai amanah untuk menegakkan keadilan malah kerap diperlakukan sebagai ladang untuk memperkaya diri. Tak mengherankan bila rakyat merasa jauh dari pusat pengambilan keputusan, sebab orientasi kebijakan lebih diarahkan pada pemeliharaan arus pendapatan bagi penguasa dan kroninya.
Terjadilah lingkaran setan: rakyat tetap miskin, pejabat semakin makmur, dan demokrasi yang mestinya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat tampak hidup hanya di permukaan, sekadar seremoni elektoral lima tahunan yang kehilangan ruh substansialnya.
Sejak zaman klasik, para filsuf telah mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya bukan hak istimewa, melainkan beban tanggung jawab. Plato berbicara tentang penguasa yang ideal sebagai philosopher king, raja filsuf yang memimpin bukan karena nafsu akan kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan dan cinta kepada kebenaran.
Dalam pandangan Nietzsche, kekuasaan memang erat dengan kehendak untuk berkuasa, will to power, namun tanpa moralitas kehendak itu hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam tirani.
Dalam tradisi Islam, kekuasaan adalah amanah, sebuah tanggung jawab yang begitu berat sehingga langit, bumi, dan gunung pun enggan memikulnya, namun manusia berani menerimanya. Al-Qur’an menegaskan bahwa amanah itu bisa menjadi sebab kemuliaan bila dijalankan dengan benar, tetapi juga menjadi sumber kehinaan bila disalahgunakan.
Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan bahwa “pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”, sebuah sabda yang mengandung pesan bahwa kekuasaan adalah pelayanan, bukan kemewahan.
Ilmu sosial-politik mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Max Weber membedakan antara power dan authority, antara kemampuan memaksa dengan kewenangan yang lahir dari legitimasi moral dan hukum.
Banyak pemimpin mungkin memiliki kekuatan untuk memerintah, tetapi tidak memiliki kewibawaan untuk ditaati dengan rela. Ketika kekuasaan kehilangan legitimasi moral, rakyat hanya tunduk karena terpaksa, bukan karena percaya. Dalam kondisi seperti itu, negara tampak hadir secara formal, tetapi secara batin ia absen di hati rakyatnya.
Kenyataan inilah yang kita saksikan ketika kebijakan publik lebih sering ditujukan untuk memperkuat jejaring elit ketimbang melayani kepentingan masyarakat luas. Rakyat miskin tetap miskin karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terhalang oleh struktur yang timpang.
Elit politik semakin makmur karena posisi mereka memungkinkan untuk mengendalikan distribusi sumber daya. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan yang rapuh. Politik lalu kehilangan makna sebagai seni mulia dalam mengelola kepentingan bersama, tereduksi hanya menjadi transaksi kepentingan jangka pendek.
Menempatkan Kembali Kekuasaan pada Rel Moral dan Sosial
Namun, situasi ini bukanlah keniscayaan yang tak bisa diubah. Kekuasaan dapat dan harus diletakkan kembali pada rel yang benar, yakni rel moral dan sosial.
Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang menghadirkan akses pendidikan yang merata, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, membangun sistem yang adil, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan.
Ukuran keberhasilan suatu kekuasaan bukanlah seberapa besar pemasukan negara yang dikuasai segelintir elit, melainkan seberapa luas manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat kecil. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghadirkan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari warganya, bukan pemimpin yang memperlihatkan jarak dengan rakyatnya.
Di sinilah kita diingatkan agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang sempit. Pragmatisme semacam itu hanya memandang politik sebagai permainan kursi dan angka, tanpa memedulikan tujuan luhur yang seharusnya dituju. Padahal, politik sejati adalah seni mulia dalam mengelola kepentingan publik demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Bila politik terjebak pada hitung-hitungan untung rugi yang dangkal, maka ia kehilangan martabatnya sebagai sarana menegakkan nilai-nilai luhur.
Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan hanya lahir ketika rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Reformasi 1998 menjadi saksi bagaimana suara rakyat mampu mengguncang bangunan kekuasaan yang korup. Harapan serupa masih ada, sejauh kesadaran kolektif bangsa ini terus dipelihara, sejauh rakyat berani menuntut agar kekuasaan diperlakukan kembali sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa. Kita membutuhkan pemimpin yang menghayati jabatan sebagai ujian, bukan pencapaian. Pemimpin yang sadar bahwa setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Kekuasaan, dengan demikian, adalah pisau bermata dua. Di tangan orang yang salah, ia melukai dan menghancurkan. Namun di tangan mereka yang jujur, berani, dan berjiwa besar, kekuasaan menjadi sarana untuk menyembuhkan luka bangsa dan membangun peradaban yang lebih adil dan sejahtera.
Bangsa ini tidak boleh menyerah pada lingkaran setan kekuasaan yang hanya melanggengkan kepentingan elit. Kita harus menuntut hadirnya kekuasaan yang sejati, kekuasaan yang bekerja untuk rakyat banyak, bukan rakyat yang bekerja untuk melanggengkan kekuasaan.
Hanya dengan menempatkan kembali kekuasaan pada hakikatnya sebagai amanah moral dan sosial, kita dapat keluar dari krisis kepercayaan politik. Hanya dengan mengembalikan kekuasaan kepada tujuannya yang luhur, bangsa ini akan mampu membangun masa depan yang lebih bermartabat. Sebab pada akhirnya, kekuasaan hanyalah sarana, bukan tujuan; ia adalah jalan menuju keadilan, bukan panggung untuk menumpuk kekayaan.