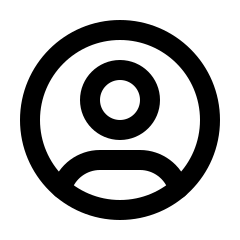Tafsir Kontemporer: Ekoteologis dalam QS. Al Baqarah Ayat 30
Oleh: Amtsal Ajhar/Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta
Krisis iklim global telah mengubah wajah Bumi. Hutan-hutan yang dulu lebat kini musnah akibat deforestasi, laut tercemar oleh sampah plastik dan polusi, udara semakin kotor akibat emisi karbon, dan cuaca yang tidak menentu mengancam ketahanan pangan dan kehidupan manusia. Dunia kini panik mencari solusi teknologis untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, Islam melalui Al-Qur'an sejatinya telah menggariskan prinsip-prinsip ekologis yang luhur yang dapat dijadikan landasan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Salah satu ayat kunci yang relevan dalam konteks ini adalah QS. Al-Baqarah: 30, yang berbunyi:
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...’" (QS. Al-Baqarah: 30).
Namun, pertanyaannya adalah, apa arti “khalifah” dalam konteks bumi yang sedang terluka ini? Apakah peran kita sebagai khalifah itu hanya terbatas pada mengelola bumi secara fisik, ataukah ada nilai-nilai spiritual yang lebih dalam yang harus kita amalkan dalam menjaga bumi?
Tafsir Klasik: Khalifah sebagai Pengganti
Dalam khazanah tafsir klasik, konsep khalifah pertama kali muncul dalam QS al-Baqarah [2]: 30, ketika Allah berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Imam al-Ṭabarī (w. 310 H), dalam Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān, menafsirkan kata khalīfah sebagai makhluk yang menggantikan makhluk sebelumnya di bumi—baik dari golongan jin maupun makhluk lain yang sebelumnya telah membuat kerusakan. Menurut al-Ṭabarī, istilah ini menunjuk pada manusia yang diberi otoritas untuk mengatur bumi dengan hukum-hukum Allah, menggantikan makhluk-makhluk yang telah menyimpang dari perintah-Nya (al-Ṭabarī, 2001: Juz 1, hlm. 230–235).
Tafsir ini kemudian diperkuat oleh mufasir lain seperti al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān, yang menekankan aspek tugas manusia sebagai ʿāmil bi al-ʿadl (pelaksana keadilan), dan bahwa pengangkatan khalifah adalah bentuk tanggung jawab ilahiah, bukan semata kehormatan. Al-Rāzī (w. 606 H) dalam al-Tafsīr al-Kabīr juga menyoroti bahwa penggunaan kata khalīfah menyiratkan penunjukan langsung dari Allah yang melibatkan amanah besar, bukan hanya posisi politis atau simbol kekuasaan.
Namun, pendekatan para mufasir klasik ini, meski sarat dengan legitimasi normatif dan institusional, banyak terfokus pada aspek legalistik dan politis. Makna khalifah cenderung ditafsirkan dalam kerangka kepemimpinan sosial dan kekuasaan manusia atas bumi dan makhluk lainnya, sejalan dengan dominasi paradigma antropocentris dalam pemikiran Islam masa klasik. Bahkan Ibn Kathīr (w. 774 H), dalam Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm, menafsirkan ayat ini sebagai penunjukan Adam dan keturunannya untuk memerintah dan menetapkan hukum di bumi, namun tidak mengeksplorasi dimensi tanggung jawab ekologis yang inheren dalam amanah tersebut.
Tafsir semacam ini, meskipun kontekstual untuk zamannya, belum cukup menjawab kegentingan ekologis yang dihadapi dunia modern. Jika kekhalifahan hanya dimaknai sebagai kuasa dan dominasi, maka relasi manusia dengan alam cenderung bersifat eksploitatif. Padahal, dalam pengertian istikhlāf (penggantian/pewarisan) terdapat pula unsur tanggung jawab kolektif (mas'ūliyyah) terhadap bumi sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan hanya dimanfaatkan.
Karena itu, sebagian cendekiawan kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Seyyed Hossein Nasr mencoba merekonstruksi makna khalifah dalam paradigma etis dan kosmologis. Nasr, dalam Man and Nature, mengkritik pandangan modern yang menjadikan manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Ia mengusulkan pembacaan ulang terhadap teks-teks Islam agar manusia diposisikan sebagai penjaga sakralitas bumi, bukan hanya pengelola sumber daya (Nasr, 1990).
Dengan demikian, sekalipun tafsir klasik menyediakan fondasi penting dalam memahami konsep khalifah, perlu ada elaborasi dan reinterpretasi agar relevan dengan tantangan zaman, khususnya dalam krisis lingkungan yang kian memuncak. Tugas kekhalifahan bukan sekadar soal otoritas, melainkan tanggung jawab spiritual, ekologis, dan moral sebagai wakil Tuhan di bumi.
Tafsir Kontemporer: Khalifah sebagai Penjaga Ekologis
Di era modern, pemaknaan tentang manusia sebagai khalīfah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Jika tafsir klasik cenderung menekankan aspek otoritas dan kepemimpinan sosial, maka para mufasir dan cendekiawan kontemporer mulai menggarisbawahi dimensi tanggung jawab moral dan ekologis yang melekat pada konsep tersebut.
M. Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbah, menyatakan bahwa posisi manusia sebagai khalifah bukan sekadar kehormatan, tetapi membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar. Ia menekankan bahwa manusia ditunjuk untuk memakmurkan bumi dengan prinsip keadilan, bukan merusaknya, sesuai dengan QS al-Aʿrāf [7]: 56 yang mengingatkan: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (Quraish Shihab, 2000: Juz 1, hlm. 236). Bagi Shihab, tanggung jawab khalifah meliputi dimensi etika, spiritual, dan sosial yang terpadu bukan dominasi, melainkan partisipasi dalam menjaga keharmonisan ciptaan.
Dalam lanskap pemikiran filsafat Islam kontemporer, Sayyid Hossein Nasr menjadi tokoh kunci yang mengusung kritik mendalam terhadap relasi manusia modern dengan alam. Dalam bukunya Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man, Nasr menyebut krisis lingkungan sebagai refleksi dari krisis spiritualitas modern. Menurutnya, manusia telah kehilangan pandangan sakral terhadap kosmos. Alam tidak lagi dilihat sebagai ayat-ayat Tuhan (āyāt kauniyyah), melainkan sekadar objek eksploitasi teknologis dan ekonomi (Nasr, 1997). Konsep tawḥīd dalam pandangan Nasr semestinya mencakup keterikatan manusia dengan alam semesta sebagai manifestasi keesaan Tuhan, yang berarti pelanggaran ekologis sejatinya juga merupakan bentuk kekufuran kosmis.
Perspektif ini menggeser diskursus khalifah dari ranah teknokratis ke spiritual-teosentris. Solusi atas kerusakan ekologis tidak cukup dengan kebijakan lingkungan atau teknologi hijau semata, tetapi memerlukan taubah epistemologis: kembali melihat bumi sebagai amanah ilahiah, bukan properti bebas guna.
Pendekatan ini juga mulai tampak dalam tafsir institusional seperti yang dikembangkan oleh Muhammadiyah melalui Tafsir at-Tanwir. Dalam penelitian Muhammad Faiz Isra (2022), dijelaskan bahwa at-Tanwir menafsirkan QS al-Baqarah [2]: 30–39 dengan pendekatan tematik yang menggabungkan nilai spiritual Islam dan kepedulian ekologis. Dalam tafsir ini, manusia sebagai khalifah dipahami sebagai subjek yang memiliki akal, hati nurani, dan kebebasan moral untuk menjaga keberlanjutan bumi. Ayat-ayat seperti QS al-Rūm [30]: 41, yang menyatakan “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia”, menjadi dasar etis dalam membangun kesadaran ekoteologis dalam gerakan dakwah dan pendidikan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan ḥikmah dalam Al-Qur’an, yang menandai bentuk kebijaksanaan spiritual yang integral. Ḥikmah bukan sekadar pengetahuan rasional, tetapi kecerdasan etis dan kosmis yang menyadari keterhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam konteks ini, menjadi khalifah berarti menghayati kembali peran manusia sebagai penjaga keseimbangan (mīzān) semesta.
Dengan demikian, tafsir kontemporer menghadirkan transformasi makna khalifah: dari simbol kekuasaan menjadi etos pengabdian; dari dominasi menjadi relasi. Konsep kekhalifahan harus dibaca ulang sebagai misi spiritual untuk menjaga kesucian ciptaan, bukan mengeksploitasinya. Maka, peran khalifah pada masa kini harus dilihat sebagai panggilan etik untuk merawat bumi dalam kerangka tauhid ekologis.
Ḥikmah: Kerangka Filsafat Ekologis dari Al-Qur’an
Dalam menghadapi krisis ekologis global, kita membutuhkan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga kerangka etis dan spiritual yang mampu membentuk kesadaran ekologis yang mendalam. Dalam konteks ini, konsep ḥikmah (kebijaksanaan) dalam Al-Qur’an dapat berfungsi sebagai fondasi filsafat ekologis Islam. Tafsir al-Mīzān karya ‘Allāmah M.H. Ṭabāṭabā’ī menempatkan ḥikmah dalam posisi sentral, tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai integrasi antara pemahaman realitas, nilai moral, dan hubungan spiritual dengan Allah. Dalam pandangannya, ḥikmah memiliki tiga dimensi utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang semuanya membentuk fondasi etis bagi peran manusia sebagai khalifah (Ahmad Nurrohim, 2019).
1. Ḥikmah sebagai Nikmat Ilahi (Dimensi Ontologis)
Pada level ontologis, ḥikmah dipahami sebagai nikmat Ilahi yang diberikan kepada manusia pilihan. QS al-Baqarah [2]: 231 dan Ali-‘Imrān [3]: 164 menegaskan bahwa ḥikmah adalah karunia yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya, bukan hasil murni dari usaha rasional manusia. Maka, relasi antara manusia dan ḥikmah adalah relasi spiritual: semakin dekat seorang hamba dengan Allah, semakin terbuka baginya hikmah-hikmah kehidupan.
Pemahaman ini memberikan konsekuensi penting dalam konteks ekologis: tugas kekhalifahan bukanlah proyek administratif, ekonomis, atau teknokratis belaka, melainkan sebuah tugas spiritual. Menjaga bumi bukan sekadar upaya pelestarian lingkungan, melainkan wujud syukur dan pengabdian atas nikmat hikmah yang diberikan. Jika alam adalah manifestasi dari ciptaan Ilahi, maka merusaknya adalah bentuk pengingkaran atas nikmat dan amanah Tuhan.
2. Ḥikmah sebagai Pemahaman yang Mendalam (Dimensi Epistemologis)
Pada dimensi epistemologis, ḥikmah adalah kapasitas memahami kebenaran secara komprehensif. QS al-Baqarah [2]: 269 menyatakan bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan barangsiapa yang diberikan hikmah maka sungguh ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Dalam konteks ini, hikmah mencakup kemampuan menyelaraskan pengetahuan rasional dengan kedalaman batiniah menggabungkan ilmu ilmiah modern dengan kesadaran spiritual.
Krisis iklim hari ini menuntut bukan hanya pemahaman saintifik, tetapi juga pengendalian ego manusia sebagai subjek epistemik. Ḥikmah berarti tidak hanya mengetahui bahwa emisi karbon menyebabkan pemanasan global, tetapi juga memiliki kematangan spiritual untuk menundukkan keinginan rakus, mengubah gaya hidup, dan menempatkan diri sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa mutlak atasnya. Maka, epistemologi Islam melalui konsep ḥikmah menjadi jembatan antara sains dan iman, antara data dan dzikir.
3. Ḥikmah sebagai Ajaran Etika Kehidupan (Dimensi Aksiologis)
Dimensi ketiga dari hikmah adalah aksiologis, yaitu nilai moral yang mengarahkan tindakan manusia. QS Luqmān [31]: 12 menyebut bahwa Allah telah memberi Luqmān al-ḥikmah, dan sebagai manifestasinya, ia bersyukur kepada Allah dan memberi nasihat yang penuh kebijaksanaan dan kesantunan. Hikmah dalam dimensi ini melahirkan tindakan yang adil, moderat, dan penuh welas asih terhadap seluruh makhluk.
Seorang khalifah sejati, dalam kerangka ini, bukanlah yang menguasai bumi dengan kerakusan, melainkan yang mampu menahan diri, bersikap adil terhadap manusia dan non-manusia, serta hidup dalam harmoni dengan ciptaan. Ekologi Islam yang berbasis pada ḥikmah mendorong praktik hidup berkelanjutan: mengurangi limbah, memilih konsumsi etis, dan menjaga keseimbangan (mīzān) yang telah Allah tetapkan di alam (QS al-Rahmān [55]: 7–9).
Dengan demikian, ḥikmah menjadi kerangka filsafat ekologis Qur’ani yang berlapis-lapis: dari pemahaman metafisik tentang kedudukan manusia di hadapan Tuhan, ke epistemologi yang menjembatani sains dan spiritualitas, hingga aksiologi yang melandasi tindakan etis terhadap bumi. Dalam dunia yang terus bergerak menuju kehancuran ekologis akibat kerakusan dan alienasi spiritual, konsep ḥikmah menawarkan jalan pulang: bahwa menjadi khalifah sejati bukanlah tentang mengatur bumi, melainkan menjaganya dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta.
QS. Ar-Rūm: 41 sebagai Peringatan Ekologis
Salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam diskursus ekoteologi Islam adalah QS Ar-Rūm [30]: 41:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Ayat ini bukan sekadar narasi, melainkan peringatan profetik tentang hubungan kausal antara tindakan manusia dan kehancuran ekologis. Kerusakan (fasād) yang disebut mencakup segala bentuk gangguan terhadap tatanan keseimbangan bumi (mīzān)—baik berupa pencemaran lingkungan, deforestasi, eksploitasi laut, krisis air, maupun perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan.
Al-Qur’an dengan tegas menyebut pelaku utama kerusakan ini adalah manusia—bukan makhluk gaib, bukan takdir alam. Frasa “bimā kasabat aydī an-nās” (disebabkan oleh ulah tangan manusia) merupakan penegasan tanggung jawab moral dan historis. Ayat ini juga menegaskan bahwa alam memiliki kapasitas respon moral: ketika batas-batas dilanggar, alam memberi peringatan melalui bencana, kelangkaan, dan ketidakseimbangan.
Kerusakan ekologis dalam perspektif Qur’ani bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga indikator spiritual: manusia telah lupa posisinya sebagai hamba dan penjaga, lalu berperilaku seolah-olah sebagai pemilik dan penguasa mutlak bumi. Oleh karena itu, QS Ar-Rūm: 41 adalah seruan untuk bertobat ekologis kembali ke jalan keseimbangan, tawāzun, dan ketaatan kosmik.
Menjadi Khalifah Hari Ini: Dari Tafsir ke Aksi
Pemaknaan manusia sebagai khalifah dalam Al-Qur'an seringkali dihubungkan dengan kehormatan, tetapi dalam konteks kekinian, ia harus dilihat lebih sebagai sebuah panggilan untuk bertanggung jawab. Ketika Al-Qur’an menyebutkan manusia sebagai khalifah, itu bukan berarti manusia diberi kekuasaan mutlak atas bumi, melainkan amanah untuk menjaga dan merawat segala ciptaan-Nya. Status ini bukan hanya tentang dominasi atau kepemilikan, tetapi tentang peran sebagai penjaga keseimbangan dan harmoni alam yang telah Allah ciptakan.
Hari ini, dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin meluas, tugas menjadi khalifah berarti lebih dari sekadar kata-kata indah dalam tafsir. Ia menuntut penerjemahan dalam aksi konkret yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Kita bukan hanya ditantang untuk menjaga alam, tetapi juga untuk memahami kedalaman tanggung jawab moral yang menyertai status tersebut. Menjadi khalifah berarti menanggapi krisis iklim dengan kesadaran penuh bahwa bumi adalah amanah yang harus dipelihara, bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
Dalam praktiknya, menjadi khalifah berarti menjalani hidup yang lebih ramah lingkungan. Ini bukan sekadar tentang mengurangi konsumsi energi atau menggunakan teknologi hijau, tetapi juga tentang bagaimana kita mengubah pola pikir kita terhadap alam. Hidup dengan cara yang lebih hemat energi, misalnya, bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang kesadaran bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Setiap kilowatt yang kita hemat, setiap langkah kecil yang mengurangi jejak karbon kita, adalah wujud pengabdian kita kepada amanah Tuhan. Itu adalah cara kita menjaga bumi yang diberikan kepada kita, agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
Begitu pula dengan pengurangan konsumsi berlebihan dan pengelolaan limbah pribadi. Dalam dunia yang sering kali didorong oleh konsumerisme dan gaya hidup serba cepat, menjadi khalifah berarti memilih untuk tidak terjebak dalam budaya konsumtif yang merusak. Mengurangi limbah, memilih produk yang lebih ramah lingkungan, dan berusaha untuk tidak membuang-buang sumber daya adalah langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua merupakan cara untuk merawat bumi, sebuah bentuk tanggung jawab moral yang diajarkan oleh Al-Qur’an.
Selain itu, mendukung energi terbarukan dan daur ulang juga menjadi bagian dari tindakan konkret seorang khalifah. Ini bukan hanya tugas pemerintah atau korporasi besar, tetapi setiap individu bisa berperan. Menyadari bahwa energi yang kita gunakan mempengaruhi kelangsungan hidup bumi, mendukung gerakan energi terbarukan, atau terlibat dalam program daur ulang adalah langkah-langkah nyata yang bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dalam konteks ini, kita diajak untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana setiap pilihan kita mempengaruhi keberlanjutan alam.
Pendidikan ekologi juga menjadi aspek yang tak terpisahkan dari peran kita sebagai khalifah. Mengintegrasikan pendidikan ekologis dalam keluarga, sekolah, dan masjid adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Keluarga sebagai lembaga pertama dalam pembentukan karakter, sekolah sebagai lembaga pendidikan, dan masjid sebagai pusat spiritual harus menjadi ruang yang menyuarakan pentingnya menjaga bumi sebagai bagian dari tugas kekhalifahan kita. Ini bukan hanya soal pengetahuan teknis tentang lingkungan, tetapi juga soal pemahaman spiritual tentang bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam.
Secara keseluruhan, menjadi khalifah dalam dunia yang dilanda krisis ekologis ini bukanlah soal membanggakan status sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi, tetapi tentang menjalankan amanah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ini adalah tentang merawat ciptaan, bukan mengeksploitasinya. Dan ketika kita mampu mengubah cara hidup kita menjadi lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan penuh kasih sayang terhadap semua ciptaan, maka kita telah memenuhi tugas kita sebagai khalifah, yang bukan hanya menguasai bumi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup di dalamnya.