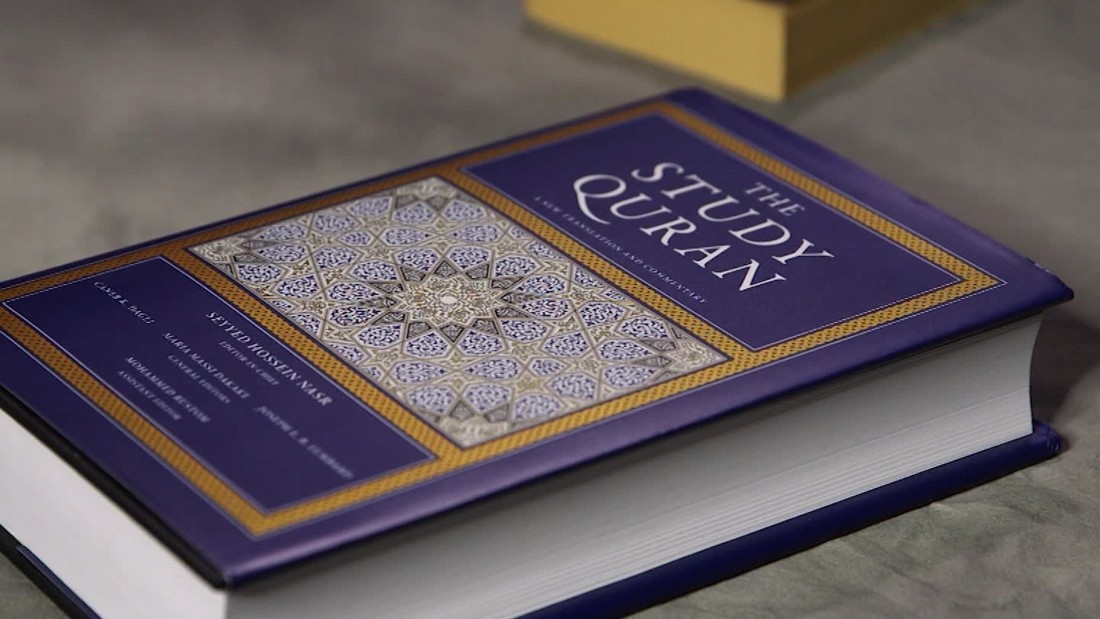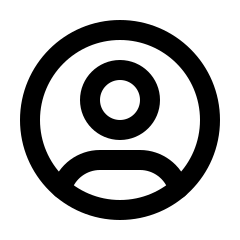Membangun Indonesia dengan Gagasan dan Akhlak
Oleh: Agusliadi Massere
Indonesia sebagai negara-bangsa terus bergerak, beradaptasi, berselancar menghadapi dinamika dan perubahan, dan saya melihat serta mengamatinya mengikuti logika dan prinsip speed is power (kecepatan adalah kekuatan dan/atau kekuasaan). Ini bisa terkonfirmasi, mulai dari dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat sampai pada perumusan dan penetapan suatu kebijakan yang berkaitan nasib rakyat, dilakukan secara terburu-buru tanpa mendengar dan memedulikan aspirasi dan pandangan publik atau masyarakat.
Dalam kontestasi dan dinamika politik menuju Pemilu 2024, dan Pilkada 2024 (yang tahapannya belum dimulai) pun, saya dan mungkin sahabat pembaca pun merasakan, kita dirasuki ekstasi kecepatan tersebut. Terlalu terburu-buru mendorong calon, terlalu terburu-buru melakukan sosialiasi rasa kampanye di luar jadwal. Bahkan persoalan makan mie instan pun yang prosesnya sudah dirancang sedemikian praktis dan cepat, masih saja diupayakan lebih cepat. Yang parah, ketika mendapatkan ijazah pun dengan proses karbitan. Ketika Rocky Gerung menegaskan “ijazah hanya tanda bahwa seseorang pernah sekolah, bukan tanda bahwa pernah berpikir”, bagi saya jika prosesnya karbitan, itu pun tidak layak menjadi tanda.
Ada yang seringkali masih menjadi “jalan sunyi”—untuk tidak mengatakan terlupakan—dalam membangun Indonesia adalah urgensi dan signifikansi gagasan dan akhlak sebagai modal utama dan ideal. Padahal, menurut Prof. Haedar Nashir dalam bukunya Indonesia Ideologi dan Martabat Pemimpin Bangsa, menegaskan “Fitrah manusia itu adalah sebagai makhluk theos dan logos” (2022: 152). Yang dimaksud makhluk theos dan logos oleh Prof. Haedar adalah “Insan yang bertuhan Esa sekaligus berakal pikiran autentik”.
Saya, meskipun dalam proses derivatif, terlalu jauh ke bawah atau keluar dalam proses pemaknaan kembali “theos” dan “logos” di atas namun secara substansial bisa dimaknai bahwa kristalisasi keduanya dalam konteks kehidupan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah gagasan dan akhlak. Makhluk logos tentunya memiliki gagasan yang cemerlang, produktif, dan konstruktif. Makhluk theos sudah pasti memiliki akhlak sebagai perasan dan hasil integratif dari keimanan dan keislaman.
Saya,—dan seharusnya kita semua—dalam konteks Pemilu 2024, dan Pilkada 2024 mendatang, ketika diajak untuk mendukung dan/atau memilih salah satu kandidat, meskipun membawa amplop yang isinya tebal, membawa embel-embel kebesaran orang tua di belakang namanya, apatah lagi hanya personal branding karbitan, yang tiba-tiba dilekatkan sendiri melengkapi narasi posternya, tidak akan pernah tergoda untuk mendukung dan memilihnya. Saya pribadi, dan sebenarnya ingin mengajak para sahabat pembaca, untuk menjadikan “gagasan” dan “akhlak” sebagai dua hal tak terpisahkan dalam menentukan pilihan terhadap sosok pemimpin dan wakil rakyat. Urusan daerah, bangsa, dan negara ini, bukanlah urusan sepele, sehingga harus memilih sosok yang tepat.
Saya menyadari bahwa ada juga yang kriteria pilihannya adalah sosok yang populis (tidak elitis, tetapi merakyat). Ada yang mendukung dan memilih sosok yang muda, meskipun dalam pandangan saya “umur muda” tidak selamanya ideal bahkan terkadang anomali dan paradoks. Hari ini, dan bukanlah fenomena yang bisa ditutup-tutupi masih banyak karena uang, dan kekuasaan aktor di panggung belakang.
Membangun Indonesia idealnya dan ini adalah modal terbaik dan utama dengan gagasan dan akhlak. Indonesia sebagai negara-bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, dan termasuk dalam mencapai tujuan pembentukan negaranya, maka harus dikendalikan oleh pemimpin dan para wakil rakyat yang memiliki gagasan cemerlang, positif, produktif, dan konstruktif sesuai dengan nilai-nilai yang melekat dalam nilai luhur bangsa, dan paradigma Pancasila. Namun, tidak cukup dengan gagasan, harus dibarengi dengan akhlak. Spirit yang mengantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan pun ternyata jika kita mencermati preseden historis dari sikap dan tindakan pendiri bangsa adalah gagasan dan akhlak.
Gagasan menjadi sangat penting. Jika kita mendalami dan merenungkannya secara mendalam segala sesuatu yang kita saksikan, amati, dan rasakan hari ini sebenarnya bermula dari sesuatu yang dimaknai sebagai “gagasan”. Bahkan keberadaan manusia pun bermula dari “gagasan” Allah, ketika Allah menegaskan kepada malaikat bahwa diriNya hendak menciptakan manusia atau khalifah di muka bumi.
Kesuksesan dan pencapaian seseorang dalam teori manajemen—jika kita mau mendalami dan meresapinya—diawali dengan gagasan. Aksioma “Gagal dalam merencanakan, sama saja merencanakan kegagalan” itu mengandung penegasan pesan pentingnya gagasan. Gagasan, jika saya mengikuti dan/atau terinspirasi dari pandangan F. Budi Hardiman dalam bukunya Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida (2015), bukan sekadar pengetahuan dan pemahaman dangkal, tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh sseseorang terhadap suatu objek dan/atau target tertentu yang melewati proses “memahami” yang sangat mendalam. Memahami sebagaimana dikutip oleh Hardiman, yang dalam istilah Jerman disebut Verstehen.
Saya senantiasa mengingatnya dengan baik, dan sangat setuju dengan pandangan Prof. Hilman Latief—pada saat itu belum menyandang gelar guru besar—dalam buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat (2015: 96-118). Prof. Hilman menegaskan “Gagasanlah yang menjadi realitas sebenarnya bila kita menggunakan cara berpikir yang bersifat ‘neo-platonistik’. Sebuah organisasi hanya dapat menjadi besar bila diiringi oleh etos dan dijiwai oleh gagasan besar”. Sebelum lanjut saya ingin menegaskan bahwa ketika saya menggunkan terma “setuju” yang ditautkan terhadap sosok yang maqam keilmuannya jauh di atas saya, maka ada sejenis beban psikologis dalam diri ini, karena seakan-akan saya memberikan penilaian.
Menyelami lebih dalam tulisan Prof. Hilman, saya menemukan satu inspirasi dan insight bahwa sebuah organisasi apalagi sebesar Indonesia, jika tidak lagi dijiwai dengan gagasan, maka kemandekan akan berpotensi menjadi keniscayaan dalam realitas empiriknya. Bahkan, berdasarkan pembacaan saya dari perspektif era disrupsi Rhenald Kasali, bisa dipastikan jika kita tidak memiliki gagasan maka akan tergilas oleh perubahan dan gerak cepat zaman.
Saya selaku sosok yang lahir dari rahim ideologis Muhammadiyah, tidak pernah menelan mentah-mentah pandangan bahwa KH. Ahmad Dahlan itu adalah “man of action”, lalu saya—sebagaimana banyak yang bersikap demikian—serta merta menyimpulkan secara membabi-buta bahwa tidak penting literasi, tidak penting gagasan, ilmu, dan teori, tetapi yang terpenting adalah aksi. Yang perlu kita pahami, bahwa KH. Ahmad Dahlan sarat dengan gagasan cemerlang, produktif, dan konstruktif. Selain itu, atribusi “man of action” (manusia aksi) yang dilekatkan pada diri Kiai Dahlan itu adalah—dalam pandangan saya—perasan atau kristalisasi dari hasil integrasi gagasan dan akhlak. Saya menyimpulkan demikian karena terinspirasi dari pemahaman terhadap tiga pilar Islam di mana akhlak pun dalam perspektif dan kajian lain dimaknai dan disejakarkan pula dengan apa yang dimaksud dengan “ihsan”.
Membaca buku Rekayasa Sosial (Cetakan pertama, edisi revisi kedua, 2021) karya Dr. Jalaluddin Rakhmat, yang akrab disapa Kang Jalal, saya menemukan urgensi dan signifikansi bahkan implikasi besar dari gagasan sebagai penentu perubahan sosial dan/atau penentu sejarah. Meskipun Kang Jalal lebih sering menyebutnya ideas (gagasan-gagasan).
Tidak cukup dengan gagasan, diperlukan pula akhlak. Akhlak akan mengarahkan gagasan yang cemerlang pada sesuatu yang konstruktif dalam bingkai nilai yang sesuai dengan nilai luhur bangsa, peta sosiologis bangsa, dan paradigma Pancasila. Paradigma Pancasila—meskipun dalam tulisan ini saya tidak uraikan panjang lebar—namun dalam pandangan Aliansi-Kebangsaan (beberapa organisasi yang berhimpun di dalamnya dan memikirkan solusi memperadabkan bangsa) menjadi modal utama dan strategis dalam membangun Indonesia dan memperadabkan bangsa.
Dr. Asep Zaenal Ausop, M.Ag menegaskan terkait tiga pilar Islam atau kerangka ajaran Islam secara komprehensif, garis besarnya yaitu akidah, syariah, dan Ihsan. Atau bisa pula disebut dengan iman, Islam, dan akhlak. Tetapi, saya lebih sering membaca dan lebih tepat dalam pandangan saya, jika yang disebut adalah iman, dan islam, maka yang ketiga berikutnya adalah ihsan, tidak menyebut akhlak. Meskipun sesungguhnya akhlak dan ihsan, pada substansinya sama.
Akhlak jika dikontekstualisasikan dalam teori pengembangan diri bisa disejajarkan dari apa yang dimaknai dengan karakter. Meskipun karakter menjadi istilah umum yang terkadang dipandang hanya sebagai akumulasi proses yang diawali dari pikiran dan perasaan, tindakan, dan kebiasaan akhirnya menuju menjadi sebuah karakter. Tetapi dalam pandangan saya karakter yang disifati dengan akhlak adalah proses dan akumulasi dari dorongan atau bisikan suara hati suci, dan percikan pikiran cemerlang yang diikuti dengan perilaku (behavior). Setelah karakter, satu langkah lagi menjadi nasib-hidup.
Akhlak, jika mengikuti pandangan dan kajian-kajian yang membahas tentang ihsan, bukan cuma kemampuan menentukan benar-salah lalu memilih yang benar, baik-buruk lalu memilih yang baik, dan patut-tidak patut lalu memilih yang patut. Akhlak termasuk pula adalah dorongan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam setiap episode kehidupannya, bukan karena mengharapkan sesuatu dalam perspektif pragmatis dan materialistis, tetapi berangkat dari kesadaran mandat kosmis kekhalifahannya, sebagai wujud ibadah kepada Allah, sebagai kesadaran anak negeri yang harus mempersembahkan madu bagi bangsa dan negaranya, dan sebagai kristalisasi dari amanah yang melewati sumpah dan janji jabatan.
Akhlak pun akan mengarahkan atau menjadi driver sikap dan perilaku bahwa kinerja bukan semata-mata bahan evaluasi periodik, semesteran atau tahunan. Semuanya dilakukan demi dorongan valensi diri, spirit kerja malaikat, untuk memenuhi tujuan dan cita-cita besar yang telah dirumuskan oleh para pendahulu yang mengerti dan memahami arti beratnya perjuangan. Akhlak yang menjadi valensi, selain berfungsi sebagai driver, termasuk pula menjadi energy dahsyat yang memberikan amunisi untuk terus membumikan gagasan.
Akhlak pun adalah integrasi antara relasi vertikal dengan Allah, relasi horizontal dengan manusia dan termasuk secara umum memantik kesadaran ekologis secara universal. Ternyata di ujung pena atas tarian lentik jemari ini, saya mendapatkan percikan inspirasi penegasan bahwa gagasan dan akhlak harus dipandang dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebagai modal untuk mencapai kemajuan suatu bangsa dan negara. Dan Indonesia, untuk kedua urusan ini, masih harus memberikan porsi perhatian yang besar atau masih menjadi PR besar dan utama. Pintu utamanya melalui Pemilu dan Pilkada 2024 kita, kita awali dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki gagasan sekaligus akhlak.
Agusliadi Massere, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PD. Muhammadiyah Bantaeng