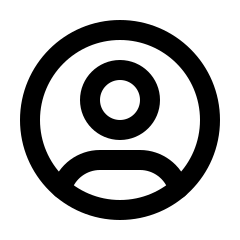Membayar Hutang Ayah, Menjaga Kehormatan Keluarga
Oleh: Babay Parid Wazdi, Kader Muhammadiyah & Aktifis IPM 1988-1991
Aku menulis kisah ini di sudut sunyi, di balik jeruji Rutan Salemba, tempat di mana waktu berjalan dengan penuh ketidakpastian. Di sinilah aku belajar bahwa kesenyapan kadang lebih lantang daripada keramaian. Tuduhan korupsi yang menimpaku terasa asing, tak pernah sejalan dengan akhlak dan laku hidup kini dan juga yang diajarkan orang tuaku. Namun tulisan ini bukan keluh kesah. Ini adalah doa tawasul kecil yang kupanjatkan sambil mengetuk pintu langit, memohon agar setiap amal bakti yang pernah kupersembahkan kepada ayah dan ibu menjadi perantara bagi kebebasanku.
Aku lahir dari seorang ibu yang berprofesi guru SD, dan ayah seorang petani sekaligus pedagang beras. Sewaktu aku SD, hidup kami sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana menurut ukuran hari ini. Rumah kami tak sampai 30 meter persegi, berdinding bilik bambu, berlantaikan bata merah, tak ber-toilet, tak ber-listrik, tanpa radio, tanpa televisi, tanpa hiruk-pikuk modernitas. Namun justru di rumah kecil itulah aku pertama kali mengenal kemewahan terbesar dalam hidupku: cita-cita.
Di atas ranjang tua yang berderit setiap kali kami bergerak, ayah menenun mimpiku dengan kisah-kisah perjuangan. Di bawah temaram lampu teplok yang bergoyang ditiup angin malam, beliau mendongengkan Sukarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, Ahmad Dahlan, Hamka, tokoh-tokoh besar yang hidup kembali dalam tutur ayahku. Ia mengenalkanku pada Al-Ghazali, Iqbal, Ibn Khaldun, Hasan Al-Banna, bahkan pada kisah Embah kami K.H. Nawawi yang wafat ditembak usai memimpin salat Magrib. Nama-nama itu, yang mungkin terlalu besar untuk dipikul anak kecil, justru tumbuh menjadi akar yang menancap dalam sanubariku: bahwa hidup harus diabdikan untuk bangsa dan kebenaran.
Ayah dan ibu selalu melihat masa depan dengan mata yang terang, meski hidup sehari-hari diselimuti keterbatasan. Ketika aku lulus SMP, mereka mengirimku ke Yogyakarta, untuk bersekolah di salah satu SMA Muhammadiyah, menitipkan impian mereka kepadaku.
Namun sebuah sore yang biasa berubah menjadi batas dari segala yang kukenal. Itulah hari terakhir aku memiliki seorang ayah.
Malam itu ayah membantu mendorong mobil mogok, bercengkerama dengan anak-anak muda di warung kecil, lalu pulang dan tidur sendirian. Pagi hingga siang, berkali-kali temannya mengetuk rumah, tapi ayah tak lagi membuka pintu. Jendela dibongkar, dan dunia kami runtuh dalam sekejap , ayah wafat begitu sunyi, tanpa sempat berpamit.
Telegram dari Karawang menyusul kami yang sedang berada di Solo. Paman merahasiakan berita itu, tetapi kegelisahan ibu tak mampu disembunyikan. Dalam perjalanan pulang, aku merasa dunia berjalan terlalu cepat, sementara hatiku masih tertinggal di masa di mana ayah duduk di samping ranjangku, bercerita tentang pahlawan dan perjuangan.
Setelah kepergian ayah, ibu menjadi single parent yang harus memikul segalanya: ekonomi, pendidikan anak, dan hutang-hutang ayah dari usaha kecilnya. Tahun 1988–1997 menjadi tahun paling gelap; ibu sakit parah, terhimpit tekanan hidup, sementara aku masih seorang anak SMA yang seharusnya menikmati masa remaja. Namun aku tak mengenal kata mengeluh. Pulang liburan berarti bekerja, menagih piutang demi piutang, untuk mencicil hutang ke Kokoh Lamaran, BRI Cikampek, dan siapa pun yang pernah membantu usaha ayah.
Pesan ibu hanya satu: “Kita mungkin tak mampu melunasi segera, tapi kita harus menunjukkan kehormatan dengan membayar pokoknya sedikit demi sedikit.”
Ketika ibu terbaring di RSUD Karawang, pikiranku terpecah antara tugas sekolah, kecemasan kehilangan ibu, dan kewajiban membayar hutang keluarga. Namun Allah Swt tak pernah tidur. Aku mendapat sedikit rezeki, THR dari Bank Dagang Negara (BDN), panen padi, hingga honor kecil dari mengisi pengajian dan khotbah jumat. Ketika pertama kali diberi honor oleh panitia, aku bahkan meminta izin kepada Pak Haryoko Kadiv SDM BDN, karena hal itu tidak pernah ada sewaktu di Yogyakarta. Aku takut menerima sesuatu yang bukan hakku. Tapi beliau berkata, “Ambil, kamu sedang berjuang.”
Dan aku pun mengambilnya, bukan untuk diriku, melainkan untuk menjaga nama ayahku, membayar pinjaman ke BRI Cikampek.
Perlahan-lahan, seiring keringat, doa, dan kesabaran yang panjang, pada tahun 1999 seluruh hutang pokok itu akhirnya lunas. Sebelas tahun lamanya kami memikul beban itu sejak ayah wafat. BRI dan Kokoh Lamaran menghapus bunganya; kami menyelesaikan sisanya dengan terhormat. Hari itu aku menangis, bukan karena jumlahnya, tetapi karena aku merasa menepati janji hidupku: menjaga nama ayah dan menenangkan hati ibu.
Kini, dari balik tembok besi ini, aku kembali mengingat perjalanan itu. Bukan untuk membanggakan diri, bukan pula untuk membela diri. Aku menuliskannya sebagai sebuah tawasul, sebagai saksi bahwa aku pernah berjuang sekuat yang aku bisa untuk menjaga kehormatan keluargaku.
Ya Allah, Engkau tahu betapa lemahnya aku. Engkau tahu bahwa aku telah berusaha membayar hutang dunia, namun yang lebih ingin kulunasi adalah hutang cintaku kepada ayah dan ibu. Jika Engkau berkenan, jadikan cerita ini saksi di hadapan-Mu bahwa aku pernah berjuang dengan jujur.
Ampunilah ayah dan ibuku. Sehatkan dan rahmatilah aku dan keluargaku. Dan bukakanlah jalan kebebasan bagi hamba-Mu yang lemah ini.
(Rutan Salemba, 27 September 2025)
Penulis adalah Direksi Bank DKI (2018 sd 2022) & Dirut Bank Sumut (2023 sd 2025). Esay ini di ketik ulang dari tulisan tangan ayahku yang berada di rutan Salemba & Esay ini bagian dari Manifesto Tawasul Sang Burung Pipit (The Bright Way to Freedom and Faith), salam Ahmad Raihan Hakim (Alumni SMA Muh 3 Jkt 2018).