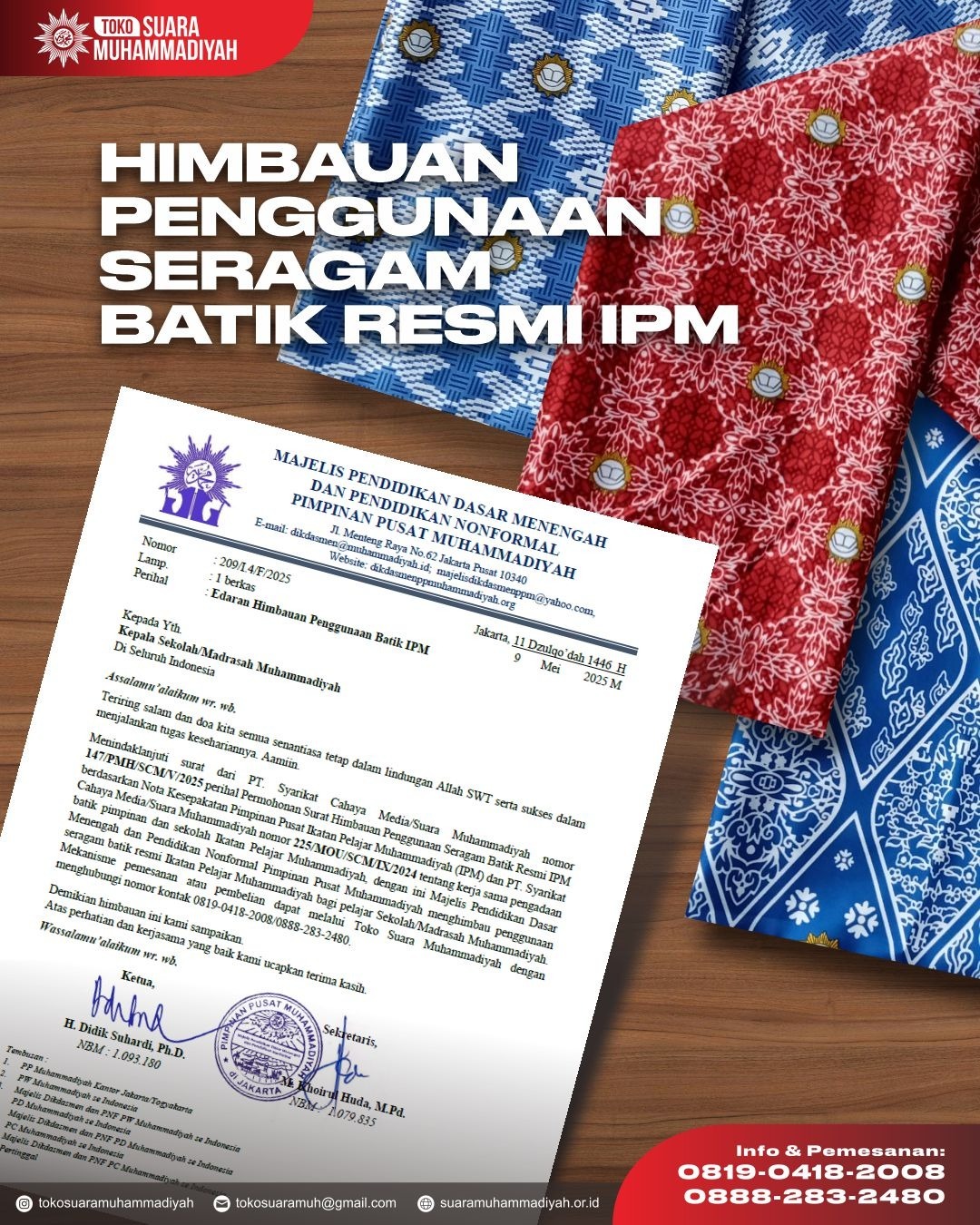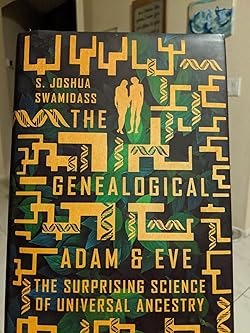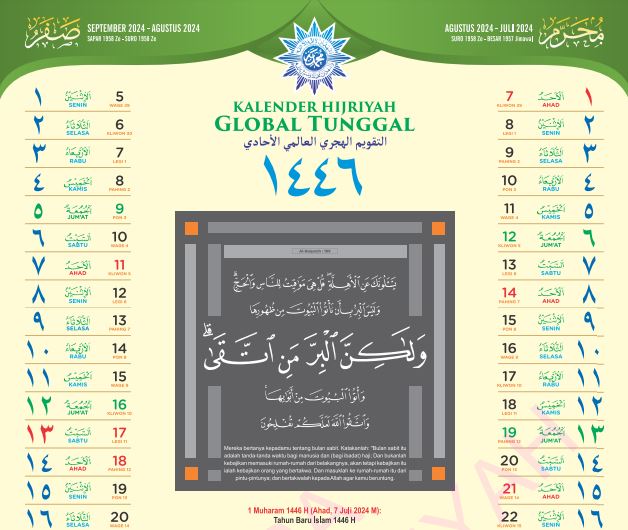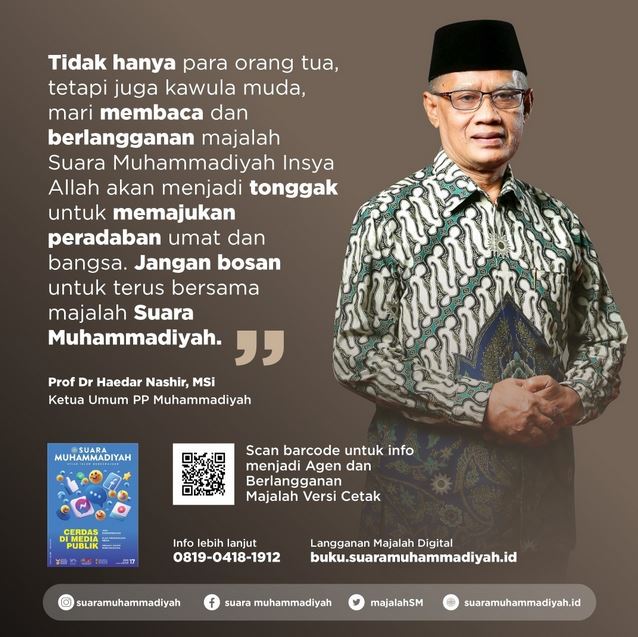Menilai Agama dengan Rasionalitas dan Etika Sosial
Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi Tinggal di Yogyakarta
Agama adalah pedoman hidup, sumber nilai, dan arah moral bagi manusia. Ia hadir bukan sekadar untuk disembah-sembah dalam ritual formal, tetapi untuk dihidupkan dalam perilaku dan relasi sosial. Namun, dalam kenyataan hari ini, wajah keberagamaan sering tampak paradoksal.
Di satu sisi, agama makin sering tampil di ruang publik melalui simbol, slogan, dan jargon keislaman; di sisi lain, nilai-nilai moral dan etika yang menjadi ruh agama justru sering diabaikan. Banyak orang mengatasnamakan agama, tetapi gagal menghadirkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam praktik hidupnya.
Menilai agama dengan rasionalitas dan etika sosial bukan berarti menundukkan agama pada kehendak akal manusia. Rasionalitas di sini bukan tandingan wahyu, melainkan instrumen untuk memahami, menafsirkan, dan mengamalkan pesan ilahi secara lebih arif. Agama mengajarkan kebenaran, dan akal sehat adalah alat untuk menangkap dan mengujinya dalam kehidupan nyata.
Dalam Islam, akal adalah nikmat besar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu membaca tanda-tanda Tuhan dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, beragama secara rasional bukan berarti mengurangi keimanan, justru memperkuatnya agar tidak mudah diseret fanatisme dan kebutaan rohani.
Fanatisme dan Hilangnya Nalar Kritis
Rasionalitas menjadi penting karena banyak orang beragama yang kehilangan daya kritisnya. Mereka lebih percaya pada otoritas kelompok atau tokoh tertentu ketimbang pada kebenaran yang dapat diuji secara etis dan rasional. Tidak jarang, seseorang menutup mata terhadap kesalahan karena dilakukan oleh pihak yang dianggap “satu barisan”. Ia membela tokohnya dengan dalih loyalitas, meski tahu ada pelanggaran moral di dalamnya.
Inilah gejala fanatisme yang kian mengkhawatirkan dalam kehidupan keagamaan kita. Kebenaran bukan lagi soal nilai, tetapi soal siapa yang mengucapkannya. Akibatnya, agama menjadi sempit, terkurung dalam kepentingan kelompok, dan kehilangan jiwanya sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Fanatisme sempit seperti itu lahir dari cara beragama yang emosional, bukan rasional. Agama dijadikan identitas politik dan alat pembeda, bukan panduan moral yang menyatukan. Ketika seseorang lebih mencintai kelompoknya daripada kebenaran, maka agama berubah menjadi ideologi eksklusif yang menolak dialog dan menghalalkan kebencian. Padahal, agama sejatinya mengajarkan keseimbangan antara iman, akal, dan akhlak. Iman memberi arah; akal memberi pencerahan; akhlak memberi makna. Ketiganya saling melengkapi. Jika salah satunya absen, agama menjadi timpang: kaku dalam dogma, tetapi lemah dalam laku.
Etika sosial menjadi ukuran penting dalam menilai keberagamaan seseorang. Ukuran keimanan tidak berhenti pada seberapa sering seseorang beribadah atau seberapa tebal simbol keagamaannya, tetapi sejauh mana nilai-nilai agama itu menjelma dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
Agama yang sejati bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Karena itu, kesalehan pribadi tidak boleh berhenti di ruang ibadah; ia harus berbuah menjadi kesalehan sosial yang menggerakkan perubahan dan kebaikan di tengah masyarakat.
Simbolisme Agama dan Krisis Keteladanan
Namun realitas hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Simbol-simbol agama makin semarak, tetapi praktik moral makin pudar. Di ruang politik dan sosial, banyak tokoh agama tampil dengan jubah keislaman, tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan agama.
Kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran moral justru dilakukan oleh mereka yang kerap tampil di mimbar-mimbar keagamaan. Fenomena ini menimbulkan kelelahan moral di tengah masyarakat. Orang bertanya-tanya: di mana letak nilai agama jika yang mengajarkannya justru tidak meneladaninya?
Ketika simbol lebih diagungkan daripada substansi, agama tereduksi menjadi alat pencitraan. Ia dijadikan hiasan di ruang publik, tetapi tak lagi menjadi sumber etika dalam kehidupan nyata. Orang sibuk memamerkan kesalehan lahiriah, tetapi lalai memelihara kesalehan batiniah. Padahal, esensi beragama bukan pada penampilan luar, melainkan pada kesadaran batin yang melahirkan kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Agama kehilangan makna ketika dijadikan tameng untuk ambisi pribadi dan alat legitimasi kekuasaan.
Karena itu, menilai agama dengan rasionalitas dan etika sosial adalah ajakan untuk kembali ke hakikat. Agama tidak membutuhkan pembelaan fanatik yang membutakan, melainkan pembuktian melalui amal dan akhlak. Kebenaran agama tidak ditentukan oleh seberapa lantang seseorang berbicara atas nama Tuhan, tetapi seberapa konsisten ia hidup dalam nilai-nilai yang diajarkan Tuhan.
Dalam kehidupan bangsa, semangat beragama seharusnya menjadi sumber integritas dan kemajuan, bukan sumber konflik atau kemunafikan. Agama yang dihayati secara rasional dan etis akan melahirkan masyarakat yang damai, jujur, dan berkeadilan.
Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki tanggung jawab moral yang besar. Mereka bukan hanya penyampai ajaran, tetapi juga teladan perilaku. Ketika seorang tokoh agama terjerat korupsi, skandal asusila, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang rusak bukan hanya dirinya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap agama itu sendiri. Masyarakat bisa kehilangan arah, dan agama pun kehilangan wibawa moralnya. Oleh karena itu, integritas pribadi menjadi pondasi utama bagi siapa pun yang membawa nama agama di ruang publik. Agama hanya akan dihormati bila para pemeluknya menampilkan akhlak yang luhur dan konsisten.
Kembali ke Hakikat Keberagamaan
Rasionalitas dan etika sosial juga penting untuk menjaga agama agar tetap relevan di tengah tantangan modernitas. Di era teknologi dan informasi, umat beragama dihadapkan pada banjir opini, narasi kebencian, dan polarisasi politik identitas. Di sinilah kemampuan berpikir kritis dan akal sehat diuji. Beragama dengan rasional berarti mampu memilah mana ajaran yang hakiki dan mana kepentingan yang diselipkan atas nama agama. Beragama dengan etika sosial berarti menolak segala bentuk kekerasan, kebohongan, dan ketidakadilan, sekalipun dilakukan oleh mereka yang memakai simbol agama.
Agama sejatinya tidak pernah mengajarkan kebencian, keserakahan, atau permusuhan. Ia datang untuk menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan memperkuat kemanusiaan. Karena itu, setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, betapapun dikemas dengan simbol keagamaan, sejatinya telah menyimpang dari semangat agama itu sendiri. Dalam hal ini, akal sehat dan nurani sosial menjadi penuntun agar kita tidak tertipu oleh kemasan keagamaan yang menyesatkan. Orang yang benar-benar beriman tidak mudah terpesona oleh retorika, tetapi menilai dari keteladanan dan tanggung jawab moral.
Menilai agama dengan rasionalitas dan etika sosial juga berarti menilai diri sendiri. Sebelum menunjuk kesalahan orang lain, setiap pribadi beriman perlu bercermin: apakah ajaran agama sudah benar-benar hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan? Apakah ibadah yang dilakukan telah melahirkan kepedulian sosial? Agama bukan sekadar urusan simbol dan seremonial, tetapi urusan transformasi diri. Keimanan sejati tampak bukan pada seberapa tinggi seseorang bicara tentang Tuhan, melainkan seberapa dalam ia mengamalkan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya.
Krisis moral yang kita hadapi hari ini tidak semata-mata karena kurangnya pengetahuan agama, tetapi karena hilangnya kesadaran etis. Banyak yang pandai berbicara tentang hukum agama, tetapi lemah dalam menegakkan keadilan. Banyak yang rajin beribadah, tetapi mudah menipu dan korup. Ini bukan krisis ajaran, melainkan krisis teladan. Dan untuk memperbaikinya, diperlukan keberanian untuk kembali kepada akal sehat dan nurani. Rasionalitas dan etika sosial harus menjadi dasar setiap langkah keberagamaan.
Agama yang rasional dan beretika akan melahirkan masyarakat yang matang. Masyarakat semacam itu tidak mudah disulut kebencian atas nama perbedaan. Mereka mampu hidup dalam keberagaman tanpa kehilangan prinsip. Mereka menjadikan agama sebagai sumber inspirasi kemanusiaan, bukan alat untuk mendominasi atau menghakimi. Sebaliknya, jika agama kehilangan rasionalitas dan etika, yang tersisa hanyalah formalitas dan fanatisme. Agama menjadi bising, tetapi kehilangan arah moral.
Karena itu, kita semua perlu kembali menegakkan cara beragama yang sehat. Mengembalikan agama pada fungsinya sebagai cahaya yang menerangi, bukan bara yang membakar. Kebenaran agama tidak boleh dijadikan alat untuk merasa lebih suci, melainkan sebagai tanggung jawab untuk berbuat lebih baik. Beragama dengan rasionalitas berarti membuka ruang dialog dan berpikir jernih. Beragama dengan etika sosial berarti menjadikan iman sebagai sumber keadilan dan kasih sayang. Itulah hakikat keberagamaan yang sejati.
Pada akhirnya, menilai agama dengan rasionalitas dan etika sosial bukanlah upaya memisahkan iman dari moral, melainkan menyatukan keduanya dalam kehidupan. Akal dan hati harus berjalan seiring. Iman tanpa rasionalitas mudah tergelincir menjadi fanatisme; rasionalitas tanpa iman mudah berubah menjadi kesombongan. Etika sosial menjadi jembatan yang menjaga agar keduanya tidak saling meniadakan. Agama yang hidup di hati dan akal manusia akan menumbuhkan peradaban yang berkeadilan, berkejujuran, dan berkeadaban.
Agama bukan sekadar untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupkan. Bukan untuk membenarkan kelompok, tetapi untuk memperbaiki manusia. Ketika agama dipahami dengan jernih dan dijalankan dengan etika sosial yang kuat, maka ia akan menjadi kekuatan moral yang mampu menuntun masyarakat menuju kemajuan.
Sebaliknya, bila agama hanya dijadikan simbol dan alat kekuasaan, maka yang lahir bukanlah kedamaian, melainkan kemunafikan. Saatnya kita menilai agama bukan dari banyaknya simbol, tetapi dari seberapa besar ia menuntun manusia untuk berbuat baik dan berlaku adil. Karena pada akhirnya, ukuran keberagamaan yang sejati bukan pada penampilan lahir, tetapi pada nurani dan tindakan yang membawa manfaat bagi sesama. (hanan)